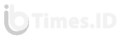Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Walaupun tidak disebut sebagai negara agama, Indonesia tentu memiliki keragaman pola dan kulturl yang beragam dalam menjalankan agama. Sebagai negara dengan latarbelakang budaya yang bergam serta kompleks, Indonesia sudah terbiasa dengan bertemunya macam-macam praktik adat tanpa adanya gesekan. Ratib Al-Haddad merupakan praktik keagamaan yang kemudian menjadi praktik adat, khususnya di wilayah Palembang.
Maraknya pembacaan Ratib Al-Haddad di kota Palembang sejatinya tidak lepas dari peran para ulama yang menyebarkannya. Tasawuf selalu berdampingan dengan proses penyebaran Islam di Indonesia, tidak terkecuali Palembang. Ulama Palembang terkenal sebagai penganut tarekat seperti, Sammaniyah, Naqsyabandiyah, dan Alawiyyah. Berbagai sejarawan tidak mengingkari akan besarnya peran ulama dalam penyebaran tarekat di Indonesia, khususnya Tarekat Haddadiyah di Palembang.
Sekilas Tentang Tarekat Haddadiyah
Tarekat Haddadiyah merupakan nama lain dari Tarekat Alawiyyah yang dinisbatkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau adalah seorang pembaru abad ke-17 M, lahir di daerah Sabir, pinggiran kota Tarim, Hadramaut, Yaman, pada Senin 5 Shafar 1044 H/1634 M. Beliau banyak menyumbangkan pikirannya tentang tasawuf dalam Tarekat Alawiyyah.
Tarekat ini terkenal dengan ratibnya, yakni Ratib Al-Haddad yang disusun langsung oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ratib Al-Haddad adalah Kumpulan beberapa ayat suci al-Qur’an dan doa. Adapun tasawuf yang digunakan dalam tarekat ini adalah tasawuf akhlaqi, yakni ajaran yang menekankan ilmu, amal, wara, dan ikhlas.
Dalam praktiknya tarekat ini tidak menekankan olah batin atau ruhani yang berat, melainkan lebih menekankan pada amal, akhlak, dan wirid yang ringan, sehingga dapat mudah dipraktikkan oleh siapa saja tanpa bimbingan mursyid secara langsung. Tarekat ini dikenal juga dengan Tarekat al-Abak wa Al-Ajdad, karena mata rantai silsilahnya turun temurun dari kakek, ayah, dan anak kaum alawiyyin (Hasanah, 2010). Tarekat ini tersebar ke penjuru dunia, seperti Yaman, Afrika, Malaysia, dan Indonesia.
Penyebaran Tarekat Haddadiyah di Palembang
Tarekat Haddadiyah telah berkembang luas bersamaan dengan datangnya para etnis Arab ke Nusantara pada abad ke-18. Sekalipun motif penyebaran kaum alawiyyin ini sering dikaitkan dengan perdagangan, namun para sarjana berpendapat bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyebarkan agama.
Tarekat Haddadiyah, dalam penyebarannya di Palembang, tidak dapat dipisahkan dari peranan seorang ulama yang bernama Syekh Ali Umar Thoyyib. Syekh Ali Umar Thoyyib lahir di Palembang pada 9 November 1952. Sejak kecil Syekh Ali telah menjadi saudara angkat dari salah satu keluarga Al-Habsyi di Pondok Pesantren Ar-Riyadh dan keluarga Syahab di kampung Muara 10 Ilir Palembang.
Pada tahun 1970 beliau memutuskan untuk memperdalam ilmu agamanya di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyyah yang berada di Kota Malang Jawa Timur. Pondok tersebut merupakan pondok yang diasuh oleh Prof. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaqih yang sekaligus mursyid Tarekat Haddadiyah. Dari gurunya tersebut, sekembalinya ke Palembang Syekh Ali kemudian menyebarkan ajaran Tarekat Haddadiyah (Ihsan, 2023).
Sekembalinya ke Palembang Syekh Ali kemudian mendirikan Majelis Awwabien. Lokasi majelis ini berada dalam satu kompleks dengan Masjid Darul Muttaqin, Kuto Batu, Palembang. Majelis Awwabien sendiri berdiri pada tahun 1986, adapun pemberian nama awwabien dengan maksud mengajak orang yang jauh dari agama untuk kembali pada nilai-nilai agama. Sebab kata awwabien, yakni orang-orang yang kembali (Putri, 2022). Dan sejak tahun 1983 Syekh Ali mendapatkan gelar dari Kesultanan Palembang Darussalam sebagai penasehat Kesultanan dengan gelar Pangeran Muhammad Noto Igamo
Majelis Awwabien telah menjadi semacam pondok (ribath) bagi para murid yang tertarik untuk belajar tarekat dan tasawuf, terutama Tarekat Haddadiyah. Di majelis ini pembacaan Ratib Al-Haddad dilakukan pada tiap malam setelah shalat isya. Banyaknya minat masyarakat untuk membaca ratib, membuat Syekh Ali membuat pedoman ratib yang lebih sistematis dengan menambahkan beberapa bagian, seperti doa Faqih Muqoddam, Zikir Taubat, dan Asmaul Husna.
Selain itu, Syekh Ali juga menasehati para muridnya untuk, 1). Tidak boleh meninggalkan sholat lima waktu, 2). Harus melakukan zikir dan fikir dalam kehidupan sehari-hari, 3). Menumbuhkan jiwa tauhid dan cinta kepada rasul beserta keluarganya, 4). Mempelajari agama terutama yang berkaitan dengan tata cara dan etika sholat (Munir, 2021).
Di kota Palembang, pembacaan Ratib Al-Haddad selain di Majelis Awwabien sebagai pusat, juga dilakukan di beberapa masjid, seperti Masjid Darul Muttaqin, Masjid Lawang Kidul, Masjid Bumi Sako Damai, dan Masjid Nur Ramadhan. Selain di masjid pembacaan ratib juga dilakukan musholla, bagi masyarakat Palembang, musholla menjadi tempat yang sangat penting untuk mengaktualisasi rasa spiritualitas mereka. Bahkan pembacaan ratib juga dilakukan dari rumah ke rumah (Noupal, 2018).
Dibandingkan dengan masyarakat keturunan Arab, khususnya kaum alawiyyin. Pembacaan dan pengamalan Ratib Al-Haddad justru mendapat antusias dari kalangan masyarakat non Arab, yakni masyarakat Palembang secara menyeluruh dalam kurun waktu dua dasawarsa.
Daftar Referensi
Hasanah, N. (2010). Pengaruh Tarekat Haddadiyah di Kecamatan Seyegan Yogyakarta. Yogyakarta: Skripsi Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga.
Ihsan, A. F. (2023). KH. Ali Umar Thoyyib (1952-2008) dan Kontribusinya dalam Perkembangan Islam di Palembang. Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam UIN Raden Fatah Palembang.
Putri, N. J. (2022). Eksistensi Majelis Awwabin dalam Mengamalkan Ritual Ratib Al-Haddad di Kota Palembang Tahun 1985-2008. Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah.
Noupal, M. (2018). Zikir Ratib Haddad: Studi Penyebaran Tarekat Haddadiyah di Kota Palembang. Intizar UIN Raden Fatah Palembang.
Munir. (2021). Tarekat Alawiyah Di Palembang Abad XXI. Palembang: UIN Raden Fatah Press.
Editor: Soleh