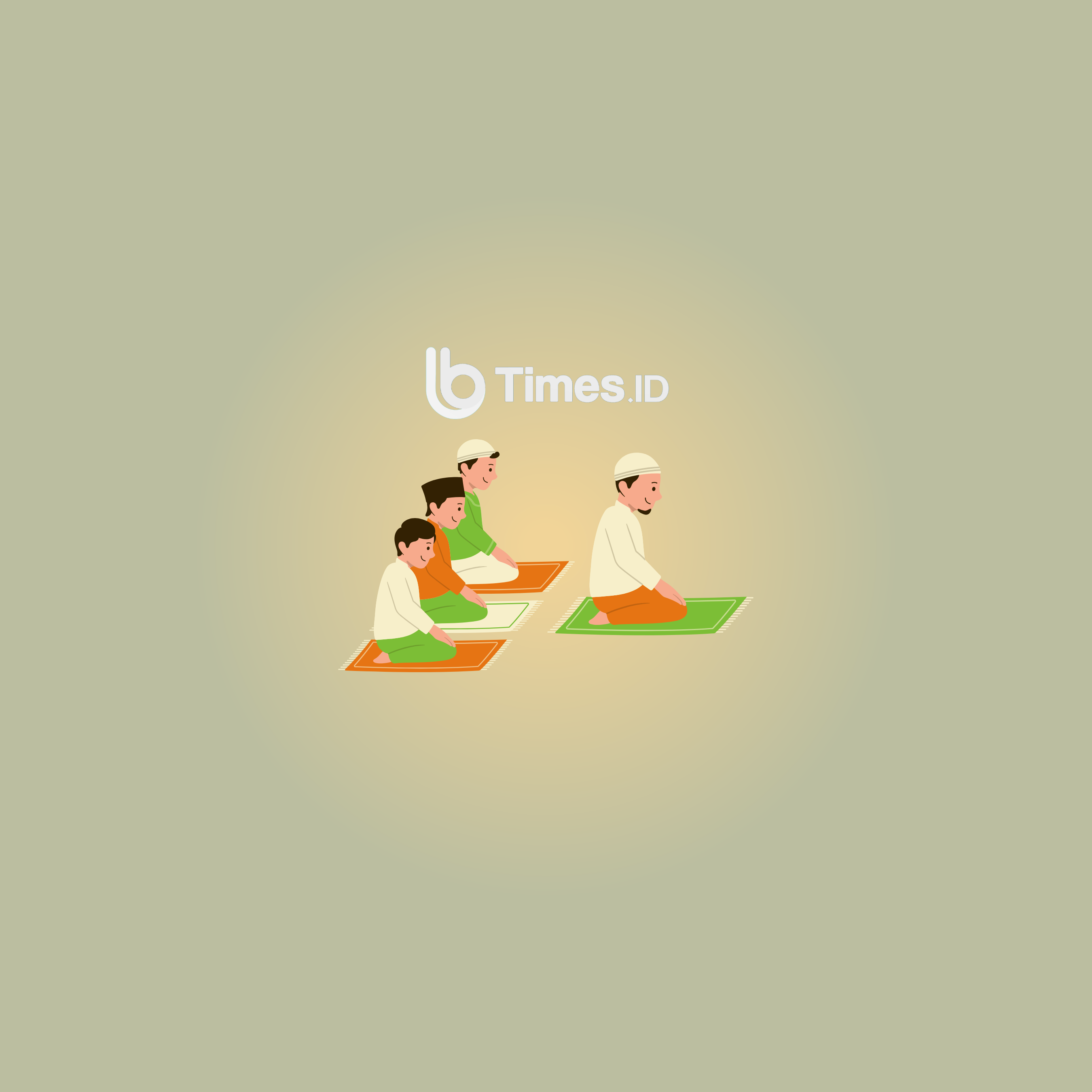Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, efisien, dan kerap dangkal secara spiritual, ibadah sunah sering kali menjadi pelengkap yang mudah dikorbankan. Banyak orang saat ini. Bahkan yang rajin menunaikan ibadah wajib, perlahan menjadikan ibadah sunah sebagai sesuatu yang opsional dalam makna yang sempit: jika sempat, dilakukan; jika tidak, tidak mengapa. Padahal, dalam sejarah Islam, ibadah sunah bukanlah ibadah kelas dua. Ia adalah jembatan penguat antara manusia dan Tuhannya yang mampu menyempurnakan dan memperdalam kualitas keimanan serta spiritualitas.
Lantas, mengapa banyak orang meremehkan ibadah sunah? Apakah karena ketidaktahuan, atau justru karena budaya instan yang mengubah cara kita memahami ajaran Islam secara utuh? Esai ini mencoba menyelami lebih dalam persoalan tersebut dari sudut pandang sosiologis, teologis, dan kritis.
Salah satu penyebab mendasar mengapa ibadah sunah diremehkan adalah pemahaman agama yang bersifat minimalis. Dalam banyak diskusi keagamaan populer, agama kerap dibingkai dalam dikotomi “yang wajib” dan “yang tidak wajib”, seakan-akan yang kedua tidak penting. Padahal, sebagaimana dijelaskan Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya Ibadah dalam Islam, ibadah sunah memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan hubungan spiritual manusia dengan Allah.
Reduksi Makna Ibadah Sunah dan Legalitas Formal
Ia adalah penyangga dan penyempurna dari ibadah wajib yang sering kali tidak kita laksanakan secara ideal. Namun dalam praktik keseharian, umat Islam cenderung mengadopsi pola pikir legal-formal. Seorang Muslim akan bertanya, “Kalau saya tidak salat sunah, apakah berdosa?” Ketika jawabannya “tidak,” maka ibadah itu segera dikesampingkan dari daftar rutinitas.
Ini menunjukkan bahwa motivasi beribadah kita masih sangat berkutat pada logika avoidance of sin (menghindari dosa), bukan pada logika spiritual yearning (kerinduan spiritual). Pandangan seperti ini juga tak lepas dari warisan pendidikan agama yang fokus pada fikih dasar dan tuntutan hukum, namun kurang mengembangkan kesadaran ruhaniah dan kedalaman makna ibadah.
Hasilnya adalah generasi yang memahami agama sebagai “kewajiban-kewajiban teknis”, bukan sebagai pengalaman spiritual yang hidup. Ibadah sunah, yang justru menawarkan ruang kebebasan dan ekspresi cinta kepada Tuhan, menjadi kehilangan daya tariknya.
Ibadah Sunah dan Budaya Instan yang Mendominasi
Kita hidup dalam zaman di mana segalanya dihitung berdasarkan efisiensi dan manfaat pragmatis. Dunia kerja modern, media sosial, dan bahkan pola belajar mengajarkan kita untuk selalu mengukur segala sesuatu dalam bentuk output yang dapat dikalkulasi. Dalam iklim semacam ini, ibadah sunah sering kali dianggap “tidak efektif” karena tidak menghasilkan sesuatu yang langsung terlihat atau terasa.
Berbeda dengan ibadah wajib seperti salat lima waktu atau puasa Ramadan yang memiliki sanksi sosial dan nilai hukum yang jelas, ibadah sunah kerap dilihat sebagai aktivitas spiritual “tambahan” yang tidak mendesak. Sosiolog Zygmunt Bauman dalam konsep liquid modernity menyatakan bahwa masyarakat modern mengalami pergeseran dari kedalaman ke permukaan.
Orang lebih sibuk mengejar yang segera, yang tampak, dan yang instan. Maka tak heran, orang lebih memilih menggulir TikTok selama 30 menit daripada membaca satu halaman Al-Qur’an, atau lebih rela menonton video motivasi daripada duduk sejenak untuk salat duha. Ibadah sunah menjadi “tidak kompatibel” dengan logika zaman yang serba instan.
Produktivitas, Ekonomi, dan Tergesernya Ibadah Sunah
Selain itu, dalam budaya produktivitas hari ini, waktu adalah uang. Bahkan waktu luang pun harus “bermanfaat” secara ekonomi atau sosial. Maka muncul prioritas baru dalam pikiran banyak orang: selama sudah salat wajib, itu sudah cukup—karena waktu selebihnya bisa digunakan untuk bekerja, membangun koneksi, atau beristirahat.
Akibatnya, ibadah sunah tersisih bukan karena dibenci, tetapi karena tidak dianggap mendesak secara sosial maupun ekonomis. Dalam masyarakat modern, kita juga menyaksikan tren spiritualitas yang bersifat kosmetik—menyentuh permukaan, namun tidak meresap hingga kedalaman jiwa.
Banyak orang mengaku ingin “dekat dengan Tuhan,” tetapi tidak mau menjalani proses sunyi dan konsisten yang ditawarkan oleh ibadah-ibadah sunah. Padahal, ibadah sunah seperti qiyamul lail, duha, witir, atau tilawah bukanlah sekadar ritual kosong, melainkan sarana kontemplatif yang membangun koneksi batiniah yang intim dengan Sang Pencipta.
Keheningan Jiwa dan Kedalaman Ibadah Sunah
Psikolog dan penulis buku The Road to Character, karya David Brooks, menyatakan bahwa kedalaman spiritual hanya bisa lahir dari proses kesunyian, keteraturan, dan praktik rutin yang tidak selalu menyenangkan. Prinsip ini sejalan dengan konsep tazkiyatun nafs dalam Islam, yang menekankan pembersihan jiwa melalui konsistensi amal, termasuk ibadah tambahan.
Dengan meninggalkan ibadah sunah, kita sesungguhnya sedang kehilangan peluang untuk menyentuh lapisan terdalam dari jiwa kita sendiri. Lebih dari itu, ibadah tambahan memberi ruang bagi manusia untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah secara personal.
Jika ibadah wajib adalah bentuk ketaatan karena perintah, maka ibadah tambahan adalah bentuk cinta karena kerelaan. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah berfirman bahwa hamba yang terus mendekatkan diri melalui amalan sunah akan dicintai oleh-Nya.
Memaknai sebagai Jalan Cinta
Maka, mengabaikan ibadah sunah bukan sekadar soal kehilangan pahala, tetapi kehilangan kemungkinan untuk dicintai oleh Tuhan. Namun, budaya modern justru sering membuat kita asing terhadap ruang-ruang kontemplatif ini. Kita lebih nyaman dalam keramaian, tergantung pada validasi eksternal, dan takut akan kesunyian.
Padahal, dalam kesunyian ibadah sunah itulah sesungguhnya jiwa dibentuk, ditajamkan, dan disucikan. Yang perlu kita benahi pertama-tama adalah paradigma kita dalam memandang ibadah secara keseluruhan. Kita cenderung menilai ibadah dari sisi hukum formal—apakah wajib, sunah, mubah, atau makruh—dan dari sana membangun hierarki nilai.
Ibadah tambahan lalu berada di posisi bawah karena dianggap tidak mengikat. Padahal, dalam laku spiritual, ukuran hukum bukan satu-satunya standar. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sosok yang paling banyak melaksanakan ibadah tambahan dan menjadikannya sebagai bentuk cinta dan keterhubungan personal dengan Allah.
Ruang Sunyi dan Penguatan Jiwa
Jika kita mengaku mengikuti beliau, semestinya kita juga memelihara semangat spiritual yang sama: melakukan ibadah bukan hanya karena diperintah, tetapi karena kita rindu. Selain itu, masyarakat kita perlu membangun kembali pemahaman bahwa ibadah sunah bukan sekadar amal tambahan, melainkan ruang personal dan eksklusif antara hamba dan Tuhannya.
Dalam era ketika kehidupan semakin publik, serba terekam, dan penuh sorotan, ibadah sunah bisa menjadi ruang batiniah yang bersih dari riya dan ekspektasi orang lain. Salat malam yang dikerjakan sendiri, tilawah yang tidak diunggah ke media sosial, sedekah yang hanya diketahui oleh Allah. Semua itu membentuk karakter spiritual yang dalam dan jujur.
Kita perlu keluar dari kebiasaan beragama yang hanya fokus pada formalitas dan menggantinya dengan pendekatan eksistensial: bahwa ibadah tambahan adalah cara kita mengokohkan jiwa dalam keheningan yang bermakna.
Langkah Awal Transformasi
Maka, jika ingin memperbaiki kualitas keislaman kita hari ini, langkah awalnya bukan selalu melalui gerakan besar atau program megah. Melainkan cukup dengan mengembalikan makna ibadah tambahan sebagai tempat mendidik diri dalam bentuk disiplin tanpa paksaan. Konsisten tanpa sorotan, dan mencintai Tuhan tanpa pamrih.
Perubahan besar dalam hidup spiritual justru dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang, dengan ikhlas dan terus-menerus. Di sinilah letak kekuatan sejati dari sunah yang selama ini kita abaikan.
Editor: Assalimi