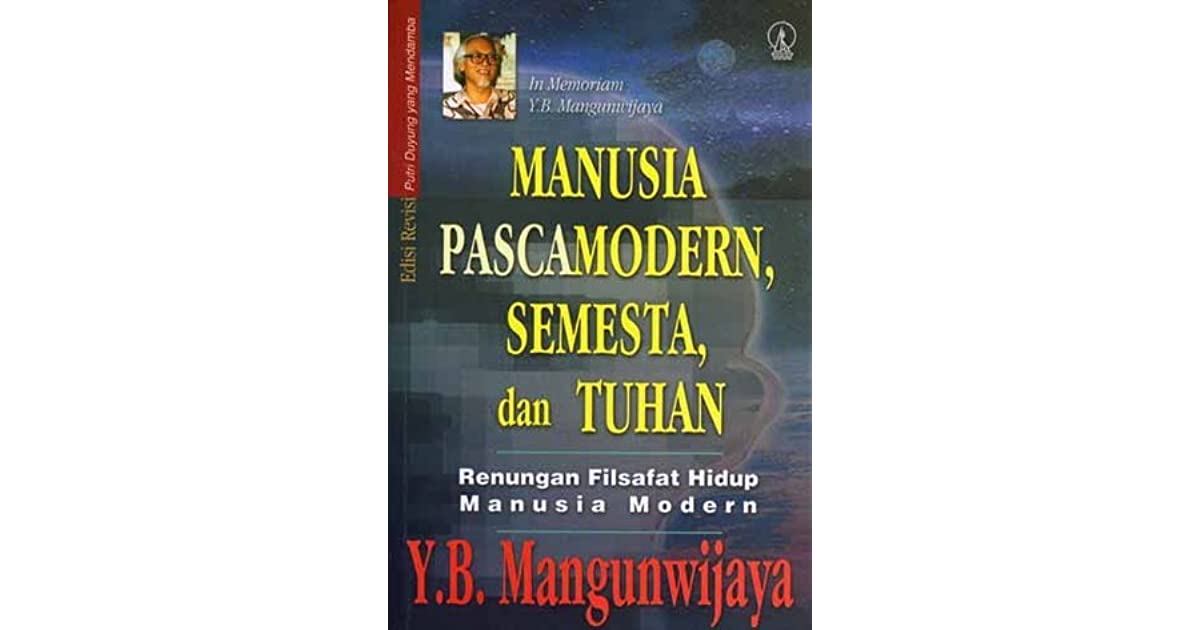Apakah peran agama tradisional pada zaman ini telah tergantikan dengan ilmu pengetahuan? Atau, apakah bisa agama tradisional tetap exist pada zaman post-mo ini? Bagaimanakah manusia harus menyikapi ini semua? Seberapa pentingkah agama berperan pada zaman ini? Setidaknya itulah beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam buku ini. Tak hanya sekedar memberi jawaban yang ala kadarnya, buku ini menuntun para pembacanya untuk jatuh dalam refleksi mendalam dan sunyi. Yang juga sangat panjang dan berarti.
Sebelum berlanjut untuk mengulas secara bebas, ada satu poin yang di awal menarik perhatian saya. Beberapa saat lalu ketika saya bertemu dengan teman saya, ia sangat keheranan dengan saya. Bukan sebagai personal, akan tetapi dengan apa-apa yang saya pikirkan, andaikan, dan refleksikan. “Kok ndadak mbok pikirke ki ngopo?”Kurang lebih seperti itu.
Hidup Secara Filosofis
Beberapa orang mungkin juga memikirkan hal yang sama terhadap temannya yang ‘kebetulan’ sedang belajar filsafat. Jika beberapa orang mencukupkan penghayatan secara naqli, tidak begitu dengan beberapa orang yang tidak memiliki kepuasan hanya dengan hal itu. Bukan atas dasar kesombongan dan juga keengganan untuk ‘beriman’. Bukan seperti itu.
Singkatnya mereka sudah terlanjur mengetahui pengetahuan juga beberapa kesangsian atau syubhat mengenai hal itu. Alangkah bahaya jika mereka berhenti. Maka dengan demikian mereka memilih untuk menghayati hidup ini beserta realitas-realitas, baik secara fisik maupun metafisik dengan cara filosofis.
Mengangkat dari berbagai macam sudut pandang, buku ini mengajak kita untuk menziarahi sejarah bangsa umat manusia dan berbagai macam perkembangan yang telah menghiasi peradaban.
Umur manusia yang kurang lebih sudah berumur 2 juta tahun ini, dalam segi pencapaian perkembangan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kurun waktu 500 tahun ke belakang. Bagaimana tidak? Manusia pada masa kini telah menembus batas paling subtil hingga serat-serat terkecil dari dunia ini.
Manusia telah bisa memandang dengan horison yang sangat luas dan tak terbatas; hal ini dianggap tabu pada masa sebelumnya. Sedangkan bumi setidaknya masih punya waktu 5 miliar tahun lagi sebelum matahari menjadi tungku yang sangat panas lalu mendidihkan segala yang ada dalam tata surya.
Lalu bagaimana dengan pembahasan-pembahasan ke depan? Bukan tidak mungkin hal yang kini menjadi sebuah tren ataupun hal yang benar-benar baru dianggap kuno pada zaman mendatang. Mungkin juga sebuah keniscayaan.
Dari Dogma Agama Menuju Ilmu
Hal itu dimulai dari meletusnya zaman renaissance dan disusul aufklarung hingga dunia yang berdasar pada agama dan dogma dikejutkan oleh “para pengejut dunia”. Maksud dari kata pengejut di sini adalah bagaimana dunia ini yang bermuara pada dogma dan para santo digeser ke ilmu pengetahuan.
Dimulai dari Copernicus yang menolak ajaran geosentris dan memperkenalkan ajaran heliosentris. Dilanjutkan dengan Charles Darwin yang dengan asumsinya menganggap dunia ini tidak ‘statis’ melainkan terus menerus bergerak, panta rhei, selalu berkreasi diri.
Jika hal di atas lebih memperhatikan aspek semesta, berbeda pula dengan sosok pria dari Wina ini. Ia lebih menaruh aspek pada psikologis manusia. Dunia lagi dan lagi dikejutkan.
Kali ini dengan penemuan Sigmund Freud tentang alam bawah sadar manusia yang masih berkuasa padanya. Berikutnya adalah sosok yang sangat masyhur, yaitu Albert Einstein. Dengan teori kenisbian (relativitas) yang ternyata sangat berkebalikan dengan ajaran kemutlakan. Demikianlah para sang pengejut dunia ini (hal. 85).
Sekularisasi: Pendewasaan Sebagai Manusia
Dalam perkembangan zaman ini kita dituntut untuk mengikutinya juga. Jika meminjam istilah dalam ilmu sosial, agar kita tidak terseret dalam arus globalisasi yang semakin lama tidak semakin surut akan tetapi semakin besar gelombangnya. Apa yang menjadi tuntutan kepada kita as a human being? Kepunyaan atas sikap dan pendewasaan diri.
Dalam buku ini, salah satu cara pendewasaan adalah dengan ber-sekularisasi. Sekularisasi mempunyai perbedaan makna dengan sekularisme. Jika sekularisme adalah sebuah proses yang di mana mengandung dua makna di dalamnya.
Pertama, adalah penghancuran agama secara penuh. Kedua, adalah menyingkirkan agama dalam segala lini kehidupan. Maka proses sekularisasi di sini mempunyai makna yang sangat lain sama sekali. Ia adalah sebuah proses manusia yang berkembang menjadi semakin dewasa jalan pikiran dan cita rasanya, berdiri di atas kaki sendiri. Ia tidak akan mau menjadi manusia yang digambarkan oleh Karl Marx.
Bagaimana manusia berlindung di balik agama untuk mencari proses pembenaran atas sikap yang padahal agama sendiri tidak mengajarkan itu. Pada manusia yang ber-sekularisasi ini tahu bahwa ia harus menjalankan kedua hal itu, agama dan ilmu. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Einstein bahwa “science without religion is lame, religion without science is blind.”
Para Pemeluk Agama: Bersatulah!
Penghayatan religius juga hal yang sangat ditekankan pada buku ini, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Penghayatan religius atau sikap religi sama sekali lain dengan religi tertentu atau agama. Lebih jelasnya, dua orang yang memeluk agama berbeda bisa saja mempunyai sikap religi yang sama, sedangkan dua orang dengan agama yang sama bisa saja mempunyai sikap religi yang sangat bertolak belakang.
Dalam fase yang paling dini, manusia biasanya merasa lebih dekat dengan kaum seagamanya dibanding dengan yang bukan. Akan tetapi dengan kedewasaan akal budi dan hati, ia akan menemukan sebuah ikatan persaudaraan meskipun dengan orang yang menganut agama lain. Perlu dicatat dan diingat dengan sangat, bahwa untuk kembali menghidupkan peran agama yang semakin lama semakin dianggap hanya ritus semata adalah tugas semua agama. Tak hanya pemeluk Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan Katolik saja. Melainkan all of us should be. Maka tanpa harus menjiplak Karl Marx, baiklah kita seru: Kaum beragama apa pun dan dari mana pun di seluruh dunia: bersatulah! (hal.149).
Berdialog dengan Tuhan
Setelah menyelesaikan buku ini, saya dapat menangkap sebuah masalah besar yang ternyata tidak mendapatkan perhatian yang begitu besar dari sebagian kita. Betapa banyak dari kita yang dari luar nampak tekun menjaga ritus-ritus agama akan tetapi jauh dalam hatinya Tuhan tidak ada atau nonsense. Entah karena ia berpikir bahwa Tuhan ada atau tidak itu bukan urusannya sebab menurutnya Tuhan itu berada tidak dalam cakrawalanya (agnostik), atau juga yang sedari dini ia ‘dicekoki’ agama tanpa diberitahu esensi di balik semua itu.
Betapa agung-Nya, betapa pemurah-Nya, betapa pemaaf-Nya Tuhan ia dapat tidak berdasar apa yang ia tangkap dalam penglihatan mata hatinya. Namun, menggunakan entah mata hati orang tuanya, gurunya, atau orang lainnya. Semoga kita senantiasa didekatkan pada sebuah refleksi dan keintiman ‘berdialog’ dengan Tuhan sesuai jalan yang kita kehendaki masing-masing.
Hal ini tentunya juga akan berdampak pada realitas-realitas yang selama ini selalu saja kita benturkan dengan idealisme. Orang-orang menganggap bahwa idealis akan dan pasti tergerus oleh realitas. Dalam bahasa lain yang lebih lantang, idealis sampai kapan pun tidak akan bisa memberi kamu sarapan dan makan siang. Beberapa waktu silam, saya membaca tweet dari pemuda yang sempat menghebohkan jagat dunia maya dengan tesis tentang melawan sekolah. Memang idealis tidak bisa memberi makan, akan tetapi ia bisa menjadi kontrol dalam realitas agar senantiasa waras dan tidak kebablasan.
Manusia Sumarah: Merawat Spiritualitas Agama
Dalam buku Manusia Pascamodern, Semesta, dan Tuhan memfungsikan sikap religius -yang menurut saya juga bisa memiliki fungsi yang sama dengan idealisme- untuk mengatur seporsi materialisme dalam hidangan yang betul.
Tak hanya mengatur porsi akan tetapi juga dalam perpaduan dengan tipe manusia sumarah. Yang mana mempunyai arti tidak pernah menganggap penting secara final segala apa yang duniawi (hal. 129).
Setelah membaca buku ini, saya semakin yakin bahwa ada banyak cara dalam merawat penghayatan spiritual. Bila kita renungkan dari besarnya semesta ini, segala bentuk keteraturan kosmos, dan berbagai macam “kebetulan”, tidak hanya dengan pikiran melainkan juga dengan cita rasa dan akal budi serta iman.
Barangkali kita akan mendongak ke atas dan diam dalam hening. “Siapakah kau, homo sapiens?” Dan Semoga juga: “Siapakah Kau, ya Tuhan?” Maka, akan terasalah betapa dungu dan primitif segala persengketaan antaragama, betapa relatif segala perumusan dogma dan adat oleh manusia, betapa kekanak-kanakan kebanyakan cita-cita dan gerak kita yang masih setingkat anak monyet berebutan krupuk (hal. 39).
Editor: Yahya FR