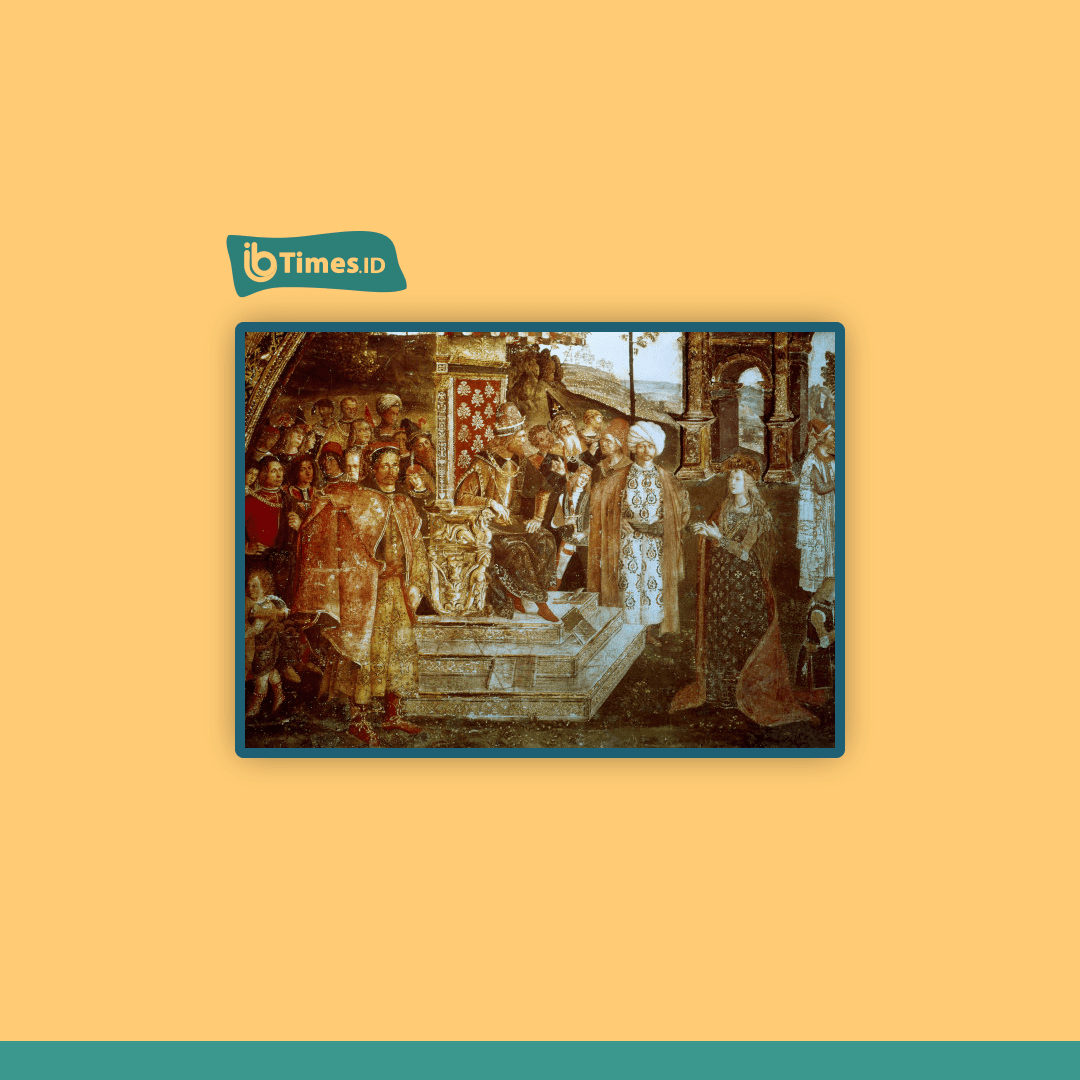Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan serangkaian perangkat lengkap dan sempurna. Tentu, setiap perangkat anggota tubuh yang membentuk manusia memiliki fungsinya masing-masing. Namun, apakah manusia sebagai makhluk yang merupakan hasil ciptaan berhak atas semua anggota tubuh tersebut? Atau manusia tak lebih dari seorang wayang yang seluruh gerakan dan perbuatannya terserah pada dalang yang menciptakannya?
Jika manusia benar-benar tidak kuasa atas perbuatannya, dengan kata lain perbuatan manusia seluruhnya mutlak kehendak Tuhan yang menciptakan. Maka tidak adil rasanya jika ada dosa, siksa, dan neraka. Dalam Islam, terdapat berbagai pandangan yang bervarian dari aliran-aliran ilmu kalam untuk menanggapi perkara “Kuasakah manusia terhadap perbuatannya?”. Sebut saja Mu’tazilah dan Asy’ariyah. Kedua aliran ini memiliki pandangan masing-masing dalam menanggapi hal tersebut.
Pandangan Mu’tazilah dan Asy’ariyah tentang Perbuatan Manusia
Mu’tazilah dengan pandangannya yang lebih mendekati pandangan Qadariyah, mereka menganggap bahwa setiap perbuatan manusia adalah mutlak kehendaknya. Dengan demikian, maka manusia akan mempertanggung jawabkan segala yang diperbuatnya, karena tidak adil rasanya jika manusia yang berbuat dosa atas kehendak Allah dan kelak Allah juga yang menyiksa. Pendapat ini sering disebut dengan free will/free act (Abdul Mun’im, t.th.: 829).
Berbeda dengan Mu’tazilah, paham Asy’ariyah justru berpandangan jika kehendak manusia adalah kehendak Tuhan pula. Berawal dari anggapan bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk lemah, yang jika tidak mendapat daya dari Allah maka manusia tidak akan bisa berlaku apa-apa. Asy’ariyah memiliki istilah al-kasb, yang intinya bahwa manusia tidak berhak atas segala perbuatannya. Menurut Al-Asy’ari, manusia hanyalah pelaku dari apa pun yang dikehendaki Allah, tak lebih adalah sebuah wayang dan Allah-lah dalangnya (Supriadin, 2014: 70).
Pandangan Asy’ariyah tersebut berangkat dari penegasan olehnya tentang Allah adalah maha segalanya, Allah juga berkehendak terhadap segala sesuatu yang mungkin dikehendaki-Nya. Tidak ada kejadian di alam semesta yang lepas dari kehendak Allah.
Namun, tentang perbuatan dan kehendak manusia ini, kemudian direvisi oleh salah satu tokoh dari golongan Asy’ariyah sendiri, yakni Al-Baqillani.
Biografi Singkat Al-Baqillani
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Thayyib bin Muhammad bin Ja’far bin al-Qasim, yang lebih dikenal dengan al-Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani. Beliau adalah mutakallim sekaligus ahli ushul fiqh yang lahir di Bashrah dan menetap di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 1013 M. di Baghdad dan dimakamkan di samping makam Ahmad bin Hambal di pemakaman Bab al-Harb (M. Syarif Hasyim, 2005: 210).
Al-Baqillani berguru pada ulama besar yang kebanyakan berpaham Asy’ariyah. Salah satunya ialah Abu Abdullah bin Muhammad bin Ya’kub bin Mujahid al-Thaiy al-Malikiy, yang merupakan seorang sahabat dan juga murid dari Al-Asy’ari. Oleh karena itu, Al-Baqillani juga termasuk dalam aliran mutakallim berpaham Asy’ariyah dan juga sebagai peletak komponen penting dalam aliran tersebut (Supriadin, 2014: 74).
Sesuai dengan namanya Al-Qadhi, Al-Baqillani adalah seorang hakim. Tugas yang diembannya seringkali berhubungan dengan perbuatan manusia, yaitu tentang keputusan atas ditetapkannya hukuman atau keadilan terhadap perbuatan manusia.
Hukuman yang dijatuhkan kepada manusia tentu adalah buah dari perbuatan jahat yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya. Hal ini berhubungan dengan pemikirannya tentang perbuatan manusia. Tidak mungkin jika Al-Baqillani menanggap bahwa perbuatan jahat manusia tersebut adalah perbuatan Tuhan. Sedangkan yang menerima hukuman adalah manusia.
Dalam hal ini, Al-Baqillani berbeda pendapat dengan pendahulunya dari kalangan Asy’ariyah. Karena menurutnya, tidaklah adil jika manusia yang dihukum atas perbuatan yang sama sekali bukan kehendaknya, melainkan kehendak Allah sesuai dengan pendapat Al-Asy’ari.
Pendapat Al-Baqillani tentang Perbuatan Manusia
Mengenai perbuatan manusia, Al-Baqillani mengadakan suatu revisi terhadap pendapat pendahulunya. Beliau menganggap bahwa manusia memanglah tidak mempunyai daya jika tidak diberi Allah. Akan tetapi, menurutnya ada perbuatan yang manusia bebas melakukannya dan ada pula perbuatan yang manusia terpaksa melakukannya.
Al-Baqillani menyebutnya dengan kemerdekaan untuk bertindak. Berbeda dengan Mu’tazilah yang memaknai kemerdekaan dengan menganggap bahwa manusia sebebas-bebasnya dalam melakukan suatu perbuatan dengan berbagai konsekuensinya.
Al-Baqillani memaknai bahwa kemerdekaan manusia dalam berbuat adalah sebatas pada kuasa atau daya yang diberikan Allah terhadapnya. Menurutnya juga, manusia hanya akan mampu berbuat ketika perbuatan itu terjadi. Karena pada waktu itulah daya atau kuasa diberikan Allah kepada manusia. Sebelum perbuatan itu terjadi, manusia memang tidak memiliki daya untuk melakukan apa pun.
Al-Baqillani memberi perumpamaan adanya daya pada manusia sama seperti cincin yang terangkat bersamaan dengan pergerakan jari (Supriadin, 2014: 75). Hal ini sama halnya dengan penulis dalam menuliskan tulisan ini, Allah akan memberi daya agar tulisan ini selesai ketika penulis memulai untuk menulis.
Jadi, pendapat Al-Baqillani tentang “Seberapa kuasa manusia atas perbuatannya?” ialah manusia akan mampu berbuat apa pun ketika diberikan daya oleh Allah kepadanya. Demikian pula Allah akan memberi daya kepada manusia ketika manusia itu melakukannya. Dengan demikian, Allah tidak kehilangan kedudukannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikuasai. Manusia juga tidak kehilangan esensinya sebagai makhluk yang merdeka.
Editor: Lely N