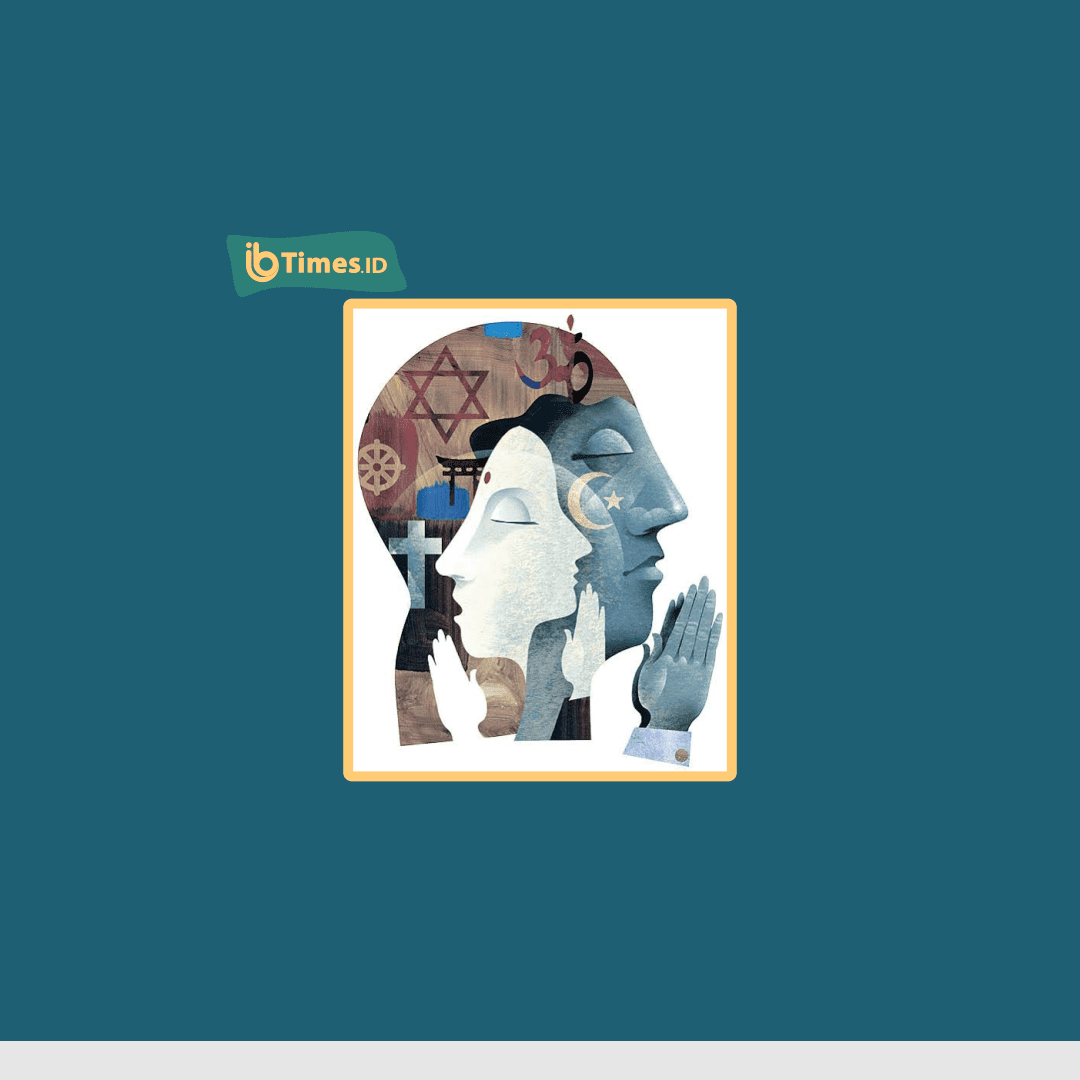Pendahuluan
Tampaknya jika kita hendak menguji sejauh mana kedewasaan umat beragama, caranya sederhana: mari bertanya kepada diri sendiri mengenai status keselamatan dan kebenaran agama-agama lain selain yang kita anut. Ujian sesungguhnya bagi umat manusia di abad ke-21 boleh jadi adalah ancaman krisis ekologi, ketimpangan sosial-ekonomi, dan disrupsi teknologi. Namun, ujian terberat bagi umat beragama terletak pada kemampuan (atau ketidakmampuan) memahami bahwa agama-agama lain bisa jadi adalah sama benarnya dan sama selamatnya.
Pada faktanya, planet Bumi yang kita huni terbukti merupakan rumah bagi siapa saja, tidak peduli apa ras, keturunan, atau bangsanya. Begitu juga anugerah kehidupan yang manusia miliki tidak diperoleh hanya oleh mereka yang berasal dari agama tertentu dan aliran tertentu. Maka sangat tidak aneh jika umat manusia semakin mampu bekerja sama meski mereka menganut identitas berlapis yang saling berbeda. Barangkali yang aneh adalah jika hari ini kita masih meyakini bahwa tidak ada titik temu antar agama dan tidak ada persaudaraan bagi semua agama.
Agama: Antara Berkonflik atau Bersaudara
Seperti biasa, agama-agama selalu dipandang sebagai warisan (ter-)penting yang kita terima dari generasi-generasi terdahulu. Kita selalu bisa merujuk pada tradisi dan ajaran agama tatkala membutuhkan pedoman moral dan kebijaksanaan hidup. Saat ini, karena hampir semua orang bisa mempelajari semua agama, maka kekayaan moralitas dan spiritualitas agama-agama berubah menjadi warisan bersama semua orang. Kini misalnya, keindahan rangkai kata ayat-ayat Al-Quran dan sejumlah maknanya yang inspiratif dan menggugah akal, bisa dimengerti oleh bukan hanya Muslim dan bukan hanya mereka yang berlisan Arab.
Meski tidak semua penganut agama mampu berpikiran simpatik seperti itu, tetap saja ada benarnya bahwa bagi seorang penganut agama tertentu akan selalu boleh dan bermanfaat jika ia mempelajari moralitas dan kebijaksanaan di luar buku-buku keagamaan dari agamanya saja. Dan, sudah sepatutnya untuk bersikap dewasa setiap kali kita menyadari bahwa sistem kepercayaan dan mitologi agama lain berbeda dari agama yang kita warisi dari orang tua. Berlindung di balik dalih kesesatan agama lain boleh jadi adalah bukti bahwa seseorang (atau sekelompok orang) menutup mata dari realitas keragaman agama dan dari fakta keragaman manusia.
Tepat ketika kita berani membuka mata dan memandang kenyataan –lantas meninggalkan ilusi dan dalih kesesatan agama lain– maka kesadaran bahwa agama-agama pada dasarnya bersaudara pun akan muncul.
Agama-agama bersaudara karena satu alasan sederhana dan gamblang, yakni bahwa umat manusia pun pada dasarnya bersaudara.
Namun, dalam hubungan antar saudara tak pelak lagi selalu terjadi dinamika. Lingkungan dan masyarakat tempat kita hidup bukanlah sebuah Taman Firdaus yang penuh kedamaian dan bukan sebuah sistem masyarakat utopis yang menjanjikan terpenuhinya keinginan semua orang. Begitu juga otak cerdas yang kita warisi dari jutaan tahun proses evolusi bukanlah mesin tanpa emosi, hasrat, dan ego. Itu semua menyediakan kondisi yang sangat mendukung bagi potensi keributan, konflik, dan kecemburuan.
***
Namun yang lebih penting adalah, tidak ada alasan untuk tidak mengakui bahwa sejumlah redaksi dalam kitab suci sejatinya berbasis pada situasi konflik, keributan, dan kecemburuan.
Bagi sejumlah Muslim hari ini, ayat Al-Quran yang berkata “Umat Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah meridhai kamu sampai kamu mengikuti agama mereka” (2: 120) dianggap sebagai takdir yang tidak akan mungkin berubah bahwa Yahudi dan Nasrani adalah musuh bagi Islam selama-lamanya.
Namun, bagi Muslim lainnya, ungkapan keras ayat tersebut tidak lain terlahir dari situasi konflik di Madinah saat itu, ketika komunitas Muslim masih berukuran sangat kecil dan selalu terancam dari serangan dan konspirasi jahat komunitas luar (outsider). Adapun situasi saat ini jelas berbeda, dan ayat tersebut bukanlah dalil untuk membenci Yahudi dan Nasrani, apalagi untuk selama-lamanya.
Jelas bahwa selalu ada perbedaan (bahkan pertentangan) antar ajaran kepercayaan agama-agama. Monoteisme Islam tak pelak lagi pasti bertentangan dengan Trinitarianisme sejumlah penganut agama Nasrani. Begitu juga dengan politeisme Hindu dan mitologi agama-agama lain. Konsepsi Nabi Muhammad tentang Tuhan jelas berbeda dengan konsepsi umat Yahudi, para penulis Perjanjian Baru, dan kitab-kitab suci yang lain. Namun, itu semua tidak ada hubungannya dengan kenyataan bahwa agama-agama itu sama-sama mengajarkan aspek ketuhanan; sama-sama mengabarkan kehormatan umat manusia; dan sama-sama bermaksud menerapkan hukum dan moral demi keadilan sosial.
Agama: Antara Tertutup atau Terbuka
Hampir sebagian besar Muslim saat ini adalah Muslim karena terlahir dalam sebuah keluarga Muslim. Jangan tanya tentang penganut agama lain, karena mereka juga demikian. Namun, terlahir dalam tradisi agama tertentu tidak semestinya membuat seseorang menganggap bahwa setiap perkataan pendakwah agamanya adalah benar. Terlahir dalam komunitas beragama tidak mewajibkan seorang manusia untuk meninggalkan akal dan intuisinya, lantas patuh secara buta terhadap golongan yang dianggap otoritas dalam agama.
Persaudaraan agama-agama adalah suatu fakta sosial yang bisa kita saksikan sendiri dengan akal sehat kita. Saat ini, secara sosial kita mampu melihat bahwa umat manusia bisa bekerja sama tanpa dihambat oleh perbedaan sejumlah aspek dalam agama yang mereka anut. Begitu juga, kondisi kerja sama sesama anak Adam demi kebaikan ini pada dasarnya merupakan cita-cita semua agama.
Atas dasar fakta dan cita-cita tersebut, sangat tidak masuk akal untuk mempertahankan kepercayaan yang negatif tentang kebenaran eksklusif agama sendiri dan kejahatan abadi agama lain. Sekalipun ribuan pendakwah masih aktif berceramah demikian, kita punya akal dan intuisi yang bisa menyaksikan kenyataan.
Semakin mengedepankan fakta dan cara berpikir rasional, tampaknya berpotensi membuat seorang penganut agama semakin dewasa dan terbuka.
Seorang Muslim yang dewasa tidak akan tergesa-gesa berkesimpulan bahwa agamanya adalah agama yang tertutup, hanya lantaran sejumlah ulama berkata bahwa ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan permusuhan Islam dengan agama lain.
Biasanya ayat-ayat itu adalah “Umat Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah meridhai kamu sampai kamu mengikuti agama mereka” (2:120), atau “Telah kafir mereka yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari tiga entitas ketuhanan” (5:73), atau “Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam” (3:19).
***
Namun, jika pada kenyataan sejarahnya komunitas beriman yang Nabi Muhammad bangun memang pernah mengalami sejumlah polemik dengan Politeis Arab dan dengan beberapa penganut Yahudi dan Nasrani, maka tidak aneh jika sejumlah redaksi Al-Quran merekam polemik itu semua.
Seharusnya yang aneh dan patut kita pertanyakan adalah mengapa rekaman Al-Quran tersebut kemudian diklaim sebagai ajaran (dan ajakan) untuk memusuhi umat beragama lain, kapan pun dan di mana pun?
Begitu juga, mengapa justru ada ajaran (dari sejumlah kalangan ulama, dulu dan kini) bahwa ayat Al-Quran tentang keselamatan agama-agama lain telah di-nasakh (dibatalkan) dan tidak berlaku lagi?
Al-Quran sebenarnya tidak hanya menyajikan rekaman dari konflik dan polemik antara konsepsi ketuhanan dalam Islam dengan agama-agama tertentu. Menurut Fazlur Rahman (pakar dan pemikir Islam terkemuka di abad ke-20), dibandingkan dengan rekaman atas polemik-polemik yang seringkali tajam tersebut, Al-Quran justru memiliki satu pesan yang lebih tegas dan jelas dalam menjawab pertanyaan status keselamatan penganut agama-agama selain Islam. Ayat tersebut adalah yang berbunyi “Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabaean, siapa saja yang beriman pada Tuhan, hari akhirat, dan berbuat kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, mereka tidak perlu takut, tidak pula mesti bersedih hati” (2:62).
Bacalah sekali lagi ayat tersebut (dan baca juga redaksi berbahasa Arabnya yang jelas sangat indah ketika dilantunkan) maka, sebagaimana Rahman, kita sendiri bisa mengerti bahwa Al-Quran tidak sepenuhnya mengutuk agama di luar Islam.
Namun yang lebih penting adalah catatan Rahman bahwa sebagian besar mufassir (penulis kitab tafsir Al-Quran) dari generasi terdahulu selalu berusaha untuk lari dan menolak makna yang terang-benderang dari ayat ini, seraya mengajukan kembali sejumlah ayat polemik untuk membenarkan superioritas Islam atas agama-agama lain.
Biasanya, puncak dari argumentasi mufassir dan ulama yang dikritik oleh Rahman tersebut adalah bahwa ayat 2:62 yang sangat positif terhadap agama lain itu telah di-nasakh (dibatalkan) oleh ayat-ayat polemik.
***
Sebagai catatan untuk kita, teori nasakh (pembatalan suatu ayat dan suatu hukum) tidak disepakati oleh semua pakar teori hukum Islam, baik dulu maupun kini.
Dan lagi pula, menganggap bahwa ayat 2:62 itu telah batal, sama saja dengan membatalkan janji dan hukum yang Tuhan telah sampaikan, yakni janji bahwa: Siapa saja yang beriman kepada Tuhan, hari akhirat, dan berbuat kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, mereka tidak perlu takut, tidak pula mesti bersedih hati.
Menganulir janji Tuhan yang tertulis secara harfiah (dan tidak memiliki kebutuhan untuk diinterpretasikan secara berbeda) boleh jadi hanya datang dari seseorang (atau sekelompok orang) yang merasa berkuasa terhadap manusia lain, melebihi kekuasaan Tuhan itu sendiri.
Jelas bahwa teori nasakh tidak berlaku untuk ayat 2:62 (dan untuk ayat mana pun). Sebab Tuhan tidak akan membatalkan dan melanggar janji-Nya sendiri (innallaha la yukhliful mi’ad) sebagaimana disampaikan Al-Quran dalam ayat 3:9.
Kesimpulan
Sudah pasti, seorang yang beriman akan melihat bahwa umat manusia selalu membutuhkan agama. Tapi sayangnya, kita sering diajari bahwa agama merupakan semacam tiket untuk bisa masuk ke dalam surga. Dengan ajaran seperti itu, kita dibentuk untuk melihat komunitas agama sendiri sebagai golongan yang selamat dan ahli surga, sementara kelompok agama lain (atau aliran/sekte lain meskipun seagama) adalah golongan sesat dan ahli neraka. Jelas tidak ada masa depan bagi persaudaraan agama-agama jika yang terus-menerus kita ajarkan adalah kepercayaan seperti itu.
Mempertahankan kepercayaan seperti itu tampaknya menjadi alasan kuat mengapa agama semakin tampak tidak relevan dengan kemajuan abad ke-21. Relevansi agama saat ini justru kerap kali terjadi pada hal-hal yang bisa merusak kehidupan bersama. Agama di abad ke-21 masih belum bisa lepas dari fungsinya sebagai alat untuk membenarkan kebencian satu kelompok manusia terhadap manusia lain. Juga tidak kalah menyedihkan adalah agama dan Tuhan yang dipertentangkan dengan usaha rasional dan ilmiah manusia untuk melindungi diri dari virus penyakit mematikan.
Dengan semua masalah yang mengelilingi agama tersebut, sudah selayaknya umat beragama hari ini mampu menciptakan pandangan beragama yang baru, yang mampu meninggalkan semua beban masa lalunya, termasuk beban konflik dan polemik antar agama.
Editor: Soleh