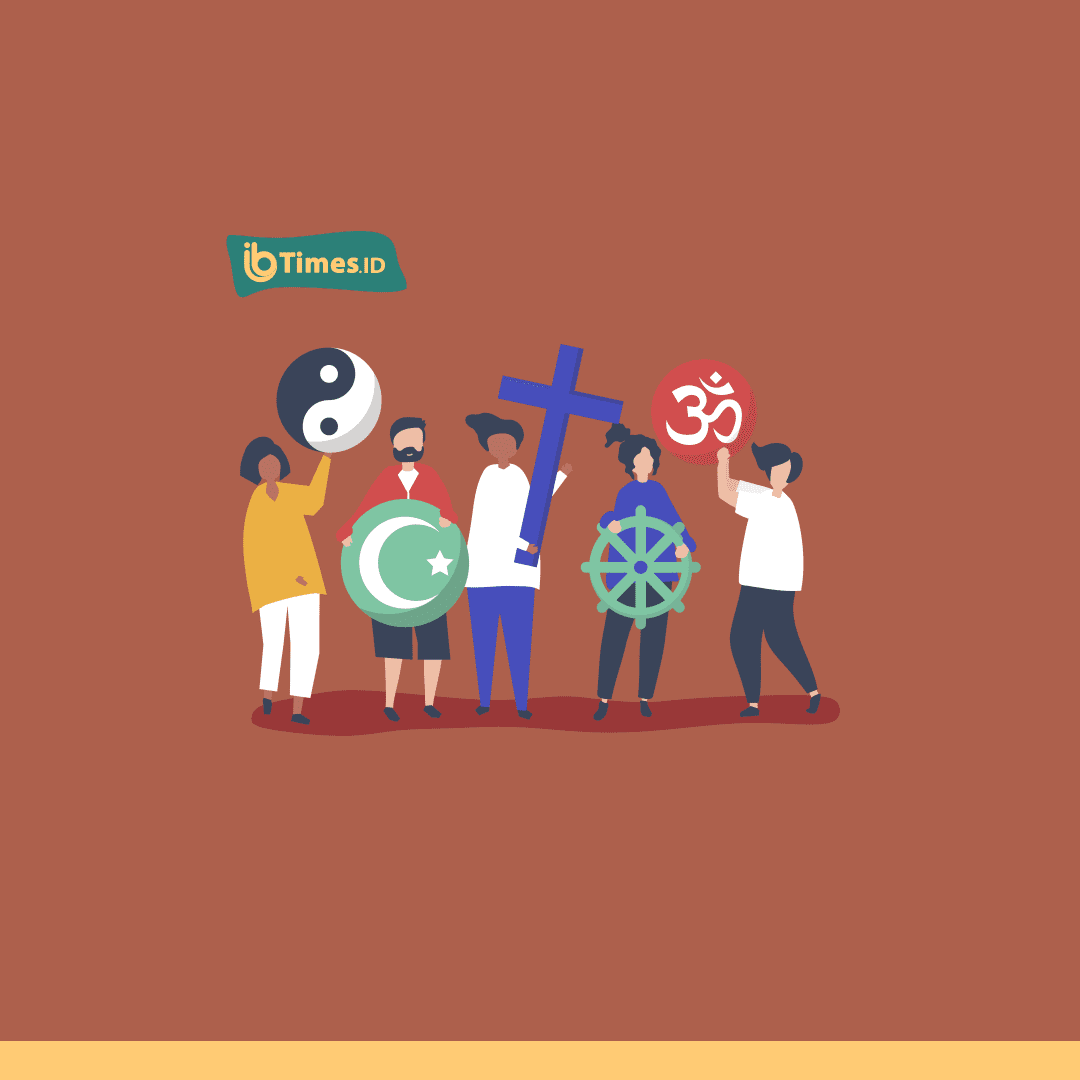Islam adalah agama yang terbuka (inklusif). Terbuka terhadap kritik, dan terbuka untuk bergaul dan bersahabat dengan (pengikut) agama lain. Penegasan dalam Al-Qur’an, “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku” merupakan cermin dari keterbukaan itu. Islam mengakui keberadaan agama lain dan antar agama yang berbeda harus saling menghormati.
Makanya, dalam Islam, dilarang untuk menjelek-jelekkan atau menghina agama lain.
Dalam Al-Qur’an disebutkan: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An’am:108)
Melihat Kebenaran dengan Perspektif yang Luas
Untuk memaknai agama secara terbuka, kita harus melihat kebenaran dalam perspektif yang luas. Dalam agama (Islam), ada dua cara memperoleh kebenaran, yakni dengan rasio (akal) dan melalui wahyu Tuhan (Al-Qur’an). Kebenaran yang diperoleh melalui rasio sifatnya relatif. Sementara kebenaran wahyu bersifat mutlak.
Namun, harus pula digarisbawahi bahwa, meskipun kebenaran wahyu itu mutlak, tapi interpretasi terhadap wahyu bersifat relatif, karena kegiatan interpretasi sudah melibatkan rasio (akal) yang menjadikan kebenaran wahyu menjadi relatif. Di sini perlu ditegaskan bahwa kebenaran wahyu (ayat) Tuhan kemutlakannya hanya pada tataran teks.
Sementara itu, kebenaran teks wahyu harus “berbunyi” dan bahkan harus berfungsi. Bagaimana agar wahyu Tuhan bisa “berbunyi” dan berfungsi membutuhkan interaksi dengan manusia, yakni dengan dibaca, dipahami, dan diamalkan. Manusia dapat berinteraksi dengan wahyu Tuhan (Al-Qur’an) melalui kaidah-kaidah yang telah disepakati.
Kaidah ilmu tajwid untuk membaca, kaidah ilmu tafsir untuk memahami, serta kaidah syariat, akhlak, dan etika sosial untuk mengamalkannya. Tapi, meskipun terdapat kaidah-kaidah, tidak menutup kemungkinan bacaan, pemahaman, dan amalan manusia terhadap wahyu Tuhan berbeda antara satu dengan yang lain.
Dalam bacaan misalnya, meskipun ada kaidah ilmu tajwid, tidak menutup kemungkinan berbeda satu sama lain. Adanya istilah “tujuh bacaan” (al-qiraat as-sab’ah) menunjukkan kebenaran ini. Kalau membaca saja sudah berbeda, apalagi memahami dan mengamalkannya, tentu akan lebih beragam lagi searah dengan keberagaman kreatifitas manusia.
Tidak Semuanya Benar
Keberagaman itu, apakah semuanya benar? Jawabannya tidak mutlak, bisa ya, bisa juga tidak. Kebenaran yang berasal dari hasil pemahaman manusia itu relatif. Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Yang jelas-jelas salah adalah ketika yang satu menyalahkan yang lain, atau saling menyalahkan dengan tanpa argumentasi yang akurat.
Menyalahkan (menuduh) tanpa argumentasi dalam term Al-Qur’an disebut dzan (sakwasangka). Allah melarang orang-orang yang beriman untuk bersakwasangka, karena sebagian sakwasangka adalah dosa (QS;49:12). Sebaliknya, menganggap diri paling benar atau paling suci juga tidak diperkenankan. QS. An-Najm (53:32) di antaranya mengisyaratkan akan hal ini.
Terhadap orang yang menganggap diri paling benar dan cenderung menyalahkan orang lain, Nabi Muhammad SAW pernah menyindir secara tajam melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Apabila kamu mendengar seseorang mengatakan: Manusia telah rusak atau binasa, maka orang itulah yang paling rusak di antara mereka.”
Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Namun demikian, bukan berarti kita harus berdiam diri terhadap (kemungkinan) kesalahan orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Kita harus tetap kritis, melakukan koreksi terhadap segala bentuk patologi sosial. Dalam doktrin Islam, sikap kritis dan korektif ini diekspresikan melalui gerakan dakwah “amar ma’ruf nahi munkar.”
Dakwah dan saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Bagi umat Islam, hal ini merupakan kewajiban. Tapi tentu saja dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah dan penuh kebijaksanaan, dan bila perlu dengan argumentasi secara baik dan benar (akurat), tanpa ada perasaan benar sendiri (memonopoli kebenaran), tanpa sikap menghakimi dan menuduh orang lain tersesat, apalagi menuduh kafir.
Dan, yang lebih penting, dalam berdakwah tidak ada paksaan untuk mengikuti apa yang kita dakwahkan. Sasaran utamanya harus diarahkan terlebih dahulu pada diri sendiri dengan keikhlasan dan kejujuran. Keikhlasan dan kejujuran pada diri sendiri akan berdampak pada sikap ikhlas dan jujur pula ketika melihat kebenaran yang ada dan diekspresikan orang lain.
Semua Agama itu Menyerukan Kebaikan
Agama, apapun namanya, bertujuan untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan hidup baik di dunia (kini) maupun di akhirat (kelak). Islam misalnya, ia hadir di pentas sejarah kemanusiaan untuk membawa rahmat bagi kesemestaan (rahmatan lil-‘alamin).
Namun, subyektivitas manusia (pemeluk agama) acap kali membuat agama menjadi destruktif. Beberapa kasus kerusuhan yang terjadi di tanah air dan pelosok dunia tak jarang dipicu karena sentimen agama. Agama dijadikan “alat” untuk membenci atau bahkan untuk melawan golongan lain yang tidak seagama. Ibarat pisau bermata dua, agama bisa berfungsi ganda, satu sisi bisa menumbuhkan solidaritas dan integrasi, tapi pada sisi lain juga potensial melahirkan disintegrasi.
Nah, setelah sedikit “berdiskusi” tentang makna kebenaran –khususnya dalam Islam, dan saya yakin, kebenaran menurut agama lain pun tidak jauh berbeda, untuk tidak dikatakan sama persis.
Maka, ada baiknya bagi umat beragama, terutama para tokoh agamawan, untuk melihat kebenaran dan ekspresi keberagamaan bukan semata dari standar pemahaman pribadinya sebagai hasil produk interpretasi dari kitab suci yang diyakini kebenarannya.
Karena ekspresi kebenaran khususnya dalam sikap keberagamaan kiranya berwajah plural dan sangat inklusif. Kesadaran akan hal ini kiranya akan menumbuhkan toleransi yang lebih arif dalam melihat dan merespon ekspresi kebenaran (keberagamaan) orang lain, apapun “nama” agama yang dipeluknya.
Menganggap Kebenaran Agama itu Monolitik, Bahaya!
Dari sejarah, kita dapat berkaca, akibat ekspresi keberagamaan yang monolitik dan eksklusif, antar sesama pemeluk Islam pun tak jarang terjadi konflik dan benturan kepentingan, apalagi dengan pemeluk agama lain. Menyebut sekedar contoh, dalam sejarah Islam, mengapa Al-Hallaj, Syeh Siti Jenar dan mungkin banyak lagi yang lain menemui ajal di ujung pedang umat Islam sendiri, semua itu akibat dari sikap keberagamaan yang tidak toleran — untuk tidak dikatakan picik.
Ekspresi kebenaran dalam beragama yang ditampilkan secara monolitik dan eksklusif harus kita waspadai. Karena, sekali lagi, sikap yang demikian itu tidak menutup kemungkinan terjadi ketegangan atau bahkan tabrakan antara satu “kebenaran” dengan “kebenaran” yang lain. Jika hal ini terjadi, kemungkinan konflik dan perselisihan atau bahkan pertikaian (bersenjata) antar sesama pemeluk agama terasa menjadi sulit untuk dihindarkan. Kewajiban kita tentu menghindarinya semaksimal mungkin, melalui upaya pemahaman agama secara komprehensif, dan dengan ekspresi keberagamaan yang inklusif, ikhlas, adil, dan toleran.