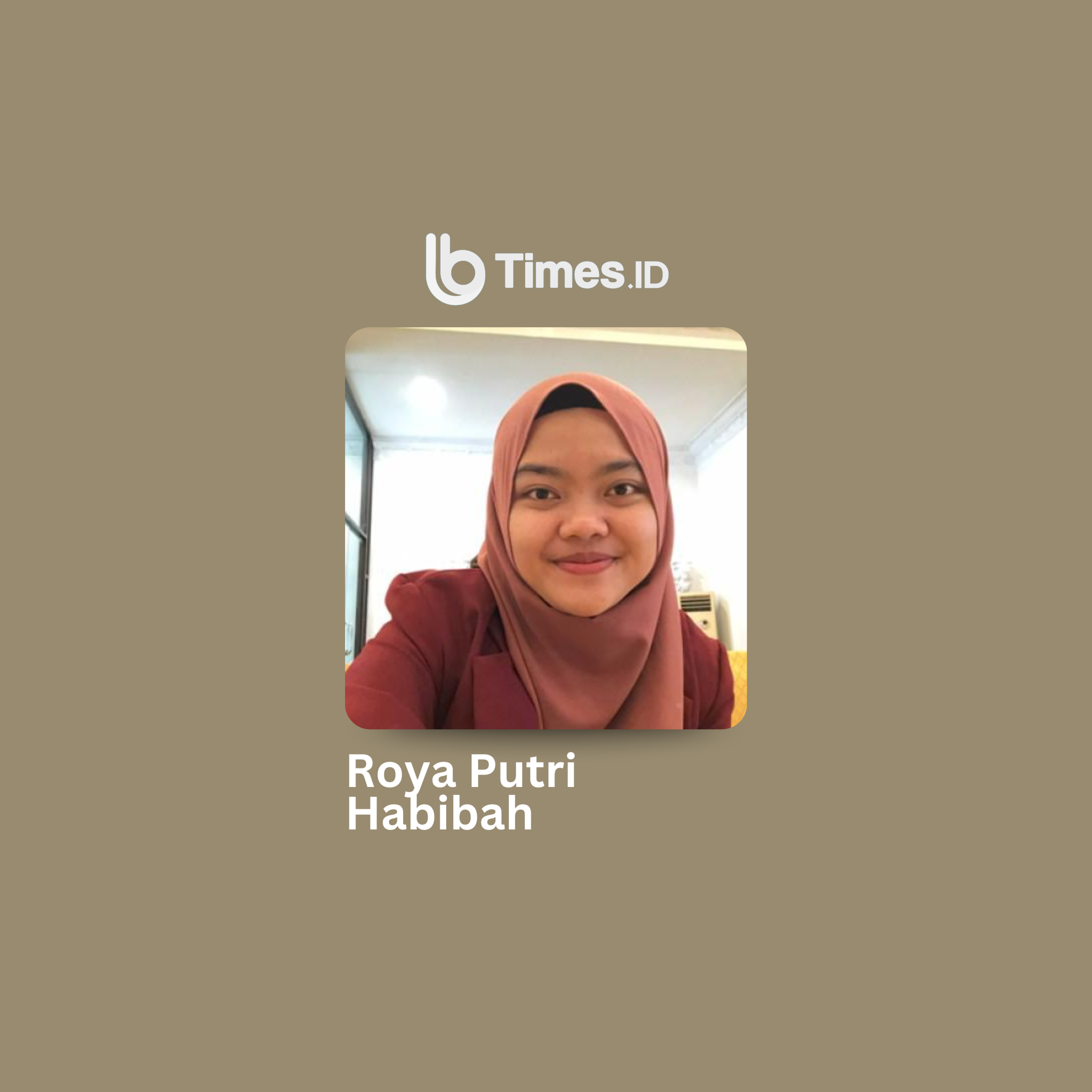Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan lebih dari ratusan korban jiwa meninggal, hilang, dan mengungsi. Tidak hanya itu, ribuan rumah rusak dan berbagai jalur vital terputus. Ini bukan hanya sekadar bencana alam, tapi wajah dari buruknya tata kelola.
Pertanyaannya sederhana, mengapa bencana ini begitu parah padahal sudah ada teknologi citra pemantauan, imbauan dari saintis iklim, dan juga histori bencana sebelumnya?. Ini bukan lagi karena kekurangan pengetahuan atau lemahnya teknologi, melainkan karena lemahnya implementasi, pengawasan, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Cuaca ekstrem, secara meteorologis, memang menjadi pemicu bencana tersebut. Namun, yang harus sama-sama kita sadari adalah kerentanan di darat memperparah risiko. Deforestasi terhadap jenggala (hutan), pelanggaran tata ruang, dan pembangunan di bantaran sungai membuat daya serap tanah turun drastis. Ketika hutan hilang, air hujan tidak lagi meresap, melainkan meluncur deras membawa lumpur dan kayu, menghancurkan yang ada di depannya. Inilah risiko yang sering diabaikan.
Deforestasi memperburuk risiko banjir bandang. Sebuah studi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Universitas Diponegoro pada tahun 2019 menjelaskan bahwa penurunan luas tutupan hutan sebesar 10% dari kondisi existing menyebabkan 58% air hujan yang jatuh menjadi limpasan permukaan.
Ketika tutupan hutan hilang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga limpasan permukaan meningkat. Air yang seharusnya meresap ke dalam tanah berubah menjadi aliran deras yang membawa sedimen dan kayu, menciptakan banjir bandang yang mematikan. Ini bukan sekadar fakta, ini adalah peringatan keras bahwa setiap hektar hutan yang hilang mendekatkan kita pada bencana.
Ironisnya, sebenarnya teknologi untuk memantau deforestasi ini sudah ada dan mudah diakses. Platform seperti Google Earth Engine dan Global Forest Watch (GFW) menyediakan dashboard yang bisa menunjukkan hilangnya vegetasi dalam kurun waktu mingguan. Semua akses itu bisa dikatakan gratis dan mampu mendeteksi perubahan tutupan hutan hampir secara real-time.
Ditambah semua teknologi ini masih gagal mencegah bencana separah ini. Mengapa? Karena data hanya berhenti di layar. Tidak efektif diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpikah pada lingkungan. Semua bisa dilihat dan dimonitoring, tapi deforestasi ‘ilegal’ tetap terus berjalan. Kita seperti memiliki kamera CCTV canggih, tetapi membiarkan pencuri masuk tanpa pengawasan.
Praktik Baik Citra
Praktik baik penggunaan teknologi citra bisa dilihat di Meksiko, teknologi ini telah digunakan untuk memantau deforestasi akibat meningkatnya permintaan untuk alpukat dari Amerika. Munculah sistem pemantauan dan peringatan deforestasi membongkar penggundulan hutan akibat perluasan kebun Alpukat di Michoacán.
Pengembang sistem tersebut membuat rekaman visual yang memperlihatkan perubahan cepat dari hutan menjadi kebun komoditas dan memastikan publik –terutama pelanggan alpukat serta lembaga sertifikasi hijau ikut memantau hal tersebut. Tentunya, ini memicu publik dan mendorong perubahan kebijakan.
Bagaimana cara kerja pemantauan ini? Sentinel-2 dengan resolusi 10 meter dan Landsat dengan resolusi 30 meter menyediakan citra multispectral yang memungkinkan perhitungan indeks vegetasi (NDVI). Ketika indeks ini turun drastis, artinya tutupan vegetasi hilang yang merepresentasikan tanah. Dengan algoritma sederhana, kita bisa mendeteksi pembukaan lahan dalam hitungan hari. Jika pemerintah mengintegrasikan sistem ini dengan kebijakan, maka akan dengan mudah menjaga hutan.
Kemauan Politik dan Kebijakan Publik
Indonesia sangat bisa meniru hal ini dan kemudian menindak tegas deforestasi dengan bukti citra satelit. Teknologi sudah tersedia seperti SIGAP KLHK atau SIMONTANA, tapi yang dibutuhkan ialah komitmen kepada publik, terutama dalam menindak tegas setiap pelanggaran.
Teknologi saja tidak cukup, perlu ada kemauan politik, tanpanya data tersebut tidak akan berujung pada tindakan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang masih lemah, koordinasi antar instansi sering berantakan, dan respons darurat terlambat. Akibatnya, bencana muncul dan korban jiwa melonjak, baik korban manusia maupun hewan penghuni habitat hutan, kerugian ekonomi membengkak, dan parahnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah runtuh.
Di era digital, ketika permasalahan mudah viral, pemerintah tidak bisa lagi bekerja di ruang tertutup. Transparansi harus menjadi fondasi. Publik berhak atas akses ke peta deforestasi untuk monitoring kebijakan. Bayangkan saja jika warga, LSM, dan media lokal bisa aktif memantau hilangnya tutupan hutan secara real-time. Setiap pembukaan lahan akan menjadi sorotan publik sudah semestinya menciptakan tekanan sosial yang memaksa tindakan cepat. Hal ini bisa menjadi langkah awal pencegahan bencana.
Peran masyarakat di sini sangat penting. Ironis memang, karena tren kebijakan publik dewasa ini seringkali baru ditindaklanjuti setelah viral, utamanya setelah adanya tekanan sosial dari masyarakat. Ketika publik memiliki akses data, mereka bisa mengawasi, melaporkan dan menekan pemerintah untuk tegas pada pelanggaran. Ini bukan lagi sekadar tentang teknologi, tetapi membangun kepercayaan dan akuntabilitas.
Bencana bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga cermin tata kelola yang buruk. Peran Pemerintah dalam hal ini sangat krusial sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah tidak boleh hanya sekadar menjadikan teknologi sebagai pajangan atau hal memukau di layar untuk dipamerkan.
Data harus diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan nyata. Integrasi pemantauan satelit dengan sistem peringatan dan penegakan hukum ialah langkah yang wajib dilakukan sekarang. Karena perubahan iklim sudah di depan mata.
Perubahan iklim ialah amplifier bencana, meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem dan ketidakpastian cuaca. Perlu sekiranya pengembangan teknologi citra ini menjadi alat yang bisa membantu pemerintah untuk memitigasi perubahan iklim dan mencegah bencana yang lebih parah. Tapi yang lebih penting, ialah kemauan politik untuk melahirkan kebijakan publik, sehingga alam dan korban tidak lagi berjatuhan.
Editor : Ikrima