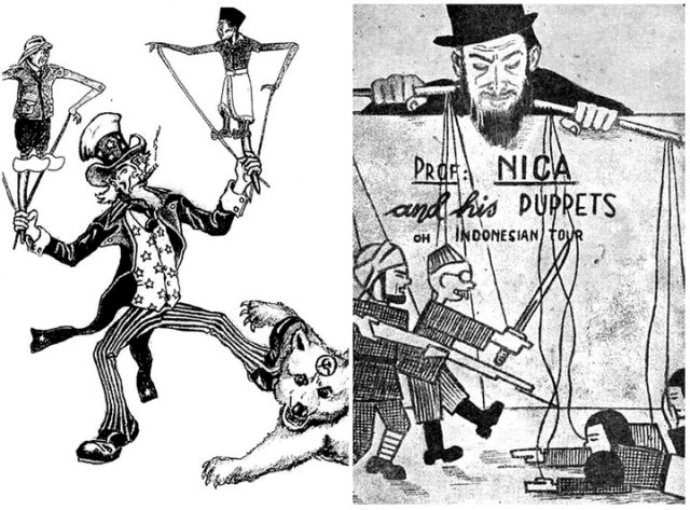Oleh: Muhamad Rofiq*
Tidak seperti dekolonisasi sistem politik yang sudah dianggap selesai dengan dicapainya kemerdekaan negara-negara terjajah pada abad dua puluh, usaha untuk melakukan dekolonisasi pengetahuan masih terus berlangsung.
Saat ini dekolonisasi tengah menjadi tren dalam semua disiplin ilmu modern, mulai dari antropologi, sosiologi, filsafat, sejarah, bahasa, pendidikan, agama, museumologi, geografi; termasuk ilmu eksakta, seperti ilmu komputer. Sebagian dari disiplin tersebut baru akan memulai proses dekolonisasi. Tetapi beberapa di antaranya, seperti antropologi, sudah masuk ke tahap lanjutan, atau istilah beken-nya sudah memiliki dekolonial versi 2.0.
Di samping itu, gerakan dekolonisasi ini bukan lagi monopoli etnis tertentu. Pada awalnya memang dekolonisasi dimulai oleh para sarjana non-white (non kulit putih), seperti Franz Fanon (Afrika), Edward Said (Arab), Gayatri Spivak (India), Linda Smith (Maori), dan nama-nama lainnya.
Tapi hari ini sudah banyak sarjana kulit putih yang ikut menggaungkan gerakan dekolonisasi pengetahuan ini. Mereka ikut terlibat dalam melakukan otokritik dan dekonstruksi terhadap bangunan keilmuan yang diciptakan oleh para pendahulu mereka di zaman kolonial.
Bidang studi agama di Barat juga tengah mengalami kebangkitan tren ini. Sampai hari ini telah banyak buku dan artikel-artikel ilmiah yang ditulis untuk mengkritik asumsi, teori, dan metode penelitian ilmiah dalam bidang ini. Dekolonisasi dalam bidang studi agama berangkat dari satu kesadaran bahwa studi agama (religious study) yang lahir pada periode kebangkitan bangsa-bangsa Eropa dan zaman kolonialisme juga membawa banyak bagasi kolonial. Dari aspek teori misalnya, banyak ide-ide yang diformulasikan untuk menjustifikasi pandangan rasis bangsa Eropa kulit putih kepada bangsa non-Eropa.
Edward Burnet Tylor (w. 1917) misalnya yang menulis tentang asal-usul agama, mengemukakan teori evolusi budaya di mana menurutnya masyarakat berkembang dari tingkatan savage, menuju barbaric, dan berhenti di tingkatan civilization. Ia meletakkan masyarakat bangsa Eropa, khususnya Inggris, di puncak evolusi budaya manusia.
Menurut Tylor, agama juga berkembang dari wataknya yang paling dasar, yaitu animisme (agama yang menurutnya masih dianut oleh suku primitif) untuk kemudian berevolusi menjadi agama monoteis.
Emile Durkheim (d. 1917), di samping pendekatan fungsionalisnya yang terkenal, juga masih berpihak pada evolusi sosial. Ia percaya bahwa agama manusia bermula dari tahapan yang paling sederhana (yaitu totemisme dalam kasus suku Aborigin) dan akan bertransformasi menjadi monoteisme.
Kedua orang sarjana Eropa ini, bersama dengan ilmuwan sosial lainnya, sekalipun mengemukakan teori dan pendekatan berbeda, memiliki asumsi yang sama, yaitu bahwa budaya berkembang dari bentuk yang belum sempurna menuju ke arah yang beradab. Asumsi inilah yang disebut dengan the notion of historical progress atau pandangan bahwa sejarah manusia terus maju ke depan. Asumsi ini selalu menempatkan bangsa non-Eropa di bagian bawah proses evolusi itu.
Kecendrungan kolonial dalam studi agama bukan hanya fenomena masa lalu. Sampai hari ini kecendrungan demikian masih terus bertahan. Para pemikir dekolonial misalnya banyak mengkritik buku Nine Theories of Religion, karya Daniel Pals. Ini adalah buku standar yang sangat terkenal dan digunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu agama untuk tingkat undergraduate di Amerika. Di Indonesia buku ini bahkan digunakan untuk paska sarjana untuk mata kuliah pendekatan-pendekatan dalam studi agama.
Buku ini memuat sembilan teori berpengaruh tentang agama dalam kajian Barat. Buku ini dikritik karena masih mengajarkan pandangan dan asumsi yang rasis dan merendahkan kepada para mahasiswa. Di samping itu, buku ini juga hanya memuat pandangan para sarjana dari bangsa kulit putih yang semuanya adalah laki-laki.
Buku ini dianggap hanya akan memperkuat sense of white superiority (perasaan superioritas kulit putih) di kalangan para pelajar dan mengafirmasi struktur ketidakadilan gender (structures of gender inequality).
Isu dan Tokoh
Pertanyaan selanjutnya yang mengemuka adalah bagaimana dekolonisasi dilakukan dalam bidang studi agama? Sejauh ini, banyak tokoh dan sarjana yang telah mencoba mengajukan gagasan. Nama-nama yang paling terkemuka antara lain adalah Talal Asad, Richard King, Malory Nye, Ananda Abeysekara, Timothy Fitzgerald, Tomoko Masuzawa, dan Daniel Dubuisson. Tulisan ini akan menggambarkan pemikiran dari dua nama yang disebutkan terakhir.
Tomoko Masuzawa adalah profesor sejarah dan perbandingan sastra di Universitas Michigan, Amerika Serikat. Secara etnis, seperti bisa dilihat dari namanya, ia berasal Jepang. Ia menulis gagasannya tentang dekolonisasi bidang agama dalam bukunya yang berjudul The Invention of World Religions. Buku ini berupaya menjelaskan sejarah kritis munculnya bidang studi atau sains agama.
Secara khusus, ia mengkritik konsep “agama-agama dunia (world religions)” yang menjadi mata kuliah dasar dalam institusi pendidikan di Amerika Serikat. Dalam konsep ini ada sepuluh agama yang disebut sebagai agama dunia, yaitu: Kristen, Buddhisme, Islam, Hinduisme, Yahudi, Konfucianism, Taoism, Shinto, Zoroastrianisme, Jainisme, and Sikhisme.
Dengan lahirnya konsep agama dunia ini, menurut Masuzawa, diskursus tentang agama dalam akademia di Barat sekilas tampak egalitarian dan inklusif (sebelumnya, dalam kajian akademik Barat, agama hanya dibagi menjadi empat, yaitu Kristen, Yahudi, Islam, dan pagan). Tetapi sesungguhnya ia masih menyimpan discourse of othering (wacana yang menganggap selain diri sendiri sebagai orang lain).
Ia berpendapat bahwa konsep agama dunia telah memungkinkan terus diproduksinya pandangan dunia yang membawa bias Eurocentric. Diskursus yang diajarkan dan dikembangkan dalam konsep agama dunia juga menurutnya secara implisit telah mempromosikan universalisme Kristen dalam bentuk yang baru.
Masuzawa menemukan genealogi konsep agama dunia pada studi teks (filologi) dan perbandingan teologi (comparative theology) di Eropa. Ia menyatakan bahwa ahli filologi pada abad ke-19 menemukan dua kategori asal bahasa, yaitu semitik dan Arya (Indo-Eropa). Bagi para filolog di era ini, bahasa semitik adalah bahasa yang tidak sempurna dan karena itu memiliki keterbatasan dengan ras.
Masuzawa mempresentasikan dua studi kasus tentang apa yang disebut agama dunia saat ini, yaitu Buddhism dan Islam. Buddhisme dimasukkan dalam kategori agama dunia melalui kerja para filolog yang menganalisis asal usul bahasa Eropa.
Mereka menemukan bahwa bahasa-bahasa Indo-European berasal dari India yang kemudian menyebar ke Asia dan Eropa. Jadi Buddhisme yang lahir di India tersebut dimasukkan sebagai agama dunia karena dianggap sebagai asal usul (precursor) dari peradaban Barat.
Selain itu, Buddhisme juga dianggap agama dunia karena dua hal lainnya, yaitu: karena ia memiliki kitab suci (teks); dan kedua karena Buddhisme dianggap sebagai bentuk reformasi dari agama Hindu. Budha menolak ajaran dalam kitab Vedha. Dua kriteria tersebut, yakni memiliki kitab suci dan lahir sebagai bentuk reformasi, adalah dua tipikal cara pandang khas Kristen (khususnya Protestan) mengenai agama.
Tokoh kedua setelah Masuzawa adalah Daniel Dubuisson. Ia adalah sarjana Perancis yang menulis buku berjudul The Western Construction of Religion. Kritik Dubuisson terkait disiplin religious study jauh lebih radikal dari Masuzawa. Ia tidak hanya mengkritik konsep “agama dunia” versi akademisi Barat, tetapi konsep “agama (religion)” itu sendiri.
Dubuisson beragumen bahwa studi tentang agama muncul pada momen tertentu dalam perkembangan sejarah peradaban Barat. Studi agama dengan kata lain adalah produk sejarah Barat yang membawa bias nilai-nilai Barat. Dengan memahami genealogi konsep agama yang berasal dari Barat, dengan demikian, menurutnya kita akan memahami bahwa dunia non-Barat sebenarnya dipaksa mengikuti istilah dan konsep pokok Barat.
Menurut Dubuisson, Barat yang Kristen telah mengembangkan diskursus tentang agama yang bersifat global dengan dipengaruhi oleh sejarah spesifiknya sendiri (its own idiosyncratic history). Menurutnya, agama, sebagai konstruksi Barat, bergantung pada sistem ide dari agama Kristen yang berpijak pada prinsip antitesis.
Dengan prinsip antitesis ini, Barat membentuk dirinya untuk melawan apa yang ada di luarnya. Jadi prinsip dikotomi digunakan untuk dua hal, yaitu mendefinisikan diri sendiri dan mendefinisikan orang lain.
Prinsip dikotomi khas Kristen yang kemudian diuniversalisasi sebagai bagian dari konsep tentang “agama” tersebut menurut Dubuisson adalah: “agama yang benar vs agama yang salah; ortodoksi vs ajaran sesat; jiwa vs tubuh; ketuhanan vs kemanusiaan; sihir vs agama; nalar vs wahyu; pengetahuan vs iman; teologi vs antropologi; orang beriman vs ateis; pendeta vs kelompok awam; sakral vs profan atau agamis vs profan; monoteisme vs politeisme; kepausan vs kerajaan; agama vs sains, dan seterusnya”.
Prinsip antitesis seperti ini, kata Dubuisson, tidak pernah ada sebagai konsep dalam kebudayaan lainnya. Jika kemudian pada periode modern semua kebudayaan mengenal konsep ini, berarti hal tersebut merupakan manifestasi infiltrasi dan pengaruh konsep Kristen.
Berangkat dari hal tersebut, Dubuisson mengajak para akademisi di Barat untuk meninggalkan konsep agama dan apa saja yang terkait dengannya yang sekali lagi sangat bias Kristen dan Eropa. Sebagai alternatif, ia mengajukan konsep yang menurutnya lebih netral dan lebih mampu mengakomodir keragamaan pandangan dunia tanpa dipengaruhi hegemoni Kristen dan Eropa.
Alternatif yang ia maksud adalah konsep kosmografi. Konsep ini menurutnya tidak bersifat universal seperti halnya konsep agama. Jadi setiap kebudayaan memiliki kosmografinya sendiri-sendiri, yang berbeda dengan kosmografi kebudayaan lainnya.
* Penulis adalah alumni PCIM Mesir dan Anggota PCIM Amerika Serikat