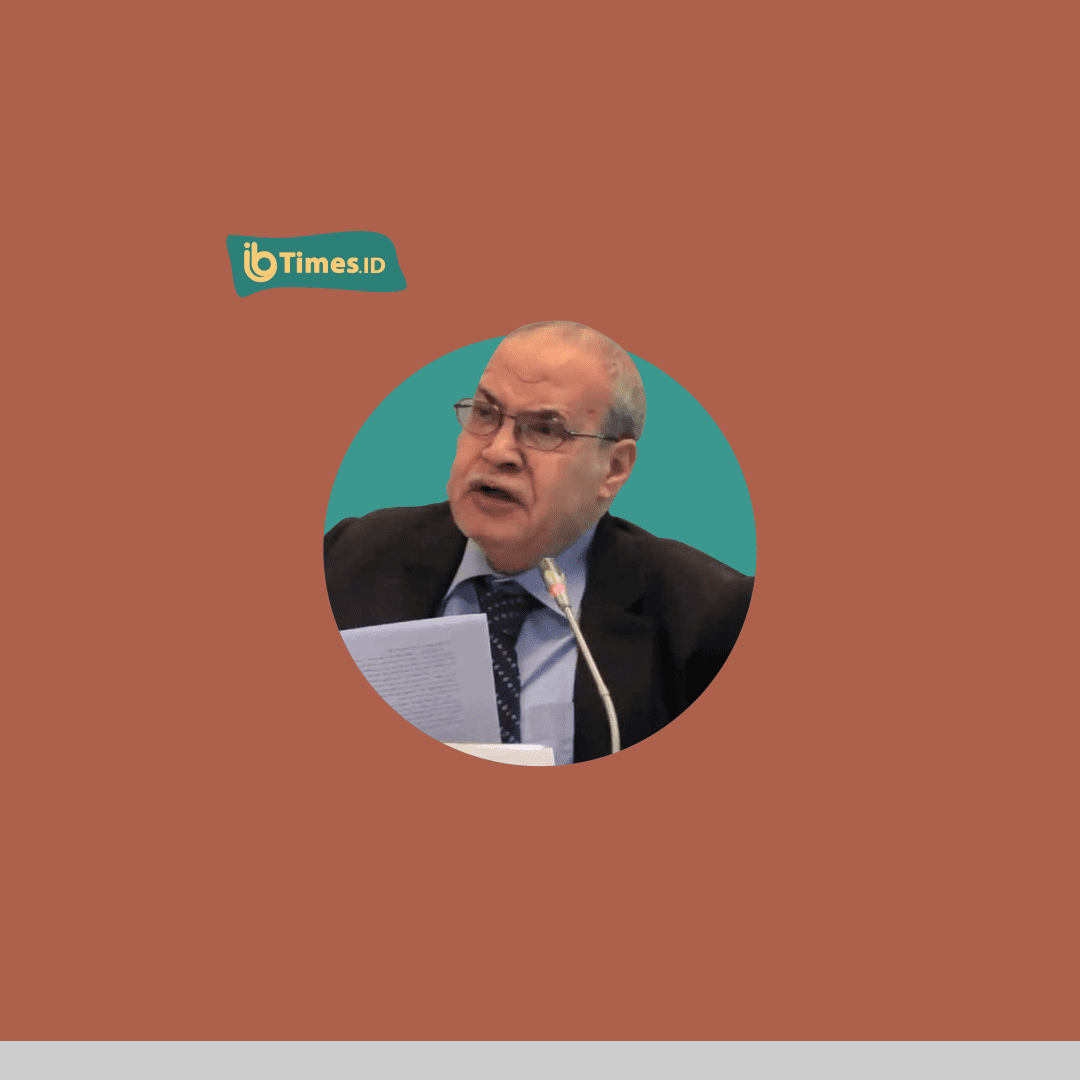Seorang pembaharu pemikiran Islam sekaligus profesor filsafat di Universitas Kairo, Mesir. Hassan Hanafi berupaya untuk mentransformasikan cara pandang terhadap zat dan sifat Tuhan. Sebenarnya hal itu sudah dilakukan oleh kaum Muktazilah dan kaum sufi. Konsepnya tentang tauhid yang “membumi” juga telah disampaikan Murtadha Muthahhari (1920-1979 M). Namun kelebihan Hanafi terletak pada kemampuannya untuk mengemas konsep-konsep yang ada menjadi lebih utuh, jelas, dan segar sehingga terasa baru.
Dalam buku Filsafat Islam karya Khudori Soleh dijelaskan, menurut Hanafi, konsep atau teks tentang zat dan sifat-sifat Tuhan sesungguhnya tidak menunjuk pada kemahaan dan kesucian Tuhan seperti yang ditafsirkan para teolog. Tuhan tidak butuh pensucian manusia, karena tanpa yang lain pun Tuhan tetap Tuhan yang Mahasuci dengan segala sifat kesempurnaan-Nya. Menurut pria kelahiran 13 Februari 1935 itu, semua deskripsi Tuhan dan sifat-sifat-Nya yang ada pada Al-Qur’an maupun Sunnah lebih mengarah kepada pembentukan manusia yang baik, ideal, dan akhirnya menjadi insan kamil.
Penafsiran Hanafi bahwa sifat Tuhan justru menuntun manusia menjadi makhluk ideal tampaknya tak lepas dari pengaruh pemikiran kaum Muktazilah. Salah satu aliran teologis Islam yang muncul di Kota Basrah, Irak, pada abad ke-2 M. Kaum Muktazilah melihat bahwa nama atau sifat Allah SWT seperti Asmaul Husna sebenarnya adalah pelajaran bagaimana manusia harus bertindak dan bersikap. Artinya, sifat-sifat itu mesti dimiliki dan dilakukan oleh seorang Muslim. Jadi, bukan penjelasan tentang eksistensi Tuhan, apalagi tentang kemahakuasaan-Nya.
Deskripsi Tuhan tentang zat-Nya sendiri memberi pelajaran kepada manusia tentang kesadaran akan dirinya sendiri, yang secara rasional dapat diketahui melalui perasaan diri. Dengan demikian, apa yang dimaksud nama dan sifat Tuhan justru melahirkan sebuah kesadaran baru. Bahwa sifat Tuhan bisa saja menjadi bagian dari manusia, jika ia berusaha untuk memahami serta bertindak konstruktif bagi kehidupannya. Niscaya sifat-sifat tersebut bersatu dalam raga. Menjadikan ia sebagai manusia sempurna. Dari hal tersebut Hanafi berusaha untuk mengubah terminologi keagamaan – nama dan sifat Tuhan–yang sebelumnya bersifat metafisik menjadi realitas empirik.
Tafsir Sifat Tuhan yang Enam
Lebih lanjut, Hassan Hanafi coba mengurai penafsirannya terhadap sifat-sifat Tuhan yang enam: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lilkhawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah.
Pertama, wujud menurut Hassan Hanafi tidak menjelaskan wujud Tuhan karena Tuhan tidak memerlukan pengakuan. Tanpa manusia, Tuhan tetap ada (wujud). Wujud di sini artinya tuntutan terhadap manusia bahwa mereka mesti mampu menunjukkan esksistensi diri. Seperti yang dikatakan cendekiawan muslim, Muhammad Iqbal dalam syairnya, kematian bukanlah ketiadaan nyawa, kematian adalah ketidakmampuan untuk menunjukkan eksistensi diri.
Kedua, qidam (dahulu) berarti pengalaman masa lalu yang mengacu pada akar-akar keberadaan manusia di dalam sejarah. Qidam menjadi modal bagi manusia untuk belajar serta memperoleh pengalaman. Teramasuk dari kejadian masa lalu, agar menjadi pelajaran di masa depan, agar tak lagi terjatuh pada kesesatan, taklid, dan kesalahan.
Ketiga, baqa (kekal) yang artinya menuntut manusia agar tidak cepat rusak atau fana. Hal itu dilakukan dengan cara memperbanyak melakukan hal-hal konstruktif baik dalam perbuatan maupun pemikiran. Serta menjauhi tindakan yang bisa mempercepat kerusakan di bumi. Jelasnya, baqa dalam pandangan Hanafi merupakan ajaran pada manusia untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Agar manusia mempu meninggalkan karya-karya besar yang bersifat monumental sehingga namanya “abadi”.
Keempat, mukholafatul lilhawadisi (berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya) dan qiyamuhu binafsihi (berdiri sendiri). Keduanya menuntut bahwa manusia mampu menunjukkan eksistensi dirinya secara mandiri dan berani tampil beda. Tidak mengekor atau bertaklid pada pemikiran atau budaya orang lain. Qiyamu binafsihi deskripsi tentang titik pijak dan gerakan yang dilakukan secara terencana. Dengan penuh kesadaran untuk mencapai sebuah tujuan akhir, sesuai dengan segala potensi dan kemampuan diri.
Kelima, wahdaniyah (esa), menurut Hanafi bukan sekadar merujuk pada keesaan Tuhan atau pensucian Tuhan dari kegandaan (syirik) yang mengarah pada paham trinitas atau politeisme. Wahdaniyah merupakan pengalaman umum kemanusiaan tentang kesatuan. Yang dimaksud adalah Kesatuan tujuan, kesatuan kelas, kesatuan nasib, kesatuan tanah air, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan kemanusiaan. Berdasarkan penafsiran Hanafi terhadap sifat wahdaniyah, maka dapat disimpulkan bahwa tauhid bukan hanya konsep yang menegaskan tentang keesaan Tuhan. Tetapi lebih merupakan kesatuan pribadi manusia yang jauh dari perilaku dualistik seperti hipokrit, kemunafikan, dan oportunistik.
Tauhid berarti Masyarakat Tanpa Kelas
Penjabaran yang berbeda dari Hanafi dalam memandang nama dan sifat Tuhan di atas turut memperkaya pemikiran terutama dalam ilmu tauhid
Hanafi menilah bahwa tauhid adalah upaya pada kesatuan sosial masyarakat tanpa kelas, kaya atau miskin. Tauhid berarti kesatuan kemanusiaan tanpa diskriminasi ras, tanpa perbedaan ekonomi, tanpa perbedaan masyarakat maju dan berkembang, barat dan nonbarat.
Pada intinya, Hanafi ingin teologi yang berbicara tentang Tuhan dan “melangit” diubah lalu diturunkan menjadi teologi yang mendiskusikan tentang persoalan manusia dan “membumi”. Sehingga hal itu bisa membuat teologi menjadi “bahan bakar” untuk membangkitkan gerakan sosial dan bukan untuk aktivitas ritual semata.
Editor: Dhima Wahyu Sejati