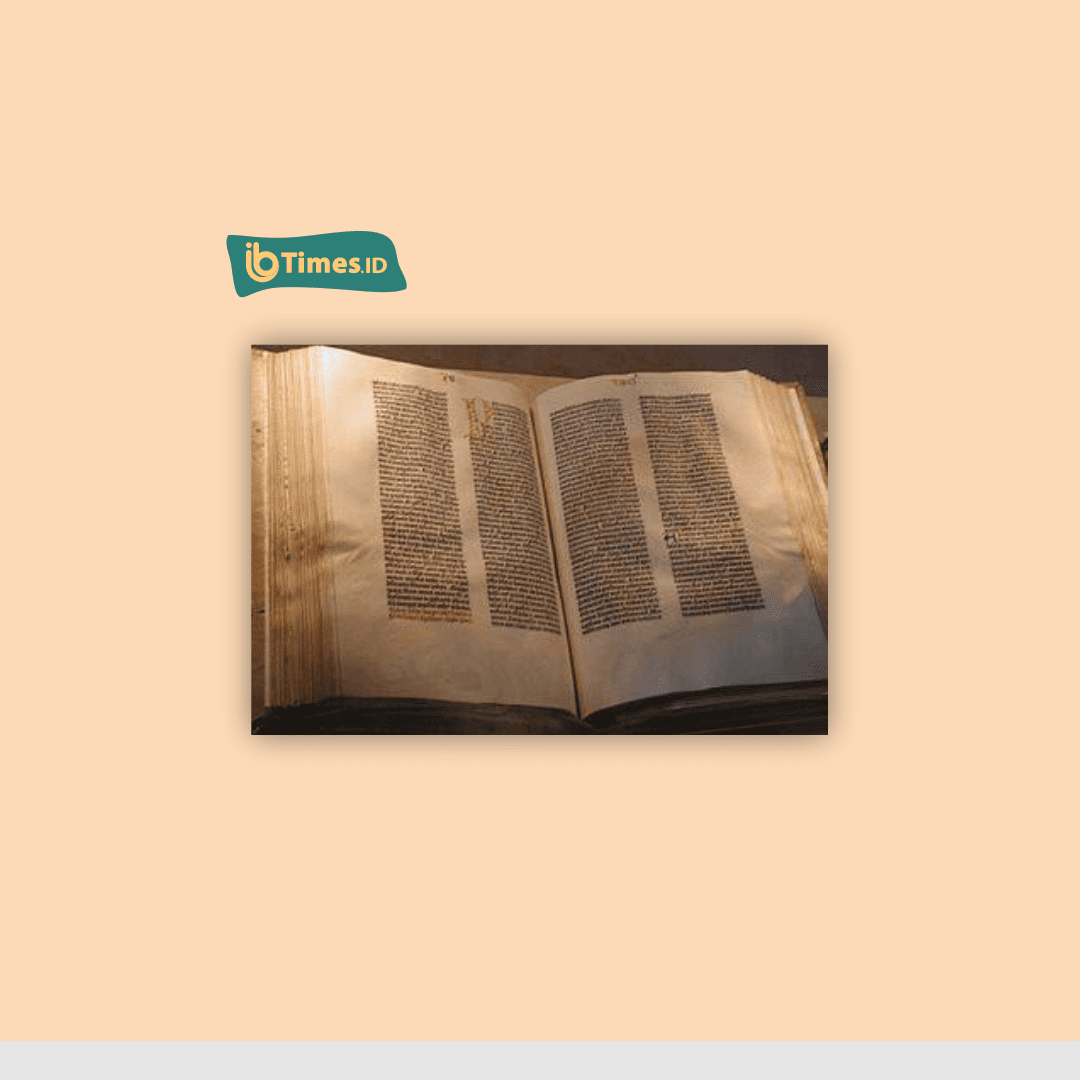Manusia yang Selalu Mencari Kebenaran
Sejarah umat manusia tidak pernah lepas dari pencariannya akan kebenaran. Bahkan hingga hari ini, mereka masih terus mengembara melanjutkan misinya-mencari kebenaran. Pada akhirnya, ada beragam jenis kebenaran yang mereka temukan. Sehingga adanya golongan-golongan dari para pencari ini menjadi suatu keniscayaan.
Bagi para filosof, kebenaran adalah sesuatu yang spekulatif. Sedangkan para saintis kebenaran ialah jika ia terukur, empiris, dan objektif. Dan bagi agamawan kebenaran sejati adalah Tuhan.
Dalam agama samawi sendiri yang ia bersifat given, maka Tuhan sebagai realitas absolut menjadi pemangku resmi kebenaran. Sedangkan utusanNya yang dikenal sebagai nabi/rasul menjadi pemegang resmi untuk menyampaikan kebenaran yang diturunkan oleh-Nya.
Lalu, hari ini ketika Nabi sudah wafat dilanjutlah oleh para mufassir untuk mencoba sebisa mungkin mendekati kebenaran yang dimaksud oleh Tuhan.
Namun, terjadi suatu ironi dalam penafsiran teks sumber Islam (Al-Qur’an dan hadis). Yakni adanya tafsir otoriter sebagaimana yang dikatakan oleh Khaled Abou El Fadl, yang mengakibatkan integritas teks-teks sumber Islam menjadi terkikis maksud dan daya gunanya. Sehingga mandek dan tidak dinamis.
Khususnya dalam masalah hukum Islam. Baginya, konsep tafsir otoriter ini mengunci maksud dari kehendak Tuhan atau kehendak teks lalu menyajikan penetapan penafsiran yang absolut dan pasti (Saifudin Qudsi, 2013:93).
Melihat hal tersebut, Abou El Fadl memberikan sebuah tawaran. Sehingga bisa terbebas dari tindakan yang sewenang-wenang dengan menggunakan metode hermeneutika.
Polemik Hermeneutika
Cara memahami teks keagamaan dengan menggunakan hermeneutika sendiri sebenarnya tidak lepas dari polemik di kalangan agamawan. Jika mengutip pendapat Romo F. Budi Hardiman, salah satu problem yang dihadapi hermeneutika ialah ketika ia mendekati teks-teks ilahiah maupun keagamaan yang lain sebagai teks biasa pada umumnya. Sehingga bertentangan bagi mereka yang mendekati teks tersebut dengan kecenderungan “apa adanya” atau “patuh begitu saja” serta menolak pendekatan rasional (F. Budi Hardiman, 2015:24).
Namun, hermeneutika sebenarnya juga tidak seberbahaya sebagaimana yang dibayangkan oleh mereka yang menolak dengan keras metode-metode diluar tradisi klasik.
Fahruddin Faiz misalnya, ia memaparkan 3 alasan yang menjadikan hermeneutika bisa menjadi alternatif atau bahkan penting digunakan dalam memahami teks keagamaan.
Pertama, para penafsir itu adalah manusia. Kedua, penafsiran itu tidak dapat lepas dari bahasa, sejarah dan tradisi. Dan ketiga, tidak ada teks yang menjadi wilayah bagi dirinya sendiri (https://tafsiralquran.id/fahruddin-faiz-dan-pentingnya-hermeneutika-al-quran/).
Bahkan jika boleh jujur, fakta hari ini teks-teks keagamaan ataupun firman ilahiah amat terbuka serta mendapatkan penafsiran yang amat beragam.
Sehingga jika boleh kita katakan bahwasannya praktik penafsiran juga merupakan bagian dari praktik hermeneutika sebagai definisi untuk memahami.
Hermeneutika Negosiatif
Hermeneutika negosiatif ini merupakan salah satu pemikiran dari Khaled Abou el Fadl. Ia merupakan cendekiawan Islam yang menjadi profesor hukum Islam di University of California Los Angeles (https://Islami.co/khaled-abou-fadl-menentang-pemahaman-hadis-yang-tak-ramah-perempuan/).
Salah satu keresahan Abou el Fadl ialah adanya otoritarianisme pembaca (penafsir). Sehingga timbul tafsir yang sifatnya otoriter. Sehingga ia tawarkan metode hermeneutika dalam membaca teks.
Dalam hermeneutika, tidak akan pernah lepas dari author, teks, dan pembaca. Author merupakan pengarang dari teks sehingga yang dapat memahami isi dari suatu teks secara pasti hanyalah sang author.
Namun, ketika teks itu terlempar ke publik, ia sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol anggapan publik atau pembaca. Teks dari author hanyalah sesuatu yang bisu dan tidak bisa menjelaskan makna.
Ia hanya bermakna apabila ada pembaca. Sehingga teks sebenarnya amat terbuka, aktif, dan dinamis untuk dipahami. Dan seorang pembaca, memiliki kemampuan untuk memaknai teks. Sehingga, teks yang awalnya bisu-bisa dipahami dan seolah-olah berbicara. Namun, pemaknaan seorang pembaca sangatlah bergantung dari pengalaman, pengetahuan, budaya, dan segala hal yang mempengaruhi dirinya. Sehingga teks yang bergulir secara bebas dihadapan publik.
Proses Negosiatif dalam Hermeneutika
Akan sangat mungkin terjebak dalam kesewenang-wenangan penafsiran. Maka perlu adanya proses negosiatif. Menurut Abou Khaled el Fadl, hermeneutika negosiatif merupakan proses pemaknaan yang seimbang.
Yaitu produksi makna dari suatu teks, haruslah ada hubungan yang seimbang antara author, teks, dan pembaca. Tidak boleh ada yang mendominasi dalam pemaknaannya (Khaled Abou el Fadl, 2014:198). Sehingga, terjadi semacam dialog antar berbagai tradisi maupun keilmuan dalam memaknai suatu teks keagamaan.
Misal dalam kata kata qawwāmūn menurut Khaled perlu dimaknai sebagai pelindung, pemelihara, penjaga, atau bahkan pelayan. Bahkan ayat ini menurutnya juga bisa berarti keadilan (Khaled Abou el Fadl, 2014:428).
Dengan begitu, pemaknaan seperti ini akan menjadi lebih relevan dan menghilangkan kesan kekerasan maupun kesewenang-wenangan terhadap perempuan. Serta menjadikan penafsiran suatu teks lebih inklusif.
Popularitas Menentukan Otoritas
Persoalan berikutnya, hari ini popularitas seseorang menentukan otoritas. Banyaknya followers maupun subscribers menjadi salah satu patokan orang tersebut memiliki kuasa untuk mempengaruhi publik.
Sehingga, kejelasan pengalaman intelektual maupun spiritual seseorang menjadi nomor yang kesekian. Hal ini juga akan berakibat pada otoritarianisme.
Pemaknaan Alternatif Kata “Khalifah”
Maka Khaled menawarkan pemaknaan khalifah (wakil Tuhan) yang lebih rasional agar tidak terjebak dan hanyut oleh para penafsir otoriter.
Dalam bukunya yang berjudul “Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women”, ia menjelaskan bahwa wakil Tuhan ini dibedakan menjadi dua. Pertama, wakil umum (common agents) dan kedua ialah wakil khusus (special group).
Para wakil umum ini menyerahkan pemaknaan atau penilaian terhadap suatu teks kepada wakil khusus. Sebab, wakil khusus dinilai memiliki kecakapan intelektual, maupun kompetensi memahami teks keagamaan. Sehingga, wakil khusus mempunyai otoritas dalam menunjukkan maksud dari suatu teks.
Jika kita lihat konteksnya di Indonesia. Maka dapat kita pahami yang bisa menjadi wakil khusus misalnya ialah Nahdhatul Ulama dengan Bahtsul Masa’ilnya. Dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya.
Editor: Rozy