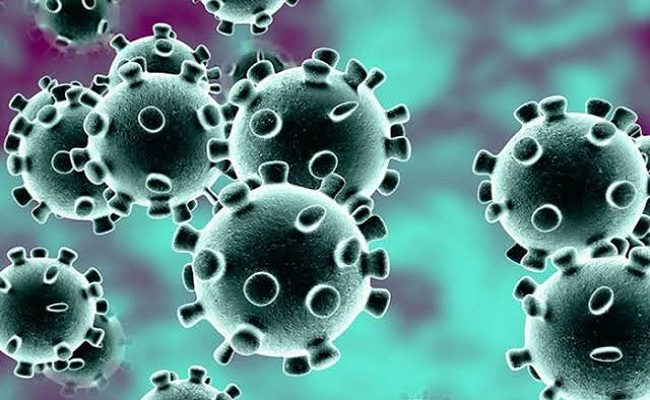Sebuah pesan WhatsApp masuk di grup keluarga dari ibunda tercinta di kampung halaman. Segera saya buka. Isinya, “Pemberitahuan bahwasanya nanti malam pada pukul 23.00 WIB, agar kita tidak ada yang keluar rumah. Jika ada yang menjemur pakaian atau makanan segera diangkat dibawa masuk, karena mulai pukul 23.00 WIB akan ada penyemprotan racun untuk virus corona dari Malaysia dan Singapura melalui udara. Bila besok pagi hujan, jangan keluar rumah dulu sampai hujan berhenti. Mohon beritahukan kepada saudara, sahabat, atau tetangga bapak ibu sekalian. Terima kasih (maaf hanya meneruskan pemberitauan saja.”
Tak berapa lama, adik saya yang mahasiswa semester akhir segera bertanya, “Informasi ini benar tidak?” Setelah beberapa kali, anggota grup ini mulai paham betapa pentingnya sebuah verifikasi terhadap suatu informasi. Tak butuh waktu lama, saya berusaha menelusuri sumber dan menemukan klarifikasi tentang ketidakbenaran berita ini. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jenderal Tan Sri Dato’ Sri Hj Affendi bin Buang TUDM membantah informasi tersebut. Pihaknya menyebut bahwa tidak benar ada helikopter Malaysia melakukan penyemprotan disinfeksi Covid-19 dari udara. Penjelasan tentang berita ini dimuat juga di www.turnbackhoax.id.
Hoaks Corona
Ada banyak lagi. Hoaks terkait dengan pandemi corona hingga 18 Maret 2020 mencapai 250 konten. Pada 10 Maret 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate mengumumkan, “Ada 187 hoaks. Itu hasil monitoring dari Cyber Drone Kominfo.” Beberapa di antaranya semisal berita Presiden Jokowi terkena corona, mencegah virus corona dengan Tito’s Vodka, konsumsi babi penyebab corona di Jakarta, virus corona diciptakan Tiongkok untuk melawan Amerika Serikat. Ada juga berita sebaliknya: Covid-19 diciptakan AS.
Berita bohong, disinformasi, dan malinformasi menjadi momok serius di saat seluruh umat manusia sedang menghadapi wabah corona. Menurut Yuval Noah Harari, salah satu keberhasilan manusia melawan virus di era modern adalah karena akses informasi. Dengan mengandalkan informasi dan pengetahuan yang terus berkembang, para ilmuwan mampu mengindentifikasi virus dan mengambil tindakan terkait dengan upaya membasmi virus tak kasat mata itu. Di abad-abad sebelumnya, wabah (bersama dengan perang dan lapar) disebut menjadi pembunuh nomor satu.
Informasi yang valid menghindarkan orang dari kepercayaan mistis dan kekuatan di luar nalar. Informasi ilmiah menghindarkan orang dari kepercayaan semisal bahwa virus ini merupakan hukuman Tuhan kepada China karena melakukan aksi pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. Satu sisi, kita semua berempati pada Muslim Uighur, dan semua tindakan anti-kemanusiaan di seluruh dunia harus dikutuk. Namun alasan tersebut tidak bisa menjadi pembenaran untuk mengkait-kaitkan suatu informasi yang tidak ada korelasinya.
Berita semisal ini terjadi di hampir setiap ada peristiwa bencana. Di saat orang panik dan dalam kondisi tidak berdaya, pihak-pihak tak bertanggung jawab justru mengeksploitasi kepanikan, kenestapaan, dan kebimbangan publik dengan menciptakan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat dalam kondisi rentan memang mudah terbuai dengan janji harapan dan pemberitaan yang memberinya rasa aman seketika. Di situasi rentan, mereka kerap mengedepankan aspek emosional dibanding pandangan rasional.
***
Konsep self defense meccanism yang dikemukakan Sigmund Freud menjelaskan tentang kecenderungan alamiah manusia untuk selalu mempertahankan eksistensinya, salah satu caranya dengan mempercayai berita yang memberi rasa aman, kebanggaan, dan kenyamanan. Media sosial dengan segala kekurangan dan kelebihannya menjadi sarana penyebaran berbagai berita hoaks yang mampu mengaduk emosi.
Berbekal telepon pintar, kita merasa tahu segala informasi. Kita merasa tahu seisi semesta, padahal mungkin hanyalah pengetahuan semu. Padahal, hanya terkurung dalam jebakan satu bilik gema kebenaran. Ketidakmampuan mengenali metakognitif, membuatnya bias dalam melihat sesuatu. Dikenal dengan teori Dunning-Kruger Effect.
Dalam dunia pasca-kebenaran ini, media dan para jurnalis harus bekerja lebih keras dengan perannya sebagai pencari kebenaran sejati (truth seeker). Para jurnalis harus selalu menjadi mata dan telinga masyarakat. Mereka harus melihat dan mendengar, lalu menyuarakan fakta-fakta tentang setiap peristiwa. Para jurnalis kerap menjadi pencatat pertama sejarah. Mereka menulis pertama kali tentang suatu peristiwa. Akurasi dan verifikasi menjadi penting karena pencatat pertama akan selalu dirujuk. Jika di kemudian hari ada peneliti yang mengkaji peristiwa itu secara khusus, maka referensi awalnya adalah catatan jurnalis.
Berita bohong biasanya disebarluaskan oleh mereka yang berprofesi bukan sebagai jurnalis. Para wartawan umumnya memiliki panduan dan serangkaian etika yang harus dijunjung tinggi. Namun dalam situasi rentan seperti ini, para jurnalis media mainstream sekalipun kerap berbuat salah. Semisal foto tentang jamaah shalat Jumat di sebuah masjid yang diklaim karena tidak mematuhi anjuran MUI. Padahal, foto itu diambil pada hari Jumat sebelumnya. Padahal bagi media, melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap informasi yang diterima merupakan kewajiban utama.
Etika Jurnalisme
Di sinilah pentingnya etika. Etika kerap disamakan dengan moral, budi pekerti, dan akhlak. Secara sederhana, etika merupakan seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku seseorang. Michael Josephson mengatakan bahwa etika memiliki dua dimensi. Pertama, kemampuan membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, patut dan tidak patut. Kedua, komitmen untuk melakukan tindakan atau perilaku benar, baik, dan patut itu.
Etika akan memandu para jurnalis untuk menuliskan atau mengabarkan informasi tentang apa yang sebaiknya diberitakan. Tidak hanya terkait dengan benar dan salah. Pertimbangan nilai kebaikan dan kepatutan menjadi penting. Pantang bagi seorang jurnalis untuk misalnya hanya memuat sepotong informasi yang meskipun benar, namun dicerabut dari konteks pembicaraan. Ada aspek kepatutan untuk tidak mencomot hanya pernyataan kontroversial dari seorang tokoh seraya melupakan substansi isi pembicaraan secara keseluruhan.
Dengan berpegang pada prinsip etika, pantang bagi seorang jurnalis atau media untuk melakukan pengadilan sendiri terhadap para korban. Termasuk di dalamnya para korban wabah corona belakangan ini. Pada kasus suspect corona pertama di Indonesia, beberapa media melakukan penghakiman terhadap korban. Eksploitasi korban dilakukan secara berlebihan. Di saat yang bersamaan, para jurnalis justru lupa menjadi pengawas bagi penguasa. Padahal media sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki peran watchdog for those in power.
***
Engelbertus Wendratama (2017) menyebut setidaknya ada empat teori klasik tentang etika jurnalisme. Pertama, rule-based tinking. Bahwa para jurnalis harus melakukan hal yang benar dengan mengikuti aturan yang berlaku. Dalam prinsip ini, mengikuti aturan dianggap sebagai perilaku etis, tanpa perlu mempertimbangkan pilihan konteks.
Kedua, end-based thinking. Bahwa para jurnalis memberitakan sesuatu dengan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat pemberitaannya. Dalam kategori ini, para jurnalis akan menimbang siapa yang diuntungkan dan dirugikan, mempertimbangkan dampak pemberitaan kepada keluarga korban atau masyarkat luas.
Ketiga, golden rule. Dalam kategori ini, para jurnalis akan memberlakukan prinsip “berbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain.” Dengan prinsip ini, seorang jurnalis misalnya akan berpikir dua kali ketika ingin mengeksploitasi atau mengulik kehidupan pribadi korban yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang diliput. Jurnalis memahami bahwa jika itu terjadi pada dirinya, dia tidak ingin dipermalukan di ruang publik.
Keempat, Aristotle’s golden mean. Filsuf Aristoteles menekankan nilai moderasi. Orang yang beretika diyakini akan menghindari sikap ekstream dalam setiap situasi. Semisal tentang pertimbangan pemuatan foto korban kekerasan, para jurnalis yang menerapkan etika moderat ini akan tetap menampilkan foto sebagai bagian dari fakta dan edukasi, namun dengan memodifikasi atau membuat foto menjadi hitam putih atau memblur bagian tertentu atau membuatnya jadi karikatur. Kepekaan dan kebijaksanaan para jurnalis sebagai guru bagi publik, menjadi faktor kunci.