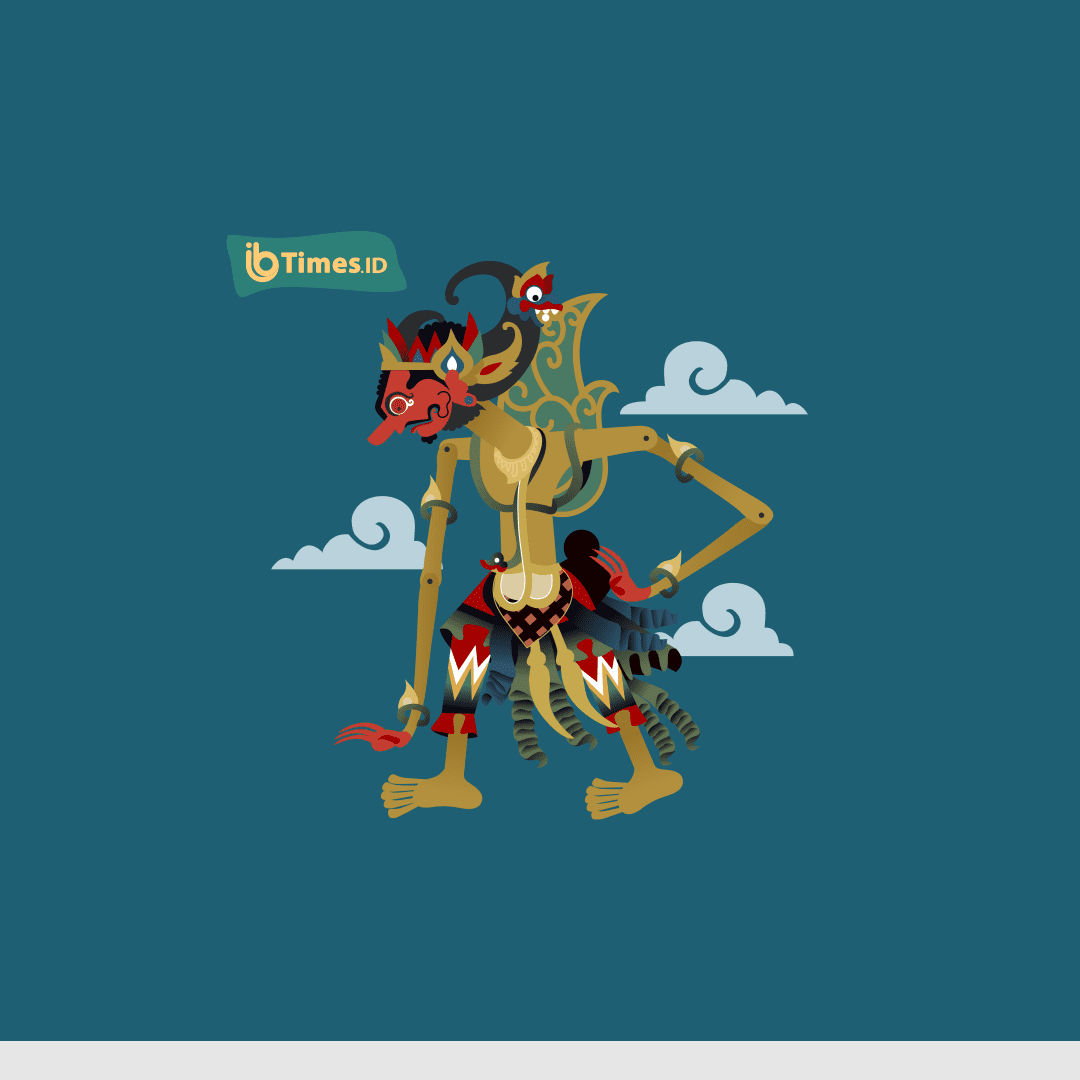Tulisan ini akan mencoba mengurai jejak-jejak romantika Islam dengan budaya lokal. Mengutip Abdul Wahid, guru besar antropologi agama UIN Mataram, Islam romantik itu Islam yang ramah dan merangkul realitas yang ada di luarnya. Bergaul, berkelindan, dan kemudian membentuk khazanah Islam itu sendiri, dalam hal ini khususnya di Indonesia.
Islam merupakan agama samawi yang membumi, dalam arti berorientasi untuk kehidupan manusia. Namun Islam bisa saja kehilangan nilai magisnya apabila antipati terhadap budaya atau dengan kata lain tidak lagi berorientasi untuk dan tentang manusia.
Relasi Kesalingan
Mengutip Kuntowijoyo (w. 2005), agama dan budaya memiliki relasi kesalingan. Pertama, budaya dapat mempengaruhi agama, nilainya budaya tapi simbolnya agama; cara kita kemudian mengekspresikan agama dilandasi oleh spirit budaya. Hal ini misalnya bisa dilihat pada tradisi atau kesenian baca tulis Al-Qur’an (qira’ah sab’ah/’asyirah, nagham, kaligrafi).
Kedua, agama dapat mempengaruhi budaya, yakni nilai-nilai yang bersumber dari agama yang kemudian terkonstruk menjadi budaya, misalnya ibadah (shalat) membawa nuansa terhadap bentuk bangunan dan gaya arsitektur masjid.
Pada konteks yang sama, salah satu fenomena menarik yang dapat kita jumpai adalah ucapan salam (Assalamualaikum), hari ini sudah menyilih menjadi budaya (akulturasi), bukan hanya di kalangan muslim, tapi secara umum. Kita sudah tak asing lagi mendengar saudara nonmuslim kita mengucap salam, bahkan istighfar, hamdalah, dan sebagainya.
Dialektika Teks dan Konteks
Al-Qur’an sebagai kitab suci agama Islam tidak diturunkan pada ruang hampa, melainkan hadir menyapa budaya yang berkembang dan berlaku di tengah masyarakat Arab yang majemuk kala itu.
Dari kenyataan tersebut, terjadi dialog yang seimbang antara Islam dengan realitas masyarakat yang didatanginya. Islam hadir bukan melulu untuk mendikte realitas. Dalam banyak hal, dinamika dan aspek-aspek sosial budaya juga diindahkan oleh Islam (Abad Badruzaman: 2018, 9).
Al-Qur’an diturunkan di tengah tatanan masyarakat yang jauh sebelum itu memiliki kebudayaan. Karena itu, budaya mengambil peran penting dalam pembentukan teks Al-Qur’an. Ayat Makkiyah dan Madaniyah menjadi bukti bagaimana Al-Qur`an berdialektika dengan realitas budaya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur’an dalam bentuk teks yang kemudian termanifestasi dalam bahasa, sudah semestinya terdapat dimensi budaya di dalamnya, sehingga meniscayakan adanya dialektika antara teks dan konteks (Nashr Hamid Abu Zaid: 2013, 3).
Interaksi Al-Qur’an dengan realitas budaya ini kemudian dapat melahirkan pembacaan atau penafsiran yang lebih produktif dan relevan (Muhammad Aminullah: 2022, 6).
Hal yang sering menjadi perbincangan di kalangan umat Islam adalah, pada persoalan epistemologis, yaitu adanya anggapan bahwa Al-Qur’an yang berbasis pada wahyu bertentangan dengan budaya yang merupakan produk atau hasil kreasi manusia (Gufron H.: 2003, 24).
Dari narasi tersebut, dapat ditarik garis lurus, bahwa manusia merupakan makhluk beragama sekaligus makhluk berbudaya. Manusia sebagai insan religi akan melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Adakalanya agama dan budaya memiliki ruang lingkup masing-masing, juga adakalanya berada dalam ruang lingkup yang sejalan (Muhammad Taufiq: 2019, 274).
Ruang lingkup agama dan budaya pada dasarnya tidak statis, tetapi dinamis. Sebab, konteks (manusia) dengan teks (Al-Qur`an) berhubungan secara dialogis (spiritualitas transendental).
Dimensi Islam
Agama Islam dapat dipahami dalam dua dimensi ajaran, yaitu normatif dan kultural. Dimensi normatif itu sifatnya tetap atau statis, karena itu dia tidak terikat oleh waktu dan tempat, berlaku secara universal sekaligus dalam konteks inilah kosmopolitanisme Islam dibangun, misalnya rukun Islam dan rukun iman.
Sedangkan dimensi kultural itu dinamis, terikat oleh realitas, yang dapat didialogkan dengan dunia kehidupan (lokalitas) seperti ekspresi sosial dan budaya. (Aksin Wijaya: 2020, 29).
Dimensi kultural inilah yang kemudian dapat melahirkan pemahaman Islam yang beragam. Rukun Islam dan rukun iman di belahan bumi mana pun tetap sama, yang berbeda adalah pada ruang lingkup budaya. Karena itu, dalam konteks lokal Indonesia, untuk menjadi muslim yang baik tidak harus mengubah diri menjadi bangsa atau identitas lain. Tetap menjadi orang Indonesia, kita bisa menjadi muslim yang baik.
Dalam hal ini, agama mesti dipahami dalam konteks masyarakat penganutnya. Karena secara praksis, agama merupakan hasil pemahaman dan pengamalan masyarakat berdasarkan kebudayaan yang dimilikinya (Mundzirin Yusuf, dkk.: 2005, 12).
Islam dan Kearifan Lokal di Indonesia
Dalam konteks Indonesia, kita sepakat bahwa Islam bukanlah agama asli pribumi. Dalam posisinya sebagai agama yang datang belakangan, Islam menampilkan wajah yang humanis, tanpa mencederai nilai-nilai kemanusiaan.
Terdapat adaptasi nilai universalitas Islam terhadap lokalitas budaya masyarakat, sehingga agama Islam dapat diterima dan menyatu dengan masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya.
Hubungan agama dan budaya dapat kita cermati ketika agama Islam masuk ke Indonesia. Terjadi pergumulan dan saling serap antara Islam melalui karakter kebudayaannya yang khas ketika berinteraksi dengan masyarakat Indonesia (Pahmi SY.: 2014, 16).
Sampai hari ini, kita dapat menemukan hasilnya, bahwa terdapat nuansa Islam dalam tradisi lokal. Hal ini menjadi ciri khas Islam Indonesia yang membedakannya dengan Islam di belahan bumi mana pun.
Jika bicara konteks daerah di Indonesia misalnya, bisa dilihat pada masyarakat Bima. Budaya sebagai jati diri masyarakat Bima tidak kemudian hilang setelah hadirnya Islam. Justru Islam hadir sebagai penguat eksistensi budaya. Hilir Ismail (w. 2011) mengutip Peter Carey menyebutkan, masyarakat Bima diakui sebagai masyarakat yang taat pada sistem budayanya dan berpegang teguh pada norma agama (Mutawalli: 2013, 2).
Kenyataan itu bisa dilihat pada berbagai tradisi masyarakat Bima, misalnya; Peta Kapanca yang diiringi bacaan surah-surah pilihan dari Al-Qur’an sebagai ritual pra pernikahan masyarakat Bima, ada juga Nggusu Waru sebagai karakter kepemimpinan masyarakat Bima yang digali dari pertalian nilai Islam dan budaya, bahkan falsafah masyarakat Bima Maja Labo Dahu merupakan kesadaran kultural masyarakat terhadap prinsip keimanan dan ketakwaan dalam Islam.
Islam hadir tanpa menampik budaya tertentu yang dianut oleh masyarakat, melainkan memberi warna dan spirit baru terhadap budaya tersebut, sehingga melahirkan Islam yang bersahabat dengan budaya, tanpa menghilangkan sakralitas ajaran utama agama Islam (tauhid).
Nuansa keislaman kita yang kaya ini harus senantiasa kita jaga. Pluralitas budaya harus dipandang sebagai aset untuk memperkaya hubungan antarlokal dan golongan (QS. al-Hujurat: 13). Spirit inilah yang sering kita sebut sebagai fastabiqul khairat (mengupayakan kebaikan yang plural).
Jejak-jejak romantika Islam dengan budaya lokal di Indonesia membuktikan eksistensi keduanya tidak dapat diragukan lagi. Dengan adanya budaya, pengamalan Islam akan senantiasa hidup dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kolektif sehari-hari. Perjumpaan nilai-nilai ajaran Islam dengan budaya lokal ini pada akhirnya telah melahirkan khazanah keislaman yang khas bagi masyarakat Indonesia.
Editor: Soleh