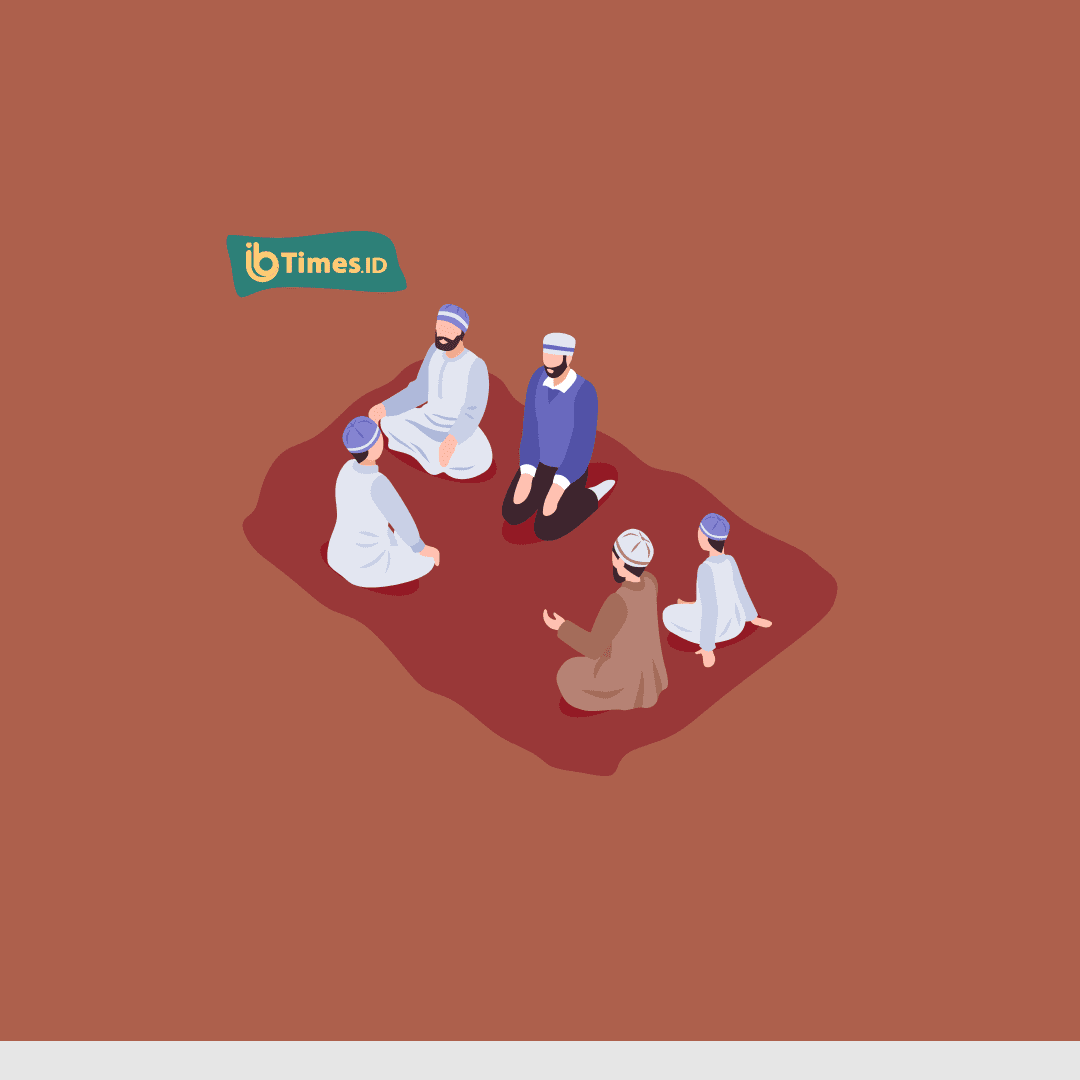Berbagai analisis menyebutkan bahwa pesantren memiliki suatu kultur budaya yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lain. Analisis tersebut didasarkan pada beberapa perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan pesantren.
Sebut saja tradisi penghormatan santri kepada kiai dan para keluarganya. Tak jarang mereka juga menyematkan gelar kepada keluarga kiai yang telah berjasa membesarkan pesantrennya. Contoh nyata dengan sapaan Gus, Ning, atau Kang yang berada dalam lingkup pesantren. Tentu saja sapaan tersebut tidak bisa dialamatkan kepada orang sembarangan.
Fenomena Sapaan Gus
Sebelum lebih jauh mengulik makna gelar Gus, pasti di telinga kita sudah tidak asing lagi dengan gelar tersebut.
Abdurrahman Wahid misalnya, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan panggilan Gusdur. Presiden keempat RI yang memiliki background pesantren ini merupakan cucu dari pendiri ponpes Tebuireng Jombang yang cukup fenomenal. Dari situlah masyarakat terobsesi bahwa sapaan Gus lekat dengan dunia pesantren.
Jika melihat dari tradisi yang sudah mengakar di kalangan masyarakat, istilah Gus sering diidentikkan dengan putra dari seorang kiai, dan jika perempuan disebut dengan Ning.
Tentu panggilan seperti itu bukan tanpa alasan. Setelah ditelisik lebih dalam, makna Gus merupakan kependekan dari istilah Raden Bagus. Bagus dalam hal ini adalah panggilan kehormatan yang dialamatkan kepada putra kiai.
Namun seiring berjalannya waktu, definisi Gus semakin melebar ke segala penjuru arah. Tak cukup dari faktor keturunan kiai saja, akan tetapi jika terdapat seseorang yang memiliki pemahaman agama yang baik juga bisa di sebut Gus.
Hingga pada akhirnya, gelar Gus semakin populer diiringi dengan kemunculan para Gus di tengah-tengah masyarakat yang di kenal melalui beberapa gaya dakwahnya yang terbilang nyentrik.
Menakar Kompetensi Gus dalam Memimpin Pesantren
Barangkali pembahasan pada bagian ini terkesan agak kurang sopan, karena memperlihatkan sisi ganjil pada sebuah lembaga pendidikan pesantren.
Akan tetapi, jika melihat realita yang terjadi pada beberapa pondok pesantren, kritik dan saran demi sebuah kemajuan menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus disampaikan. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, “Qulil haq walau kana murron”, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit.
Pesantren memang dikenal sebagai tempat yang banyak menyimpan tradisi. Salah satunya mengenai regulasi pergantian pola kepemimpinan yang terbilang cukup simpel.
Beberapa kiai yang memimpin pondok pesantren masih menganut pola pewarisan kekuasaan yang diberikan secara langsung kepada putra-putrinya.
Merujuk pada sistem transisi kepemimpinan tadi, muncul sebuah pertanyaan besar, “Apakah seorang Gus mampu memiliki kapabilitas yang sama seperti ayahnya?”.
Hidup menjadi orang yang dihormati, ditambah lagi dengan sistem pengalihan kekuasaan yang nyaris tanpa seleksi dari kiai kepada putranya, membuat beberapa Gus yang di-ninabobokkan oleh jabatan sang ayah justru membuatnya terbelenggu dalam zona nyaman.
Berbicara mengenai kapabilitas seorang Gus yang dibesarkan dalam zona nyaman, tentu akan sangat berpengaruh pada kondisi pesantren yang akan ia pimpin.
Sebagai contoh, jika generasi awal (ayahnya) seorang kiai yang betul-betul alim dalam artian memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, belum tentu seorang Gus mampu memiliki kapasitas ilmu yang sama seperti sang ayah.
Apalagi jika seorang Gus yang dibesarkan dalam kondisi serba enak, lantas hanya terkesan leyeh-leyeh saja tanpa memperhatikan kualitas keilmuannya, jangankan mengungguli kualitas keilmuan sang ayah, wong mengejarnya saja masih sulit, gimana mau mengungguli.
Seorang Gus Harus Bisa Legowo
Sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu dan nilai-nilai agama sebagai upaya dalam melakukan kontrol sosial, rasanya sangat tidak mudah untuk menjadi pimpinan pondok pesantren. Belum lagi jika ia di libatkan dalam menandangi persoalan umat.
Melihat kualitas ilmu yang beliau miliki, bukan sesuatu yang tidak mungkin jika beliau-beliau ini diikutsertakan dalam menggarap PR umat dan negara. Walaupun hanya sekadar dimintai pendapat dan do’a, apa yang mereka lakukan terbukti mujarab dalam mengobati penyakit bangsa ini.
Mengacu pada beberapa persoalan di atas, paling tidak terdapat dua pijakan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan dinamika jika seorang Gus ingin melanjutkan sepak terjang sang ayah dalam mengelola pesantren.
Pertama, sudah saatnya seorang Gus menggali potensi dengan terus belajar ilmu agama maupun umum secara proporsional sehingga kualitas ilmu yang didapatkan sepadan dengan sang ayah. Atau syukur-syukur bisa melebihi.
Kedua, dalam hal ini profesionalitas lembaga juga turut dipertanyakan. Jika terlalu memasrahkan Gus sebagai pewaris tahta rasanya merupakan hal yang kurang tepat. Karena tidak semua Gus memiliki kapabilitas yang sama seperti sang ayah.
Bilamana memasrahkan pembelajaran agama kepada orang yang bukan ahlinya, tentu akan menimbulkan masalah yang besar. Realita ini pun sejurus dengan sabda Nabi, “Jika suatu perkara dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran”.
Secara tidak langsung, realita tersebut memberikan tamparan bagi seorang Gus yang hendak melanjutkan kepemimpinan sang ayah. Demi kemajuan lembaga pondok pesantren, seorang Gus harus bisa legowo jika tidak memiliki kapabilitas ilmu yang mumpuni, ada baiknya memberikan kepemimpinan sang ayah kepada orang yang lebih mumpuni.
Editor: Lely N