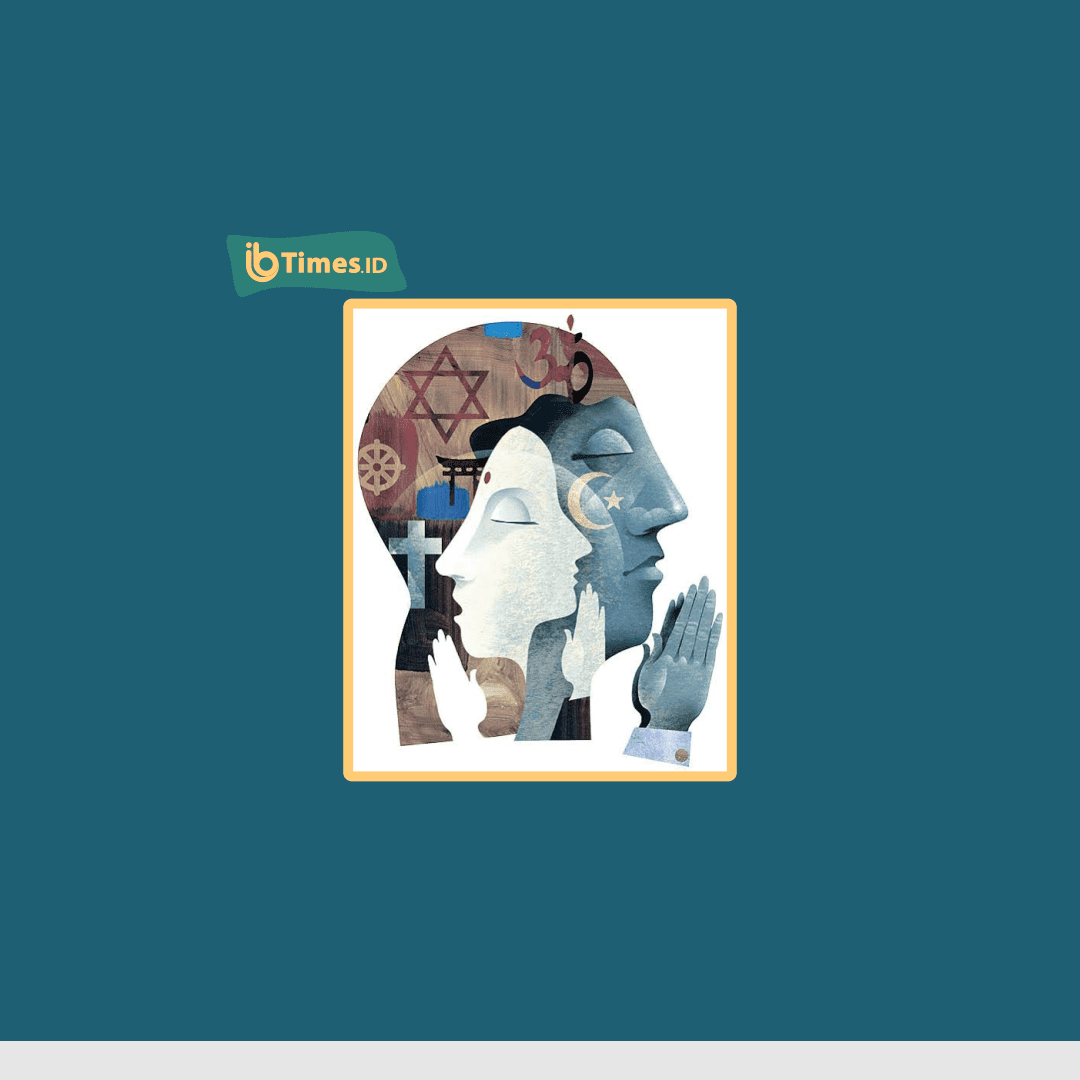Kepercayaan kepada Tuhan pada masyarakat agraris di pedesaan, mungkin tidak bersambung dengan realitas kehidupan pemeluknya. Dogma, ritus, dan doktrin agama melalui khutbah dan ceramah, serta seperangkat perayaan dan peringatan keagamaan, dianggap telah menyucikan batin sang pemeluk agama, walaupun tidak berbanding lurus dengan perilaku etis di ruang publik.
Sementara, warga masyarakat yang menjadi pengikut pemuka agama, dan dianggap sebagai pemeluk yang taat selama hadir pada setiap momen acara keagamaan. Walaupun sesungguhnya realitas sosial dan kemanusiaan sang pemeluk dan pengikut agama tidak mampu, disebabkan keterbatasan ekonomi. Akan tetapi, harus memaksakan diri untuk “tampil” sebagai pemeluk agama yang taat di depan pemuka agama. Sehingga dari “kaca-mata” orang lain masyarakat tersebut dianggap religius, pemuka agamanya sangat spiritualistik dan para pengikutnya seakan-akan khusyuk menghadap Tuhan dengan transedental.
Revolusi Teknologi di Tengah Spiritual yang Rapuh
Tentu keadaan di atas sangat berbeda dengan masyarakat industri di perkotaan. Mereka hidup secara sendiri-sendiri. Kesadaran beragama tidak kolektif melalui komando pemuka agama, tapi lebih kepada rasionalitas mereka memandang agama pada untung-ruginya bagi mereka. Kehidupan kota yang keras, penuh hingar-bingar dan hiruk-pikuk, tak mampu memberikan penyadaran tanpa pendekatan-pendekatan yang realistis. Hal tersebut dikarenakan berjaraknya rasa kemanusiaan antar warga, dan agama belum mampu menunjukkan eksistensi sebagai “lembaga” Tuhan yang mampu menyelamatkan kemanusiaan pemeluknya. Sehingga orang desa yang mengaku sangat religius menganggap orang kota sangat sekuler.
Namun, ketika era kelimpahan (globalisasi) hadir tanpa mengenal ruang, tempat, dan waktu, keheranan orang desa berubah 180 derajat terhadap apa yang pernah mereka persepsikan tentang orang kota yang mereka anggap sebelumnya sebagai sekuler. Saat HP menjadi tren, pola-pola kehidupan perkotaan berkembang pesat di pedesaan, cara berpakaian, gaya bicara, tata busana, dan sensasi kemodrenan lainnya, merubah pola-pola kehidupan desa yang sebelumnya sangat humanis, naturalis, religius, dan kebersahajaan.
Era mitologi yang pernah jaya di pedesaan hilang “dibombardir” dengan banyaknya tower berjejeran di pinggir jalan, sawah, dan perbukitan. Hantu, dedemit, ifrit, pocong, dan makhluk halus yang dahulu menakutkan harus “hijrah” menceri habitat baru yang lebih ramah pada mereka, mungkin di belantara hutan yang belum dimasuki manusia, atau gunung-gunung yang masih jauh dari pengaruh hegemoni manusia.
Maka, jadilah masyarakat pedesaan sekarang menjadi “desa” universal di era kelimpahan. Dan paradigma masyarakat berubah menjadi konsumen teknologi dengan mengikuti tren zaman globalisasi. Dari era mitologi ke era teknologi informasi, sebuah sensasi yang luar biasa untuk memanjakan diri.
Peranan lembaga keagamaan tergantikan oleh berbagai instrumen dan “institusi” yang ada dalam benda “ajaib” HP dengan berbagai mode dan programnya, seperti Instagram, Whatsapp, Twitter, Facebook, BBM, dan jenis lainnya.
***
Pandangan keagamaan tergerus oleh dogma, ritus, khutbah, dan ceramah dari sumber internet. Pandangan sekulerisasi menjadi piranti yang mengayomi hidup era globalisasi. Dogma, ritus, khutbah, ceramah, dan perayaan keagamaan dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemanusiaan umatnya. Mungkin karena terlalu “suci” sehingga dogma, ritus, khutbah, dan ceramah hanya memberi hawa sejuk saat bulan Ramadhan dan acara pelepasan jenazah.
Sebagaimana dikatakan Zuly Qodir dalam buku Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 61). Sekulerisme merasuki sudut-sudut kebatinan pemeluk agama, dengan masifnya penganut agama menggunakan perangkat teknologi yang memudahkan dan memanjakan hidup mereka. Dogma sekulerisme menjelajah pada “ritus” materialisme. Seperti: kartu ATM (credit card) lebih dipercaya langsung memberikan “pertolongan” dengan keluarnya lembaran uang kertas, dibandingkan dengan susah-susah ibadah dan memanjatkan doa kepada Tuhan; HP (handphone) lebih dipercaya langsung memberikan respon di tengah situasi sulit, darurat, dan genting, dibandingkan doa yang panjang yang tak dihiraukan Tuhan.
Jadi, “Mbah” Google dan koran lebih dipercayai informasi dan dijadikan “referensi” ketimbang Kitab Suci yang kusam dan bisu terpajang di dalam almari.
Di tengah arus sekulerisme dan materialisme mencocoki komunitas besar penganut agama. Mampukah pemuka agama melakukan pendekatan rasionalitas serta kontekstual dengan realitas kemanusiaan di era kelimpahan ini? Atau malah sebaliknya penganut agama akan menganggap agama sebagai masa lalu yang sudah selesai dan ketinggalan zaman. Kalau hal itu yang terjadi, tentu agama dianggap sebagai “berhala” yang dijadikan objek, dan dimusiumkan, hanya pada momen tertentu akan diwacanakan dan diperbincangkan. Di sinilah peran pemuka agama sebagai elan vital misi profetik agama untuk menyelamatkan spiritualitas pemeluknya di tengah derasnya revolusi teknologi yang merapuhkan keimanan pemeluk agama.
Nalar Keimanan dan Nestapa Kemanusiaan
Di tengah yang papa (dhu’afa) terkapar dengan busung lapar, bayi kekurangan gizi dan nutrisi, terbelit hutang pada rentenir, hingga mencari jalan pintas untuk sesuap nasi dengan menjadi pengamen, buruh kasar, tukang parkir, preman jalanan, begal, bahkan lebih sadis dengan jual diri dan kehormatan.
Sementara itu, kaum berduit (agniyah) berulang kali berangkat haji, tiap tahun ikut umroh, tiap Jumat asyik masygul dalam majelis zikir berurai air mata, dan riuh dalam berbagai perkumpulan profesi, serta histeria dalam berbagai training spiritualitas.
Dalam konteks yang paradok di atas, benarkah agama mampu mewujudkan rasa kepedulian dan kemanusiaan di tengah kenestapaan kaum papa? Padahal penganut agama dan pengikut risalah para Nabi dan Rasul terus mendapat bimbingan dari pemuka agama dengan berbagai dogma, doktrin, dan ritus spiritual lainnya.
Mengapa dogma, doktrin, dan ritus agama belum “berdaya” mengantarkan penganut agama menuju ketercerahan spiritual secara sosial? Mengapa kesalehan privasi belum berbuah pada kesalehan publik? Apa sesungguhnya yang “khilaf” dalam dogma, doktrin, dan ritus keagamaan selama ini?
Padahal, para penganjur agama dengan indah mengkhutbahkan dogma dan doktrin dalam berbagai saluran, seperti; televisi, radio, internet, selebaran, khutbah, ceramah, kultum, seminar, training, workshop, dan saluran lainnya. Akan tetapi, kesadaran hanya terbatas pada tempat, arena, dan saat forum berlangsung, setelah itu pengikut agama kembali pada realitas yang sekuleristik dengan humanisme yang minus.
Trepidasi Nalar Keimanan untuk Kemanusiaan
Mungkin saja berjaraknya antara kata dan laku, iman, dan kemanusiaan, disebabkan pemahaman tentang iman bagi pemeluk agama hanya terbatas pada rasa percaya pada Tuhan. Sehingga seakan-akan beragama hanya memuaskan dahaga spiritual kepada Tuhan yang melahirkan pribadi yang saleh ritual tapi minus saleh sosial, taat dalam ritus privasi tapi jauh dari “ritus” keberpihakan pada kemanusiaan secara publik.
Padahal sesungguhnya, nalar keimanan tidak dapat “digetarkan” (tripidasi) hanya dengan pandangan, bahwa iman diartikan dengan percaya saja. Karena beragama bukan hanya menjadikan penganutnya untuk “ego” spiritual bisa “bermanja-ria” dengan Tuhan; seakan-akan menyenangkan “hati” Tuhan tapi melukai “hati” kemanusian. Atau meninggikan pristise ibadah dengan “maqam” spiritual yang bergensi melalui haji dan umroh, tapi tak peduli dengan ratap dan jerit kemiskinan tetangga dan masyarakat sekitar.
Maka, konteks pengertian iman secara umum hanya percaya kepada Tuhan mesti dikontekstualisasi dalam realitas sosial-kemanusiaan. Seperti pemahaman, bahwa iman juga berasal dari akar kata yang sama dengan kata “aman”, yaitu kesejahteraan dan kesentosaan.
Pengertian tersebut dapat dipahami secara subtansi, bahwa wujud keimanan adalah membuat kondisi aman yang teraplikasi pada keberpihakan pada mustadha’afin, sehingga kondisi aman terpelihara dengan adanya “kebersambungan” hati antara yang kaya dengan yang miskin.
Kondisi amanpun terpelihara dengan emansipasi kemanusiaan para muzzaki yang menyantuni mustahiq dari keterpurukan ekonomi dan krisis pangan, seperti busung lapar, gizi buruk, terjerabab di lumpur pelacuran, terjerat renternir, berlumur di alam premanisme, dan “nasib” tidak beruntung lainnya, yang sering disalahkan adalah takdir dan “ketidakadilan” Tuhan.
***
Bila hal tersebut terwujud, tentu masyarakat makin aman, kesejahteraan masyarakat pinggiran terentaskan dengan bimbingan kewirausahaan dari lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang disertai dengan modal usaha produktif, serta pinjaman tanpa bunga bagi usaha mikro yang sudah mulai mapan secara ekonomi.
Pembinaan dan bimbingan intensif antarlembaga dan kelompok mikro di masyarakat pinggiran akan berbuah kesejahteraan bagi mereka, serta kesentosaan bagi bangsa. Inilah pemahaman makna iman yang mesti dikontekstualisasikan dengan realitas kemanusiaan di era kelimpahan yang cenderung sekulerisme.
Esensi iman pun harus dipahami, bahwa iman juga berasal dari kata “amanat”, yakni bisa dipercaya atau diandalkan, lawan dari khianat. Iman memang persoalan privasi hamba dengan Tuhannya, namun mesti teraktualisasi dalam realitas publik. Yakni, dengan memelihara amanah bagi yang diamanahi peran-peran struktur dan kultur sebagai “penggembala” umat. Sehingga amanah tidak dikhianati dengan perilaku minus-etika (akhlak), seperti: korupsi, kolusi, neopotisme, kekerasan, pelecehan, pergaulan bebas, curang, culas, sombong, angkuh, riya, iri hati, purbasangka, dan lain-lain.
Subtansi “amanah” hidup yang dititipkan Tuhan bukanlah konsong tanpa pertanggungjawaban, bukanlah bebas tanpa batas, dan bukanlah lepas tanpa sanksi. Inilah bentuk kontekstualisasi makna iman secara kemanusiaan.
Transformasi Tripidasi Nalar Keimanan
Doktrin agama sesungguhnya mengajarkan prinsip-prinsip universal tentang indahnya getaran iman dalam kalbu orang beriman. Seperti sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:
Ada tiga hal, jika ketiganya terdapat pada diri seseorang maka ia telah merasakan manisnya iman: (1) Hendaknya Allah dan RasulNya lebih ia cintai daripada selain keduanya; (2) Hendaknya ia mencintai seseorang hanyalah demi karena Allah; (3) hendaknya ia benci kembali kepada kekufuran sesudah diselamatkan Allah seperti tidak mau dirinya dilemparkan ke dalam api neraka (H.R. Bukhari dan Muslim).
Rasa dan getaran keimanan orang beriman berbanding lurus dengan komitmen tauhidnya kepada Allah, keberpihakan kepada kemanusiaan, dan mengentaskan segala bentuk “kekufuran” kemanusiaan yang menyelimuti kaum dhu’afa/mustadha’afin serta kaum termarginal lainnya.
Manisnya getaran iman harus dengan perasan spiritual yang bening, natural, dan sublim, bahwa manusia dan kemanusiaan merupakan tanggung jawab penganut agama yang mengaku beriman kepada Tuhan, yang ditunjukan dengan cinta, tulus, dan welas asih.
***
Ibnu Q ayyim Al-Jauziyyah, dalam kitab Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu, (Jakarta: Darul Falah, 1427, h. 50.) menjabarkan arti cinta sebagai berikut: Pertama, putih dan bersih. Adanya ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan terhadap yang dicintai. Kedua, tinggi dan tampak. Mengutamakan kehendak yang dicintai daripada kehendak dirinya sendiri. Ketiga, terus-menerus dan kokoh. Memelihara kecintaan dan tidak mau jauh dari kekasih. Keempat, inti atau saripati sesuatu. Kesediaan untuk memberikan yang paling berharga yang dimilikinya.
Hal di atas sejalan dengan sabda Rasulullah Saw, “Bukti cinta sejati itu ada tiga: (1) Ia memilih perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain; (2) Ia memilih bergaul dengan kekasihnya daripada orang lain; (3) Ia memilih kesenangan kekasihnya daripada kesenangan orang lain.
Getaran keimanan yang bertemu dengan realitas kemanusiaan menjadikan orang beriman asyik masgul dengan capaian spiritual yang matang dan transedental yang mapan. Karena tidak berjarak antara kata dan laku, doktrin agama dan realitas kemanusiaan, serta teoritis dogma dan praksis sosial-kemanusiaan. Barangsiapa mencintai sesuatu, ia pasti banyak menyebutkannya. barangsiapa mencintai sesuatu, ia pasti jadi budaknya (Ahli Hikmah).
Editor: Yahya FR