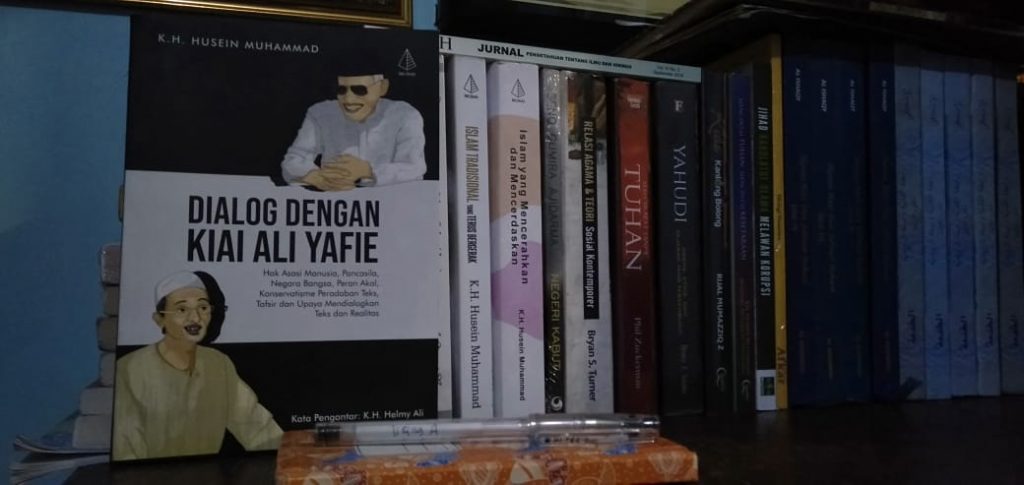Diaolog Dengan Kiai Ali Yafie, semacam dokumen hasil wawancara pendek namun serius antara dua intelektual muslim; K.H Husein Muhammad dan Prof. Kiai Ali Yafie.
Buku Kiai Husein—entah sudah yang keberapa—ini cukup kompleks berbicara seputar realita masyarakat kita. Banyak poin-poin penting yang dewasa ini telah dianggap sebagai sesuatu yang final akan tetapi sebetulnya jalan masih panjang atau bahkan sudah merasa sampai tujuan padahal sedang tersesat. Poin-poin itu antara lain tentang prinsip HAM, Pancasila, negara bangsa, peran akal, konservatisme peradaban teks, tafsir, dan upaya mendialogkan teks dan realitas.
Tersusun dari dua bagian; Dialog Dengan Kiai Ali Yafie dan Menghidupkan Cahaya Akal. Keduanya saling mempertegas satu dengan yang lain. Hasil tanya jawab (kalau saya cermati lebih semacam keresahan) Kiai Husein terhadap Kiai Ali yang kemudian jadi bentuk fisik (buku) ini, penting kita dialogkan juga. Buku ini membeberkan persoalan-persoalan urgen yang tidak jarang kita alami. Utamanya sebagai masyarakat berbangsa dengan kemajemukannya.
Dialog itu terjadi beberapa hari setelah istri Kiai Ali berpulang. Kondisi beliau kurang begitu sehat sehingga Kiai Husein datang disambut oleh putranya; KH. Helmy Ali dan kemudian lahirlah semacam diskusi kecil di kamar Kiai Ali.
Pembahasan tentang Maqashidus Syariah
Mula-mula, Kiai Husein menanyakan perihal prinsip-prinsip kemanusian universal, yang demikian masih berikat kuat dengan lima dasar Islam (al-kulliyat al-khams) rumusan Abu Hamid Al-Ghazali tentang tujuan syariat (maqashidus syariah).
Lima dasar itu antara lain; hifdzu ad-din (perlindungan atas agama), hifdzu an-nafs (perlindungan atas jiwa), hifdzu al-‘aqli (perlindungan eksistensi nalar), hifdzu an-nasl (perlindungan berketurunan) serta hifdzu al-mal (perlindungan atas harta). Demikian lima dasar ini berurut.
Namun kata kiai Ali Yafie, “Seharusnya hifdzu an-nafs lebih diprioritaskan dari hifdzu ad-din, menimbang bahwa orang beragama harus bernyawa”. Pendapat kiai Ali Yafie ini di luar dugaan Kiai Husein. Beliau dengan usia yang sudah udzur (94 tahun), kata Kiai Husein, masih juga tajam dan merdeka dalam bernalar.
Dari Pancasila hingga Al-Ghazali
Seusainya, Kiai Husein berlanjut menanyakan, “Apakah Pancasila sudah sesuai syariat? Dan kiai Ali dengan mantap meng-iya-kan. Pancasila adalah satu-satunya asas NKRI yang ditetapkan sebagai bentuk negara final dalam Islam.
Jika ada suatu golongan yang unjuk dengan menjajakan produk-produk mereka sambil menyematkan panji Islam dan bersikukuh hendak menegakkan sistem khilafah, maka aduhai kolotnya mereka. Bukankah masa kekhalifahan sudah berakhir pada 1923 yakni periode Turki Utsmani atau Ottoman? Tidak ada jalan lagi menuju kebuntuan, bukan?
Selain itu, Kiai Husein banyak bertanya tentang logika Aristotelian di mana Al-Ghazali terlibat soal ini. Pada satu kalimatnya Al-Ghazali nampak setuju dengan jalur filsafat ala Aristoteles. Pada kalimatnya yang lain mengatakan sebaliknya bahkan mengklaim sesat Aristoteles. Dari kebimbangan ini, Ihya’ Ulumiddin sebagai masterpiece antara karyanya yang lain secara tak langsung menyatakan Al-Ghazali berusaha menyatukan antara rasionalisme dan spiritualisme.
Berpikiran Luas
Lebih dari itu semua, Kiai Husein nampaknya ingin mengajak kita berpikir luas dengan arti merdeka seutuhnya. Tidak lagi terpaku pada teks melainkan harus seragam dengan konteks.
Pada dasarnya, apa yang disebut Al-Qur’an adalah nash (teks). Dan dengan keyakinan bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allah—sementara kalam adalah sifat dan itu berlaku selamanya, tanpa batas ruang atau waktu—maka nash Al-Qur’an memiliki wadah luas yang mampu menjawab semua realita sosial. Tentu, untuk menuju itu diperlukan nalar kritis, pandangan jauh, serta ta’wil (interpretasi) yang sesuai.
Dewasa ini, pemahaman demikian acap kali dianggap liberal; istilah dengan konotasi yang cenderung mengarah negatif. Barangkali apa yang disebut liberal adalah berpikir atau melihat sesuatu sampai pada akar-akarnya; bukan sekadar melihat apa yang ada di permukaan.
Mengapa Harus Ta’wil?
Ta’wil dan Tafsir, keduanya suatu yang lain. Apa yang lumrah terjadi pada hari ini ialah tafsir, bukan ta’wil. Hematnya, menurut Murata, tafsir ialah pembacaan terhadap teks (nash) berdasarkan apa yang diturunkan kepada kita lewat tradisi (naql).
Sementara ta’wil merupakan metodologi pembacaan terhadap teks (nash) dengan memperhatikan implikasi-implikasi yang tersembunyi di balik makna harfiah teks sekaligus merenungkannya hingga menemukan gagasan idealnya.
Artinya, dengan ta’wil seseorang berijtihad intelektual untuk mengungkap makna, tujuan, atau maksud yang dikehendaki Yang Pertama (Tuhan). Dengan demikian, ta’wil berarti kembali pada asal-usul sesuatu demi mengungkap makna dan signifikasinya.
Imam besar mufassir, Ibnu Jarir At-Thabari menyematkan judul pada kitabnya Jami’ul Bayan fi Ta’wili Ayi Al-Qur’an bukti bahwa istilah ta’wil lebih dulu dipakai sebagai metode pembacaan pada teks secara jeli dan mendalam.
Juga doa nabi kepada Ibnu Abbas—sahabat yang diberi gelar Tarjumanul Quran berkat kepiawaiannya mengurai isi Al-Qur’an—dengan allahumma faqqihhu fid diin wa ‘allimhu at-Ta’wil.
Sementara tafsir hanya merujuk pada lingkup pembacaan teks tanpa disertai al-umuru al-kharijiyyah (faktor luar; sosial, ekonomi, dan budaya). Oleh karena demikian, perlu adanya kesadaran diri untuk berpikir lebih merdeka dalam menyikapi persoalan-persoalan yang dinamis.
Menolak Tunduk Pada Teks
Pertanyaan menggelitik pernah diajukan Renan, seorang sarjana Eropa, kepada Syekh Muhammad Abduh: “Jika umat muslim menganggap agamanya salihun fi kulli zamanin wa makanin, tunjukkanlah kepada saya bukti empirisnya, negara mana?”
Pertanyaan serupa satire itu harus kita jadikan pecut agar lari makin kencang. Seorang muslim yang moderat harus ‘liberal’. Liberal dalam arti membaca sesuatu sampai akar-akarnya; tidak sekadar melihat apa yang tampak di permukaan.
Jaringan Islam Liberal (JIL)—organisasi yang dikecam negatif dan berpotensi merusak asas umat muslim, warga NU utamanya—barangkali lahir dari semacam keresahan-keresahan mendalam atas banyaknya masyarakat yang masih menghamba pada teks.
Oleh kawan-kawan JIL, diistilahkan sebagai ubbadu an-nushuh (kaum yang tunduk pada teks). Namun, terlepas dari kepentingan pribadi, organinasi semacam JIL perlu ada dan harus diciptakan agar kemerdekaan berpikir benar-benar tercipta.
Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu empat pendiri madzhab, dikenal sebagai ahl hadist karena lebih mendahulukan teks ketimbang rasio. Dua muridnya; Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga diakui sebagai pengikut golongan tekstualis. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam sejarahnya kemudian dijuluki sebagai pemimpin kaum fundamentalis (imam al-mutasyaddidin).
***
Kiai Husein dalam bukunya Dialog Dengan Kiai Ali Yafie banyak menyurati kita agar paham; jika kita masih tunduk pada teks dan acuh pada realita maka kita akan tertinggal sebab zaman senantiasa bergulir.
Ushul Fikih sebagai metodologi penentu hukum berperan penting dalam keterlibatan ini. Pun istilah-istilah semacam muhkam-qath’i (hukum praduga dan pasti) atau al’ibrah bi ‘umumi al-lafdzi la bi khusushi as-sabab menjadi satu pertimbangan penting dalam pengambilan hukum.
Imam Syafi’i, dokumenter pertama yang menulis ushul fikih, mengarang Ar-Risalah sebagai acuan dasar dalam memahami metodologi pemutusan hukum.
Dari Ar-Risalah itu kemudian lahir produk lain yang serupa. Seperti, Al-Mahsul karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Mustasyfa milik Al-Ghazali. Keduanya (juga seluruh kitab ushul fiqh) berinduk pada ar-Risalah. Utamanya, Jam’u al-Jawami’ karangan Imam As-Shuyuthi yang kerap dipelajari di banyak pesantren itu merupakan kumpulan intisari yang diperas dari kitab-kitab induk.
Kiranya sangat penting nasihat (baca: ajakan) Kiai Husein; maka sudah saatnya bagi kita untuk kembali memahami teks-teks keagamaan kita (Islam) secara lebih terbuka, dari tafsir ke cara ta’wil, dari konservatisme ke progresifisme dan dari langit ke bumi, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama dan sarjana muslim awal. Adalah Islam yang dinamis, Islam yang menciptakan peradaban dunia yang toleran dan mengapresiasi setiap pemikiran yang baik dan bijak dari manapun datangnya dan oleh siapapun.
Sekian.
Judul : Dialog dengan Kiai Ali Yafie
Penulis : K.H. Husein Muhammad
Penerbit : IRCISOD
ISBN : 978-623-7378-64-8
Tebal : 132 hlm
Tahun : 2020