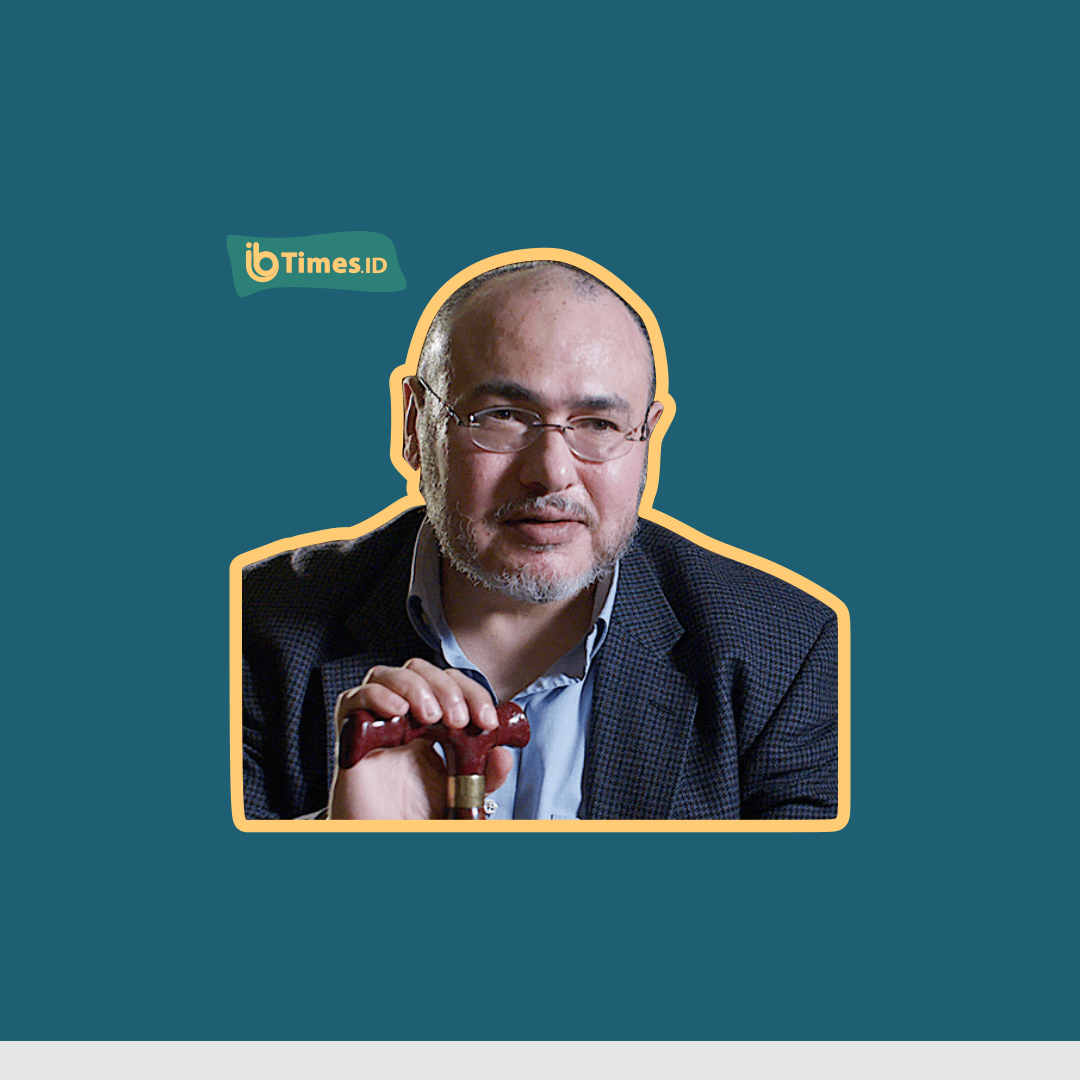IBTimes.ID — Keterbelakangan dunia Islam selalu berhadapan dengan kebutuhan adanya rekonstruksi hukum dan pemahaman Islam. Banyak pemikir yang menawarkan bermacam gagasan agar eksistensi hukum Islam senantiasa fungsional, salah satunya Khaled Abou El Fadl. Tawaran Abou El Fadl dalam mengatasi persoalan ini pertama-tama adalah membedakan terma Syariah dan Fikih yang selama ini dipahami sebagai istilah sinonim.
“Harus ada pembedaan yang jelas antara Syariah dan Fikih. Syariah itu basisnya keilahian, bersifat absolut, universal, nilai-nilainya tinggi. Sedangkan Fikih bersifat subyektif, sangat terikat atau dipengaruhi kekurangan manusia yang mencoba untuk mengaplikasikan hukum-hukum Tuhan. Karena itu Fikih bersifat fleksibel serta bergantung pada tantangan umat manusia. Meski demikian, basis Fikih adalah Syariah,” terang Qaem Aulasyahied dalam diskusi bedah buku yang diselenggarakan oleh PCIM Amerika Serikat pada Sabtu (23/1).
Berdasarkan keterangan Qaem, Syariah berarti hukum ilahi (divine law) yang bersifat universal, abadi, dan merupakan nilai-nilai paling esensi dalam ajaran Islam. Sedangkan Fikih ialah aspek kognitif hukum Islam dan bukan wahyu dari langit (non-divine law). Fikih merupakan produk ijtihad yang tak lepas dari konteks spasialnya, maka ia bersifat partikularistik-kasuistik.
Setelah membedakan posisi syariah dan fikih, Qaem menuturkan bahwa Abou El Fadl menawarkan gagasan syariah humanistik yang secara diametral berbeda dengan syariah klasik. Namun, Qaem menggarisbawahi bahwa term “humanisme” dalam paparannya tidak merujuk pada pengertian humanisme sebagai basis filsafat Barat. Ia menggunakan istilah tersebut untuk memudahkan paparannya dalam menjelaskan pemikiran Abou El Fadl.
Pandangan Syariah Klasik
Menurut Qaem, syariah klasik memandang persoalan terlalu hitam putih dan legal formal. Hal tersebut lantaran sebuah hukum sangat tergantung dengan realitas yang melingkupi hukum itu (al-hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman). Artinya, dalam syariah klasik hukum berubah sesuai dengan ada atau tidaknya ‘illat. Karenanya, kantong-kantong hukum hanya berisi aturan-aturan praktis tanpa menampilkan nilai-nilai esensi dalam syariah.
Qaem menuturkan bahwa aspek inilah yang menuai kritik dari Abou El Fadl yang mengatakan bahwa syariah akan tersusupi bias kepentingan dan klaim kebenaran. Qaem menjelaskan bahwa seharusnya eksistensi hukum tidak hanya tergantung pada ‘illat saja, melainkan juga pada aspek nilai-nilai dasar dalam Syariah (al-hukmu laysa yaduru ma’a illatihi faqath bal yaduru ma’a qiyamihi al-asasiyayati wujudan wa ‘adaman). “Jadi hukum itu tidak tergantung pada ‘illat saja tetapi juga bergantung pada syariah atau basic value seperi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Quran,” tambahnya.
Lebih jauh, Qaem mengembangkan pemikiran Khaled Abou El Fadl ini dengan menampilkan bangunan syariah humanistik. Komposisi syariah humanistik terdiri dari: 1) basic value atau nilai-nilai esensi Syariah seperti kesetaraan, kedamaian, kemaslahatan, dan lain-lain; 2) interconnective principles yang menghubungkan antara nilai dasar dengan realitas konkret atau particular principle; dan 3) particular principle yang berisi hukum-hukum praktis.
Konstruksi Syariah Humanistik
Qaem mencontohkan konstruksi syariah humanistik ini dalam kasus kepemilikan harta. 1) basic value dalam syariah, salah satunya adalah setaranya laki-laki dan perempuan dalam kesempatan melakukan kebaikan; 2) interconnective principles dalam Syariah sebagai turunan dari basic value adalah adilnya kepemilikan harta antaran laki-laki dan perempuan; dan 3) particular principle sebagai putusan praktisnya adalah pembagian harta dilakukan dengan semangat wasiat.
Qaem menuturkan bahwa Majelis Tarjih juga menggunakan paradigma yang menghubungkan antara Syariah dan Fikih. Paradigma tersebut dikenal sebagai teori pertingkatan norma. Dengan teori ini, Fikih Muhammadiyah memuat tuntunan dan pedoman yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi ruang dan waktu. Karenanya Muhammadiyah sebenarnya mengikuti jejak para ulama klasik yaitu merancang bangunan kaidah-kaidah fikih (qawaid al-fiqhiyyah) untuk kemudian digunakan sebagai respon terhadap kasus-kasus yang berkembang di masa depan.
“Berdasarkan teori pertingkatan norma muncul produk-produk Majelis Tarjih yang dianggap progresif. Bukan berarti ini lebih unggul dari karya fikih terdahulu, mungkin zaman dulu belum menemui problem seperti sekarang. Majelis Tarjih menggunakan paradigma ini karena memang jalan seperti inilah yang diyakini Majelis Tarjih sebagai solusi,” tegas Qaem.
Selengkapnya baca disini