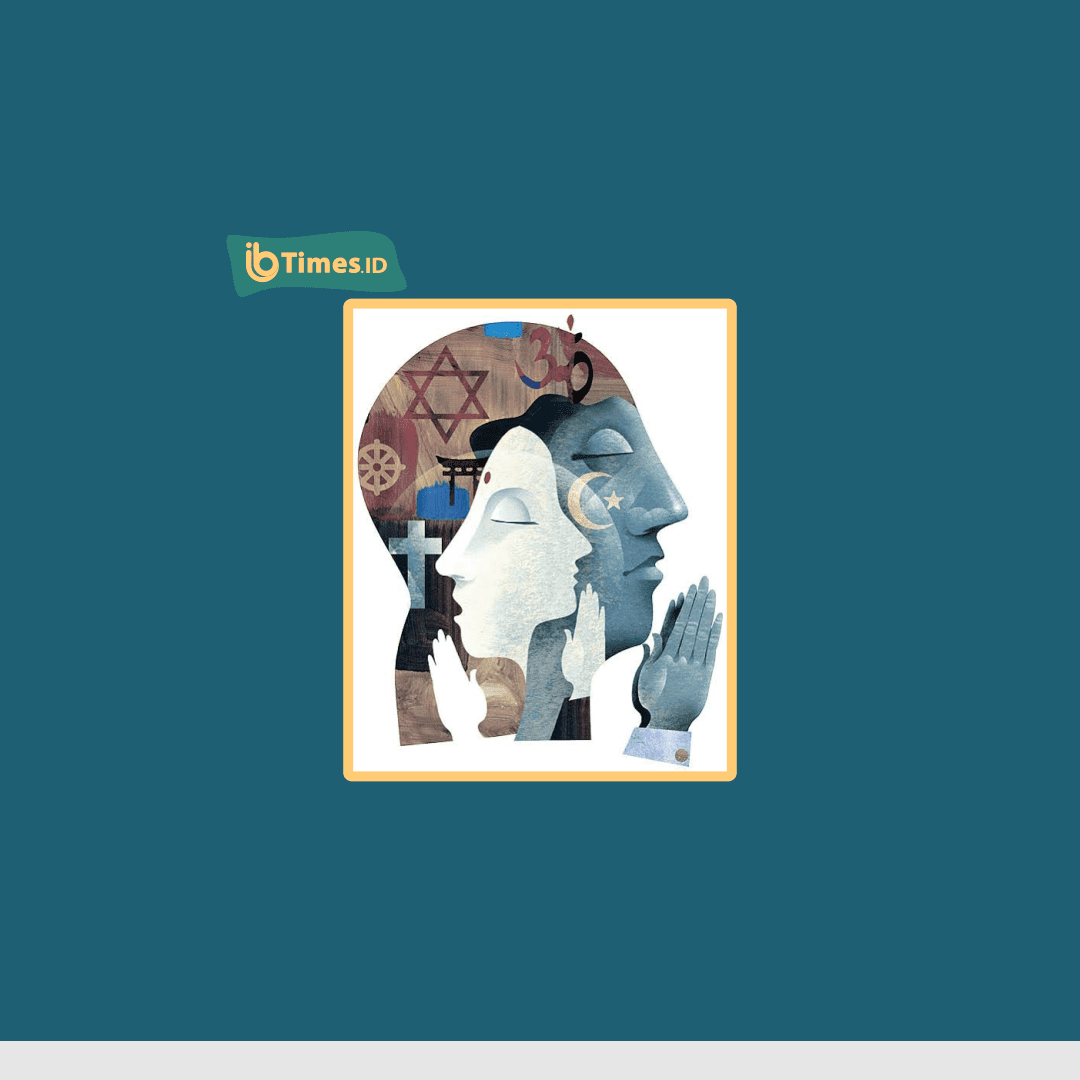Motif Fisiologis
Dari dua teori manusia beragama yang sebelumnya, yakni: Teori Psikoanalisnya Sigmund Freud tentang “libido/nafsu/id” beragama dan teori Behaviorisme-nya John Broadus Watson dan B.F. Skinner tentang motif fisiologis beragama. Maka, berikut ini adalah teori humanistiknya Abraham Maslow dan pengikutnya.
Kajian teori ketiga ini cukup menarik, dikarenakan eksistensi manusia tidak dipandang hanya sekedar makhluk materiil belaka, juga bukan pemenuhan motif fisiologis saja.
Akan tetapi, manusia memiliki spirit yang bersifat mental dalam perjuang untuk menentukan eksistensinya. Serta adanya upaya manusia secara rohaniah untuk menempa pengalaman keagamaan hingga manusia melepaskan dimensi fisiknya dan menyatu dengan kekuatan transedental.
Upaya dan usaha manusia dalam meraih eksistensinya secara rohaniah bukanlah hal yang mudah. Perjuangan tidak cukup hanya pengertian atas dogma dan doktrin agama saja. Akan tetapi, juga disertai dengan ke-kudus-an diri dalam melewati lapisan-lapisan rohaniah dalam dirinya yang tidak kasat mata.
Kompetensi Spiritualitas Manusia Beragama dalam Teori Humanistik
Berbicara teori humanistik, berarti mengenal tokoh yang diambil dari kelompok ini yakni Abraham Maslow. Dalam pandangan Maslow, sebagaimana dijelaskan Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso (1995: 74), bahwa semua manusia memiliki perjuangan atau kecenderungan yang dibawa sejak lahir untuk mengaktualisasi diri.
Kita didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang universal yang dibawa sejak lahir, yang tersusun dalam suatu tingkatan, dari yang paling lemah sampai yang paling kuat. Tingkatan-tingkatan kebutuhan seperti layaknya tangga di mana kita harus meletakkan kaki pada anak tangga pertama sebelum mencapai anak tangga kedua, dan seterusnya.
Prasyarat untuk mencapai aktualisasi diri adalah memuaskan empat kebutuhan yang berada pada tingkat yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan memiliki cinta, dan kebutuhan akan pernghargaan.
Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat perkembangan yang paling tinggi, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita. Orang yang mengaktualisasikan diri didorong oleh metamotivasi (metamotivation).
Pendekatan humanistik mengakui eksistensi agama. Maslow sendiri dalam teorinya mengemukakan konsep metamotivation yang di luar kelima hierarchy of needs yang pernah dia kemukaan.
Mystical atau peak experience adalah bagian dari metamotivation yang menggambarkan pengalaman keagamaan. Pada kondisi ini manusia merasakan adanya pengalaman keagamaan yang sangat dalam. Pribadi (self) lepas dari realitas fisik dan menyatu dengan kekuatan transedental (self is lost and transcended). Di mata Moslow level ini adalah bagian dari kesempurnaan manusia.
***
Ada kesempatan-kesempatan di mana orang-orang yang mengaktualisasikan diri mengalami ekstase, kebahagiaan, perasaan terpesona yang meluap-luap, suatu pengalaman keagamaan yang sangat mendalam.
Selama pengalaman puncak ini, yang dianggap Maslow bisa terjadi di kalangan orang-orang yang sehat, diri dilampaui dan orang itu digenggam suatu perasaan kekuatan, kepercayaan dan kepastian, suatu perasaan yang mendalam bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikannya.
Pengalaman puncak yang transeden digambarkan sebagai sehat supernormal (normal seper healthy) dan sehat super super (super super healthy). Maslow menyebutkan peakers (transcenders) dan non-peakers (non-transcenders).
Non-peakers cenderung menjadi orang-orang yang praktis, berinteraksi dengan dunia secara efektif dan kurang dengan dunia kehidupan N (B-living) yang lebih tinggi. Mereka cenderung menjadi perilaku, bukan mediator atau kontemplator, efektif dan pragmatis bukan estetis, menguji kenyataan dan kognitif bukan emosional dan mengalami. Sebagai contohnya adalah Eleanor Roosevelt, Harry S. Truman dan Dwight Eisenhower.
Peakers memiliki pengalaman-pengalaman puncak yang memberikan wawasan yang jelas tentang diri mereka dan dunia mereka. Mereka cenderung menjadi lebih mistik, puitis dan saleh, lebih tanggap terhadap keindahan dan kemungkinan lebih besar menjadi pembaharu-pembaharu atau penemu-penemu. Beberapa peakers adalah Aldaus Huxley, Albert Schweitzer, Albert Eintein.
Kompetensi Spiritual dalam Al-Quran
Kompetensi, baik dalam pengertian “sehat” maupun “tidak sehat” (berkompetensi secara sehat, atau sebaliknya), merupakan watak manusia ketika ia sudah lahir dan berkembang dalam kehidupannya dari waktu ke waktu di sepanjang hayat dikandung badan.
Kompetensi merupakan motif psikologis manusia secara alamiah. Dalam Al-Qur’an memotivasi manusia untuk melakukan persaingan dalam ketakwaan kepada Allah Swt beramal baik.
Berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, mengikuti aturan Tuhan dalam kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah Swt, keluarga, maupun masyarakat. Adapun kompetensi spiritualitas manusia dalam Al-Qur’an antara lain adalah:
Pertama, berkompetensi dalam meraih ketakwaan untuk mendapatkan posisi istimewa di akhirat kelak (surga).
Dengan cara itu, manusia akan meraih ampunan dan keridaan Allah Swt, serta meraih kenikmatan masuk surga. Sebagaimana firman Allah Swt:
“Sesungguhnya orang-orang yang taat itu benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dari atas dipan-dipan, mereka memandang Kamu akan mengetahui pada wajah-wajah mereka itu ada cahaya kebahagiaan. Dihidangkan kepada mereka khamar yang masih disegel. Kesudahannya wangi kesturi, dan untuk itu, hendaknya berpaculah orang-orang yang mau berlomba itu.” (QS. Al-Muthaffifin {83}: 22-26)
Kedua, berkompetensi dalam meraih ketakwaan dengan “berinvestasi” kebaikan kepada siapapun. Sinyal inilah yang tercermin dalam firman-Nya:
“Dan masing-masing (pemeluk agama) memiliki kiblat (sendiri) di mana ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan….” (QS. Al-Baqarah {2}: 148)
***
Ketiga, berkompetensi dalam meraih ketakwaan dengan menebarkan cinta-kasih-sayang sejati pada semua makhluk Allah. Sinyal langit telah menyentak kesadaran hamba-Nya dengan firman-Nya:
“Kemudian Kami susulkan pada jejak mereka rasul-rasul Kami, dan Kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan Kami telah memberinya Injil. Kami jadikan pula di dalam hati orang-orang yang mengikutinya perasaan kasih dan sayang. Mereka mengada-adakan rabbaniyyuh, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, (mereka sendiri yang mengada-adakannya) untuk mencari keridaan Allah, tetapi mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Kemudian, Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka ganjarannya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Hadid {57}: 21)
Keempat, berkompetensi dalam meraih ketakwaan dengan menanam “saham” kebajikan yang tulus pada Tuhan dan kemanusiaan. Spirit itulah yang terekam dalam firman Allah yang menyatakan:
“…maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kalian semuannya, lalu Dia memberitahukan kepada kalian hal-hal yang dahulu kalian perselisihkan padanya.” (QS. Al-Maidah {5}: 48)
Motif Beragama sebagai Fitrah Ketuhanan dalam Diri Manusia
Menurut Muhammad Utsman Najati (2005: 62-63), bahwa motif beragama adalah motif psikologis yang memiliki basis alamiah dalam sifat penciptaan manusia. Di lubuk hatinya yang paling dalam, manusia merasakan adanya suatu motif yang mendorongnya pada pencarian dan kontemplasi untuk mengenal Penciptanya yang juga Pencipta kosmos, beribadah kepada-Nya, berhubungan dengan-Nya, serta berlindung kepada-Nya sambil memohon pertolongan setiap kali musibah dan bencana menderanya. Dalam perlindungan dan penjagaan-Nya itu, manusia merasakan ketenangan dan ketentraman.
Ada beberapa motif beragama sebagai fitrah ketuhanan dalam diri manusia, yakni:
Pertama, beragama merupakan sifat fitrah dari penciptaan dan pembawaan manusia.
Dalam fitrah manusia, yakni dalam penciptaan dan pembawaannya, terdapat kesiapan fitri untuk mengenal Sang Khalik, Pencipta semua makhluk. Dari pengenalan itulah manusia mengambil benang-merah tentang eksistensi keberadaan dan keesaan Allah Swt, serta tujuan keberadaan semua makhluk di jagad raya ini.
Hal ini sangat sesuai dengan ‘sinyal’ langit yang difirmankan Allah:
“Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (Allah) dengan lurus. (Tetaplah pada) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengannya. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum {30}: 30)
Kedua, dalam perjanjian primordialisme di alam rahim, manusia berkomitmen sebagai manusia-tauhid dan berkarakter hanif (fitrah, suci, benar, bersih, sublim).
Semua manusia di alam rahim telah mengakui (bersaksi) atas ke-rubbubiyah-an Allah yang berakar dari fitrah manusia. Kenyataan itu sudah ada sejak azalinya pada bagian (diri) manusia yang paling dalam secara rohaniah.
Inilah yang terkandung dalam firman Allah yang menyatakan:
“Dan ingatlah ketika Rabb-mu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka (seraya berfirman), ‘Bukanlah Aku ini Rabb kalian?’ Mereka menjawab, ‘Benar (Engkau adalah Rabb kami), kami menjadi saksi, ‘supaya pada hari kiamat kalian tidak mengatakan, ‘Sesungguh kami (Bani Adam) lengah terhadap ini’.” (QS. Al-A’raf {7}: 172)
***
Ketiga, kecenderungan kesiapan fitri untuk mengenal dan mengibadahi Allah Swt.
Semua manusia yang dilahirkan di alam dunia ini adalah dalam keadaan memiliki kesiapan fitri untuk menganut agama yang lurus.
Itulah esensi dari risalah Rasulullah Saw yang menyatakan:
“Tak seorang pun anak melainkan dilahirkan dalam keadaan fitri. Namun, kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagaimana binatang melahirkan binatang yang mulus, adakah kalian merasakan kekurangan padanya?” Kemudian Abu Hurairah berkata, “Bacalah jika kalian mau, ‘(Tetaplah pada) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengannya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi)
Keempat, adanya motif fitrah manusia bersandar kepada kekuatan Maha Gaib (Allah). Dalam segala dinamika dan problematika hidup manusia membutuhkan kekuatan yang maha dahsyat.
Manusia memiliki batas kemampuan dalam mencari solusi dan obsi terhadap prolematika atas pasang-surutnya kehidupannya. Kekuatan Allah menjadi sandaran dan pegangan yang kokoh, karena hidup tanpa pandu tak akan tentu arah akan dituju!
***
Gejala psikologis itulah yang digambarkan Allah dalam firman-Nya:
Dia-lah yang membuat kalian dapat mengadakan perjalanan di daratan dan di lautan. Hingga ketika kalian berada di dalam kapal, dan melajukan kapal itu dengan membawa mereka dengan embusan angin yang baik serta mereka merasa senang karenanya, datanglah badai menerpanya dan gelombang menghampirinya dari segala tempat, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata. ‘Sungguh jika Engkau menyelamatkan kami dari ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur.” (QS. Yunus{10}: 22)
Kelima, beragama merupakan fitrah dalam sifat kemanusiaan manusia. Dalam segala “cuaca” dan “iklim” yang meliputi hidup manusia di sepanjang sejarah, ia membutuhkan penuntun dan tuntunan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Penuntun dan tuntunan merupakan panduan manusia dalam melakoni hidup yang penuh dinamika dan romantika sepanjang masa.
Spirit itulah yang terekam dalam firman Allah yang menjelaskan:
“Katakanlah, ‘Siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan di darat dan di laut, yang kalian berdoa kepada-Nya dengan merendahkan diri dan suara perlahan. Sungguh jika Dia menyelamatkan kami dari ini, tentu kami akan benar-benar menjadi orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-An’am {6}: 63)
Esensi Keparipurnaan Manusia Mencapai “Ekstase” Ketuhanan
Dari pandangan Abraham Maslow, yang menyatakan, bahwa manusia memiliki perjuangan atau kecenderungan yang dibawa sejak lahir untuk mengaktualisasi diri.
Hal itu menunjukkan, bahwa semua manusia memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang universal yang dibawa sejak lahir, yang tersusun dalam suatu tingkatan, dari yang paling lemah sampai yang paling kuat.
Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa prasyarat untuk mencapai aktualisasi diri adalah memuaskan empat kebutuhan yang berada pada tingkat yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan memiliki cinta, dan kebutuhan akan pernghargaan.
Jadi, teori humanistik mengakui eksistensi agama. Maslow sendiri dalam teorinya mengemukakan konsep metamotivation yang di luar kelima hierarchy of needs yang pernah dia kemukaan.
Mystical atau peak experience adalah bagian dari metamotivation yang menggambarkan pengalaman keagamaan. Pada kondisi ini manusia merasakan adanya pengalaman keagamaan yang sangat dalam.
Pribadi (self) lepas dari realitas fisik dan menyatu dengan kekuatan transedental (self is lost and transcended). Di mata Moslow level ini adalah bagian dari kesempurnaan manusia.
Ada kesempatan-kesempatan di mana orang-orang yang mengaktualisasikan diri mengalami ekstase, kebahagiaan, perasaan terpesona yang meluap-luap, suatu pengalaman keagamaan yang sangat mendalam.
Selama pengalaman puncak ini, yang dianggap Maslow bisa terjadi di kalangan orang-orang yang sehat, diri dilampaui dan orang itu digenggam suatu perasaan kekuatan, kepercayaan dan kepastian, suatu perasaan yang mendalam bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikannya.
Manusia senantiasa melakukan pencarian terhadap eksistensinya secara rohaniah. Maka kompetensi spiritualitas merupakan tangga-tangga manusia dalam meraih eksistensi dan posisi secara spiritual di hadirat Tuhan.
Maka pengalaman puncak yang transeden digambarkan sebagai sehat supernormal (normal seper healthy) dan sehat super super (super super healthy). Maslow menyebutkan peakers (transcenders) dan non-peakers (non-transcenders).
Non-peakers cenderung menjadi orang-orang yang praktis, berinteraksi dengan dunia secara efektif dan kurang dengan dunia kehidupan N (B-living) yang lebih tinggi.
***
Mereka cenderung menjadi perilaku, bukan mediator atau kontemplator, efektif dan pragmatis bukan estetis, menguji kenyataan dan kognitif bukan emosional dan mengalami.
Dari perjalanan panjang secara spiritualistik lah, manusia memiliki pengalaman puncak (peakers). Dan pengalaman-pengalaman puncak itulah yang memberikan wawasan yang jelas tentang diri mereka dan dunia mereka.
Mereka cenderung menjadi lebih mistik, puitis dan saleh, lebih tanggap terhadap keindahan dan kemungkinan lebih besar menjadi pembaharu-pembaharu atau penemu-penemu.
Kemampuan mengaktualisasikan diri secara spiritualistik membuat manusia yang beragama mengalami ekstase, kebahagiaan, perasaan terpesona yang meluap-luap, suatu pengalaman keagamaan yang sangat mendalam.
Mungkin sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, rasa manis tidak cukup dijelaskan dengan kata-kata, akan tetapi harus dirasakan sendiri. Yang merasakan tentu berbeda dengan yang hanya sekedar mengatakannya saja.
Jadi, esensi keparipurnaan manusia adalah dari kompetensi spiritualitas secara hanif, dengan kemampuan menyadari secara transedental tentang motif beragama sebagai fitrah ketuhanan dalam diri manusia yang ada sejak di alam rahim hingga akhir hayatnya.
Editor: Yahya FR