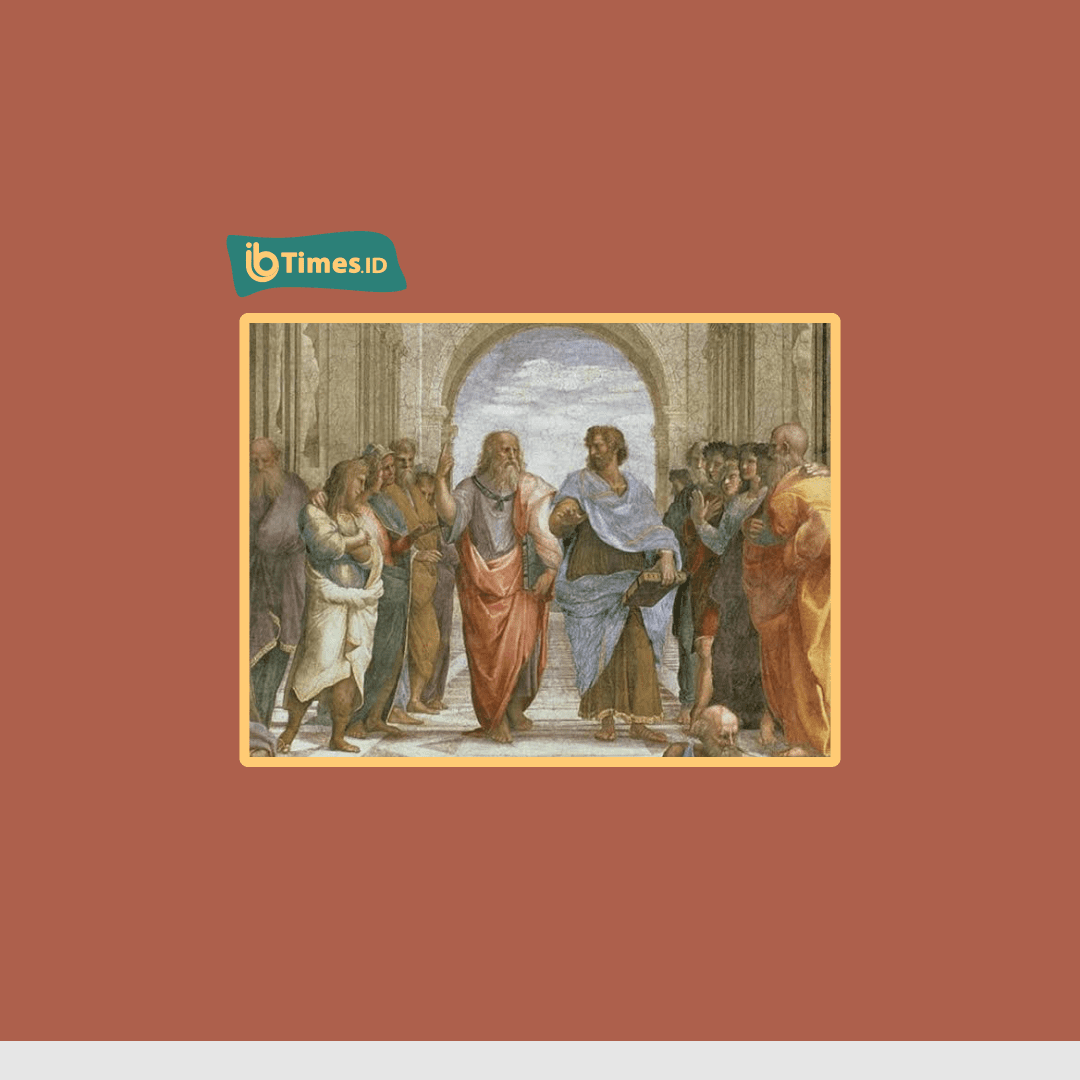Artikel ini akan mencoba menjelaskan secara ringkas bagaimana Plato dan Aristoteles merespon kaum Sofis. Saya akan menjelaskan bagaimana Plato dengan alegori gua dalam mencari suatu kebenaran merespons kaum Sofis saat itu. Sementara dalam pemikiran Aristoteles akan digunakan pendekatan tiga ranah ilmu untuk merespons Sofisme, terutama dalam isu politik. Saya berpendapat metode dari Plato dan Aristoteles bisa menjadi awal dalam berusaha memahami informasi, pengetahuan, dan “kebenaran” hari ini.
Alegori Gua dari Plato
Relativisme yang dibawa kaum Sofis lewat Protagoras, membawa doktrin bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Jika manusia menganggapnya demikian, maka demikianlah adanya. Dan jika tak demikian, maka tak demikian pula. Doktrin ini ditafsirkan, setiap manusia adalah ukuran segala sesuatu, dan jika manusia saling berbeda pandangan maka tak ada kebenaran objektif, benar ataupun salah. Doktrin ini bersifat skeptis dan didasarkan pada sifat indera manusia yang cenderung ‘menipu’. Sehingga, kebenaran menjadi tergantung pada manusianya itu sendiri. Tidak ada kebenaran sejati.
Kebenaran harus bisa diraih menurut Plato sehingga ia menawarkan teori Idea sebagai metode. Manusia memang mencari kebenaran, namun tolok ukur yang tentu saja ia dapatkan dalam jiwanya, mesti diukur oleh sesuatu di luar dirinya yang bersifat objektif yaitu Idea, yang dalam bentuk ultimanya bernama kebaikan. Bila Sofisme meletakkan manusia sebagai pusat, Plato akan mengembalikan lagi tempat manusia sebagai “makhluk antara” (Setyo Wibowo, 2016).
Alegori Gua adalah cara Plato menjelaskan bagaimana pengetahuan (kebenaran) itu dicapai. Tidak berhenti pada pemikiran awam atau opini/doxa, namun sampai pada pengetahuan sejati atau episteme. Dijelaskan bahwa di dalam sebuah gua, terdapat sekumpulan tahanan yang duduk bersandar di tembok dan kaki tangannya dirantai seumur hidup. Mereka hanya bisa memandang ke satu sisi tembok gua di depan tempat mereka duduk.
***
Di belakang mereka, dinyalakan semacam api unggun. Di depan api unggun tersebut, berkegiatanlah orang-orang. Bayang-bayang orang yang berkegiatan itu akan tampak pada tembok di depan para tahanan. Para tahanan akan melihat bayangan-bayangan tersebut sebagai realitas sepanjang hidupnya. Lalu ada seorang tahanan yang lepas. Ia dapat melihat ternyata bayang-bayang yang biasa ia lihat, hanyalah pantulan dari orang-orang di sekitar api. Kemudian ia terus berjalan sampai keluar gua. Setibanya di luar gua, ia melihat danau yang memantulkan bayangan sebuah pohon. Kemudian ia sadar bahwa di pinggir danau ada pohon yang terpantul di permukaan danau karena adanya matahari.
Penjelasannya sebagai berikut; bayangan yang dilihat para tahanan adalah opini dalam level paling rendah disebut conjecture. Bayangan adalah sekadar bayangan. Dia bukan realitas. Lalu, pada saat sang tahanan berhasil melihat bahwa di dalam gua ada api dan orang lain itu juga masih dalam level opini, tapi sedikit lebih jelas disebut dengan belief.
Sang tahanan mulai mungkin untuk percaya apa yang sebelumnya dilihat (indera mata) ternyata adalah api dan benda-benda yang menjadi sumber bayang-bayang. Saat ia keluar gua dan melihat bayangan pohon di danau, ia sudah mendapat pengetahuan yang disebut reason. Sang tahanan mulai mendapat bukti-bukti faktual, dapat diukur, matematis, tidak semata-mata inderawi, bahwa ternyata apa yang dilihat dalam gua, sangat jauh dari realitas di luar gua. Ia sudah semakin dekat dengan kebenaran.
Baru saat ia melihat bahwa ternyata memang ada pohon di pinggir danau yang terpantul oleh sinar matahari hingga muncul bayangan di danau, ia mendapatkan understanding atau pengetahuan sejati yang mengenalkan kita dengan Idea. Begitulah metode yang ditawarkan Plato untuk meraih kebenaran, sangat bertolak belakang dengan kaum Sofis.
Tiga Ranah Ilmu Aristoteles
Aristoteles membagi ranah ilmu menjadi tiga bagian. Yang pertama, ilmu teknis atau poiesis. Ilmu teknis ini mempelajari teknik-teknik dalam membuat sesuatu. Misalnya, teknik membuat jembatan, membuat gedung atau bangunan, hingga membuat pakaian. Dalam ranah ilmu ini, kebenaran tidaklah penting. Yang lebih penting adalah kegunaannya. Baju kegunaannya untuk dipakai oleh manusia, tidak penting apakah penjahit atau desainernya beragama apa, lulusan mana, dan sebagainya.
Ilmu kedua adalah ilmu teoretis, contohnya adalah ilmu matematika, fisika, teologi dan filsafat. Dalam ranah ilmu ini, berlawanan dengan ilmu teknis. Kebenaran, dalam teoretis, sangat penting. Kegunaan malah menjadi tidak penting. Contohnya adalah hasil penemuan secara teoretis yang sering kita temui di jurnal-jurnal keilmuan terakreditasi (peer-reviewed). Teori-teori baru tersebut tentulah benar, dilihat secara metodologis menghasilkan teori yang benar. Apakah teori itu berguna? Bisa jadi teori tersebut tidak berguna, paling tidak untuk hari ini. Kemudian hari nanti bisa jadi berguna. Meski tidak (belum) berguna, teori-teori atau hasil penelitian tersebut memiliki tingkat kebenaran karena sudah melalui proses penelitian yang ketat hingga berhasil tayang di jurnal.
***
Lalu, ranah ilmu terakhir adalah ilmu praksis. Dalam ranah ilmu ini, kebenaran tidak mutlak, tidak hitam, tidak putih, tapi abu-abu. Jadi tidak ada kebenaran maupun kesalahan mutlak. Untuk kegunaan, tidak mudah juga menentukannya. Ia tergantung dari kesepakatan agen-agen yang terlibat di dalamnya. Contohnya adalah ilmu etika dan politik.
Dilihat dari ketiga ranah ilmu tersebut, keahlian retorika kaum Sofis berada dalam ilmu praksis. Tidak ada kebenaran mutlak dalam ilmu praksis, begitu juga dengan tawaran dari kaum Sofis. Bagi mereka, kebenaran tidaklah penting. Yang lebih penting adalah memenangkan argumen, meski dengan argumen absurd sekalipun.
Kritik Aristoteles terhadap kaum Sofis, dapat dilihat dalam Buku Etika Nikomakea. Duke menjelaskan; Aristoteles menyatakan bahwa kaum sofis cenderung mereduksi politik menjadi retorik dan terlalu menekankan peran yang dapat dimainkan oleh persuasi rasional dalam ranah politik.
Bagi kaum Sofis, yang utama adalah bagaimana memenangkan argumen. Argumen yang benar adalah argumen yang menang. Kebenaran sesungguhnya tidaklah penting. Jika menggunakan pemikiran Aristoteles, kebenaran dan kegunaan dalam politik memang “abu-abu”, yang perlu diperjuangkan adalah mencari jalan keluar dengan pertimbangan rasional sesuai dengan habitus dan konteks.
Kaum Sofis 4.0
Kaum Sofis memang fenomenal. Mereka menjadi “musuh” Sokrates dan kemudian Plato. Mereka hadir di Athena saat polis tersebut sedang berjaya dan makmur. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang, bukan asli Athena.
Mereka datang untuk mencari uang dan nama besar. Caranya mencari uang adalah dengan menjadi tutor atau pengajar bagi kaum kaya Athena. Berbeda dengan para filsuf Athena yang memang pemikir tanpa harus ada iming-iming uang dalam berbagi ilmu.
Modus operandi kaum Sofis tidak berhenti mengikuti runtuhnya Athena sekitar lebih dari 2000 tahun lalu. Kita masih sering melihat cara kerja Sofisme di era 4.0. Apalagi dengan teknologi informasi secanggih sekarang, kebenaran menjadi barang mahal; atau kebenaran menjadi sesuatu yang relatif dan masing-masing pihak memaksakan kebenaran tersebut.
Bahkan, isu seperti korupsi saja masih ada yang merespons bahwa hal itu bukan kesalahan. Respons seperti; mungkin ia sedang butuh uang, mungkin ia dijebak, mungkin sang koruptor terjebak hutang dan “mungkin-mungkin” lainnya sangat sering kita dengar pada saat koruptor kena OTT. Satu yang pasti seharusnya adalah; korupsi itu salah. Titik.
Kebenaran bukan hal utama bagi kaum Sofis, kemenangan argumen yang lebih penting. Hal seperti ini juga sekarang sering kita lihat dalam perdebatan-perdebatan di media dan media sosial. Memenangi argumen menjadi telos (tujuan). Apakah argumen tersebut mengandung banyak kecacatan logika berpikir tidak jadi soal, yang penting adalah lawan bicara terdiam dan tidak bisa merespons lagi.
Gaya Sofisme memang masih tumbuh subur sekarang ini. Kita perlu lebih teliti dalam memercayai suatu informasi, meyakini opini, dan menyetujui argumentasi. Kita perlu tahu mana opini dan mana pengetahuan yang bersumber dari metode berpikir. Sumbangan metode berpikir dari Plato dan Aritoteles mungkin bisa jadi bahan pegangan menghadapi Sofisme 4.0.
Editor: Yahya FR