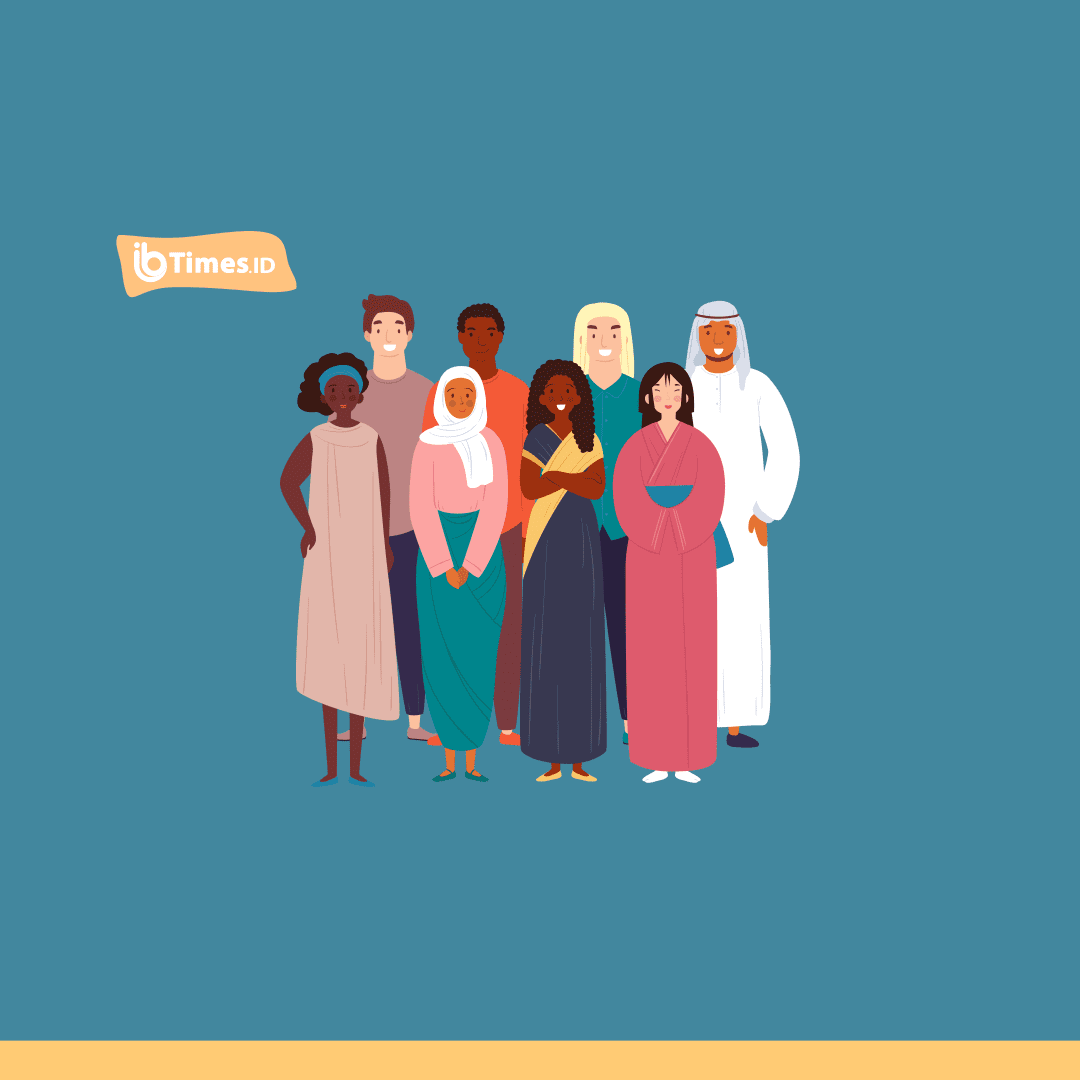Kalau agama hanya dipahami sebagai “gincu”, maka jangan heran apabila pemeluk agama hanya sibuk pada ritual ibadah mahdah yang mereka rasa langsung bertemu Tuhan dan tercerahkan dahaga spiritualnya. Sementara, hal-hal yang bersifat sosial dan kemanusiaan dianggap bukan bagian dari ibadah yang esensial. Jangan heran kalau kebodohan bertambah, kemiskinan tak terentaskan, busung lapar terjadi, kesengsaraan mendera kaum papa, dan kesulitan hidup diderita oleh sesama saudara kita: kaum termarginalkan!
Sementara itu, di tengah kepiluan kemanusiaan, orang kaya asyik masgul berwisata rohani berkali-kali, umrah dianggap penambah ‘gizi’ batin, sehingga dengan mudah uang digelontorkan untuk memenuhi spiritual pribadi yang “egois”; dan jutaan, bahkan milyaran uang dicairkan untuk kegiatan keagamaan baik atas nama umat beragama maupun ormas keagamaan.
Agama dan Kemanusiaan
Apakah bukan ibadah namanya, kalau menyelamatkan anak miskin yang kurang gizi? Apakah tidak esensi iman namanya, kalau tubuh-tubuh layu yang digerogoti penyakit dibantu pengobatannya? Apakah bukan amal saleh namanya, kalau menyantuni anak-anak fakir dan miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar SPP dan iuran sekolah? Apakah bukan subtansi beragama, kalau memberikan bantuan biaya berobat dan rumah sakit bagi keluarga kurang mampu yang terkapar tak berdaya di rumah sakit?
Tidaklah tepat menyalahkan kaum papa yang secara struktural mereka “dikalahkan” dalam kompetensi pembangunan. Mereka tersudutkan oleh nafsu serakah untuk meraih gensi, ambisi, materi dan kursi para pengenggam kekuasaan dan kebijakan, dan mereka dijadikan komunitas isu dan jargon atas nama rakyat oleh para perebut kekuasaan dan pejabat pemerintahan pada level manapun.
Itulah sikap keagamaan yang masih tubuh subur di kalangan pemuja agama dan pengikut kepercayaan pada Tuhan. Agama hanya sampai pada pengertian dan simbolik yang ada pada ritual, diartikan hanya dogma dan doktrin yang difatwakan dan dikhotbahkan para pemuka agama: agama “diberhalakan”. Sungguh ironi, agama belum menjadi “garam” yang mampu memberikan rasa dari kepahaman memaknai simbol ritualitas, subtansi dogma dan esensi doktrin, yang dipahami secara utuh, bening, suci dan tulus.
Purbasangka dalam Spiritualitas yang Dangkal
Ketidakberpihakan umat pada kemanusiaan disebabkan sebagian umat lebih bersikap acuh dengan penderitaan dan kesengsaraan orang lain. Sikap tersebut berarti menghidupkan Sunnah Sayyiah, yakni menganggap seseorang miskin karena bodoh, kurang semangat bekerja keras, tidak memiliki spirit berprestasi, fatalistis, apatis, jauh dari jiwa wirausaha-enterpreniurship, menyerah pada takdir dan menyalahkan nasib, serta menganggap mereka menderita dan sengsara dalam hidup karena dosa-dosa mereka dahulunya: “karma”.
Sehingga kebanyakan orang yang beruntung menganggap kemiskinan dan penderitaan sebagai masalah pribadi dan individu masing-masing, yang solusinya harus dicari sendiri oleh orang miskin tersebut. Itulah penyakit asosial yang akut saat ini!
Sedangkan, keberpihakan kepada kemanusiaan adalah wujud pelaksanaan Sunnah hasanah, yakni kebiasaan yang baik yang diimplementasikan dengan menggerakkan daya dan upaya umat Islam untuk bersama-sama membantu meringankan beban penderitaan dan kesulitan hidup sesama kaum Muslimin. Sehingga jiwa kemanusiaannya bangkit dengan kesadaran spiritual yang frekuensinya tinggi, yakni memandang kemiskinan dan penderitaan umat sebagai masalah sosial dan kemanusiaan yang solusinya mesti dilakukan secara kolektif melalui aksi sosial-kemanusiaan bersama-sama, baik ormas, pemerintahan, wakil rakyat, dan segala pemanggu kebijakan lainnya.
Purbasangka terhadap kaum dhu’afa dan mustadha’afin lainnya merupakan sikap keberagamaan dengan spiritualitas yang dangkal. Sungguh sebuah ironi kemanusiaan kalau umat beragama hanya mengejar “egoisme” spiritual pribadi, sementara kaum papa terkapar dalam penderitaan dan kesengsaraan yang akut. Dan kaum termarginalkan menggugat keadilan atas mereka sampil menegadahkan tangan setiap hari dari pintu ke pintu rumah warga.
Wujud empati tidak cukup dengan doa dan air mata saja, akan tetapi butuh bukti nyata dengan menunjukkan keberpihakan dan pembelaan terhadap kaum papa, kaum pinggiran, kaum dhu’afa, wong cilik dan mustadha’afin lainnya. Wujud ketulusan dan kejujuran beragama bukan pada dogma, doktrin dan ritual ibadah saja. Namun sikap hidup dalam pergaulan sosial dan kemanusiaan merupakan implementasi nyata kesalehan sosial yang sangat diperhitungkan Tuhan atas aksi hamba-Nya, kaum beriman.
Menganut Agama, Memperjuangkan Kemanusiaan
Menurut Nurcholish Madjid, dalam buku Islam, Kemodernan, dan Kemanusiaan, (Bandung; Mizan, 1987, h. 185-186), bahwa humanisme adalah sebuah agama baru hasil ciptaan manusia. Tidak seperti agama-agama lain, ia tidak berbicara tentang Tuhan. Tetapi, seperti agama-agama lain, ia membicarakan sesuatu yang sangat prinsipal, yaitu penentuan nasib manusia, dan penentuan tentang sesuatu yang bersifat suci. Dan mereka percaya bahwa humanisme berlaku di mana saja dan kapan saja: universal, malahan abadi.
Karena agama meniscayakan nilai-nilai kemanusiaan, maka sangat wajar kalau humanisme adalah sebuah “agama” baru hasil ciptaan manusia. Tidak seperti agama-agama lain, ia tidak berbicara tentang Tuhan. Sebab, kemanusiaan merupakan nilai sadar manusia; ia membicarakan sesuatu yang sangat prinsipal, yaitu penentuan nasib manusia, dan penentuan tentang sesuatu yang bersifat suci. Dan mereka percaya bahwa humanisme berlaku di mana saja dan kapan saja: universal, malahan abadi. Tentu humanisme bukanlah agama resmi, akan tetapi merupakan esensi dari agama dan sikap hidup manusia yang menganut agama.
Sungguh naif sekali kalau penganut agama melecehkan kemanusiaan atau apatis tentang nasib kemanusiaan dan masa depan kemanusiaan. Apapun agama dan keyakinan pasti menjadikan kemanusiaan sebagai elan vital yang mesti diselamatkan dengan kesadaran bersama umat manusia di bumi ini.
Humanisasi itulah makna yang tepat untuk menunjukkan keberpihakan kepada kemanusiaan, seperti pernyataan Kuntowijoyo yang dikutip Wan Anwar dalam buku Kuntowijoyo: Karya dan Dunianya, (Jakarta; Grasindo, 2007), h. 159) menjelaskan:
Humanisasi dilakukan dalam rangka melawan dan melenyapkan keadaan dehumanisasi yang melanda masyarakat modern sebagai dampak negatif kemajuan industri dan teknologi. Manusia mesin yang hanya memiliki satu dimensi, yang hanya dihitung sebagai angka dalam kalkulasi pasar dengan orientasi material, sepantasnya dikritik dengan mengedepankan semangat humanisasi (pemanusiaan). Segala tindak-tanduk manusia yang cenderung merendahkan derajatnya sebagai manusia dalam paradigma Tuhan harus diperbaiki.
Itulah kenyataan aktual di abad modernitas, bahwa dalam era industri kompetensi diri menjadi ukuran untuk meraih kehidupan bergensi, dan manusia di seperti robot yang dikendalikan sistem mekanik. Manusia pun dikalkulasi menurut kebutuhan, bursa pasar, dan dihitung sesuai dengan kebutuhan para pemilik modal dan pemilik saham. Nurani dan kemanusiaan hanya ilusi sunyi yang tidak terdengar dari hingar-bingar kehidupan kota dan nyaringnya desing mesin yang dioperasikan, serta hilang dalam megahnya gedung-gedung pencakar langit.
Memulihkan Kepedulian Kemanusiaan
Perjuangan untuk memulihkan kepedulian kemanusiaan dengan sikap empati dan welas asih tidak cukup dalam hitungan tahun. Akan tetapi, harus dirumuskan dan diperjuangkan dalam tindakan nyata dalam derap kehidupan yang kian bising ini. Mengapa demikian? Karena generasi penerus membutuhkan pandu sebagai penentu arah yang dituju dalam dimensi kemanusiaan dengan bimbingan agama.
Keterlenaan dalam dunia yang semakin sekulerisme, hedonisme, glamorisme, dan premisivisme, terkadang budaya negatif modern terwariskan pada anak-anaknya. Maka menjadi tanggung jawab umat beragama mengingatkan, bahwa humanisasi butuh sikap berani dan berpihak. Di situlah butuh kesabaran yang tinggi supaya nilai-nilai humanisasi menjadi watak umat beragama, menjadi karakter bangsa dan menjadi budaya manusia beradab.
Jadi kata Nurcholish Madjid, dalam buku Pesan-pesan Takwa: Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina, (Jakarta; Paramadina, 2000, h. 49), bahwa, sabar itu sendiri mempunyai dimensi waktu. Pembuktian kebenaran sejati memerlukan waktu. Menegakkan keadilan juga perlu waktu. Tidak bisa instan. Apalagi bila kebenaran itu menyangkut masyarakat yang besar. Di mana human investment atau tanaman kemanusiaan.
Waktu yang dibutuhkan untuk membuktikan hasilnya adalah satu generasi. Apa yang kita mulai sekarang ini, dalam skala besar, baru 20 tahun lagi akan betul-betul terwujud. Ahli pendidikan umumnya mengatakan, kalau kau tanam jagung, tunggulah tiga bulan baru panen, kalau kamu tanam kelapa, sabarlah lima tahun untuk panen. Tapi kalau tanamnya adalah human investment, mendidik manusia, menegakkan keadilan, dan sebagainya, maka kamu harus sabar menunggu satu generasi.
Kesesuaian Humanisme dan Islam
Untuk memperjuangkan nilai kemanusiaan yang sudah nestapa ini, sangat dibutuhkan kesabaran. Kesabaran yang melintasi ruang dan waktu. Karena perjuangan untuk kemunusiaan tidak bisa diukur dengan waktu, masa maupun batas akhir. Maka sabar dalam perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan kemanusiaan adalah tiada akhir.
Memang harus diakui, bahwa sabar itu sendiri mempunyai dimensi waktu. Maka pernyataan di atas sangat rasional, bahwa pembuktian kebenaran sejati memerlukan waktu. Menegakkan keadilan juga perlu waktu. Tidak bisa instan. Apalagi bila kebenaran itu menyangkut masyarakat yang besar. Di mana human investment atau tanaman kemanusiaan.
Dalam Islam, humanisme itu adalah relegius atau humanisme berdasarkan takwa kepada Allah Swt. Inilah yang kemudian juga dikembangkan oleh pemikir di Barat, termasuk John Loch, ketika dia merumuskan dan mengatakan bahwa hak asasi manusia itu tiga, yaitu life, liberty and property sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan Nabi Muhammad dengan life, property, and dignity. (Ibid, h. 162)
***
Kemanusiaan dalam perspektif Islam bukan hal yang baru, dalam Islam humanisme itu adalah relegius atau humanisme berdasarkan takwa kepada Allah Swt. Inilah yang kemudian juga dikembangkan oleh pemikir di Barat, termasuk John Loch, ketika dia merumuskan dan mengatakan bahwa hak asasi manusia itu tiga, yaitu life, liberty, and property sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan Nabi Muhammad dengan life, property, and dignity. Pendapat John Loch di atas secara kontekstual merupakan perpaduan konsep Islam dengan konsep Barat yang pada intinya keberpihakan pada kemanusiaan universal bukan parsial.
Dan John Loch pun mempertegaskan pendapatnya, bahwa: Julian Huxley, seorang humanis terkenal, tegas-tegas mengatakan bahwa humanisme adalah sebuah agama baru. Karena dia mempercayai akan adanya evolusi kemanusiaan dalam menemukan nilai-nilai kebenaran (sampai kebenaran terakhir), maka ia menamakannya humanisme evolusioner (evolutionary humanism).(Madjid, loc cit., h. 185)
Jadi, Julian Huxley, yang seorang humanis terkenal ini dengan tegas mengatakan bahwa humanisme adalah sebuah agama baru. Hal tersebut dikarenakan dia mempercayai akan adanya evolusi kemanusiaan dalam menemukan nilai-nilai kebenaran (sampai kebenaran terakhir), maka ia menamakannya humanisme evolusioner (evolutionary humanism).
Kasih-sayang di Bumi Diridhai di LangitNya
Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Orang-orang yang suka menyayangi mereka itu akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Kasihilah siapa yang berada di bumi, niscaya kamu akan dikasihani oleh yang berada di langit.”
Esensi yang terkandung pada pesan moral yang disampaikan Rasulullah Saw di atas adalah; bagaimanapun bentuk, rupa dan jenis makhluk Allah di muka bumi ini harus disayangi, kecuali beberapa jenis binatang yang membahayakan dan diharuskan untuk dihindari.
Spirit hadits itu, mengajarkan karakter kasih-sayang sesama ciptaan Allah, baik sesama manusia maupun dengan makhluk yang ada di alam semesta ini. Karakter kasih sayang merupakan wujud humanis dari pancaran sifat Rahman dan Rahim Allah yang dititipkanNya di kalbu manusia.
Suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan latar belakang sosial, politik dan ekonomi hanyalah identitas bukan prioritas ketakwaan di hadiratNya. Keberpihakan pada kemanusiaan, pembelaan pada kaum dhuafa, marginal, wong cilik, dan mustadha’afin lainnya, itulah esensi iman fungsional dalam kehidupan nyata.
Editor: Nabhan