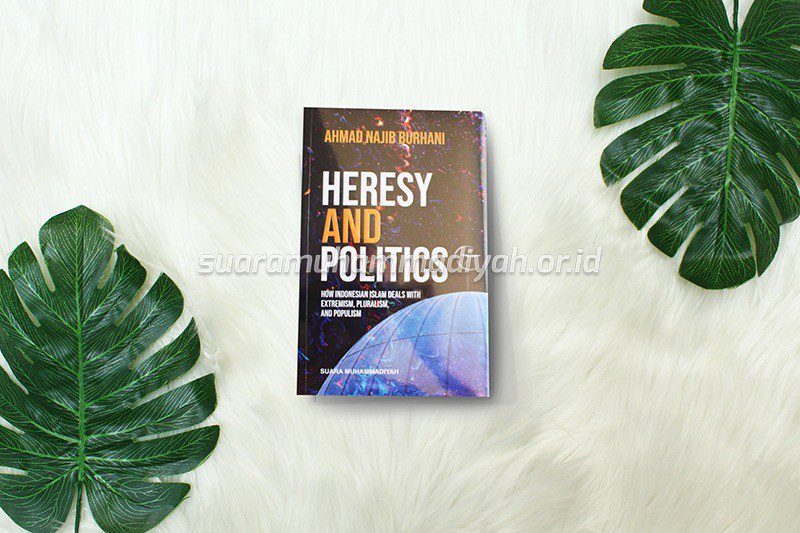Pernah suatu ketika dalam kuliah umum daring, Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia), Profesor Muhadjir Effendy menandaskan bahwa, “Ketika berhadapan dengan wabah pandemik COVID-19, kami berdoa mudah-mudahan kondisi kita tidak terlalu parah. Sekurang-kurangnya masih menyisakan akar.”
Harapan “menyisakan akar” ketika harus bertahan hidup di tengah kompleksitas yang dihadapi, mudah-mudahan akan kembali menumbuhkan batang yang hijau, kemudian trubus dan pada akhirnya menjadi pohon besar yang rimbun dan berbuah manis. Kurang lebih, itulah gambaran bangsa Indonesia.
Kita ini memang berhadapan dengan masalah yang berat, banyak dan kompleks. Kemudian, diperparah oleh merebaknya “pageblug” global virus Corona. Tapi barangkali, siapa saja yang mampu bertahan (asalkan tidak mati) dari segala cobaan yang ada, niscaya itulah mereka yang lebih kuat, digdaya, sakti, dan mampu membawa kemajuan.
Kompleksitas Islam Indonesia
Ahmad Najib Burhani, intelektual Muslim garda depan, memberikan catatan khusus mengenai “kompleksitas” bangsa dan spirit survival kita. Mengutip filsuf Friedrich Nietzsche, “Was mich nicht umbringt, macht mich starker”, ia menggarisbawahi, tantangan berat apa saja yang tidak membunuh diri kita – karena mampu bertahan, itulah yang membuat kita lebih kuat.
Nah, ternyata catatan khusus mengenai hal ini, oleh Najib dituangkan dalam karya terbarunya yang bertajuk “Heresy and Politics: How Indonesian Islam Deals with Extremism, Pluralism and Populism” (Suara Muhammadiyah, 2020). Survival yang dimaksudkan oleh Najib, terutama dalam konteks ujian bangsa Indonesia mempertahankan persatuan, kesatuan, dan kemajemukan.
Buku ini secara garis besar hendak menunjukkan adanya “puzzle” yang sudah disusun dengan baik. Puzzle yang mengisahkan bukan hanya tentang kompleksitas Islam Indonesia, namun juga bagaimana kompleksitas tersebut ternyata memiliki dampak yang signifikan pada proses marginalisasi kaum minoritas.
Dus, puzzle ini mengarah kepada argumentasi bahwa selama ini memang kepentingan politik yang memiliki relasi khusus dengan ekstremisme, lantas diledakkan citranya oleh tren populisme. Maka kemudian, marginalisasi terjadi terhadap mereka yang dianggap sebagai kelompok lain (liyan).
Bagaimana Puzzle ini Disajikan?
Profesor riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini membagi bukunya ke dalam tujuh bagian penting. Bagian pertama tentang politik identitas dan pergumulannya dalam konteks politik elektoral di Indonesia (h. 9-28). Bagian kedua, menyoroti betapa bukan hanya Muhammadiyah (yang terkenal puritan) lalu menjadi konservatif, namun juga ternyata petaka konservatisasi menghinggapi Nahdlatul ‘Ulama (NU) (kelompok tradisionalis yang selama ini dianggap paling moderat dalam beragama) (h. 29-44).
Bagian berikutnya, ia menunjukkan hubungan yang berat sebelah (dominatif) antara kelompok keagamaan mayoritas dan Ahmadiyah; representasi minoritas (h. 45-64). Bagian ini dilanjutkan dengan pembahasan tentang meningkatnya isu radikalisme dan terorisme (h. 65-88). Di tengah adanya proses dominasi yang represif terhadap Ahmadiyah, ternyata kaum Muslim tanah air juga sedang bersentuhan dengan aktivitas kelompok keagamaan garis keras. Semakin keras beragama, semakin berlaku tidak adil terhadap mereka yang tersisih.
Di bagian kelima, ia berupaya menengok bagaimana Muhammadiyah -yang selama ini diperjuangkan sebagai kekuatan masyarakat sipil Islam “moderat”- berhadapan dengan menjamurnya tren keagamaan dengan spektrum luas (bukan hanya ke kanan-radikal, tapi juga ke kiri dan liberal) (h. 89-122).
Setelah itu, intelektual muda Muhammadiyah ini mendiskusikan secara kritis, isu yang lebih umum namun tetap seksi: pem-Barat-an dan peng-Arab-an (Westerinzation and Arabization) (h. 123-145). Khusus mengenai hal ini, ia meletakkan bagaimana sebenarnya persoalan modernisasi memiliki dampak terhadap pandangan, cara, dan gaya dalam beragama.
Isu Pamungkas yang Dibahas
Bagian pamungkas dari buku ini membahas tentang Islam Indonesia dari segi ideologi, ritual, dan praktik sosialnya. Isu-isu menarik yang diangkat, ada tentang hijab, ibadah, dan wacana keagamaan sehari-hari lainnya (h. 147-164). Namun, bagian ini belum benar-benar menjadi penutup. Buku Najib Burhani juga menyajikan berbagai respon intelektual dari para kritikusnya, seperti Luthfi Assyaukanie (Peneliti di KITLV Leiden) (h. 134-137), Tufail Ahmad (peneliti di Middle East Media Research Institute, Washington) (h. 167-173), Bambang Muryanto (jurnalis di The Jakarta Post) (h. 174-176), Hasnan Bachtiar (h. 177-181), dan Mitsuo Nakamura (profesor emeritus di Chiba University, Jepang) (h. 182-186).
Buku ini secara bahasa, -karena ditulis dengan bahasa Inggris yang baik dengan cita rasa yang tinggi- sangat mudah dipahami. Benar-benar enak dibaca dan renyah. Mungkin karena penulisnya lama mengenyam pendidikan di Eropa dan Amerika (meraih doktor dari The University of California, Santa Barbara).
Buku ini secara substansial, cocok sekali dibaca oleh para sarjana, mahasiswa dan aktivis pro-minoritas, pembela HAM (human rights defender), pemerhati politik kebangsaan dan demokrasi Indonesia, serta siapa saja yang berminat menikmati kajian Islam Indonesia. Buku ini juga menarik dijadikan sebagai kado untuk para “survivor” kebhinnekaan di negeri tercinta ini. Akhirnya, belilah buku ini, anda tidak akan rugi!