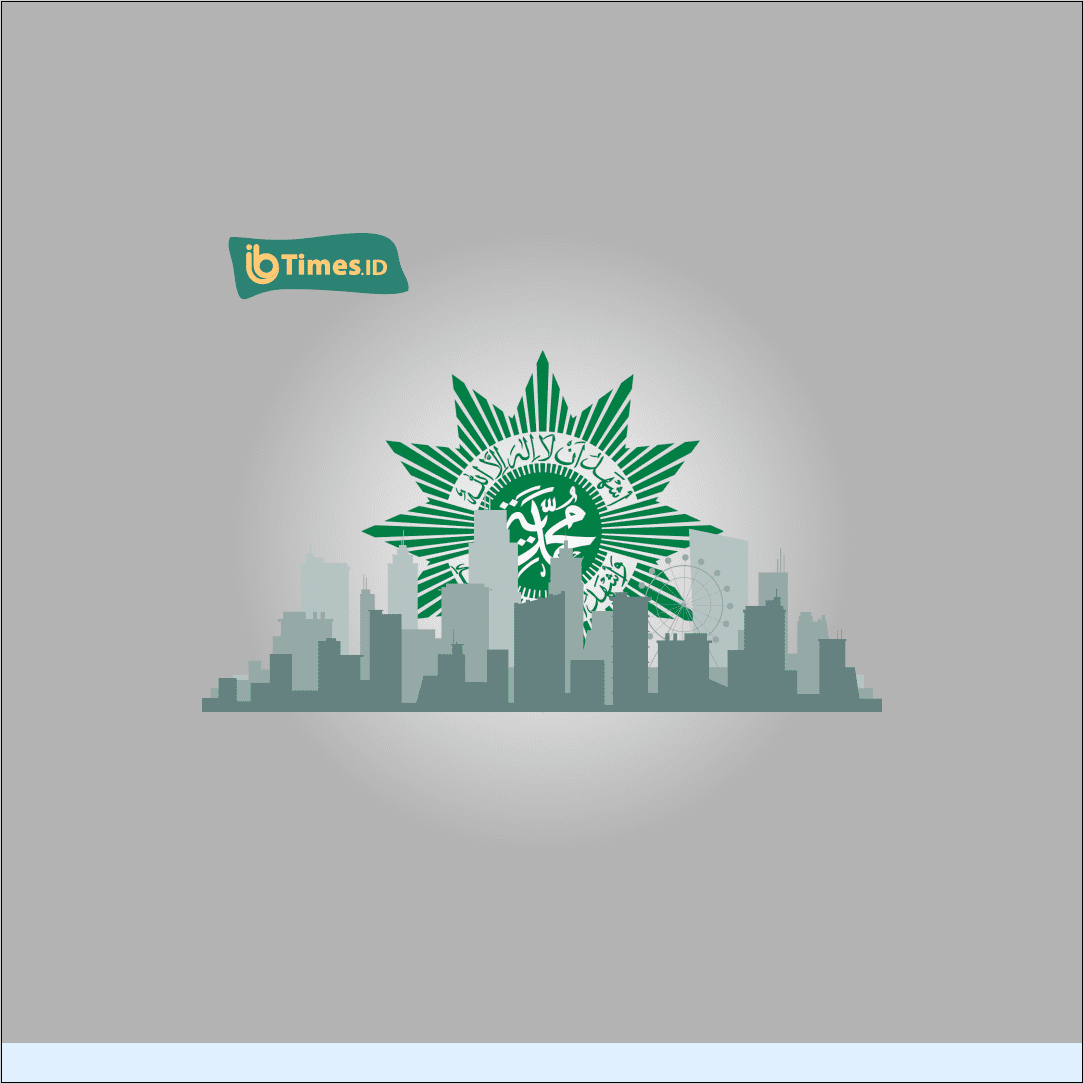Beberapa hari yang lalu, lewat IBTimes, Mr. Ode Prabtama menuliskan usulannya agar dibangun sebuah Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Muhammadiyah. Saya adalah salah satu yang beruntung dibolehkan membaca draf tulisan tersebut sebelum dimuat. Di ujung tulisan, Mr. Ode Prabtama secara persuasif meyakinkan pembaca kalau ide itu tidak mustahil.
Saya tahu, Mr. Ode Prabtama sudah lama gelisah dengan tiadanya STF Muhammadiyah, sementara kawan-kawan nasrani bergiat dengan filsafat hingga membangun sekelas sekolah tinggi. Kawan-kawan NU bahkan selalu punya simpul-simpul komunitas filsafat: di Kota Malang ada beberapa. Gus Dhofir Zuhry bahkan membangun STF al-Farabi di Kepanjen.
Sementara di kalangan kita, Muhammadiyah, simpul semacam itu jarang. Ada pun hanya embrio. Tradisi filsafat telah digalakkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah―sekurang-kurangnya di Malang. Filsafat masuk ke dalam silabus Darul Arqam Dasar, juga intens dikaji berbulan-bulan di komisariat, dianggap sebagai bekal wajib bagi kader baru.
Tantangan membangun STF tidaklah berat. Mungkin hanya akan diseneni. Sebab label filsafat sudah telanjur jelek dan diidentikkan dengan sikap liberal. Padahal, di Muhammadiyah terdapat rekam jejak pertarungan kubu konservatif dan progresif (yang dianggap liberal), yang memuncak tahun 2005 dan menguat kembali sepanjang persaingan Jokowi-Prabowo.
Namun, tantangan semacam itu bukanlah tantangan. Sudah menjadi darah daging Muhammadiyah untuk berjuang sambil diseneni, tapi setelah perjuangan itu menampakkan hasil, mereka yang nyeneni akan mengikuti. Tantangan yang lebih riil adalah bagaimana memulainya, bagaimana merawat istiqomah dan memahami urgensi.
Urgensi STF Muhammadiyah
STF Muhammadiyah, bila PP Muhammadiyah mau mendukung, hakikatnya bukan sekadar sekolah filsafat. STF Muhammadiyah, dalam imajinasi Mr. Ode Prabtama, adalah alternatif pendidikan Muhammadiyah, suatu kampus yang tidak tunduk pada dogma kemajuan yang latah ditiru oleh kampus Islam, tak terkecuali kampus Muhammadiyah.
Tetek bengek scopus, misalnya, yang dikejar secara karikatif dan kerap mendorong pemuatan jurnal secara transaksional, STF Muhammadiyah harus menghapusnya. Dosen STF Muhammadiyah seyogianya fokus saja membangun pengetahuan. Membaca buku sebaik-baiknya, menulis sebaik-baiknya, berdiskusi semarak-maraknya. Produksi, bukan replikasi.
Kerja semacam itu hanya bisa lahir bila kampus ada iklim intelektual yang pekat, bukan sibuk menjual citra dan berlomba menambah jumlah mahasiswa (baca: menambah kapital). STF Muhammadiyah bisa memelopori upaya ‘menjauh’ dari ‘hiruk pikuk’, mulai ‘berpuasa’, ‘bertirakat’, dan ‘berkhidmat’ melahirkan pelajar sungguhan, bukan budak industri.
Kerja semacam itu juga bisa lahir dari kampus yang tidak terlalu banyak perayaan tawa aktivitas-aktivitas non akademik yang menyita waktu dosen sebagai seorang akademisi. Birokrasi dibuat ramping, seremonial dibuat sederhana, sehingga dosen menjadi semakin produktif dan dana kampus bisa dimaksimalkan untuk edukasi. Perayaan secukupnya sajalah.
STF Muhammadiyah, dalam imajinasi saya untuk menyempurnakan imajinasi Mr. Ode Prabtama, juga tidak membebankan biaya pendidikan yang tinggi pada mahasiswa (yang tidak perlu banyak jumlahnya itu). Aturan kampus juga tidak usah terlalu ruwet, namun diiringi konsekuensi, yakni mahasiswa harus siap diberi perkuliahan berstandar tinggi, digembleng dengan tuntutan-tuntutan membaca, menulis, dan berdiskusi.
Artinya, STF Muhammadiyah harus punya sumber dana dari luar, untuk operasional pendidikan dan kesejahteraan guru. Saya kira, Muhammadiyah tidak kurang kaya pengalaman dalam hal ini. Pendidikan Muhammadiyah sejak mula memang membebaskan biaya bagi umat sehingga sekolah harus mandiri mencari sumber dana lain, seperti amal usaha, funding, dll. Prinsip itu, harus diakui, mulai memudar.
Urgensi STF Muhammadiyah lainnya adalah kehadirannya sebagai think tank paradigma gerakan bagi Muhammadiyah di berbagai sektor.
Ambillah misal sektor pendidikan, STF Muhammadiyah harus mampu memikirkan dan merekomendasikan jalan keluar bagi problem linearitas, agar saran-saran mengenai “kesaling-sapaan ilmu” tidak disuarakan oleh individu semata (contoh: Prof. Amin Abdullah).
Pada sektor lingkungan hidup misalnya, STF Muhammadiyah harus mampu merekomendasikan dekonstruksi etika dan cara pandang mengenai manusia di bumi dalam hal relasinya dengan lingkungan hidup.
Mendukung Impian Mendirikan STF Muhammadiyah
Tentu saja saya antusias dengan usulan Mr. Ode Prabtama agar Muhammadiyah mendirikan sebuah STF. Sebab, usulan itu tidak ada hubungannya dengan mengejar tren. Ia lebih merupakan suatu kebutuhan yang terinspirasi dari prinsip-prinsip lugas sekolah-sekolah tinggi filsafat di Indonesia―yang umumnya diasuh oleh komunitas Kristiani.
Apakah boleh bagi kita terinspirasi dari orang Kristen? Lebih jauh lagi, apakah boleh umat Islam menggunakan ilmu yang dikembangkan oleh Barat-Kristen?
Bagi saya, boleh, dan saya menyarankan untuk membaca buku-buku bagus di seputar topik ini. Ada karya-karya Nidhal Guessoum, ada karya-karya Tariq Ramadan.
Dalam konteks beragama, filsafat bisa mendorong umat mengupas lebih dalam dan detail kebenaran Islam hingga sampailah umat pada kebijaksanaan bahwa di dunia ini tidak ada yang patut diberi pujian kecuali Allah. Kebijaksanaan itu bisa berupa wajah umat yang moderat dan cendekia.
Kebijaksanaan lahir dari pergelutan akal budi secara maksimal. Pada akhirnya, “Kalau mau belajar sesuatu,” dawuh Kiai Dahlan pada suatu senja, “kamu harus berprasangka baik.”
Wallahu a’lam bisshawab.
Editor: Lely N