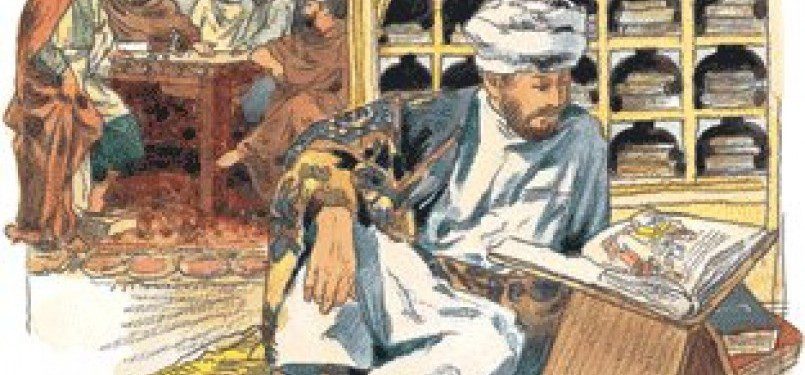Kita tahu, bahwa Najmuddin Al-Thufi (w. 716 H/1316 M) adalah ulama dalam Mazhab Hambali yang terkenal dengan konsep ri’ayah al-mashlahah (memelihara kemaslahatan). Ia berpendapat bahwa ri’ayah al-mashlahah sebagai tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum, merupakan sesuatu yang mesti diutamakan, sekalipun terkesan bertentangan dengan nash dan ijma’.
Hadits Nabi Saw yang berbunyi, “La dharara wa la dhirar,” cukup menginspirasi Al-Thufi dalam memaknai ri’ayah al-mashlahah ini. Apalagi jika dihubungkan dengan dalil-dalil lain dalam al-Qur’an dan sunnah, yang semuanya bermuara kepada pemeliharaan kemaslahatan dan menolak segala yang berpotensi membawa kepada kerusakan dan bahaya.
Tentu saja, jalan pikiran Al-Thufi, dalam hubungannya dengan ri’ayah al-mashlahah ini. Ia menjelaskan bahwa nash dan ijma’ adalah dua dalil hukum yang secara umum tidak menghendaki adanya kemudharatan atau mafsadat dalam kehidupan, melainkan kedua dalil itu menghendaki adanya ri’ayah al-mashlahah dalam setiap penetapan hukum.
Itu sebabnya, ketika menjadi pertentangan antara ri’ayah al-mashlahah dengan nash dan ijma’ di sisi lainnya, maka yang harus diutamakan adalah ri’ayah al-mashlahah, karena ia merupakan dalil yang disepakati, baik oleh nash, ijma’, maupun ulama.
***
Tak hanya itu, Najmuddin Al-Thufi membagi maqashid asy-syari’ah itu kepada dua bagian. Pertama, maqashid asy-syariah yang berkenaan dengan hak Allah Swt semata, yaitu hal-hal yang yang berkenaan dengan ibadah. Kedua, maqashid asy-syariah yang tidak berhubungan langsung dengan hak-Nya atau berada di luar hak Allah Swt, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan persoalan kehidupan manusia sehari-hari (muamalah).
Menurut Al-Thufi, berkenaan dengan persoalan ibadah yang merupakan hak Allah Swt semata. Sedangkan ri’ayah al-mashlahah hanyalah ditentukan oleh Allah Swt dan manusia tidak berwenang menentukannya. Adapun tentang ri’ayah al-mashlahah yang berhubungan dengan muamalah, maka manusialah yang menentukan dan menilai maslahah atau tidaknya sesuatu tersebut. Bahkan, menurut Abudul Wahhab Khalaf, maslahah dalam pemikiran Al-Thufi adalah dalil yang paling kuat secara mandiri dan dapat dijadikan alasan penetapan hukum syara’.
Salah satu alasannya bahwa maslahah itu merupakan dalil yang disepakati oleh semua ulama. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa syariat yang diturunkan Allah Swt bertujuan sepenuhnya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.
Hal ini menempatkan maslahah pada tempat yang lebih utama. Ini juga terlihat ketika terjadi pertentangan antara maslahah dengan nash dan ijma’, maka yang dijadikan pegangan itu adalah maslahah, bukan nash ataupun ijma’. Tentunya, sekali lagi, hal ini berlaku dalam bidang muamalah.
Empat Konsep Maslahah Najmuddin Al-Thufi
Bahkan, lebih lanjut, dalam mengutarakan teori maslahah-nya, Najmuddin Al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama. Masing-masing prinsip merupakan kerangka utama yang dijadikan Al-Thufi sebagai pijakan epistemologinya. Empat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, istiqlal al-uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid. Prinsip ini menjelaskan bahwa akal manusia secara independen dapat menemukan maslahah dan mafsadah. Namun demikian, independensi rasio dalam menemukan maslahah ini bukanlah pada semua bidang termasuk ibadah. Namun Al-Thufi membatasi hanya pada bidang muamalah serta adat-istiadat (bukan ubudiyyah).
Prinsip pertama Al-Thufi yang mengedepankan peran rasio ini jelas sangat berbeda dibandingkan dengan para ushuli yang lain, yang mengakui maslahah sebagai sumber hukum setelah ditunjukkan oleh hukum serta terjustifikasi oleh nash. Independensi akal bagi Al-Thufi akan semakin tampak ketika menyimak dari ungkapannya, “Amma mashlahah siyasah al-mukallafin fi huquqihim fahiya ma’lumatun lahum bi hukmi al-adah wa al-aqli.”
Perlu dipahami, bahwa yang dimaksud Al-Thufi dengan yang kemampuan akal mengetahui maslahah dan mafsadah ini hanya dalam hal muamalah dan adat-istiadat, sedangkan dalam hal ibadah, akal tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui maslahah dan mafsadahnya.
Kenapa demikian? Karena menurut Al-Thufi ibadah merupakan ranah eksklusif dan prerogatif Allah Swt. Hanya Allah-lah yang mengetahui rahasia suatu ibadah, waktu, jumlah, dan tempatnya. Berkaitan dengan ini, Al-Thufi mengatakan, “Dalam masalah ibadah, manusia berstatus sebagai seorang hamba yang harus mengikuti tuannya. Dengan mengikuti keinginan tuannya, maka berarti hamba tersebut telah berbuat kebaikan.”
***
Kedua, al-mashlahah dalilun syar’iyun mustaqillun an-nash. Dari ungkapan ini bisa dimengerti bahwa, dalam pandangan Al-Thufi, maslahah merupakan dalil syar’i yang independen. Dalam pengertian Al-Thufi, maslahah tidak memiliki ketergantungan kepada kesaksian atau konfirmasi nash, melainkan cukup bergantung kepada akal. Dalam pernyataan Al-Thufi bahwa untuk menyatakan semua itu maslahah atau bukan, maka cukuplah dengan uji coba lewat adat-istiadat dan tidak perlu membutuhkan petunjuk nash.
Demikian juga, dalam pandangan Al-Thufi, apresiasi terhadap maslahah tidak sebegitu spesifik sebagaimana para ushuli merincikannya. Namun, bagi Al-Thufi, sesuatu itu dianggap maslahah atau tidaknya cukup dilihat bagaimana sesuatu itu termasuk maslahah, atau sebaliknya, mafsadah. Di sinilah tampaknya Al-Thufi lebih memprioritaskan akal sebagai epistemologi hukum Islam dalam posisinya yang independen.
Ketiga, mashlalah dalil syar’i li al-mu’amalah wa al-adah. Maslahah sebagai dalil syar’i lapangan (objek), penggunaannya terbatas dalam bidang muamalah dan bidang adab. Dengan demikian, maslahah menurut Al-Thufi tidak bisa menjamah pada bidang yang bersifat ritual (ibadah). Dalam bidang ibadah, menurut Al-Thufi, yang berhak hanyalah Allah semata. Di sini akal tidak punya wewenang untuk menentukannya.
Dengan kata lain, akal hanya meneruskan aspek kelestarian dari ibadah itu sendiri. Sedang aspek perubahan itu pada wilayah muamalah serta adat. Hal ini bersesuaian dengan ungkapan Al-Tuhfi yang menyatakan sebagai haqq al-Syari’. Artinya, bagi Al-Thufi, akal manusia tidak sanggup untuk menembus rahasia maslahah di balik ibadah.
Keempat, al-mashlahah aqwa adillah al-syar’i. Dari ungkapan ini bisa dimengerti bahwa dalam pandangan Al-Thufi ada sembilan belas dalil syar’i yang bisa dijadikan sebagai metode istinbath al-ahkam. Dalil-dalil tersebut antara lain: Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ al-Ummah, Ijma’ Ahl al-Madinah, Al-Qiyas, Qaul al-Shahabi, Al-Mashlahah al-Mursalah, Al-Istishab, Al-Bara’ah al-Ashliyyah, Al-Awaid, Istiqra’, Sad adz-Dzari’ah, Al-Istidlal, Al-Istihsan, Al-Akhdzu bi al-Akhaf, Al-Ishmah, Ijma’ Ahlu al-Kufah, Ijma’ al-Itrah, Ijma’ al-Khulafa ar-Rasyidun.
Kesimpulan
Jelas sudah bahwa Al-Thufi menjabarkan adanya sembilan belas dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalam istinbath al-ahkamh. Namun, dalam pandangan Al-Thufi, dalil yang paling kuat untuk digunakan adalah nash dan ijma’. Dan, ketika terjadi pertentangan antara maslahah dengan nash dan ijma’, maka jalan yang ditempuh Al-Thufi adalah memenangkan maslahah dibanding nash dan ijma’.
Dari sini bisa dipahami bahwa maslahah sebagai dalil (sumber) hukum tidak saja fungsional ketika nash dan ijma’ tidak mengcovernya, melainkan juga fungsional ketika nash dan ijma’ terjadi pertentangan. Ini mengindikasikan bahwa, Al-Thufi sangat mementingkan maslahah dibandingkan dalil yang lain. Dalam keadaan semacam ini, Husein Hamid Hasan berkesimpulan bahwa maslahah bagi Al-Thufi merupakan dalil syar’i yang paling kuat secara mutlak.
Itu artinya, sekiranya terjadi pertentangan antara nash dan ijma’ di satu sisi dengan maslahah di sisi lain, maka maslahah di sini harus dimenangkan (diutamakan) karena tujuan lebih utama dibandingkan dengan sarana. Sedangkan nash dan ijma’ tidak lebih sebagai sarana mencapai tujuan itu sendiri, yaitu kemaslahatan.
Alasan tersebut tampaknya bersesuaian dengan apa yang diungkapkan Al-Thufi: “Karena maslahah merupakan tujuan (maqshudah) dari seorang mukalaf dalam menetapkan hukum, maka mengesampingkan dalil sebagai sarana atas maslahah sebagai tujuan menjadi urgen (wajib), karena tujuan harus didahulukan daripada sarana.”
Dari sini kita tahu, bahwa kecenderungan Al-Thufi untuk memprioritaskan maslahah dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain sangat kentara. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa maslahah di sini berperan sebagai substansi dari hukum itu sendiri. Wallahu a’lam bishawab.
Editor: Soleh