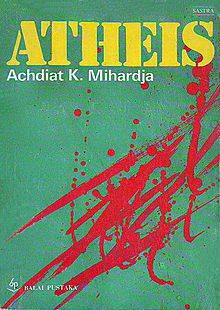Taqlid buta adalah fenomena yang dapat dijumpai dalam berbagai aliran pemikiran dan keagamaan di sekitar kita, termasuk dalam agama Islam. Dalam novel Atheis, Bung Achdiat Karta Mihardja menggambarkan problem kehidupan seorang Hasan yang terjebak dalam taqlid buta dan berbagai tantangan dan catatannya.
Tentang Hasan, Tokoh Utama ‘Atheis’
Hasan adalah seorang tokoh utama dalam novel Atheis. Dalam novel Atheis tersebut, Hasan digambarkan sebagai seorang yang lahir dalam lingkungan keluarga yang religius. Ayahnya adalah seorang pensiunan mantri guru yang alim dan saleh. Hidupnya banyak diisi untuk beribadah kepada Allah, begitu pun juga ibunya. Kelak, mereka berdua belajar tarekat kepada Kiyai Mahmud di Banten setelah mendapat nasehat dari Kiai Haji Dahlan yang masih sekeluarga dengan ibunya.
Sedari kecil, Hasan sudah diajari salat dan mengaji oleh kedua orang tuanya. Novel Atheis menggambarkan awal mula taqlidnya dengan Hasan dicekoki dogma-dogma tentang surga dan neraka yang ia patuhi tanpa ada kesangsian. Dan, ia tak pernah sedikitpun melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai dogma-dogma tersebut.
Saat sudah dewasa dan bekerja di gemente (Kotapraja), ia pun bertekad belajar tarekat kepada Kiai Mahmud di Banten. Walau sebenarnya, tekad ini dipicu oleh perasaan kecewa akibat diinggal kekasihnya, Rukmini. Bung Achdiat menuliskan perilaku Hasan semenjak belajar tarekat, Hasan menjadi semakin rajin beribadah. Terlebih, ia sanggup melaksanakan amalan-amalan yang berat seperti, puasa tujuh hari tujuh malam, mandi di Kali Cikapundung selama empat puluh kali dalam satu malam, dan mengunci diri dalam kamar selama tiga hari tiga malam dengan tidak tidur, makan dan tidak bercakap-cakap dengan orang lain.
Sejak itulah, ia merasa sudah menjadi manusia sempurna dan berangan-angan ingin menginsyafkan orang lain. Namun, setelah cukup lama menjalankan amalan yang berat itu, pekerjaan kantornya menjadi terbengkalai, wacahnya kian pucat, dan kemudian terkena penyakit TBC.
Menghadapi Syubhat Dunia
Meski demikian, rencananya akhirnya tercapai saat ia bertemu Rusli (kawannya saat kecil). Rusli adalah seorang yang berpaham materialisme dan berpikir radikal terhadap segala hal. Saat itu, Rusli bersama Kartini. Kartini adalah perempuan yang dipaksa ibunya menikah dengan rentenir tua Arab demi menggaruk kekayaannya. Namun, setelah ibunya meninggal, ia segera meninggalkan rentenir itu dan akhirnya menjadi janda muda.
Achdiat Karta Mihardja menuliskan konflik Hasan dengan mereka, bahwa mereka menempuh jalan yang menyimpang dari moralitas Islam. Karena itu, Hasan mengklaim mereka sebagai orang kafir dan berinisiatif menginsafkannya. Apalagi sejak pertama kali melihat Kartini ia sudah memendam rasa kepadanya. Namun, Rusli yang sudah belajar banyak ilmu pengetahuan justru mencabik-cabik keimanannya. Lebih-lebih, saat ia menegaskan bahwa “Tuhan tidak ada, saudara” (halaman 67).
Perkenalannya kemudian dengan Anwar (seniman anarkis) yang mendaku bahwa Tuhan itu aku sendiri (halaman 180), telah menimbulkan gejolak dalam keimanannya. Fondasi keimanannya pun kemudian roboh setelah mendengarkan uraian dari Bung Parta (kawan Rusli yang dituaakan) dalam sebuah pertemuan bahwa Tekniklah tuhan kita (halaman 120).
Pertentangan Hasan dengan Orang Tua
Suatu hari ia pulang ke rumah orang tuanya bersama Anwar. Tidak seperti biasanya, pulangnya kali ini malah membawa kesedihan. Bagaimana tidak, ia berani berdebat dengan ayahnya perihal agama dan Tuhan hingga ayahnya tak bisa berkutik. Tak syak lagi ayahnya kemudian berkata:
“Kalo begitu, baiklah kita berpisah jalan saja. Kau sudah mendapat jalan sendiri, ayah dan ibu pun sudah ada jalan sendiri. Jadi, baiklah kita bernapsi-napsi saja menempuh jalan masing-masing (halaman 168).”
Orang tuanya akhirnya menjadi sedih. Kesedihan ini kian menyesakkan kala ia mengutarakan niat untuk menikahi Kartini. Mereka tentu tidak setuju mengingat ia akan dijodohkan dengan adik pungutnya, Fatimah. Namun, ia tetap bertekad menikahi Kartini karena ia telah berhasil mengambil hatinya.
Perselingkuhan Kartini dan Tobat Hasan
Sayangnya, setelah menikah dengan Kartini bukan kebahagiaan yang berbuah, melainkan bencana. Betapa tidak, Kartini sering jalan bersama dengan lelaki lain, terutama Anwar, yang mengakibatkan Hasan terbakar api cemburu.
Hingga suatu hari, diceritakan dalam novel Atheis, saat Kartini pulang sehabis jalan-jalan dengan Anwar, Hasan menumpahkan seluruh api itu. Kartini dibentak-bentak dan dipukuli hingga ia kemudian kabur dari rumah. Saat berada di jalan, ia bertemu dengan Anwar. Anwar kemudian mengajaknya pergi ke penginapan. Namun, Anwar justru hendak memperkosanya, yang akhirnya memaksanya lari ke Kebon Manggu.
Setelah kejadian kaburnya Kartini itu, Hasan menyesal telah berperilaku bengis kepadanya. Ia juga menyesal telah durhaka kepada orang tuanya dan terutama kepada Tuhan. Karena itulah, ia mengutuki teman-temannya yang mengubahnya menjadi ateis. Ia kemudian bertekad kembali berpedoman pada ajaran Islam. Tekad ini kian mantap mengingat ia diusir oleh ayahnya saat sedang menenaminya menghembuskan nafas terakhir.
Sayang, hal tersebut belum sempat terlaksana, karena ia ditembak mati saat peristiwa kusuheiko setelah ia pulang menjenguk ayahnya. Di sela-sela kematiannya, ia berhasil mengucapkan ‘Allahu Akbar’, sekalipun dengan bersusah payah.
Taqlid Buta dan Kafir-Mengkafirkan
Melalui novel Atheis ini, Achdiat Karta Mihardja sebenarnya ingin memukul palu godam terhadap kondisi masyarakat saat itu yang diselimuti oleh taqlid buta dan gampang mengkafirkan orang lain dalam beragama. Mereka yang taat mutlak atas dogma-dogma kaku, dan mengingkari akal kritis dalam beragama. Biasanya, mereka mengklaim cara beragamanya lah yang paling benar. Oleh karenanya, mereka gampang mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan dengannya.
Novel Atheis ini ditulis oleh Achdiat Karta Mihardja pada tahun 1949. Jika ditarik mundur sembilan tahun, Soekarno sudah mengemukakan pandangan yang seperti itu melalui artikelnya yang berjudul ‘Islam Sontoloyo’ di Panji Islam. Dalam artikel itu, Soekarno mengecam habis-habisan orang islam yang berpandangan sontoloyo.
Dua di antaranya adalah orang yang mengurung akal kritis (taqlid buta) dan gampang mengkafirkan orang lain. Baginya, ajaran Islam itu tidak kaku, dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan konteks zaman. Sehingga, diperlukan akal yang bebas untuk mencapai itu. Jika tidak demikian, kata ‘kafir’ mudah sekali keluar dalam mulutnya. Ulama-ulama pada masa itu mengangap karya Soekarno ini sebagai manifesto pembaharuan Islam.
Pandangan mereka mirip dengan sosok mufti besar Mesir pada akhir abad ke-19 yakni Muhammad Abduh. Menurut Abduh, keterbelakangan umat Islam saat itu berpangkal pada kejumudan (beku) akibat taqlid buta terhadap dogma-dogma Islam. Sehingga, Islam kemudian kehilangan otentisitasnya. Pada posisi inilah, ia menyerukan pentingnya menggunakan akal kritis dalam beragama. Kelak, pemikirannya ini sedikit-banyak mengilhami generasi pembaharuan islam tahun 90-an di Indonesia.
Tampaknya dalam konteks sekarang pandangan-pandangan demikian tetap relevan digunakan mengingat masih banyak orang di Indonesia beragama dengan taqlid buta dan gampang sekali mengkafirkan orang lain.
Editor: Shidqi Mukhtasor/Nabhan