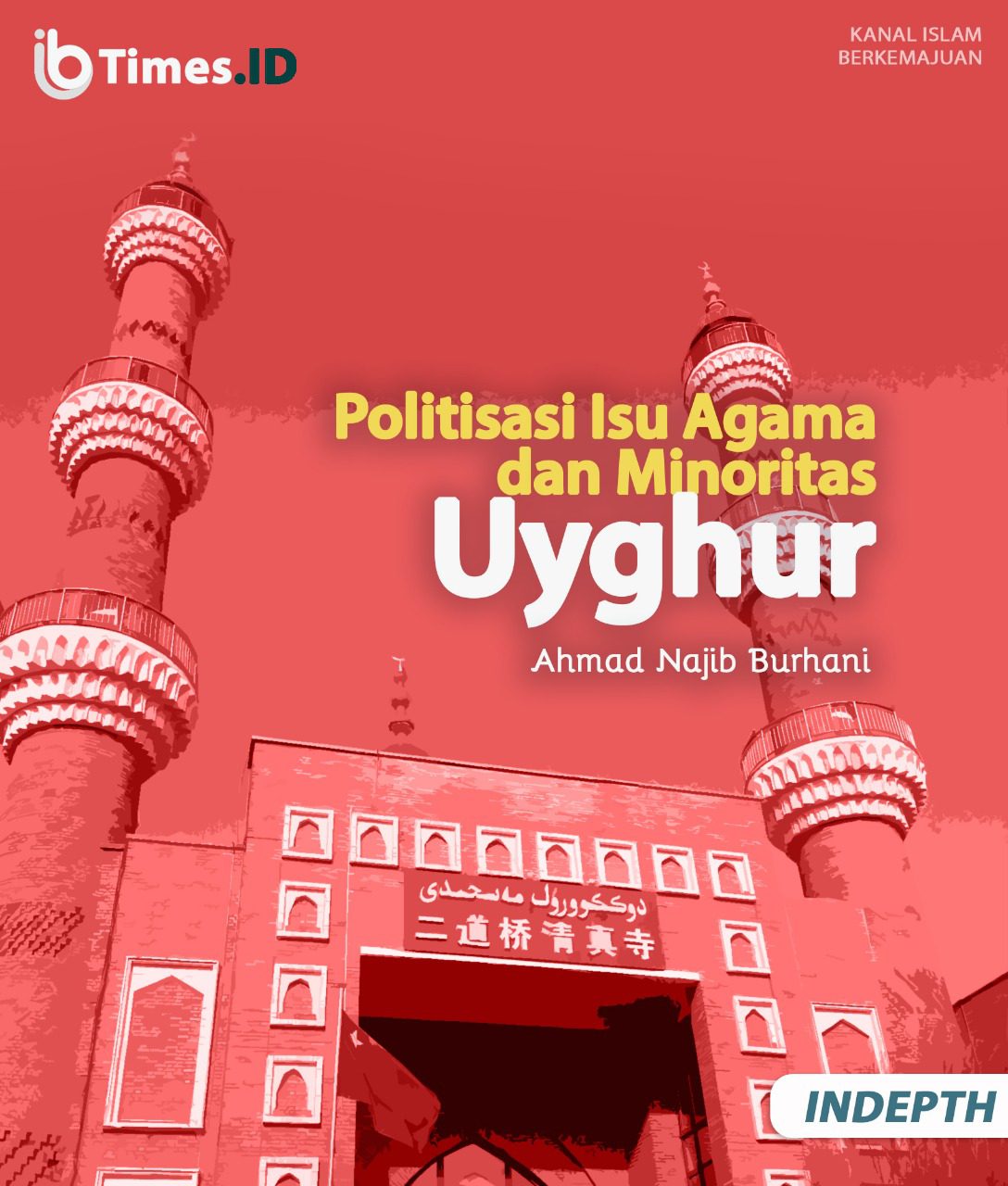Oleh : Ahmad Najib Burhani*
Nasib minoritas Muslim di negara lain sering menjadi isu besar di Indonesia, baik itu terkait Rohingnya di Myanmar, Uyghur di Tiongkok, maupun komunitas Muslim di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan juga Australia dan Selandia Baru. Jika mendapat kabar bahwa mereka mendapat diskriminasi atau penindasan, baik benar maupun hoax, maka berbagai demonstrasi berseri pun sering digelar di berbagai kota di Indonesia dan terutama di depan kedutaan besar negara terkait.
Beberapa demonstrasi juga acap diadakan di depan kantor pemerintah Indonesia dan menuntut keterlibatan lebih banyak dari pemerintah dalam ikut serta membantu menangani nasib minoritas Muslim di negara lain. Kadangkala, sebagian dari kita seakan lebih peduli terhadap minoritas Muslim di negara lain daripada minoritas di negeri sendiri. Atau bahkan, sambil meneriakkan pembelaan kepada nasib yang menimpa minoritas di negara lain, mereka melakukan diskriminasi terhadap minoritas di negeri sendiri.

Isu semisal Uyghur dan Rohingya seringkali menjadi komoditas politik dengan label “solidaritas”. Karena eratnya solidaritas dalam Islam, kerap kali isu-isu ini menjadi bungkus dari aktivitas yang dilakukan oleh berbagai kelompok konservatif dan radikal untuk menggalang massa dan dana demi tujuan-tujuan mereka. Ini, misalnya, yang terjadi beberapa kali demonstrasi terkait Uyghur, Rohingya, dan Palestina yang terjadi di Solo. Dengan menggunakan isu tersebut, mereka ingin menyulut emosi massa agar mereka marah terhadap kelompok yang mereka tuduh sebagai penindas, seperti “China” dan non-Muslim. Mereka ingin menanamkan kebencian dan terus menyebarkan kecurigaan terhadap kelompok “kafir”, bahwa mereka itu tak akan pernah suka dan ridho dengan keberadaan umat Islam serta terus berkeinginan untuk menghancurkan umat Islam.
Lebih dari itu, dalam beberapa kasus, beberapa kelompok radikal menggunakan video-video terkait pembantaian umat Islam di negara lain untuk merayu umat Islam agar mereka mau melakukan perang dan “jihad”. Mereka yang tersulut emosinya oleh video-video tersebut merupakan sasaran empuk dari upaya perekrutan anggota kelompok radikal. Mereka yang mencoba bersikap kritis terhadap berbagai video dan upaya-upaya pembakaran emosi masa ini dengan mudah dilabeli liberal atau antek Amerika atau paling ringan dituduh tidak memiliki solidaritas terhadap nasib umat Islam lain atau tidak memiliki rasa dan semangat ukhuwah Islamiyah. Hadits yang sering dikutip terkait ini adalah al-muslimuna ka-l jasadi al-wahid, bahwa seluruh umat Islam itu seperti tubuh yang satu, jika satu sakit, maka seluruhnya akan sakit.
Tulisan ini hanya akan mengambil satu contoh, yaitu nasib minoritas Muslim Uyghur, dalam kaitannya dengan “solidaritas” sesama Muslim yang pada saat bersamaan digunakan untuk menanamkan kebencian kepada kelompok lain, seperti “anti-China”, menyulut kemarahan kepada pemerintah, dan bahkan menjadi medium untuk merekrut “jihadis”. Data untuk tulisan ini didasarkan pada kunjungan singkat penulis bersama delegasi Indonesia ke Xinjiang dan Uyghur, Tiongkok pada 20-27 Maret 2019.
“Camp” Deradikalisasi
Jumlah umat Islam di Tiongkok, menurut penuturan beberapa perwakilan pemerintah dan CIA (China Islamic Association) kepada delegasi Indonesia, adalah sekitar 23 juta orang dari 1,3 milyar total penduduk. Mayoritas dari mereka berasal dari suku Uyghur dan Hui. Mayoritas dari suku Uyghur berada di daerah otonomi Xinjiang dengan komposisi mencapai 40 persen. Mereka memiliki budaya yang unik serta distingtif dari mayoritas masyarakat Tiongkok. Bahasa Uyghur dan tulisan dengan huruf Arab adalah diantara yang ciri budaya Uyghur.

Berdasar informasi yang ditampilkan di pameran yang diberi nama Exhibition on Major Incidents of Violence and Terror in Xinjiang Uyghur Aotonomous Religion (Pameran tentang Kekerasan dan Terorisme Besar di daerah Otonomi Xinjiang Uyghur), sejak 1992 terdapat 22 tindak kekerasan dan terorisme besar di daerah itu. Banyaknya kasus terorisme inilah yang menyebabkan pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan “khusus” terhadap mereka yang terindikasi radikalisme dan terorisme.

Pemerintah Tiongkok lantas membangun “camp” untuk mengatasi persoalan di atas. “Camp” sebetulnya merupakan istilah yang sering dipakai oleh media Barat untuk menyebut pusat deradikalisasi di Kashgar dan ditujukan terutama kepada komunitas Uyghur. Seperti tercantum di gerbang salah satu tempat tersebut, pemerintah Tiongkok menggunakan nama “Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja”. Tempat yang dikunjungi penulis ini ditujukan kepada mereka yang terpapar radikalisme tingkat rendah. Sementara mereka yang lebih keras radikalismenya kemungkinan ada di tempat lain dan delegasi Indonesia tidak dibawa ke sana.
Dari penuturan pihak pemerintah, guru, pimpinan, dan juga peserta didik di Pusat pendidikan deradikalisasi, pembantaian terhadap suku Uyghur itu tidak ada. Itu hanya hoax yang diciptakan oleh mereka yang tidak menyukai pemerintah Tiongkok. Di dalam tempat yang disebut “camp” itu juga tidak terjadi penyiksaan terhadap etnis Uyghur yang terpapar radikalisme dan terorisme. Mereka justru mendapat pendidikan gratis, bantuan ekonomi, dan bekal kerja dalam bentuk pelatihan ketrampilan. Materi pendidikan di “camp” terdiri dari empat elemen, yaitu: Bahasa Mandarin, wawasan kebangsaan dan konstitusi, pendidikan ketrampilan (vokasi), dan pendidikan deradikalisasi.

Pimpinan pesantren dan Asosiasi Muslim Tiongkok yang dikunjungi oleh delegasi Indonesia juga memberikan kesan positif terkait pemerintah Tiongkok. Dintaranya, pemerintah memberikan bantuan pemeliharaan masjid dan pelatihan kepada para imam. Bahkan, pemerintah juga mengelola penyelenggarakan haji yang jumlahnya mencapai 12.000 jamaah setiap tahun. Pemerintah juga memberi bantuan bagi pendidikan pesantren yang berjumlah 10 buah. Negara ini memiliki 35.000 masjid, 10 pondok pesantren, dan 51.000 imam. Pemerintah Tiongkok juga membangun Xinjiang dan Kashgar menjadi kota yang indah dan maju secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kota ini termasuk tertinggi di Tiongkok, yaitu 8,7%. Selain membangun Xinjiang, Tiongkok juga membangun Hui Cultural Park, sebuah taman Islam, di Yongning, Yinchuan.
Beberapa Anomali
Memang, seperti disampaikan oleh seorang mahasiswa di Tiongkok dalam sesi dialog di KBRI Beijing (26/3), ada beberapa anomali di Xinjiang dan Tiongkok secara umum. Ia menyebutkan tentang minimnya atau absennya anak-anak muda Tiongkok di masjid. Atau, masjid hanya diisi oleh mereka yang berusia senja. Ini, baginya, merupakan indikasi adanya gairah keagamaan yang lemah atau mati di negara Tirai Bambu ini.
Apa yang disampaikan mahasiswa itu bisa jadi benar dan itu juga terlihat pada beberapa masjid yang terkesan hanya menjadi museum. Namun, kondisi keagamaan yang menurun tak bisa sepenuhnya dituduhkan kepada pemerintah sebagai penyebabnya. Kondisi itu bisa juga disebabkan oleh tantangan hidup di era kapitalisme-modern yang menuntut disiplin kerja tinggi dan ketatnya jam kerja kantor sehingga tidak memungkinkan untuk datang di masjid pada setiap waktu sholat. Argumen ini diantaranya disampaikan oleh pimpinan Asosiasi Muslim Tiongkok (CIA).

Bisa juga masyarakat menjadi kurang beragama karena lingkungan umum yang sekuler dan ateis. Kehidupan di Tiongkok tentu berbeda dari Indonesia yang menyediakan tempat ibadah hampir di semua perkantoran, pabrik, tempat perbelanjaan, dan bahkan terminal dan stasiun. Bukan hanya memberikan fasilitas tempat ibadah, beberapa kantor pemerintah, kantor swasta, dan pabrik-pabrik pun memberikan toleransi dan, ada juga yang, mendorong karyawannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika bulan Ramadan tiba, siswa mendapat masa libur yang panjang agar bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman.
Kondisi Xinjiang lebih dekat dengan fenomena di Eropa ketika sebagian umat Kristiani meninggalkan agama dan beberapa gereja terpaksa tutup karena tak lagi memiliki jemaat. Seperti di Eropa dimana beberapa gereja berubah menjadi bar, di Tiongkok pun ada masjid yang berubah fungsi karena sudah tidak berfungsi lagi sebagai tempat ibadah.
Selain anomali terkait tempat ibadah, ada anomali lain dalam hal kehidupan keagamaan di Uyghur. Dalam beberapa kali pertemuan dengan masyarakat etnis Uyghur, tidak ditemukan perempuan berjilbab [dengan model yang umum dipakai di dunia Islam]. Demikian pula di jalan-jalan selama perjalanan ke beberapa tempat di wilayah Xinjiang. Bisa jadi jilbab seperti yang umum dipakai di dunia Islam itu bukan menjadi tradisi di sana. Karena beberapa perempuan dewasa memakai tutup kepala seperti kerudung di Jawa, namun diikatkan ke belakang. Jadi, meski Xinjiang itu banyak pemeluk Islam, mereka yang hadir di kota ini tak akan bisa melihat simbol-simbol Islam dan ritual keagamaan dengan mudah di sembarang tempat.
Ekspesi keagamaan di Xinjiang, terutama di Kashgar, itu seakan berbeda dari Beijing. Di ibu kota Tiongkok yang metropolitan dan persentase umat Islamnya jauh lebih sedikit, identitas keagamaan bisa lebih ditampilkan secara terbuka. Orang berjilbab bisa dengan mudah ditemui di jalan-jalan. Restoran halal dan tempat ibadah yang terbuka lebih mudah ditemui. Ini bisa jadi karena identitas keagamaan di kota seperti Beijing tidak dipandang sebagai ancaman, tapi lebih sebagai komodifikasi agama.
Selain dua persoalan di atas, ketika berkunjung ke tempat yang biasanya disebut “camp deradikalisasi”, delegasi Indonesia diajak ke kelas-kelas peserta “deradikalisasi”. Ketika mengucapkan salam [assalamu’alaikum], tidak ada jawaban dari mereka. Tidak adanya jawaban ini tentu saja tak bisa serta merta dianggap bahwa mereka dilarang mengucapkan salam. Bisa jadi itu karena mereka tidak terbiasa menjawab salam dengan keras dan beramai-ramai. Bisa juga karena tak memperhatikan ucapan salamnya. Dan mungkin juga karena tak berkenan atau menganggap bahwa mereka berada di tempat yang mesti steril dari simbol-simbol agama.
Para peserta didik juga dilarang melaksanakan sholat dan mengaji di tempat pendidikan. Menurut info dari kepala sekolah, para siswa di tempat tersebut bahkan tidak diperbolehkan melaksanakan ritual keagamaan di kamar masing-masing. Namun persoalan ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Pertama, Tiongkok memang melarang melaksanakan ritual keagaman di tempat umum (public space). Ini tidak hanya berlaku pada umat Islam, tapi juga kepada pemeluk agama lain. Kedua, informasi dari kepala sekolah ini juga mendapat bantahan dari pihak pemerintah Xinjiang yang mendampingi delegasi. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada yang menghalangi jika para peserta deradikalisasi itu melaksanakan ritual keagamaan di kamar masing-masing. Hanya di tempat umum saja larangan itu diberlakukan.

Berbeda dari Indonesia yang menjadikan agama sebagai elemen penting program deradikalisasi, Tiongkok, sebagai negara komunis, tidak memasukkan agama dalam program pendidikan kepada mereka yang terindikasi radikalisme. Penanganan radikalisme di Indonesia menggunakan perpaduan antara soft-approach dan hard-approach. Dalam soft-approach, mereka yang terpapar radikalisme dan terorisme diberikan pemahaman keislaman yang moderat dan membetulkan pemahaman-pemahaman teologis terkait jihad, kafir, hubungan antar agama, dan pentingnya tasamuh (toleransi). Materi-materi itu tidak berlandaskan pada wawasan kebangsaan saja, tapi juga wawasan keagamaan yang moderat.
Materi pendidikan deradikalisasi di “camp” itu sayangnya terlewatkan untuk digali lebih dalam selama kunjungan ke Uyghur. Namun jika program deradikalisasi ini tidak memasukkan elemen agama, maka pertanyaannya adalah apa antidote (obat penawar) bagi mereka yang terjangkiti radikalisme karena keyakinan teologis? Apa obat penawar bagi bagi mereka yang meyakini bahwa berbeda agama itu boleh dibunuh? Kemungkinan, soft-approach yang dipakai pemerintah Tiongkok dalam menangani radikalisme adalah penguatan budaya dan tradisi Uyghur, seperti lagu-lagu dan tarian tradisional Uyghur. Di luar tiga aspek pendidikan yang pertama seperti tersebut di atas, pendidikan terkait budaya ini yang ditemukan dalam salah satu kelas di pusat pendidikan deradikalisasi itu. Bahkan di beberapa tempat yang dikunjungi oleh delegasi Indonesia, surface culture dalam bentuk tarian, musik, dan simbol-simbol kultural lain itulah yang selalu ditampilkan di Uyghur.

Catatan Akhir
Kesimpulan sementara dan berdasarkan data-data terbatas, bisa dikatakan bahwa pemerintah Tiongkok memberlakuan kebijakan yang berbeda terhadap tiga elemen budaya yang ada di Uyghur. Untuk warisan budaya dalam bentuk pakaian, tarian, musik, arsitektur, dan sejenisnya, maka pemerintah sangat mendukung pemeliharaan dan pengembangannya. Elemen budaya yang bisa disebut sebagai bagian dari surface culture didukung penuh oleh pemerintah.

Elemen budaya dalam bentuk bahasa, pemerintah Tiongkok cenderung membiarkan dan masyarakat digalakkan untuk menggunakan Bahasa Mandarin. Wakil dari pemerintah yang mendampingi delegasi Indonesia beberapa kali menegaskan bahwa banyak warga suku Uyghur yang tidak bisa berbahasa Mandarin dan itu menjadi persoalan terkait persatuan bangsa. Ini bisa dipahami mengingat dalam beberapa kasus di Eropa, bahasa merupakan salah satu faktor yang membuat kelompok minoritas tertentu dalam suatu negara menuntut kemerdekaan. Ini yang terjadi dengan Flemings dan Walloons di Belgia dan Catalonia di Spanyol.
Elemen budaya dalam bentuk agama berkali-kali ditegaskan sebagai kebebasan individu, namun tidak boleh ditampilkan di publik. Pemerintah Tiongkok memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk beragama dan tidak beragama. Namun bagi mereka yang beragama, tempat-tempat umum (public sphere) seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor-kantor pemerintah harus steril dari urusan agama, termasuk di pusat pendidikan dan pelatihan kerja bagi mereka yang terindikasi terorisme dan radikalisme.
*Peneliti Senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)