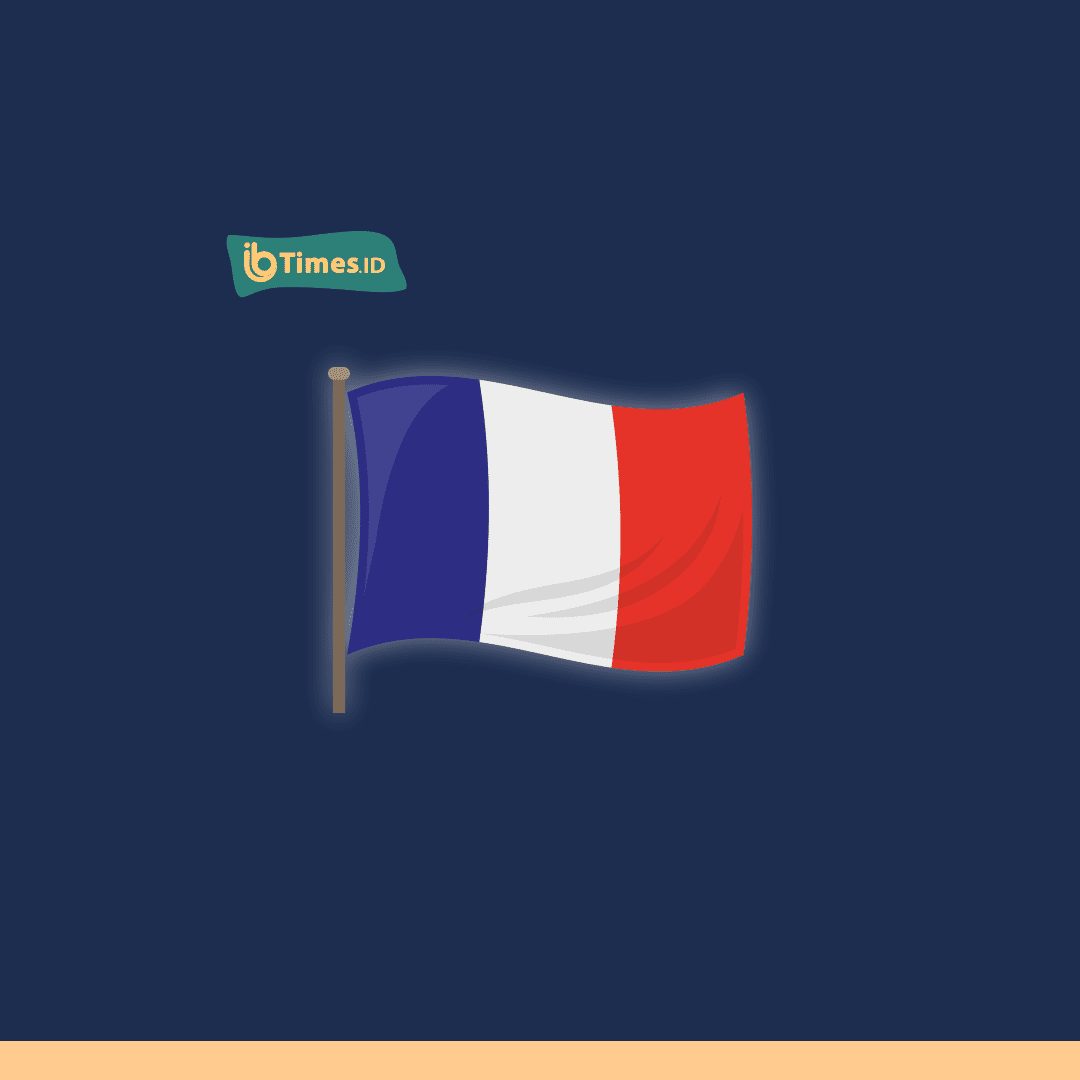Akhir-akhir ini atmosfer internasional publik terasa begitu menyesakkan. Perselisihan antara Prancis dan umat Islam semakin memanas seiring teguhnya kebenaran versi tiap pihak yang digemborkan. Kedua pihak seakan saling memberi ultimatum, tanda berakhirnya kompromi sekaligus dimulainya ‘perang’.
Secara historis, perselisihan antara Prancis–republikan dan pemerintahnya–dan umat Islam tak sekompleks seperti saat ini. Bahkan, awalnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam sebagai agama. Seiring berjalannya waktu, persoalan yang ditangani tidak tepat laksana ‘bola saju yang menggelinding’, semakin lama semakin runyam.
Akar Permasalahan Konflik Prancis vs Islam
Imam Marzuki dalam artikel Peran Politik Umat Islam di Prancis pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2012:423-430) menguraikan bahwa sentimen Prancis terhadap Islam sudah ada sejak terjadinya imigrasi besar-besaran dari negara-negara Maghribi seperti Aljazair, Maroko dan Tunisia ke Prancis pasca Perang Dunia II.
Awalnya, imigran dari beberapa negara Maghribi adalah pekerja hasil kolonialisasi Prancis di era Perang Dunia I. Mereka adalah yang diperdayakan untuk memperbaiki porak-porandanya Prancis akibat perang. Pasca Perang Dunia II, imigran yang mayoritas muslim ini datang ke Prancis dengan tujuan memperbaiki nasib dan mencari pekerjaan.
Banyaknya imigran asal negara kolonial–terutama negara Maghribi-yang datang ke Prancis untuk mencari kerja, membuat stereotip yang buruk bagi sebagian besar pribumi. Menurut mereka, imigran adalah tenaga kerja muda yang kurang berkompeten dan tidak berpendidikan. Selain itu, imigran yang datang dari negara kolonial pun dianggap sebagai masyarakat dengan status yang lebih rendah, karena mereka adalah negara yang pernah ditaklukkan (dijajah) oleh Prancis. Walhasil, Prancis tidak begitu saja menerima kebudayaan para imigran.
Agama dan Budaya: Sumber Konflik?
Kondisi ini kian diperparah dengan justifikasi Samuel P. Huntington melalui teori bentrokan budaya miliknya. Teorinya menyebutkan bahwa agama dan budaya seseorang adalah sumber konflik utama pasca perang dingin. Memang, secara genealogi pribumi Prancis dan para imigran memiliki perbedaan yang mencolok.
Sebagaimana diutarakan oleh Petsy Jessy dalam Islamofobia di Prancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi (2016:223), pribumi Prancis menganggap kebudayaan mereka adalah kebudayaan Eropa yang berasal dari “Judeo-christian” (penganut Yahudi-Kristen). Sedangkan negara-negara Maghribi adalah mayoritas pemeluk agama Islam.
Ketakutan pribumi Prancis terhadap imigran (xenophobia) diperparah dengan isu terorisme Islam yang booming pada 2001. Serangan jaringan Al-Qaeda di gedung World Trade Center (WTC), Amerika berdampak amat luas terhadap ketakutan di seluruh penjuru Eropa. Warga pribumi yang sejak awal sudah xenophobia, kini beralih menjadi Islamophobia.
Sisa-sisa stereotip buruk pribumi Prancis terhadap imigran–khususnya umat Islam–masih terlihat jelas pada tahun 2005 saat undang-undang imigrasi (French Immigration and Integration Law) disahkan. Nicolas Sarkozy yang dahulu masih menjabat Menteri Dalam Negeri mengutarakan bahwa non-pribumi Prancis adalah sampah masyarakat (racaille). Begitu pun tatkala Sarkozy menjadi presiden, isu-isu imigran dan umat Islam semakin sering dimainkan. Seperti larangan memakai simbol keagamaan di ruang publik, batasan tinggi menara rumah ibadah, dan lain sebagainya.
Selain faktor perseteruan Prancis dan umat Islam (imigran) di atas, faktor lain dalam diri Prancis yang turut mempersulit penerimaan budaya imigran – terutama muslim, adalah paham laïcité. Dyah Arum Nindya Kirana dalam Analisis Respon European Court of Human Rights Terhadap Pengajuan Protes Interdisant la Dissimulation Du Visage Dans L’espace Public (2018:27-28) menyebutkan bahwa laïcité merupakan prinsip lama mereka yang memisahkan antara urusan gereja dan negara sejak 1905.
Prancis dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya bukan hanya tidak mencampurkan urusan agama dengan urusan pemerintahan, namun juga menjamin atas pelaksanaan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan (liberty, equality, fraternity) sebagaimana tercantum dalam konstitusi Prancis 1948. Praktiknya, imigran muslim yang kental dengan simbol keagamaan dianggap penghalang bagi jalannya tiga nilai tersebut. Padahal, bagi umat Islam simbol keagamaan seperti hijab, jenggot, dan lain sebagainya merupakan tanda kepatuhan dan kebebasan dalam beragama.
Perjuangan Konstitusional Umat Islam: Mungkin?
Waktu kian berlalu, sementara akar permasalahan di atas tak kunjung mendapatkan solusi yang terbaik. Nilai-nilai yang masing-masing pihak anut, dipegang secara kaku, sehingga kebenaran menurut versi masing-masing telah menutup jalannya dialog yang konstruktif. Pihak Prancis mengklaim berjuang atas nilai kebebasan berekspresi bagi warga negaranya. Sedang di sisi lain, umat Islam mengklaim berjuang atas kebebasan beragama yang dilanggar oleh Prancis.
Umat Islam di Prancis sejatinya telah berupaya secara konstitusional melalui tuntutan ke Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia perihal banyaknya hak beragama yang terlanggar. Seperti kasus Christiane Ebrahimian yang dipecat lantaran enggan menanggalkan jilbabnya saat bekerja dan kasus penggambaran Nabi Muhammad pada sampul majalah Charlie Hebdo.
Menurut pasal 9 dan pasal 10 Europan Convention on Human Rights (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dalam memutus suatu perkara tentang kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama harus patuh dan tunduk pada undang-undang negara terkait. Sehingga serangkaian upaya konstitusional umat Islam dalam memenuhi hak beragamanya menjadi kandas di tengah jalan.
Perlawanan demi perlawanan umat Islam di Prancis sebenarnya hanyalah dampak dari ketidakadilan dan diskriminasi yang dirasakan. Usut punya usut, sebelum kasus Samuel Paty yang dibunuh oleh oknum umat Islam lantaran menunjukan gambar Nabi Muhammad saat proses belajar mengajar, sejatinya kasus dengan motif yang sama sudah mendahuluinya. Seperti kasus penyerangan di kantor majalah Charlie Hebdo pada 2 November 2011 dan 7 Januari 2015 akibat sampul majalahnya yang mengolok konsep syariah serta menggambarkan karikatur Nabi Muhammad.
Prancis vs Islam Semakin Runyam
Pada kasus Samuel Paty, pertikaian antara Prancis dan umat Islam semakin kentara. Bagi umat Islam, Samuel Paty telah melecehkan ajaran mereka. Namun apresiasi dan kecaman negara yang dialamatkan langsung kepada umat Islam, tentu semakin menambah api permusuhan. Pada 21 Oktober yang lalu, Presiden Emmanuel Macron memberikan penghargaan sipil tertinggi, yakni Legion of Honor kepada Samuel Paty. Macron juga mengecam bahwa terbunuhnya Samuel Paty adalah sebab Islam ingin merebut masa depan Prancis. Bahkan, sebuah masjid di pinggiran timur laut Paris ditutup.
Melihat apresiasi dan kecaman yang berlebihan dari Macron, umat Islam di seluruh dunia mulai melawan. Di berbagai negara yang mayoritas muslim, seruan boikot produk negara Eiffel begitu masif digalakan. Bahkan, beberapa negara seperti Qatar dan Turki pejabatnya secara langsung mengajak untuk memboikot produk yang berasal dari Prancis.
Beberapa negara dan organisasi keagamaan seperti Liga Muslim, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Irak, Pakistan, Indonesia, Aljazair, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan lain sebagainya melalui pernyataan resminya pun turut mengecam pernyataan Macron 21 Oktober yang lalu. Tak mau kalah, bahkan pemain sepak bola, Paul Pogba juga dikabarkan akan mengundurkan diri akibat pernyataan Macron tersebut.
Sentimen demi sentimen bersahutan tak terbendung. Seakan tak mau kalah, Pemerintah Prancis turut menghimbau warganya yang berada di negara mayoritas berpenduduk muslim agar berhati-hati terhadap kemungkinan pelampiasan serangan yang dialamatkan kepada Presiden Macron. Bahkan dari siaran Youtube CNBC Indonesia (28/10), Macron juga mewacanakan agar dibentuk undang-undang tentang separatisme Islam.
Dari rentetan historis pertikaian di atas, sejatinya banyak negara yang tidak tinggal diam melihat Prancis ‘dibombardir’ oleh umat Islam. Contohnya Uni Eropa beserta 27 negara di belakangnya, bahkan India, menyatakan sikap berdiri bersama Prancis. Sulit dibayangkan bahwa perseteruan antara dua kubu yang saling berlandaskan perjuangan membela hak asasi manusia ini bisa terjadi.
Mengatasi Eksklusivisme Prancis dan Umat Islam
Memperhatikan serangkaian sejarah pertikaian Prancis vs umat Islam di atas, sejatinya fanatisme satu golongan, baik dari kedua pihak, hanya merumitkan permasalahan. Dialog lintas agama dan negara perlu digalakkan dalam rangka melaksanakan instropeksi diri terhadap apa-apa yang sudah terjadi.
Prancis dan Islam tidak bisa menganggap bahwa mereka masing-masing adalah korban semata, sedang di sisi lain ia bersalah. Seperti kata mutiara Arab ‘Aṣliḥ nafsaka yaṣluḥ laka al-nāsu‘ (Perbaikilah dirimu, maka orang lain akan memperbaiki perilakunya). Hanya dengan jalan memperbaiki dirilah Prancis dan umat Islam akan memajukan peradaban dunia.
Perbaikan diri bukan sekedar menjadikan baik dalam versi umat saja, namun juga dalam perlindungan HAM yang selama ini digaungkan oleh Barat. Arti penting hak dalam ajaran liberalisme mampu mendukung individu untuk mendapatkan kebebasan dalam rangka berpartisipasi membangun peradaban manusia.
Tatkala seseorang semakin terjamin kebebasan dan pemenuhan hak individunya, maka ia semakin besar memiliki kesempatan berkontribusi. Kontekstualisasi dari isu ini, jika umat beragama semakin dijamin hak beragamanya, maka semakin besar pula kontribusi mereka dalam membangun peradaban Prancis.
***
Bagi umat Islam, perbuatan buruk dan diskriminasi oleh Prancis dari zaman ke zaman terhadap hak beragamanya perlu ditanggapi secara bijak. Tentu saja ada alasan yang melatarbelakanginya. Umat Islam harus menjawab diskriminasi tersebut melalui bukti bahwa mereka bukan sekedar imigran yang pendidikan dan ekonominya lemah di Prancis. Islam harus menjadi bukti bahwa agama ini adalah agama yang damai sesuai dengan arti Islam itu sendiri.
Akhir al-kalām, eksklusivisme Prancis terhadap hak kebebasan berekspresi dan Islam terhadap hak beragama, perlu diubah dengan dialog dan perubahan perlahan terhadap paradigma yang selama ini terbangun. Seperti kata Helmut Schmidt dalam Universal Declaration of Human Responsibilities tahun 1997, kita harus beralih dari kebebasan yang separatis menuju kebebasan yang kontributif, “We must move away from the freedom of indifference towards the freedom of involvement.”