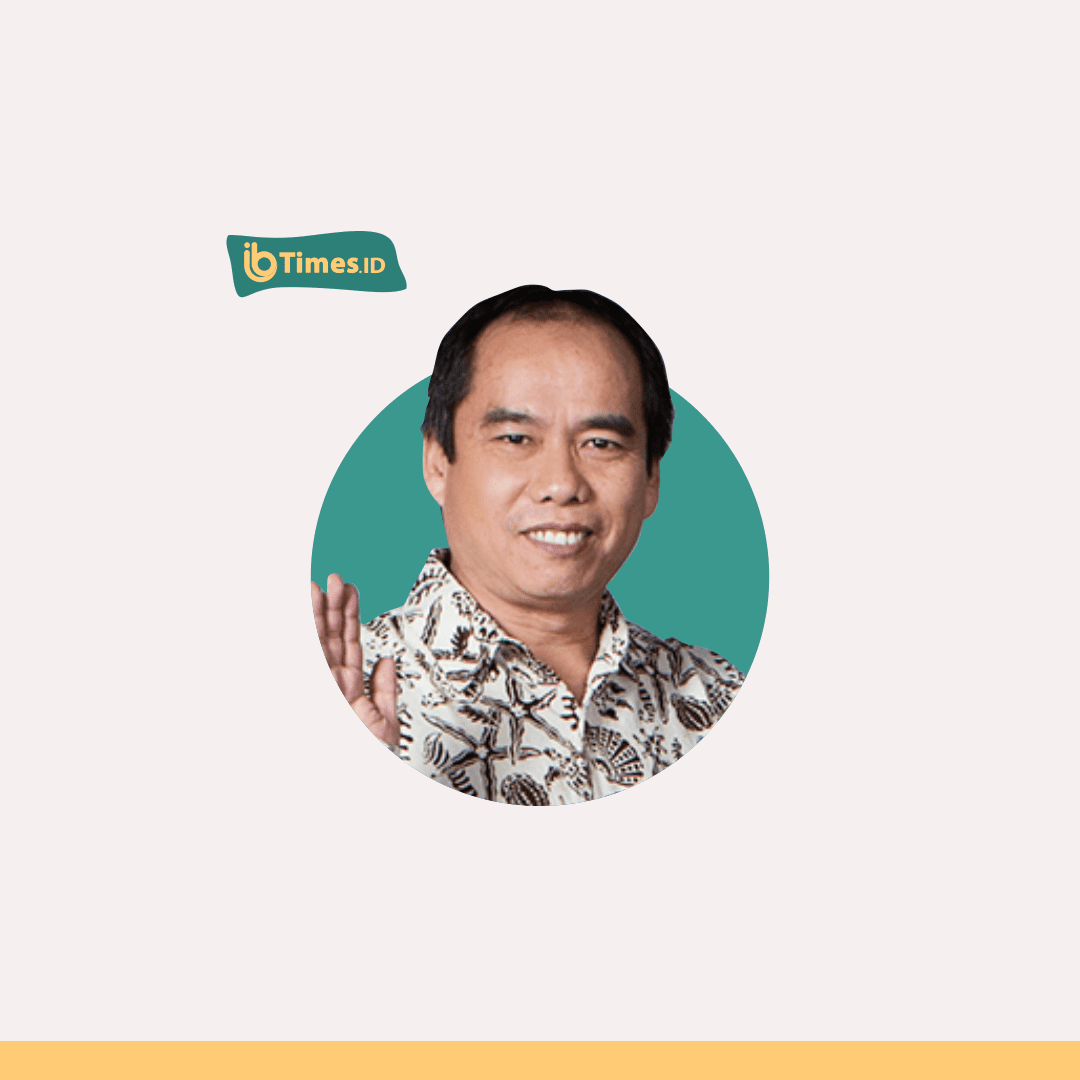Punggung Bukit Barisan, Kerinci, pada suatu pagi di tahun 2012. Udara pegunungan terasa sangat sejuk dan kami masih dalam suasana mudik lebaran. Sebuah mobil putih plat AB yang aku kendarai sendiri dari Jogja dengan gagah berani menuruni lembah untuk kemudian parkir di tepi Air Lingkat, anak cucu sungai Batanghari. Istri dan dua anak gadisku asik bermain di tepi sebuah kolam air deras Habibi, kemenakanku. Ribuan ikan berenang dengan gembira. Tetapi aku sedang tidak gembira. Aku malah sengaja menyendiri di tepi sungai, di ujung bukit dan di hilir kolam.
Di balik bukit itu ada sawah yang lama berjasa menghidupi keluarga besar kami. Ada banyak kenangan masa kecilku disana. Tetapi aku tidak bisa mengunjunginya. Tidak ada lagi jalan setapak untuk menjangkaunya. Tidak juga bisa dengan menghiliri selokan di tebing bukit. Selokannya sudah lama runtuh. Itulah sebab sawah itu ditinggalkan. Sawah itu memang berada di kawasan tanah yang mudah longsor. Maka dikenal dengan sawah runtuh. Dalam dialek setempat diucapkan Sawah Untoh.
Sawah Untoh
Sawah Untoh adalah salah satu dari dua sawah keluarga kami. Sawah lainnya adalah Sawah Panjang. Kedua sawah yang berjasa menjadi sumber utama makanan pokok keluarga kami ini diperoleh dari warisan sejak zaman baheula. Sawah Untoh warisan Indok dari Kakekku Haji Muhammad Nuh. Dua kakak Indok yaitu Makbuh Haji Adnan dan Makcik Haji Dahlan memperoleh bagian di lokasi yang lain. Karena itu Sawah Untoh bisa kami kerjakan sepanjang musim tanam.
Di sawah untoh ini kami menanam padi dan sesekali menanam kacang putih yang banyak digunakan untuk membuat kacang tujin, makanan kecil kesukaanku. Sedangkan Sawah Panjang kami berasal dari warisan Upoak. Disebut Sawah Panjang karena meliputi lahan yang memanjang cukup luas untuk ukuran negeri di pegunungan berbukit-bukit seperti dusunku ini. Tetapi Sawah Panjang hanya bisa kami garap secara bergilir dengan saudara sesama satu pehut. Pehut adalah kumpulan orang yang berasal dari satu ibu/rahim moyang yang sama. Secara norma adat sawah ini disebut pusaka rendah keluarga besar kami.
Sebagaimana pusaka tinggi yaitu gelar adat, sawah sebagai pusaka rendah dipergilirkan penggunaannya kepada semua ahli waris. Dengan begitu dari sebuah lokasi sawah warisan ini kami bisa mengetahui siapa saja saudara satu pehut yang bergiliran dengan kami menggarap sawah ini. Karena tidak dibagi habis maka area lahan sawah warisan ini masih lumayan luas sehingga bisa mencukupi kebutuhan pangan penggarapnya untuk satu musim panen.
Menaruko untuk Membuka Lahan
Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk beberapa keluarga bisa mengembangkan kawasan baru dengan cara menaruko, yaitu membuka lahan baru di dalam tanah ulayat adat kami yang sangat luas. Tradisi menaruko Ini menjadi cikal bakal dari lahirnya sebuah desa baru. Dengan demikian setiap keluarga akan tetap memiliki lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan meraka. Setidaknya inilah yang terjadi pada masyarakat kami sampai era 1970-an saat aku masih menjadi petani. Tepatnya menjadi anak petani di kampung halaman kami.
Selain sawah keluarga kami memiliki ladang di tiga lokasi: Bukit Melgan, Ujung Tanjung, dan Jalan Lurus. Jalan Lurus dalam dikel kami diucapkan dengan Jelen Luhuih. Sebenarnya ada beberapa lokasi lain ladang kami sebelummya. Seiring dengan kakak-kakakku yang menikah maka masing-masing mereka mendapat modal sebidang lahan untuk membangun keluarga baru.
Ketika aku besar, maka yang aku tahu ladang yang masih dikelola langsung Indok-Upok tinggal pada tiga lokasi itu. Pada masing-masing ladang ini kami menanam kopi dan kulit manis. Tetapi masing-masing ladang ini tidak terlalu luas dibandingkan dengan yang dimiliki teman-teman Upoak.
Luasan lahan akan sangat tergantung pada ketersediaan waktu dan tenaga manusia penggarapnya. Ini karena cara bertani kami masih tradisional. Belum banyak menggunakan teknologi pertanian. Sedangkan waktu yang Upoak miliki sebagai petani nampaknya banyak tersita oleh kegiatan beliau sebagai aktivitas masyarakat, yaitu sebagai pemangku adat sekaligus sebagai buya atau tokoh agama di negeri kami pada era itu. Sehingga secara sosial ekonomi keluarga kami bukanlah keluarga petani kaya walaupun bukan juga petani miskin. Secara sosial ekonomi pada era 1980-an dan sebelumnya antar warga di dusun kami tidak terdapat jarak sosial yang lebar. Antara orang termiskin dengan orang terkaya hanya beda-beda tipis.
Proses Manual dari Persiapan Tanam Hingga Panen
Sebagai petani keluarga kami memang petani tradisonal. Semua pekerjaan dilaksanakan secara manual. Artinya, proses produksi sampai konsumsi dikerjakan dengan perlatan sederhana tanpa teknologi yang melibatkan mesin.
Parang panjang digunakan untuk proses awal pengolahan sawah yaitu menebas atau menghilangkan rumput-rumput yang menutup sawah pasca musim panen beberapa bulan sebelumnya. Setelah itu rumput-rumput dikumpulkan untuk dibakar. Selanjutnya pangko (pacul) dan telapak kaki digunakan untuk mencangkul dan membajak lahan yang sudah diairi beberapa minggu sebelumnya.
Penyiapan bibit juga dilakukan manual. Ini diawali proses perendaman padi dalam ember di rumah. Padi yang sudah berkecambah lalu disemai di bagian paling subur dari sawah sampai siap cabut. Berkirang atau menanam bibit juga dilakukan secara manual. Setelah beberapa bulan maka dilakukan pembersihan gulma yang tumbuh di sela-sela batang padi. Beberapa bulan berikutnya setelah air sawah dikeringkan maka padi akan tumbuh menguning. Saat itulah dilakukan proses menghalau burung. Proses produksi ini berakhir dengan menuai atau menyabit padi. Semua proses produksi ini dikerjakan secara manual. Tidak ada bantuan hewan ternak, traktor, ataupun mesin lainnya.
Pengerjaan secara manual juga berlaku pada pasca produksi. Padi yang sudah dituai diikat dalam kepalan yang berisi beberapa tangkai padi. Kepalan ini kemudian diangkut untuk disimpan ke dalam bilik (lumbung padi) atau di rumah masing-masing. Setiap keluarga besar di desa kami pada masa itu pada umumnya memiliki bilik yang berdiri mengelompok di ujung dusun. Ketika diperlukan untuk konsumsi maka padi dikeluarkan dari bilik untuk diirik, digerus dengan telapak kaki untuk memisahkan bulir-bulir padi dari tangkainya.
Selanjutnya berlangsung proses ngampa imin, yaitu menjemur padi di halaman rumah di atas tikar anyaman daun sangke, daun yang ujungnya berduri yang tumbuh subur di tepi Sungai Batang Merangin dan Air Lingkat yang membelah desa kami. Setelah padi kering maka diangkut ke lesung air, sebuah teknologi sederhana manual tepat guna yang menggunakan tenaga kincir air untuk menumbuk padi. Pada sebuah lesung air terdapat pada rata-rata 10 lesung. Seingatku pada masanya terdapat lima lesung air di dusun kami. Salah satunya adalaah milik kakak Indok yaitu Makcik Haji Dahlan. Beras hasil tumbukan di lesung air ini disimpan di dalam kaleng di pojok dapur dan mencukupi kebutuhan keluarga selama beberap minggu ke depan.
Proses Manual Pengerjaan Ladang
Proses manual ini juga berlangsung pada pengerjaan ladang-ladang kami. Peralatan utama dari proses berladang adalah beliung, parang panjang, dan parang pendek, dan tajak. Beliung digunakan untuk menebang pohon, sebesar apapun pohon itu, dalam rangka membuka ladang baru.
Setelah pohon ditebang maka dilanjutkan dengan proses menebas dan membakar rerumputan dan batang pohon-pohon yang ada di dalamnya. Proses pembakaran ini memperhitungkan dengan cermat turunnya musim hujan. Selanjutnya lahan ladang digunakan untuk menanam tanaman muda seperti cabe, terong, dan sayuran lainnya, disela tanaman utama yaitu kopi dan kulit manis. Tanaman muda hanya digunakan menjelang naiknya batang-batang kopi dan kulit manis. Setelah beberapa tahun masa panen kopi maka yang tertinggal adalah pohon-pohon kulit manis yang bisa bertahan sampai dua puluh tahun lebih. Seluruh proses perladangan ini dijalankan secara manual dengan peralatan utama seperti disebutkan diatas.
Ekonomi Subsisten untuk Ketahanan Pangan
Ekonomi pertanian kami dijalankan dengan pola yang secara teori disebut ekonomi subsisten. Dalam hal ini proses produksi dan konsumi berada pada satu tangan. Dengan kata lain dalam bersawah, misalnya, padi ditanam untuk dimakan sendiri. Dalam hal ini semua penduduk asli dusun kami memiliki lahan sawah yang diperoleh terutama dari warisan generasi sebelumnya.
Meski tidak telalu luas sawah yang ada bisa menghasilkan padi yang melebihi kebutuhan akan beras sebagai makanan utama selama satu musim panen. Kepalan-kepalan tangkai padi yang disimpan secara alami di Bilik bisa bertahan beberapa tahun. Ketika hasil panen baru sudah tiba sedangkan padi lama masih belum lagi habis, maka padi baru akan ditumpukkan di atas padi lama. Jika tidak ada gagal panen maka padi-padi itu akan menumpuk sampai memenuhi Bilik. Hanya ketika terjadi gagal panen, dan ini jarang terjadi, padi lama yang dikenal sebagai padi usang memperoleh kesempatan untuk dikonsumsi.
Kenapa kelebihan padi atau beras itu tidak dijual? Inilah pertanyaan yang akan muncul dalam model ekonomi kapitalis. Jawabannya adalah tidak ada pembeli. Semua keluarga memiliki stok padi dalam bilik ataupun di rumah mereka masing-masing. Demikian juga padi itu tidak dijual ke desa tetangga dekat maupun jauh karena penduduk disana juga memiliki sawah dan bilik sebagai pengaman ketahanan pangan mereka masing-masing. Oleh sebab itu sawah-sawah di desa kami hanya ditanami satu kali dalam setahun. Sedangkan sisa waktu dalam setahun itu lebih banyak digunakan untuk mengurus ladang.
Kerinci Hilir yang Makmur
Dengan pola pertanian seperti ini maka dusun kami dan Kerinci Hilir pada umumnya pada masa itu dikenal sebagai kawasan yang makmur. Kebutuhan dasar akan beras relatif aman. Sedangkan dari mengolah ladang dihasilkan dua komoditas utama yaitu kopi dan kulit manis. Meskipun masa penennya tidak bisa sesingkat menanam padi, tetapi luasan lahan dan harga komodidtas yang tinggi membuat pedapatan masyarakat menjadi tinggi pula pada masa itu. Ukuran sederhana untuk kemakmuran ini mayoritas penduduk generasi kakek-nenekku dan generasi ayah-ibuku pada umumnya bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
Hasil dari kopi dan kulit manis ini pula yang menghantarkan generasi ayahku pada masa Belanda bisa bersekolah di Padang Panjang, pusat pendidikan Islam di Indonesia pada masa itu. Belakangan hasil berladang ini juga menghantarkan salah satu kakakku dan beberapa teman seangkatannya melanjutkan studi di IAIN Sunan Kalijaga Jogja setelah menamatkan Thawalib Padang Panjang pada 1975.
Dalam hal ini nasib baik kurang berpihak padaku. Aku melanjutkan sekolah SMP di Jogja pada 1979. Ketika tamat SMA pada 1985, produktivitas keluargaku sudah menurun. Ayahku saat itu sudah berumur 75 tahun, umur yang tidak lagi muda untuk petani tradisional. Lahan yang diolah masih sama tapi hasilnya tidak lagi sanggup menopang kebutuhan si bungsu ini untuk lanjut kuliah di rantau.
Editor: Nabhan