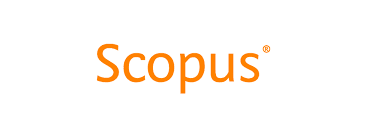Tidak sedikit akademisi Indonesia menolak kewajiban menulis jurnal yang terindeks global, salah satunya adalah Scopus. Setidaknya, ada tiga alasan; 1) itu merupakan bagian dari industri kapitalisme akademik yang bekerja secara global; 2) nasionalisme Indonesia sebagai bahasa yang harus dipertahankan; 3) kemalasan dengan dalih macam-macam di tengah proyek-proyek pembangunan dari kementerian ataupun donor.
Ketiga alasan ini adalah benar dan tidak salah. Namun, jika kita menghindari dan bahkan melawannya, justru sedang mengalami proses pengisolasian diri di tengah dunia akademik yang saling terhubung secara global.
Di sisi lain, sebagai bagian dari negara berkembang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Indonesia memiliki data yang berlimpah dan cerita yang kaya dengan kontradiksi dan tingkat kerumitannya sendiri. Informasi itu memungkinkan seorang sarjana memberikan semacam kebaharuan dari teori-teori ilmu sosial dan humaniora yang telah ada dengan menjadikan Indonesia sebagai studi kasus dan contoh. Karena itu, tidak sedikit para sarjana asing terangkat namanya dalam dunia akademik internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai lapangan kerja-kerja akademik mereka.
Dampak Isolasi dari Scopus
Dengan jalan sunyi, teman-teman di Perguruan Tinggi Agama Islam, sebenarnya sudah memulai itu dengan banyaknya sejumah karya-karya akademisi jebolan luar negeri ini di tingkat akademik internasional. Dengan menggunakan pengetahuan lokal ekspresi Islam di Indonesia, mereka bisa bersuara ke level lebih tinggi sehingga karya-karyanya banyak dikutip.
Bahkan, mereka telah membikin gelanggang tanding sendiri dengan masuknya jurnal-jurnal mereka yang terindeks Scopus. Misalnya, IAIN Salatiga dengan Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (Q1), UIN Surabaya dengan Journal Indonesian Islam (Q2), UIN Syarif Hidayatullah dengan Studia Islamika (Q2), UIN Sunan Kalijaga dengan Al-Jamiah (Q2), dan IAIN Kudus dengan Qudus Internasional Journal of Islamic Studies, baru masuk perekaman Scopus. Kondisi ini memungkinkan mereka bisa bersuara sekaligus berdialog dalam indeks kutipan dengan para sarjana internasional lain di bidangnya.
Penolakan sebagai proses pengisolasian diri tidak hanya menjadikan akademisi Indonesia sebagai informan yang karyanya hanya dikutip sebagai bahan penguatan data. Hal ini juga menjadi objek riset itu sendiri melalui hasil wawancara oleh akademisi luar negeri. Akibatnya, ketika ada isu-isu penting yang sedang hangat di Indonesia dan menjadi bagian dari subyek riset yang menarik, akademisi Indonesia kalah cepat. Mereka juga tergagap dalam menjelaskan konteks sosial, politik, dan kebudayaan atas apa yang terjadi di Indonesia.
Sebaliknya, para sarjana Internasional ini dengan cepat menulis dan melakukan konseptualisasi dengan teori-teori terbaru yang canggih. Tidak sedikit yang justru dari konteks ini memberikan semacam pembaharuan gagasan dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan di bidangnya masing-masing melalui jurnal-jurnal bereputasi di bidangnya. Dengan kata lain, kita baru memikirkannya, tulisan mereka sudah terbit. Tidak ayal, saat meriset dan kemudian menuliskan untuk sebuah jurnal, mau tidak mau, sarjana Indonesia harus membaca karya-karya mereka terlebih dahulu.
Di sisi lain, negara-negara di Asia Tenggara sedang berbenah ke arah sana, seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Sementara itu, dengan memanfaatkan situasi kawasan, Singapura menempatkan diri sebagian dari negara berkembang dengan memainkan posisi strategis dalam ilmu-ilmu sosial.
Tantangan untuk Indonesia
Atas nama Asia Tenggara, kampus-kampus di Singapura mengembangkan kajian kritis sebagai bagian dari desentralisasi pengetahuan sosial Barat dan Eropa dengan mengajukan studi-studi poskolonial dan kajian budaya dengan mengapropriasi gagasan-gagasan lokal. Meskipun kenyataannya, mereka menjadi bagian dari negara maju. Karena itu, di tengah kondisi semacam ini, Singapura memainkan posisi yang sangat strategis dalam ilmu-ilmu sosial.
Banyaknya sarjana Singapura yang belajar di luar negeri dan kembali ke kampusnya masing-masing serta melalui sistem meritokrasi yang jelas, membuat mereka menjadi pemain utama di sejumlah ilmu-ilmu sosial. Indikasi ini bisa dilihat dengan banyaknya kutipan karya-karya mereka sekaligus produksi karya mereka di sejumlah jurnal internasional bergengsi dan diakui. Dengan mendatangkan para profesor yang ahli di bidangnya juga memperkuat sekaligus mengangkat kolega dari akademisi Singapura di luar negeri. Kondisi ini berbeda dengan Filipina. Dengan memiliki tradisi panjang akademik dan aktivisme sosial, para sarjana Filipina lebih mampu untuk berbicara tentang masyarakatnya sendiri.
Memang, selain tiga alasan tersebut, ada banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh para sarjana Indonesia. Mulai dari beban administrasi, kuatnya birokratisisasi, kentalnya patronase dalam hubungan para peneliti dan dosen, khususnya antara senior dan junior, hingga upaya penghidupan untuk mengepulkan dapur dengan proyek riset-riset untuk mengintervensi kepentingan pemodal yang membuatnya tidak bisa bersikap jauh lebih independen.
Namun, adanya sejumlah beasiswa dalam luar dan luar negeri yang memberikan kesempatan emas para akademisi muda untuk belajar di negara-negara maju. Hal ini dapat ditempuh baik melalui jalur LPDP dan Program 5000 Doktor ataupun beasiswa negara lain. Mereka inilah sebagai tenaga muda yang memungkinkan bisa memainkan peran itu dalam level internasional.
Tentu saja, kunci utamanya adalah keterbukaan terhadap persaingan, baik di kampus ataupun di lembaga riset dengan meminimalisasi ego senioritas sekaligus hierarki akademis untuk mereka mengambil peran yang lebih besar.