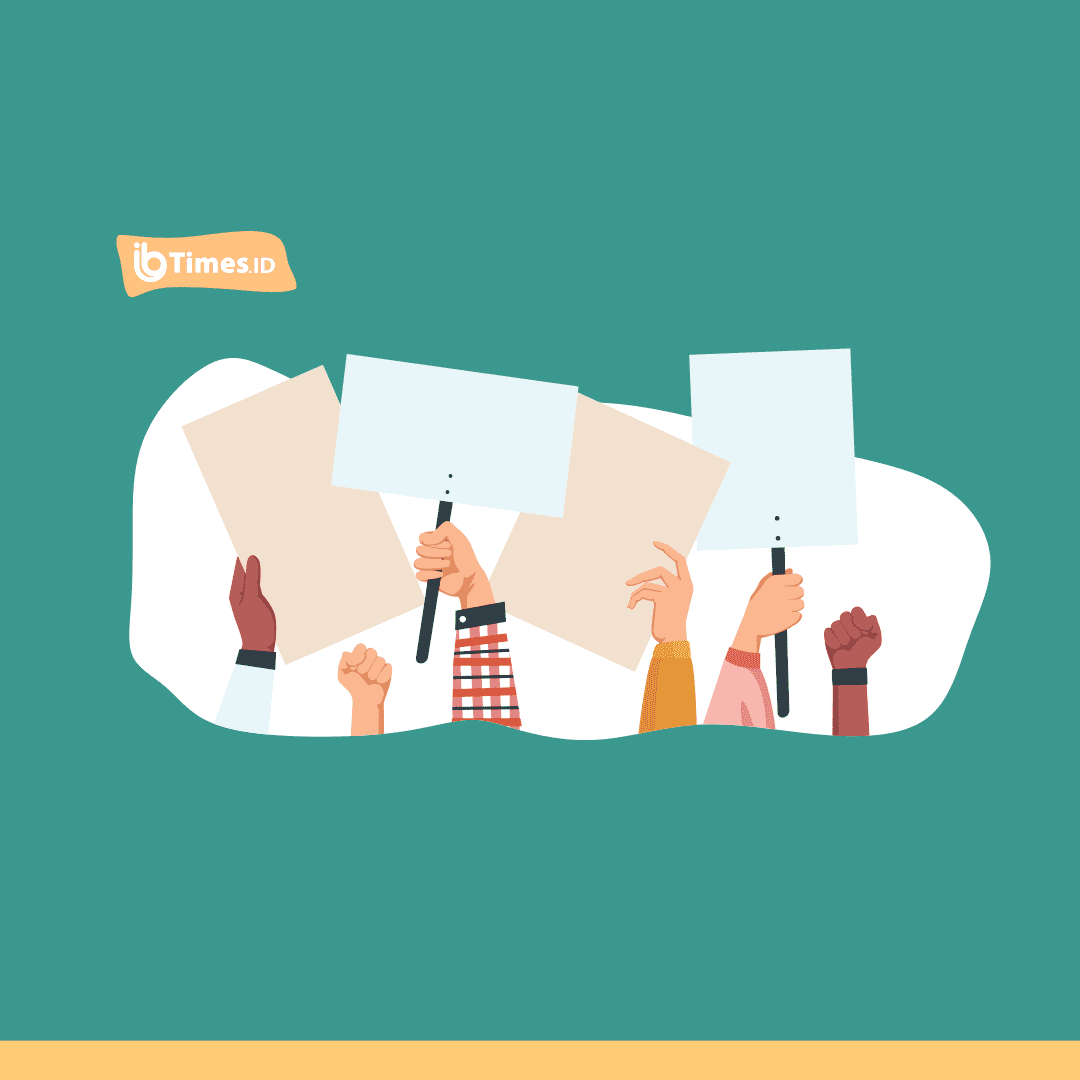Sesekali, sempatkanlah memandang wajah-wajah sendu itu. Wajah para orang tua, yang walau dengan berat hati terpaksa harus melepas putra-putrinya demo, ikut turun ke jalan. Berhadap-hadapan dengan gas air mata, sepatu lars, gagang senapan dan resiko penularan Covid-19, demi sebuah gagasan demokrasi. Dengan harapan bisa melakukan perubahan dan agar para pemegang kekuasaan mau mendengar.
“Hati-hati Saar, jaga teman-temanmu. Ayah dengar polisi sudah keluarkan larangan demo. Kalian mungkin akan dihadapi keras. Tetap solid dan berangkulan antar teman bila diserang. Jadikan tubuh-tubuh kalian sebagai tameng di antara kalian untuk saling melindungi.” Beberapa waktu lalu, kalimat-kalimat serupa itu berseliweran di media sosial. Kalimat berisi pesan seorang ayah saat melepas keberangkatan putranya yang hendak menyampaikan aspirasi, menolak Omnibus Law.
Terasa ada yang menggenang di kelopak mata saya. Dan walau sudah berupaya menahannya, tetap saja ada yang mengalir lalu jatuh saat saya berkedip. Terkadang saya memang sesentimentil itu jika sudah menyangkut urusan anak. Mungkin karena saya juga punya anak lelaki. Entah mengapa setiap kali mendengar kata demo, selalu terbersit hal-hal yang menakutkan di benak saya. Sering kali saya merasa dihantui oleh bayang-bayang chaos, demonstran hilang atau terluka dan hal buruk lainnya yang bahkan untuk membayangkannya pun rasanya saya tak sanggup. Kadang kala saya merasa bahwa dengan berangkat demo seolah seperti sedang menuju ke medan perang.
Orang Tua, Ketika Anaknya Ikut Demo
Sehingga mau tak mau, lantas mengingatkan saya akan riwayat Perang Al-Qadisiyyah. Teringat sosok Al-Khansa binti Amru, ibu yang melepas keempat putranya ke medan pertempuran. Yang sembari menahan pilu, memompakan semangat serta sikap pantang menyerah agar jangan mundur satu langkah pun. Seakan mengabaikan sang maut yang mengintai di setiap sudut dan siap mencabik-cabik jiwa mereka.
Itu yang membuat saya trenyuh ketika menyaksikan para orang tua yang mendukung putra-putrinya turun ke jalan. Anggaplah saya pecundang, sebab keberanian saya belum sampai di level itu. Saya begitu khawatir akan bahaya yang nantinya dihadapi. Disamping was-was dengan resiko tertular Covid, saya juga mengkhawatirkan provokasi dan potensi bentrok.
Dari situlah muncul rasa takut sehingga lebih memilih diam daripada melawan. Padahal konon, tak akan ada perubahan tanpa perlawanan. Meskipun terkadang ketakutan itu juga dibutuhkan sebagai alat kontrol diri agar tetap bertindak rasional. Kekecewaan yang dirasakan atas jauhnya perbedaan antara idealisme dengan realitas hidup yang ada, acap kali menjadi pemantik. Hingga kemudian mereka membuat gerakan dengan turun ke jalan.
Bukankah yang kita nikmati saat ini pun adalah hasil gerakan reformasi berdarah-darah yang mereka perjuangkan kala itu? Jadi jahat sekali yang sampai hati mencaci perjuangan ini.
Namun sering kali ada segelintir orang yang memanfaatkan keadaan untuk berbuat anarkis atas nama demo. Ada elemen lain yang masuk dengan kepentingan berbeda, bisa jadi bahkan berlawanan. Sebab selalu saja ada penyusup di setiap kerumunan. Pola-pola semacam inilah yang diduga digunakan untuk menghancurkan gerakan. Alih-alih mendulang simpati dan dukungan, malah caci makilah yang didapat.
Gerakan yang niat awalnya sebagai protes moral dan sosial, dalam sekejap menjelma menjadi perusakan fasilitas publik. Kita pernah, dan sampai kapan pun akan selalu sepakat bahwa perusakan tidak boleh dibenarkan. Hanya saja, kondisi yang ada menjadikannya sering kali tak terelakkan. Dan ujung-ujungnya, fasilitas publik yang rusaklah yang lagi-lagi dipersoalkan untuk mendiskreditkan para demonstran.
Wajah Payah, Penuh Amarah
Selama ini kita sudah cukup lelah dihajar pandemi. Tidak sedikit kawan yang susul-menyusul pergi dengan tiba-tiba. Dan kita pun, tak ada jaminan sampai kapan akan terus bisa selalu prima. Sejenak, coba perhatikanlah wajah-wajah kita. Wajah payah yang masih penuh amarah, walau sudah sama- sama terluka. Wajah-wajah letih menahan perih, namun tetap saja terus saling menyakiti.
Barangkali memang bukan suatu hal baru tatkala melihat penampakan wajah yang penuh amarah. Dan itu kerap berulang, terutama menjelang pilpres atau pilkada. Namun disaat kita sedang terseok dan tertatih di tengah wabah ini, sungguh seakan tak percaya jika wajah-wajah itu masih ada. Wajah dengan seringai marah yang menyeruak di sela rerimbunan bait-bait lagu duka. Sungguh jemu menyaksikan kita saling berseteru. Sedih melihat kita saling hujat hanya karena tak sepakat, saling caci cuma gara-gara beda diksi. Tidak bisakah sejenak kita berkompromi, menepis gengsi, melerai amarah, meluruhkan angkuh pada diri yang sering kali merasa seolah paling paham segalanya?
Kompromi mungkin tak cukup mampu mengobati semua luka dan kepedihan yang ada. Namun setidaknya akan membuat kita tampak sebagaimana semestinya manusia. Bukan sekedar seperti sekumpulan pohon pisang yang cuma punya jantung, tapi tidak memiliki hati. Atau jangan-jangan, kita memang sudah bebal nurani dan fakir afeksi?
Seperti yang pernah ditulis Iqbal Aji Daryono dalam bukunya, Out of The Truck Box (2015), bahwa banyak kekacauan dalam hidup yang terjadi karena kita hanya mengandalkan kognisi, akal dan sisi rasionalitas belaka. Segalanya hanya dimaknai dengan kerangka nalar yang akhirnya berujung sebagai pemahaman benar salah semata. Kita sepertinya sudah melupakan afeksi, olah rasa, bahasa kasih sayang dan katresnan. Padahal dengan semua itulah kita akan lebih utuh sebagai manusia.
Editor: Dhima Wahyu Sejati