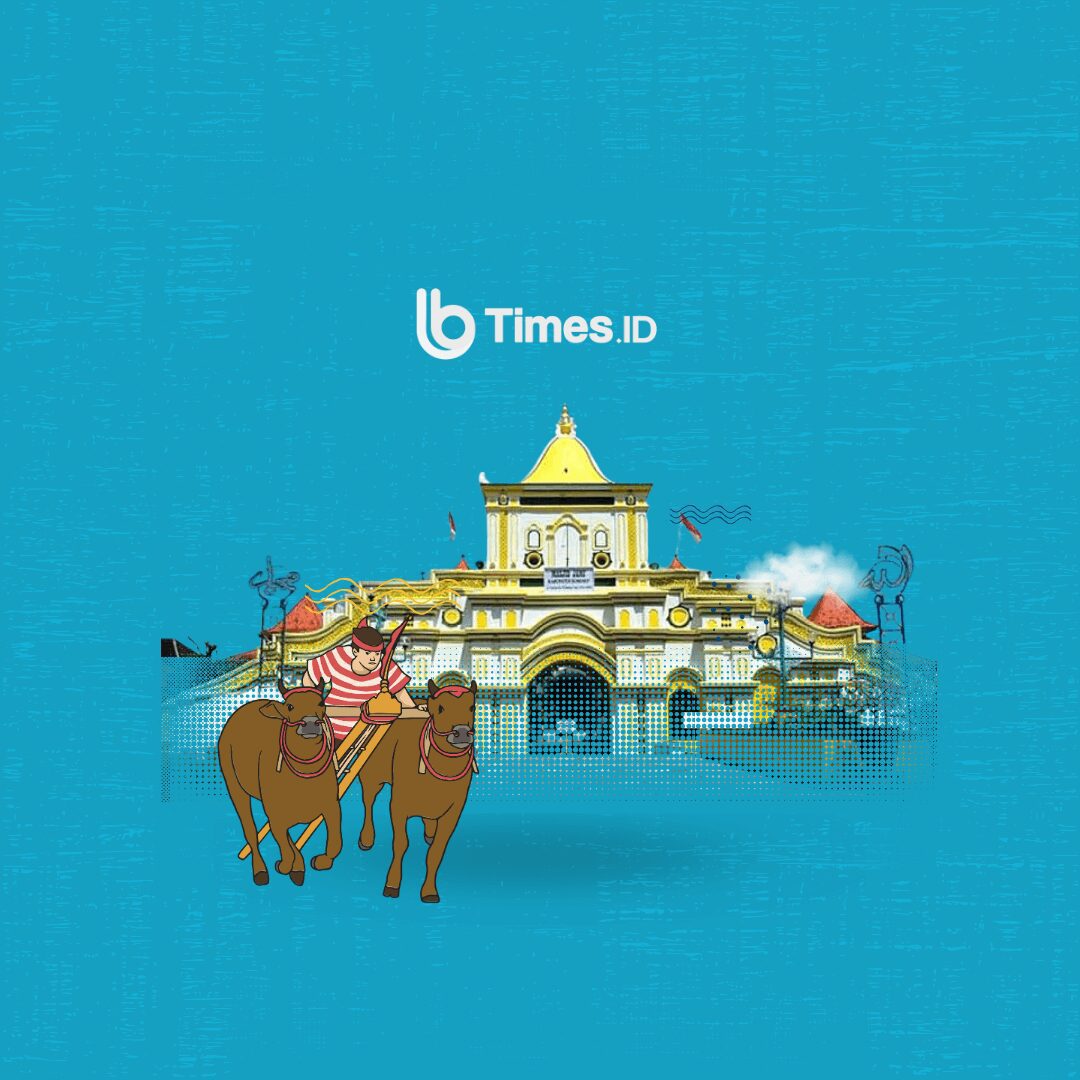Memperbincangkan Madura tanpa menyentuh aspek Islam akan menjadi tidak afdal. Mengingat, Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Madura, sekaligus mempunyai basis ulama dan pondok pesantren dengan jumlah besar.
Selama ini, Islam di Madura mendapatkan pandangan dari masyrakat luas sebagai entitas yang tidak mempunyai persoalan sosial di dalamnya. Padahal, Islam di Madura, turut mempunyai dimensi hitam di dalamnya.
Dimensi hitam Islam di Madura bukan hanya berbicara pada relasi konfliktual antara NU sebagai basis masyarakat Madura dengan Muhammadiyah. Begitu juga tidak terbatas pada relasi hegemoni Kiai terhadap pendominasian pada perempuan.
Namun, dimensi hitam Islam di Madura juga berkaitan dengan pertentangan relasi antara Islam pesantren dengan Islam kampung. Permasalahan pertentangan relasi antara Islam pesantren dengan Islam kampung, menjadi fokus penelitian oleh Mohammad Hefni yang terangkum di buku berjudul Islam Madura: Sebuah Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Relasi Islam Pesantren dan Islam Kampung di Sumenep Madura.
Dualitas pandangan Islam Pesantren dan Islam Kampung
Hefni melihat bahwa Islam kampung yang direpresentasikan oleh masyarakat Pinggir Papas, sering mengalami pendistorsian oleh Islam pesantren. Sebab, Islam kampung mempunyai tradisi berbeda perihal mempraktikan ajaran Islamnya. Masyarakat Pinggir Papas mengalami hibriditas identitas antara ajaran leluhurnya dengan ajaran Islam.
Ajaran leluhur masyarakat Pinggir Papas berorientasi terhadap upacara pada makam leluhur, yakni keluarga Anggasuto dan melakukan praktik upacara ritual penyembahan makhluk gaib. Sekalipun demikian, masyarakat Pinggir Papas juga melakukan praktik keagamaan Islam sesuai dengan syariat Islam, yakni salat, puasa, dan ngaji.
Hibriditas Islam kampung oleh masyarakat Pinggir Papas, tidak sejalan dengan Islam pesantren. Islam pesantren menjalankan ajaran Islam secara utuh, tanpa melakukan praktik ritual yang bermakna “syirik”, karena menyembah selain kepada Allah.
Pandangan Islam pesantren dengan bersifat murni terhadap ajaran Islam, menjadikan masyarakat Sumenep sebagai basis lokasi penelitian, memandang Islam kampung sebagai identitas menyimpang. Hal ini terjadi akibat posisi Islam pesantren yang direpresentasikan oleh NU menjadi basis pengetahuan agama oleh masyarakat Sumenep secara menyeluruh.
Melalui persoalan tersebut, maka Hefni mengajukan dua pertanyaan penelitian dalam bukunya. Yakni, bagaimana relasi Islam pesantren dan Islam kampung di Sumenep, Madura? Kemudian, bagaimana Islam pesantren dan Islam kampung memainkan kepemilikan modalnya dan penggunaan habitus?
Dominasi Islam Pesantren
Kemunculan konsep “modal” dan “habitus” dalam pertanyaan penelitian, berasal dari konsep teoritik Bourdieu sebagai analisis teorinya. Hefni menggunakan konsep modal untuk memahami proses pendominasian relasi antara Islam kampung dengan Islam pesantren. Sedangkan konsep habitus berguna untuk menggambarkan ritus pengetahuan yang teraktualisasikan pada Islam pesantren dan Islam kampung.
Hefni dengan meminjam konsep pemikiran Bourdieu, mendapatkan fakta bahwa modal dari Islam pesantren lebih mapan daripada Islam kampung. Tidak mengherankan ketika Islam pesantren mampu mendominasi pandangan hidup masyarakat Sumenep perihal nilai-nilai menjalankan ajaran Islam. Setidaknya, Islam pesantren mempunyai modal budaya, modal sosial, dan modal ekonomi.
Modal budaya dari Islam pesantren terbentuk pada posisi Kiai sebagai pelembagaan pengetahuan. Kiai sebagai pelembagaan pengetahuan, menjadikan masyarakat Sumenep memandang bahwa ajaran yang diajarkan oleh Kiai mempunyai otoritas lebih baik. Sehingga, sesuatu yang bernilai tidak sesuai dengan ajaran Kiai, akan termaktub sebagai tindakan amoral.
Pengagungan Kiai oleh masyarakat Sumenep terbentuk karena Kiai telah mengalami musafir pengetahuan agama Islam di semasa hidupnya. Para Kiai sudah menyelami banyak kitab dan ilmu Islam di berbagai pondok pesantren. Sehingga, pengetahuan Islamnya bersifat mapan.
Kiai untuk menyebarkan pengetahuan agamanya kepada masyarakat Sumenep tidak mengalami kesulitan. Melalui kepemilikan modal ekonominya, Kiai bisa membangun pondok pesantren. Terlebih lagi, Kiai di Sumenep mempunyai modal sosial berupa hubungan sosial sesama Kiai. Kepemilikan hubungan sosial berguna membantu memperkenalkan pondok pesantrennya.
Pondok pesantren menjadi arena bagi Kiai untuk menginternalisasikan ajaran Islam yang dipandang tidak menyimpang. Kiai pada dasarnya juga sering melakukan ritual keagamaan, tetapi, tidak melakukan penyembahan selain pada Allah. Para santri saat berada di pondok, biasanya rutin melakukan pengajian, tahlil, salawat, dan khataman Al Qur’an.
Pengajian, tahlil, salawat, dan khataman Al Qur’an telah menjadi habitus dari Islam pesantren, yang kemudian para santri mengalami sosialisasi pengetahuan. Bourdieu dengan konsep habitusnya ingin menggambarkan bahwa pengetahuan akan menjadi identitas bagi seseorang, melalui pengulangan nilai pengetahuan pada individu lainnya. Pengulangan pengetahuan, pada akhirnya akan membentuk perspektif.
Ketertundukan Islam Kampung
Oleh sebab itu, posisi Islam pesantren bersifat dominasi daripada Islam kampung. Dominasi Islam pesantren telah menyebabkan kuasa simbolik kepada Islam kampung. Kuasa simbolik tidak bersifat menyiksa secara fisik, melainkan berjalan dengan kasat mata melalui penundukan kesadaran. Penundukan kesadaran oleh Islam pesantren tercerminkan dengan memaknai berbagai ritual Islam kampung sebagai perbuatan menyimpang dari ajaran Islam.
Melalui kuasa simbolik oleh Islam pesantren, menyebabkan Islam kampung tidak mempertahankan ritual yang bernilai menyesatkan menurut pandangan dari Islam pesantren. Pada akhirnya, masyarakat Pinggir Papas melakukan perubahan makna di ritualnya. Semisal, mengubah makna nyadhar yang awalnya menjadikan Anggasuto sebagai leluhurnya serupa Allah. Akhirnya berubah makna sebagai tindakan menghargai jasa Anggasuto.
Contoh lainnya adalah mengubah makna olesan cairan bedak di ritual nyadhar dan sandegah bhumi. Awalnya, pengolesan cairan bedak bagi masyarakat Pinggir Papas bermakna penolak balak. Kini berubah sebagai tanda seseorang sudah melakukan ritual. Begitu pula pada penyajian sesaji di rokat tase’, bukan lagi diniatkan untuk setan. Sekarang sesaji berfungsi sebagai perwujudan rasa syukur pada Allah.
Dengan demikian, relasi Islam di Madura masih bersifat pada pengukuhan homogenitas daripada heterogenitas. Homogenitas Islam masih tertunduk pada ajaran-ajaran yang sesuai berdasarkan perspektif para Kiai.
Lantas, apakah Islam di Madura dengan berporos pada kuasa simbolik Kiai akan menghadirkan konfliktual? Besar kemungkinan bisa memunculkan pertengkaran, dengan menilik kembali peristiwa konflik Syiah dan Sunni di Sampang. Sebab, penulis selaku orang Madura melihat bahwa pada dasarnya, orang Madura memiliki kekayaan pandangan hidup dan budaya.
Editor: Yahya