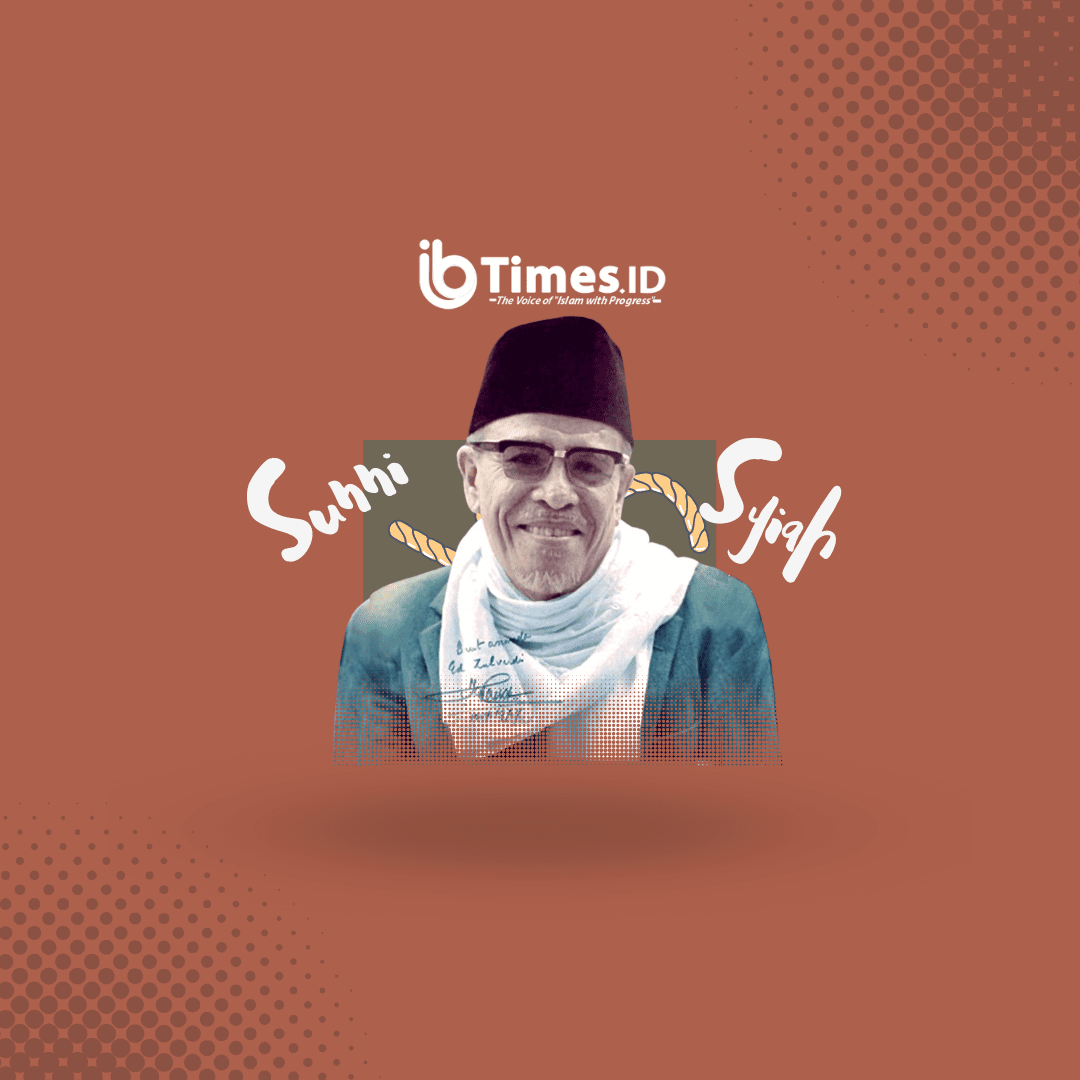Muhammadiyah dan Sunni-Syiah
Dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, dialog Sunni-Syiah menjadi salah satu dari isu strategis keumatan yang menjadi perhatian Muhammadiyah.
Hasil muktamar tersebut menegaskan — di antara sekian isu strategis keumatan — seruan Muhammadiyah tentang dialog intra-Islam. Melihat fakta tersedotnya energi umat untuk pertentangan antara kelompok Sunni dan Syiah – yang dilatari beragam faktor – dan potensi meluasnya kekerasan yang terjadi di tingkat lokal, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog intra Islam.
Dialog ditujukan pada penguatan sikap saling mengerti persamaan dan perbedaan, komitmen untuk memperkuat persamaan, dan sikap saling menghormati perbedaan, serta kesadaran historis bahwa kaum Sunni dan Syiah memiliki sejarah kohabitasi dan relasi konstruktif yang sangat panjang (Baca Berita Resmi Muhammadiyah: Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, h. 113-4).
Untuk meneguhkan ajakan Muhammadiyah ini tentu upaya-upaya intelektual perlu dilibatkan. Di antara upaya yang penting dilakukan adalah menggali pemikiran tokoh-tokoh besar di Muhammadiyah tentang sikap terhadap Syiah atau tentang hubungan Sunni dan Syiah.
Pertanyaannya, apakah ada tokoh Muhammadiyah yang pemikiran dan sikapnya dapat menjadi preseden yang baik untuk (di tengah banyak fokus Muhammadiyah membangun peradaban berkemajuan) mengajak warga Muhammadiyah, dan juga umat Islam secara lebih luas, guna membangun dialog Sunni-Syiah? Siapakah yang dapat menjadi rujukan terpercaya bagi umat dalam masalah membangun moderasi dalam masalah Sunni-Syiah?
Mengapa Buya HAMKA?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini mencoba memotret pandangan dan sikap intelektual HAMKA terhadap Syiah. Mengapa Buya Hamka? Mengangkat pemikiran Hamka dalam kaitan isu Sunni-Syiah ini “mungkin” dan “penting”.
“Mungkin” karena Hamka memiliki banyak karya tulis dalam cakupan tema yang sangat luas. Sebagian karyanya berkaitan dengan tema akidah. Yang lebih penting lagi, HAMKA menyusun kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Azhar.
Itu berarti HAMKA juga menafsirkan ayat-ayat yang sentral bagi suatu aliran keagamaan dalam Islam, termasuk ayat-ayat yang menjadi pilar doktrin keagamaan Syiah. Hingga taraf tertentu bahkan dapat diklaim bahwa Hamkalah ulama Nusantara yang menulis tentang Syiah lebih banyak dibanding ulama lain pada masanya dan masa sebelumnya.
HAMKA , yang seorang penulis prolifik, tentu menulis banyak sekali topik, namun HAMKA menuliskan banyak catatan tentang sejarah dan doktrin Syiah, terutama dalam buku Di Tepi Sungai Dajlah (terbit sejak 1952), Pelajaran Agama Islam (terbit sejak 1956), dan Sejarah Umat Islam (ditulis antara 1930-an hingga 1960-an).
Tafsir al-Azhar Buya HAMKA juga turut memuat rujukan kepada sebagian tafsir Syiah, utamanya al-Mizan, dan memuat kisah-kisah tokoh Syiah.
***
“Penting” karena HAMKA adalah seorang tokoh besar Muhammadiyah, bahkan tokoh dunia Islam. Dia pun dikenal memiliki keteguhan pendirian sekaligus dikenal toleran dan terbuka dalam menyikapi perbedaan fikih.
Orang boleh bertanya apakah keterbukaan HAMKA tidak hanya melintasi keragaman mazhab fikih di dalam Ahlu Sunnah, dan apakah HAMKA juga memiliki keterbukaan pada mazhab teologis yang berbeda.
Ahmad Syafii Maarif (2017) menyebut HAMKA sebagai pemikir bebas dan pencari kebenaran. James Rush (2016) menggarisbawahi perannya dalam menuliskan banyak pandangan ulama dari berbagai latar belakang untuk mendorong pendekatan yang inklusif terhadap berbagai mazhab. Khoirudin Aljunied (2018) menyebutnya sebagai pengusung pembaruan yang bersifat kosmopolitan, yang melampaui sekat-sekat agama.
Kajian tentang pemikiran HAMKA seputar Syiah sebelumnya terserak dalam tulisan-tulisan semi-populer yang terserak di media, baik cetak ataupun daring. Tulisan-tulisan ringan itu sering terjebak dalam pro-kontra apakah HAMKA mendukung Syiah atau tidak. Tentu diperlukan kajian yang lebih serius tentang apresiasi dan kritik HAMKA terhadap Syiah, dan bagaimana Hamka melihat hubungan antara Ahlu Sunnah dan Syiah.
Cara HAMKA Memahami Syiah
Dalam membincang pandangan dan sikap HAMKA , cakupan “Syiah” di sini akan diklasifikasi menjadi tiga: 1) Syiah sebagai suatu firqah (kelompok keagamaan dengan pandangan teologis tertentu); 2) pemahaman keagamaan yang sentral dalam Syiah; serta 3) tokoh dan literatur Syiah.
Yang pertama untuk melihat bagaimana Syiah sebagai suatu kelompok didefinisikan dan dinarasikan oleh Hamka. Yang kedua untuk melihat komentar HAMKA terhadap ajaran atau pandangan pokok Syiah. Yang ketiga untuk melihat sikap Hamka terhadap kisah atau karya tokoh Syiah.
Pandangan dan sikap intelektual HAMKA yang dipaparkan di sini adalah yang utamanya terekam dalam Tafsir al-Azhar, namun juga dengan melihat karya-karya HAMKA yang lain.
Telaah awal terhadap Tafsir al-Azhar di sini dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menelusuri kata “Syiah” dalam tafsir ini. Kedua, dengan melihat penafsiran HAMKA terkait dua belas ayat yang paling sering diperdebatkan dalam kaitannya dengan isu Ahlu Sunnah dan Syiah. Ayat-ayat tersebut adalah: al-Ahzab ayat 33 (tentang ahlulbait), al-Nisa’ ayat 59 (tentang ulil amri), al-Ma’idah ayat 55 (tentang wilâyah Imam ‘Ali), al-Ma’idah ayat 67 (tentang pesan keimaman ‘Ali yang harus Nabi sampaikan), al-Nisa’ ayat 24 (tentang mut’ah), al-Baqarah ayat 125 (tentang imamah), Al ‘Imran ayat 7 (tentang al-râsikhûn fî al-‘ilm), al-Tawbah ayat 100 (tentang sahabat Nabi), al-Syura ayat 23 (tentang al-qurbâ), al-Ma’idah ayat 3 (tentang wilâyah), Al ‘Imran ayat 28 (tentang taqiyah), dan al-Nahl ayat 106 (tentang taqiyah).
Daftar lebih lengkap tentang ayat-ayat yang kerap diperdebatkan di antara ulama Sunni dan Syiah ini dapat dilihat dalam karya saya, Tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an: Sectarian Tendencies in al-Tabataba’i’s al-Mizan and al-Shanqiti’s Adwa’ al-Bayan (2016).
Syiah dalam Deskripsi HAMKA: Paham Politik
Dalam suatu uraian, HAMKA menggambarkan Syiah lebih sebagai suatu paham politik yang bertumpu pada keyakinan bahwa Imam ‘Ali mendapatkan wasiat dari Rasulullah untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin umat.
Syiah didefinisikan oleh HAMKA sebagai “satu golongan yang mempunyai aliran paham politik bahwa yang berhak menjadi Imam kaum Muslimin sesudah Rasulullah wafat hanyalah Saiyidina Ali bin Abu Thalib.” Menurut Syiah, sebagaimana ditulis HAMKA , Ali menerima wasiat dari Nabi Saw untuk menjadi penggantinya memimpin kaum muslimin sesudah wafatnya Rasulullah.
HAMKA memperkenalkan perbedaan pokok Sunni Syiah sebagai timbul dari pertentangan paham politik. Sunni mengakui keempat sahabat Nabi (Abu Bakr, ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali) memiliki hak yang sama menjadi khalifah dan sama-sama sah.
Sedangkan Syiah berpegang teguh pada pendapat bahwa sudah ada ketentuan pasti dari Nabi tentang pelanjutnya, yaitu ‘Ali bin Abi Thalib, sehingga kekhalifahan Abu Bakr, ‘Umar dan ‘Utsman tidaklah menurut prosedur yang sah.
Saat menguraikan Syiah, tak jarang HAMKA mengenalkan keragamaan kelompok ini. HAMKA menyebutkan beberapa kelompok di dalam Syiah: Imamiyah Itsna ‘Asyriyah, Ja‘fariyah, Zaidiyah, Isma‘iliyah, Kisaniyah, dan lain-lain (Cek Pelajaran Agama Islam).
Dalam uraiannya, HAMKA tidak tampak memberikan penekanan yang kuat pada kesesatan ajaran Syiah. Pada satu sisi, HAMKA tak jarang mengesankan bahwa di kalangan Syiah ada kelompok yang ekstrem atau berlebihan (ghulât). Tapi pada sisi lain, HAMKA juga tidak segan memuji salah satu kelompok Syiah, seperti saat mengulas kelompok Zaidiyah – yang ditulis secara hati-hati oleh HAMKA sebagai “termasuk golongan Syiah,” namun “orang menganggapnya Syiah yang moderat“.
HAMKA menyebut kelompok ini sebagai kelompok yang mementingkan penyebaran agama Islam dengan melakukan dakwah terus-menerus namun tidak memperuncing perbedaan Sunni-Syiah ataupun membuat panas hubungan dengan mazhab Sunni.
Posisi HAMKA dalam hal ini mengingatkan saya pada posisi sebagian pembaru Islam era modern seperti Muhammad Rasyid Rida yang memandang Syiah sebagai “sebagiannya kufur, sebagiannya bid’ah, dan sebagian lainnya tidak keduanya.”
Pandangan HAMKA terhadap Doktrin Syiah dan Praktiknya
Walau tidak sering, HAMKA di berbagai tempat memberikan komentar terhadap beberapa paham ajaran Syiah dan pengamalannya. Misalnya tentang taqiyah. Mengapresiasi pandangan Syiah tentang taqiyah, HAMKA mengatakan: “Terlepas dari pendirian penafsir sendiri yang bukan Syiah, melainkan penganut mazhab Sunni, penafsir kagum akan ajaran taqiyah kaum Syiah itu. Sebab bagi mereka taqiyah bukan kelemahan, melainkan satu siasat yang berencana.”
HAMKA tidak setuju pandangan bahwa sikap taqiyah menunjukkan sikap yang lemah. Syiah sebagai mazhab politik banyak sekali mempunyai rencana-rencana rahasia, yang baru diketahui oleh musuh setelah mereka terpaksa menghadapi kenyataan. Kerajaan-kerajaan Syiah kebanyakan pada mulanya adalah gerakan yang dirahasiakan.
Namun, mengenai pandangan Syiah tentang mut’ah, HAMKA tampak kritis sekali. HAMKA kritis terhadap sikap Syiah membolehkan mut’ah. Baginya nikah ini adalah pembelokan maksud agama yang sangat mencolok, dan sesuatu yang memalukan. Tidak ubahnya seperti mencari perempuan lacur untuk dipakai semalam.
Kritik lain HAMKA terhadap Syiah adalah pada praktik pemujaan kubur yang cukup kuat di kalangan mereka. Walaupun kritik HAMKA tidak eksklusif tertuju kepada Syiah, melainkan juga kepada pemujaan kubur di kalangan Sunni, Hamka kerap mengesankan bahwa praktik ini subur di kalangan Syiah. Hamka kerap kali menyertakan Syiah dalam kritiknya terhadap kelompok di mana pemujaan terhadap kubur tumbuh subur.
Tokoh dan Literatur Syiah dalam Karya HAMKA
Kutipan kisah atau pernyataan tokoh Syiah, tidak terlalu sulit untuk ditemukan di Tafsir al-Azhar. Misalnya ketika menafsirkan surah Ali ‘Imran ayat 134, HAMKA mengutip suatu cerita tentang Musa al-Kazhim yang berwudu untuk salat subuh.
Saat menafsirkan surah al-Baqarah ayat 31-3, HAMKA mengutip pendapat Ja‘far al-Shadiq dan Muhammad al-Baqir (dua dari dua belas imam dalam Syiah Imamiyah). Saat menafsirkan surah al-A‘raf ayat 199, Hamka juga mengutip perkataan Ja‘far al-Shadiq, tokoh yang disebutnya sebagai “Imam Syiah yang besar”.
Dalam Tafsir al-Azhar, HAMKA pun menggunakan beberapa literatur tafsir Syiah. Sebagaimana ia sampaikan dalam catatan kaki bibliografinya, keterbukaan HAMKA pada literatur tafsir Syiah bermula dari pertemuan dengan seorang perwakilan Syiah di Mekah, Sayyid Asad Syahab, pada 1973.
Sekembalinya ke Tanah Air, HAMKA dikirimi dari Teheran tiga buah tafsir Syiah: al-Mîzân (al-Thabathaba’i), Âlâ’ al-Rahmân (Jawad al-Balaghi), dan al-Bayân (al-Sayyid al-Musawi al-Khu’i). HAMKA memandang tambahan referensi tiga tafsir ini “amat penting”. Menurut HAMKA , tidak masalah menggunakan tafsir-tafsir Syiah karena toh tafsir Muktazilah seperti al-Kasysyâf saja juga banyak dipakai sebagai perbandingan. HAMKA pun tidak segan untuk menyebut al-Thabathaba’i sebagai “ulama Syiah terbesar di zaman kita”.
Walaupun mengutip karya-karya tafsir mereka, tampaknya HAMKA sering kali tidak tertarik untuk mengungkap pandangan mufasir Syiah ketika menafsirkan ayat-ayat yang krusial bagi doktrin keagamaan Syiah – yang umumnya ditafsirkan secara panjang lebar oleh al-Thabathaba’i.
Misalnya, HAMKA tidak masuk ke dalam perdebatan mengenai makna dan cakupan ahlul bait saat menafsirkan al-Ahzab ayat 33, ataupun makna dan cakupan ulil amri saat menafsirkan al-Nisa’ ayat 59.
***
HAMKA juga tidak menyebut-nyebut Imam ‘Ali saat menafsirkan surah al-Ma’idah ayat 55 dan 67. HAMKA juga tidak berbicara mut’ah saat menafsirkan surah al-Nisa’ ayat 24. HAMKA juga tidak menyinggung imamah saat menafsirkan surah al-Baqarah ayat 124. Pun HAMKA juga tidak menyinggung para imam maksum saat menafsirkan ungkapan al-râsikhûn fî al-‘ilm di surah Al ‘Imran ayat 7.
Akan tetapi, di luar tema-tema sensitif Syiah-Sunni, HAMKA tidak jarang menyertakan pandangan kaum Syiah saat menyebutkan keragaman pendapat. Misalnya saat menerangkan pendapat tentang bismillah, tentang Adam sebagai khalifah, tentang mubahalah, atau tentang kemaksuman nabi-nabi.
HAMKA juga menuturkan kecintaannya kepada keluarga Nabi Muhammad Saw, termasuk dua cucu beliau, al-Hasan dan al-Husayn. Dalam suatu sambutan pengantarnya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk suatu buku M.H. Alhamid Alhusaini berjudul Alhusain (1978), HAMKA bahkan mengawali sambutan dengan mengutip syair Imam al-Syafi‘i, “Jika saya dituduh orang Syiah karena saya mencintai keluarga Muhammad, maka saksikanlah oleh seluruh manusia dan jin bahwa saya ini adalah penganut Syiah.”
Tentu HAMKA , sebagaimana Imam al-Syafi‘i tidak sedang menyatakan diri seorang Syiah, melainkan orang yang benar-benar mencintai keluarga Nabi Muhammad Saw. Sikap ini persis seperti jawaban HAMKA kepada orang yang berkata, “Mazhab Syafii adalah mazhab yang paling dekat kepada Syiah dan paling cinta kepada Husain.”
HAMKA menjawab, “Maaf, saya tidak bermazhab Syiah tetapi saya mencintai Husain.” Di akhir sambutannya, HAMKA menegaskan, “Bertambahlah teguh rasa cinta saya kepada kedua cucu Rasulullah Saw, Hasan dan Husain, di samping bertambah teguh keyakinan saya dalam mazhab Sunni. Sebab cinta lain dan pendirian agama lain pula.”
Di luar Tafsir al-Azhar, keterbukaan Hamka pada literatur Syiah sangatlah terlihat di buku Di Tepi Sungai Dajlah, yang di dalamnya Hamka bahkan menerjemahkan cukup banyak syair-syair orang Syiah, termasuk yang menunjukkan kecintaan mereka kepada Imam al-Husain.
Manhaj HAMKA dalam Menyikapi Syiah
Tentu HAMKA tidak menerangkan “manhaj”-nya dalam menyikapi Syiah secara sistematis. Akan tetapi, berbagai bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sikap intelektual Hamka terhadap Syiah berayun-ayun di antara dua sikap: tegas-kritis dan terbuka-toleran.
Manhaj moderat HAMKA dalam menyikapi Syiah tampak lebih dekat atau sesuai dengan nilai-nilai filosofis-ideologis yang hidup di Muhammadiyah. Sikap HAMKA yang mencoba adil dengan memberi apresiasi dan kritik dapat dibaca sebagai contoh penerapan nilai-nilai ber-Muhammadiyah. Seperti sepuluh sifat Muhammadiyah, yang di antaranya adalah sikap adil dan korektif baik ke luar maupun ke dalam, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang di antaranya memberi pedoman agar setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat kritis, terbuka menerima kebenaran dari mana pun datangnya, dan senantiasa menggunakan daya nalar.
Kebenaran dapat datang dari mana saja, dan kita tidak elok untuk merasa paling benar sendiri dan mempertahankan pendapat sendiri sebagai final dan benar.
Inilah sikap yang sudah diwariskan secara turun-temurun di Muhammadiyah sejak zaman Ahmad Dahlan. Tentu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya adalah rujukan, namun masalah-masalah ijtihadiyah tidak semestinya dibuat menjadi pendirian yang tidak boleh lagi berubah. Tentang ini HAMKA menyebut para ulama seperti para imam mazhab, yang berani mengubah pendapat mereka, sebagai teladan.
Terkait sikap terhadap Syiah, HAMKA menegaskan bahwa amat sempit paham orang bila tidak mau memperhatikan pendapat hanya lantaran berasal dari Syiah. Ini melengkapi keterbukaan HAMKA untuk menggunakan literatur tafsir Syiah, mengutip pendapat ulama Syiah, menceritakan kisah tentang seorang tokoh Syiah, dan lain sebagainya, dengan tidak menanggalkan kesunniannya.
***
Sebagaimana sifat Muhammadiyah yang memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah islamiyah, HAMKA berulang kali tampak menekankan persamaan di antara kaum muslimin. Saat membicarakan perpecahan dalam Islam, HAMKA menyatakan bahwa kita patut bersyukur karena perpecahan itu tidak sampai menyebabkan perpecahan masjid. HAMKA memberikan contoh: orang Syiah masih menganggap sah bermakmum kepada penganut Sunni, dan orang Muktazilah juga demikian terhadap firqah yang lain. (Tafsir al-Azhar, jilid 2, h. 879).
HAMKA kerap kali menyebutkan dampak negatif dari sikap ta‘ashshub pada mazhab – termasuk mazhab kalam ataupun fikih. Misalnya, HAMKA beberapa kali menyebutkan kehancuran Dinasti Abbasiyah sebagai buah dari adanya perpecahan atau kefanatikan mazhab teologis.
Dinasti ini hancur karena khalifahnya Sunni, dan wazir besarnya Syiah. Wazir al-Alqami membeberkan rahasia pertahanan negara kepada Hulagu Khan, yang kemudian meluluhlantakkan Baghdad, dan membunuh khalifah serta wazir besar itu.
Walau mengesankan wazir Syiah sebagai pemberi andil utama kehancuran Dinasti Abbasiyah, namun yang digarisbawahi oleh HAMKA bukanlah kesyiahan sang wazir, melainkan sikap ta‘ashshub-nya. Ini hanyalah salah satu contoh pengaruh negatif ta‘ashshub. Selain contoh ini, Hamka juga menyebutkan contoh-contoh lain perpecahan yang timbul akibat sikap ta‘ashshub.
Catatan Akhir
Pandangan HAMKA terhadap Syiah dapat dibaca baik dengan bingkai besar ataupun bingkai kecil. Dalam bingkai yang lebih besar, sikap HAMKA terhadap Syiah mewakili sikap kelompok mayoritas Ahlu Sunnah, yang lebih sering “memberi ruang kebenaran” bagi ijtihad yang berbeda.
Dalam bingkai yang lebih kecil, sikap HAMKA menampilkan contoh dari respon alam pikir Muhammadiyah terhadap isu keragamaan internal umat Islam. Dengan demikian, walau tulisan ini menampakkan keterbatasan, jelaslah bahwa pemikiran HAMKA , yang mencoba jernih dan berimbang dalam menyikapi perbedaan, dapat menjadi bahan atau pendorong dialog Sunni-Syiah yang coba dibangun oleh Muhammadiyah.
Editor: Yahya FR