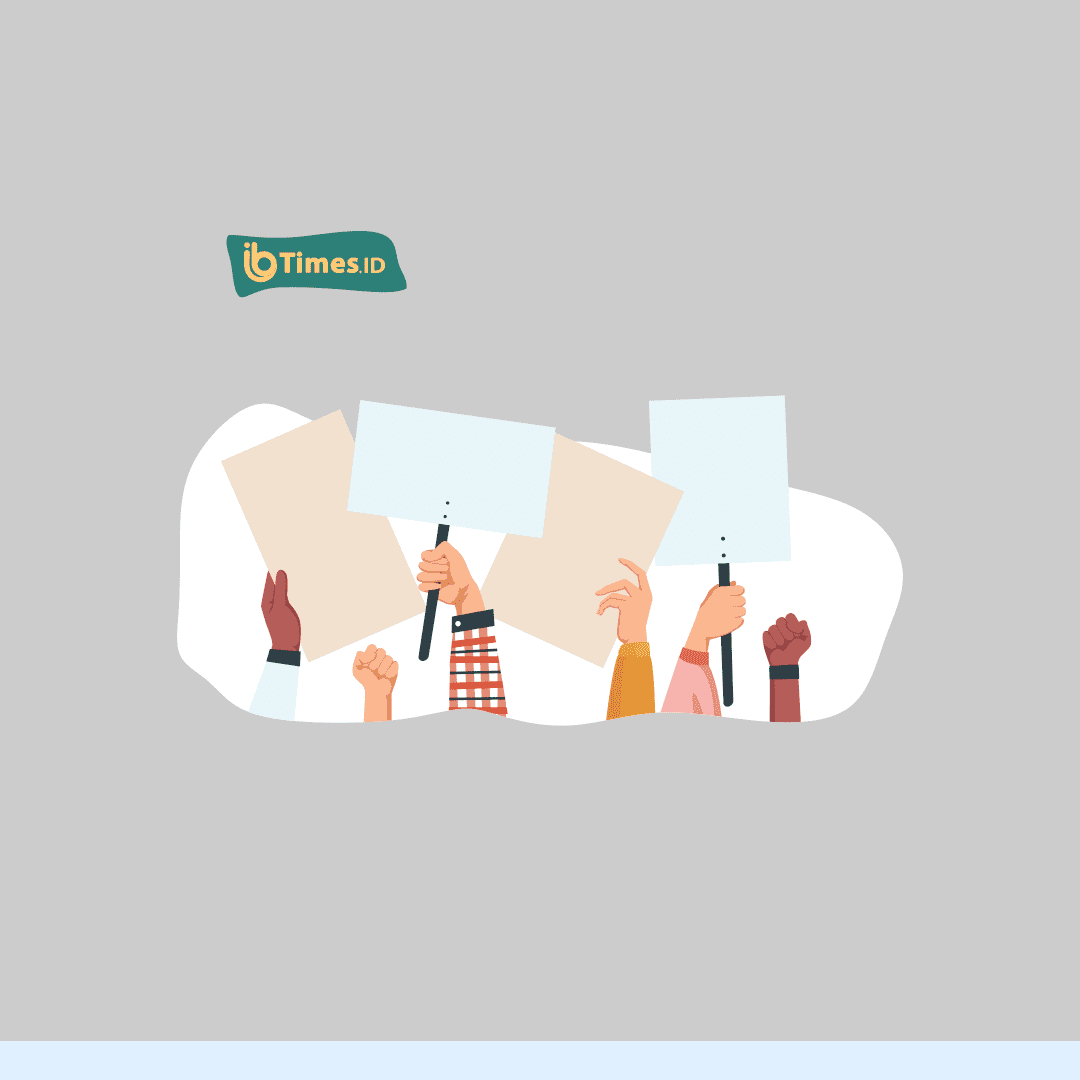Dikutip dari laman Setneg.go.id, pada hari Rabu (11/01/2023) Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM). Dari laporan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan keterangan resmi dan mengakui bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanah Air dalam rentang sejarah Indonesia. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM pada sejumlah peristiwa, salah satunya adalah peristiwa 1965-1966. Meskipun sudah terjadi lama, peristiwa 65 ini masih menyisakan berbagai macam persoalan yang belum tuntas.
Salah satu problem yang belum tuntas adalah pemberian hak-hak kewarganegaraan yang adil bagi tahan politik (Tapol). Tapol tragedi 1965-1966 ialah mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Dikutip dari Kompas, para Tapol ini dihukum tanpa melalui persidangan. Beban hukuman yang mereka terima diukur dari tingkat keterlibatan mereka dalam peristiwa G30S. Mereka benar-benar dijauhkan dan diasingkan dari keluarga, sahabat, dan masyarakat.
Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto membangun kamp konsentrasi khusus untuk para Tapol (Detik). Tahanan laki-laki diasingkan ke Pulau Buru di Maluku, sementara tahanan perempuan dikirim ke Plantungan di Kendal, Jawa Tengah. Menurut laporan BBC, setidaknya ada sekitar 500 Tapol perempuan yang mendekam di sana. Mereka dikategorikan golongan B, yakni mereka yang dianggap terlibat secara tidak langsung dengan G30S dalam bentuk keaktifan mereka dalam organisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), salah satunya adalah Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Tak hanya Gerwani saja, cukup banyak perempuan yang bukan anggota Gerwani tetapi hanya ikut-ikutan saja, juga ikut ditangkap.
Dibebaskan dengan “Setengah Hati”
Apa yang dialami oleh para Tapol ini lambat laun menyita perhatian publik, termasuk dunia internasional. Dilansir dari Tirto, saat Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Perancis, selain disambut secara hangat oleh pemerintah setempat, ia juga disambut kritik dari kelompok pembela hak asasi manusia di sana. Kritik itu tidak lain menyasar pada kebijakan rezimnya terhadap para Tapol G30S. Mereka bahkan menyamakan Soeharto dengan Nazi Jerman. Tak lama setelah peristiwa itu, organisasi Tapol yang bermarkas di Inggris juga menggelar aksi kampanye menuntut pembebasan para Tapol di seluruh Indonesia, aksi protes serupa terulang saat Soeharto mengadakan kunjungan ke Inggris. Desakan untuk pembebasan tapol bahkan juga digaungkan oleh Amnesty International. Tekanan-tekanan internasional semacam inilah yang turut mempercepat proses pembebasan Tapol di bawah rezim Soeharto. Setelah melewat berbagai lika-liku proses, akhirnya pembebasan terhadap Tapol 65 terealisasi pada akhir tahun 1977.
***
Dalam bukunya yang berjudul Musim Menjagal Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966, sejarahwan Geoffrey Robinson menarasikan betapa para eks-Tapol ini tidak diperlakukan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Sebelum dibebaskan, para tapol ini dipaksa membuat pernyataan untuk tidak menyebarkan paham komunisme dan terlibat dalam kegiatan apapun yang berpotensi mengacaukan keamanan. Para eks-Tapol ini kemudian dibatasi ruang geraknya di masyarakat oleh pemerintahan Soeharto. Pembatasan ini tak hanya memengaruhi kehidupan mereka, tapi juga keluarga, kerabat, dan juga teman-teman mereka. Misalnya, KTP yang mereka miliki dituliskan tanda khusus: ET (Eks Tapol). Mereka juga wajib memiliki surat izin khusus untuk bepergian.
Bahkan, mengutip Wicaksana dalam Kompas, tak sedikit eks-Tapol perempuan yang mengalami diskriminasi dan intimidasi di lingkungan sosial. Mereka dipaksa oleh keadaan untuk beradaptasi, namun di sisi lain, masyarakat belum siap untuk menerima mereka. Akibat resistensi dari masyarakat yang tinggi, banyak dari anak eks-Tapol ini tidak ingin lagi berhubungan dengan ibu/keluarganya. Penyebabnya, mereka tidak ingin dijauhi oleh masyarakat dan dianggap sebagai anak PKI. Para eks-Tapol yang “berhasil” diterima masyarakat adalah mereka yang memiliki usaha dan tekad kuat untuk berbaur dalam kehidupan umum di lingkungannya. Mereka telah memutus hubungan dengan masa lalunya yang dianggap dekat dengan PKI. Mereka tidak mau lagi bertemu dengan teman-teman semasa di penjara. Bahkan tak sedikit dari mereka mengganti nama dan memulai kehidupan yang baru.
Dari Jalur Struktural hingga Kultural: Upaya Eks-Tapol 65 Memperjuangkan Keadilan
Amurwani, dalam bukunya yang berjudul Suara Mereka yang Kembali dan Dikembalikan, mengisahkan betapa gigihnya para eks-Tapol ini berjuang untuk mendapatkan keadilan sebagaimana warga Indonesia lainnya dan menghapus stigma buruk masyarakat terhadap mereka. Setelah dikembalikan ke masyarakat, mereka mulai mencoba membangun relasi dan perkumpulan dengan sesama eks-Tapol seperti Paguyuban Korban Orde Baru (Parkoba), Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966, Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham), dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan dengan aktivis pembela HAM seperti LBH Jakarta, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.
Bersama-sama dengan kelompok HAM, mereka menuntut pemerintah untuk mengakui adanya pelanggaran HAM sepanjang masa Orde Baru serta menuntut pemerintah untuk mengembalikan nama baik mereka. Perjuangan mereka menemukan secercah harapan kala pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2005 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sayangnya, upaya KKR terpaksa berhenti di tengah jalan kala Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh materi UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Tak terima dengan keputusan tersebut, para eks-Tapol mengajukan class action dan menggugat kelima presiden mulai dari Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, usaha ini pun gagal.
***
Dalam buku yang diterbitkan dari hasil disertasinya tersebut, Amurwani mendapati pergeseran upaya para eks-Tapol dalam memperjuangkan hak dan menghapus stigma buruk terhadap mereka. Yang awalnya menggunakan cara-cara birokratis-struktural, kini beralih ke cara-cara kultural. Cara kultural ini berupa kegiatan-kegiatan yang tujuannya ingin memberikan narasi tandingan yang dikemas dengan konsep yang menarik. Mereka berkolaborasi dengan anak-anak muda melalui seni pertunjukan dan menonjolkan sisi kemanusiaan dan perempuan.
Maka, terbentuklah Wanodja Binangkit pada tahun 2005, Paduan Suara Dialita di tahun 2011, dan Kiprah Perempuan (Kipper) pada tahun 2006. Di setiap pertunjukkannya, kelompok-kelompok ini tak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga pesan tentang kemanusiaan. Seringkali pertunjukan itu mengusung tema atau memerankan lakon pertunjukan yang dianggap berhubungan erat dengan pengalaman mereka ketika ditangkap dan dipenjara.
Usaha-usaha kultural ini cukup menyita perhatian publik terutama kalangan muda. Mereka berbondong-bondong hadir dalam setiap pertunjukkan ibu-ibu eks-Tapol 65. Lewat pertunjukan ini, rekonsiliasi di antara masyarakat, terlebih kelompok muda, bisa terjalin tanpa melibatkan pemerintah.
Dalam buku tersebut, Amurwani ingin menunjukkan bahwa perjuangan mendapatkan keadilan ternyata dapat ditempuh dengan berkesenian dan berkebudayaan. Apa yang dilakukan eks-Tapol ini, menurutnya, bisa menjadi inspirasi bagi para aktivis lainnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM supaya sejarah yang gelap di Indonesia tidak lagi menjadi beban pada generasi selanjutnya.
*Artikel ini dihasilkan berkat kerjasama antara IBTimes.ID dengan INFID
Editor: Saleh