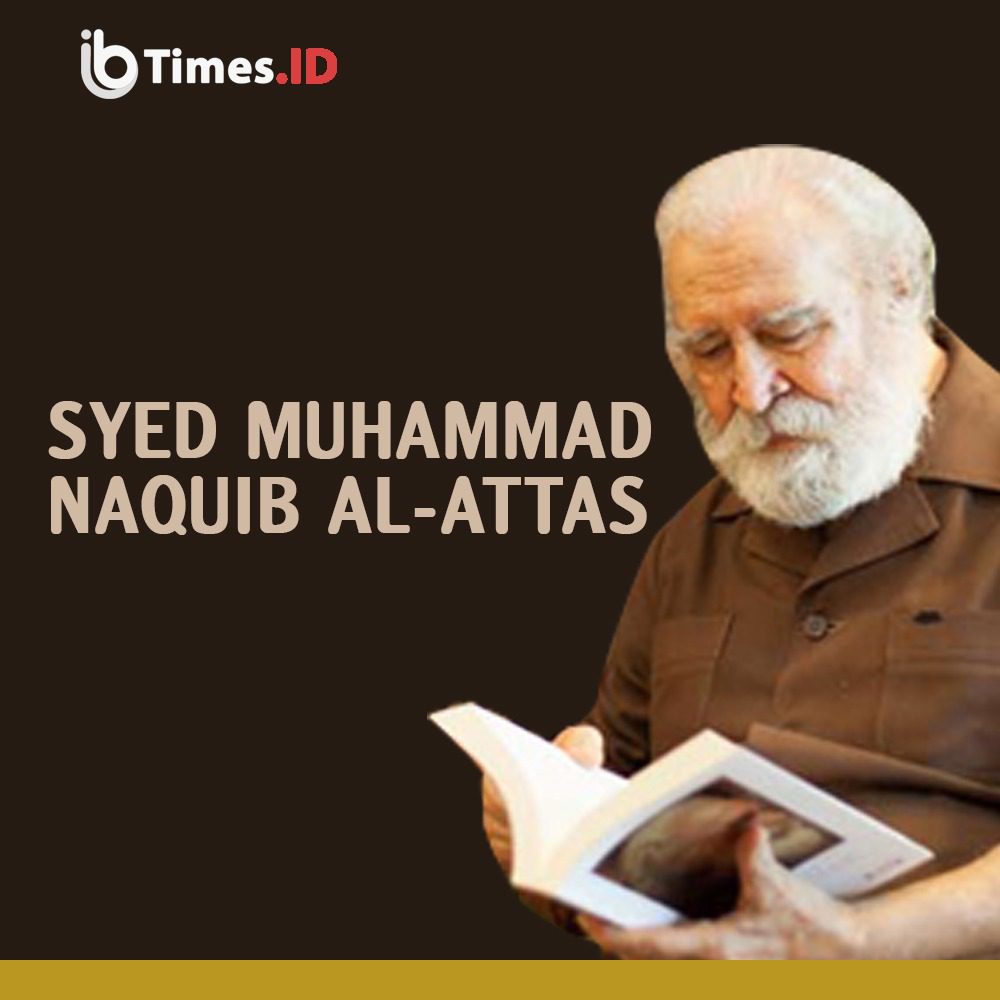Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan itu terkejawantahkan dalam syariatnya yang tidak lekang oleh zaman dan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan. Hanya saja, tidak semua umat muslim mengakui kesempurnaan itu, khususnya bagi yang berpaham sekular. Bagi mereka, menjadi sekular merupakan suatu keharusan dalam menghadapi perkembangan zaman. Berbagai penemuan dalam ilmu pengetahuan, mendorong sebuah kebenaran yang netral dari paham agama (Elson-Baker & Lightman, 2020, p. 141). Sehingga upaya pemisahan antara ranah agama dan dunia menjadi semakin menguat.
Tesis utamanya yaitu agama adalah ranah spiritual pribadi, sehingga tidak bisa dibawa ke ruang publik yang plural (Cox, 2013, p. xliii). Kaum sekularis dalam bersikap akan selalu terdikotomi. Di satu sisi mengakui kebenaran agama secara spiritual, tetapi di sisi lain menolak melibatkan kebenaran agama dalam ruang publik. Dalam beberapa paragraf di bawah akan diuraikan pendapat kaum sekularis yang salah dalam memahami kesempurnaan Islam sekaligus konsep islamisasi ilmu pengetahuan sebagai basis counter sekularisme
Paham Kaum Sekular terhadap Agama
Terma sekular berasal dari bahasa Latin saeculum, yang memiliki dua konotasi yaitu waktu dan lokasi. Dua konotasi itu merupakan representasi dari keadaan “sekarang” dan “di sini” yang berarti masa kontemporer, atau kedisini-kinian (Al-Attas, 1993, p. 16). Pengertian ini memiliki makna kemandirian manusia dalam mengurus kehidupan dunia berdasarkan akal budinya. Hal ini tidak bisa terlepas dari sejarah kelahiran sekularisasi yang berasal dari ketidakmampuan gereja dalam mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan di Barat (Elson-Baker & Lightman, 2020, p. 142).
Oleh karenanya, dalam pandangan kaum sekularis, perlu dilakukan pembagian urusan akhirat dengan urusan keduniawian. Dalam bahasa Nurcholish Madjid, mengembalikan mana yang sakral sebagai sakral, dan yang profan sebagai profan (Madjid, 2019, p. 281). Kebenaran agama bersifat sakral tetapi relatif pada setiap orang, sedangkan pengetahuan sains bersifat profan tetapi universal.
Beberapa cendekiawan membedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Pembagian ini nantinya digunakan untuk menolak bahwa sekularisasi adalah menyingkirkan agama dari kehidupan manusia (atheisme). Harvey Cox dalam bukunya The Secular City (1965) menjelaskan,
Secularization implies a historical process, almost certainly irreversible, in which society and culture are delivered from tutelage to religious control and closed metaphysical world-views. We have argued that it is basically a liberating development. Secularism, on the other hand, is the name for an ideology, a new closed world-view which functions very much like a new religion. (Cox, 2013, p. 25)
Berdasarkan uraian di atas, sekularisasi adalah proses dinamis menempatkan yang sakral dan profan pada posisinya. Kesakralan hanyalah ada pada Tuhan, bukan produk pengetahuan manusia. Sedangkan sekularisme adalah paham keduniawian yang percaya secara mutlak pada rasio sehingga anti-agama. Penggunaan istilah ini sebenarnya rancu mengingat kenyataannya, enlightment Eropa telah melahirkan filsafat sekularisme yang secara khusus memiliki spirit anti-agama. Maka sulit menentukan kapan proses sekularisasi dalam makna sosiologisnya, berubah menjadi sekularisme filosofis (Madjid, 2019, p. 342).
Selain itu, meski secara sekilas sekularisasi sosiologis tidaklah bermasalah, tetapi di sana terkandung dualisme kebenaran yang akut. Problem epistemologis ini yang kemudian melahirkan cendekiawan muslim tetapi sinis terhadap syariat Islam khususnya menyangkut ranah publik. Maka tak heran jika kemudian muncul komentar seperti “Tidak perlu membawa-bawa Tuhan dalam ekonomi” (Rusyd, 2021b).
Komentar di atas menunjukkan ajaran agama telah tereduksi menjadi kebenaran yang bersifat sepihak serta pelbagai konsep dalam ekonomi Islam, tidak lebih dari fikih hasil pemikiran ulama. Dengan berpegang teguh pada prinsip universal -yang bisa jadi merupakan konstruk pikiran- , mereka mengabaikan syariat dalam bentuk formalnya. Padahal, di setiap syariat formal dalam Islam (khususnya dalilnya qat’i), selalu mengandung hikmah yang belum tentu bisa manusia tangkap (Nurnazli, 2018). Berbagai upaya pemaknaan nilai disebaliknya, tidaklah bisa menegasikan kenyataan turunnya bentuk syariat itu. Dengan begitu, problem epistemologis kaum sekularis ini berbahaya karena merelatifkan kebenaran syariat Islam.
Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang Disalahpahami (Al-Attas)
Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan salah satu upaya cendekiawan muslim untuk mengatasi problem sekularisasi. Hanya saja, banyak orang salah paham terhadap konsep ini. Seperti ungkapan Hoodbhoy dalam bukunya Islam and Science Religious (1991), bahwa mengagas sains Islam merupakan sesuatu yang sia-sia, karena kebenaran tidak terikat nilai suatu agama (Hoodbhoy, 1991, p. 77).
Selain itu, banyak juga orang menganggap sinis islamisasi ilmu pengetahuan hanyalah proses ayatisasi, fikihisasi, maupun bentuk glorifikasi masa lalu yang takut perubahan (Rusyd, 2021a). Kesemua kritik tersebut merupakan bentuk kesalahpahaman terhadap konsep Islamisasi ilmu pengetahuan berbasis Islamic worldview yang Syed Muhammad Naquib Al-Attas tawarkan.
Menurut Al-Attas, semua bangunan pengetahuan disusun di atas sebuah worldview atau pandangan hidup. Worldview yang berisi konsep-konsep dasar untuk memandang realitas, berfungsi sebagai interpreter ilmu alam maupun ilmu sosial yang mempengaruhi arah studi suatu ilmu pengetahuan (Al-Attas, 1995, p. 113). Perbedaan worldview antara Barat yang sekuler dengan Islam tentu akan berpengaruh terhadap ilmu yang dihasilkannya.
Jika kita melihat Barat sekarang sebagai pemimpin kemajuan teknologi tetapi kehilangan ketenteraman dan tujuan hidup, kesemua itu merupakan produk pengetahuan yang mereka bangun (Al-Attas, 2019, p. 11). Ilmu pengetahuan Barat tidak membawa manusia pada tujuan penciptaannya, karena dimensi ketuhanan sengaja dicerabut darinya. Di sini Al-Attas mencoba menegaskan ketidaknetralan ilmu pengetahuan yang disebabkan worldview yang melandasinya.
Ilmu Pengetahuan Menurut Al-Attas
Ilmu pengetahuan menurut Al-Attas merupakan sesuatu yang menyebabkan bertambahnya iman seseorang. Hal ini berkonsekuensi semua ilmu haruslah memiliki dimensi ketuhanan di dalamnya. Misalnya, pada pengembangan ilmu alam atau sosial diperlukan pemahaman yang selaras dengan konsep seperti khalifah, insan kamil, dsb sehingga tidak menyebabkan kerusakan.
Selanjutnya Al-Attas juga menjelaskan, pengetahuan didapat bukan berdasarkan pada suatu fenomena. Hal ini dikarenakan, kebenaran bukan hanya kesesuaian antara pernyataan, kepercayaan, dan penghakiman dengan beberapa fakta. Ketikdaknetralan fakta menjadi problem menentukan kebenaran di sini, karena ia bisa salah, dan bahkan bisa dibuat (Al-Attas, 2017, p. 80). Islam tidak menolak pengetahuan yang didapat dari proses korespondensi maupun kohesi, hanya saja tidak berhenti di situ, ia harus berdasar panduan dalam menempatkan/mengkonstruk ilmu pengetahuan agar sesuai dengan hakikat kebenaran yang ditanzilkan Tuhan (Al-Attas, 2019, p. 15).
Pemahaman ini akan meluruskan stigma bahwa Islam menolak ilmu kontemporer seperti fisika, matematika, psikologi, sampai ekonomi, karena islamisasi ilmu merupakan proses filterisasi bagian-bagian yang tidak sesuai dengan worldview Islam yang juga berfungsi sebagai petunjuk sekaligus koridor kebenaran. Pada akhirnya, proses islamisasi pengetahuan ini merupakan hal yang alami bagi seorang muslim jika ia masih memegang erat prinsip-prinsip ajaran Islam.
Editor: Nabhan