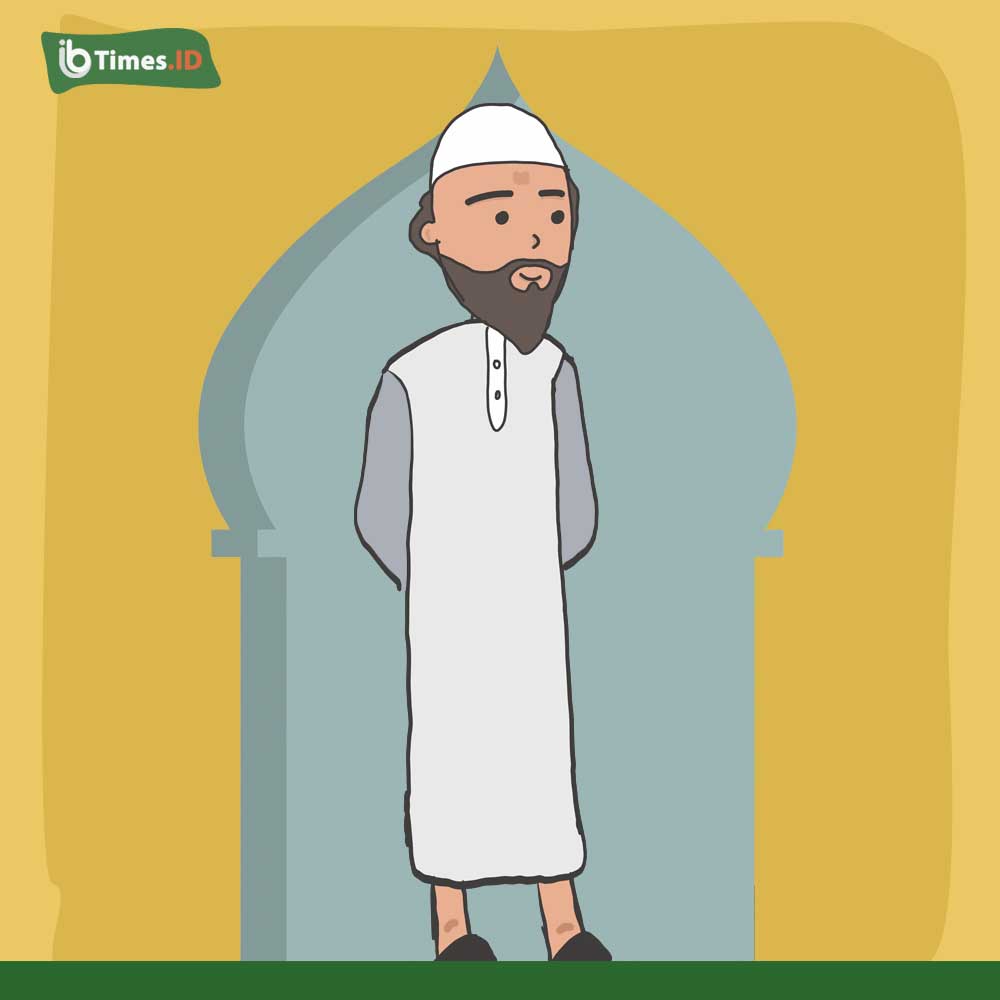Oleh Mu’arif
Sempat viral diskusi tentang baju gamis yang dipublis ibtimes.id beberapa bulan lalu. Saya memang tidak proaktif merespon isu ini, tetapi cukup menikmati diskusi yang sampai kelewat sarkas. Baju gamis, cadar, dan poligami memang menjadi isu yang hangat. Nah, setelah isu-isu tersebut kembali mengendap—karena orang sedang fokus pada banjir di Jakarta—saya mencoba merespon isu baju gamis sambil mengorek kembali beberapa loker arsip file yang lama tidak dibuka. Lalu ketemu arsip file artikel, “Baju Gamis.”
Artikel ini lahir dari pengalaman saya secara pribadi selama menempuh studi di salah satu madrasah di Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah. Sepintas, fenomena baju gamis yang menjadi perdebatan viral di media sosial memang mirip seperti kisah pengalaman saya pada 22 tahun silam. Peristiwa di masa lalu memang tidak akan terulang kembali. Tetapi saya termasuk orang yang percaya bahwa ide di balik peristiwa dapat terulang kembali, melintasi ruang dan waktu. Dengan cara seperti ini, saya termasuk orang yang menjadikan pengalaman sebagai guru. Dan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Beginilah kisahnya:
Kelompok Khittah
Kebumen 1998. Dalam sebuah diskusi dengan seorang Ustadz, saya sempat menanyakan tentang perilaku “aneh” dari sekelompok orang yang oleh masyarakat setempat dijuluki “kelompok khittah.” Mereka memakai baju gamis yang tampak sangat mencolok. Pada umumnya, kelompok ini memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut: celana cingkrang (di atas dua mata kaki), berkopiah putih—ada juga yang pakai torbus ala budaya Turki, memelihara jenggot panjang, dan sering bergerombol tapi tampak jarang berbaur dengan masyarakat setempat.
Jika diamati secara seksama, di jidat mereka tampak goresan warna kehitam-hitaman. Mereka juga memelihara cambang lebat. Yang cukup unik, ke mana-mana mereka selalu berjalan kaki sambil menenteng kitab Al-Firqatun Najiyah (secara kebahasaan artinya “Sekte yang Selamat”). Keunikan lainnya, setiap kali mereka berpapasan dengan orang lain yang bukan bagian dari kelompok ini, biasanya ucapan salamnya seperti ini: “Alaikum!” (Gaya pengucapannya kelewat fasih sampai-sampai terdengar lucu gitu). Mendengar ucapan salam yang tidak biasa seperti itu, benak saya terusik. Ini di luar kelaziman sebagaimana ucapan salam yang saya ketahui selama ini.
Setelah mendengar pertanyaan saya, Pak Ustadz—sengaja saya tidak sebut namanya secara eksplisit karena beliau masih aktif mengajar di madrasah tersebut—menjelaskan fenomena unik ini. Katanya, “Mereka adalah pengikut Nabi SAW. Memakai baju gamis adalah sunnah Nabi. Dan jidat mereka sampai kelihatan kehitam-hitaman karena begitu khusyu’ ketika menjalankan shalat. Sampai-sampai bekas sujud masih nampak jelas di jidat mereka. Dan, termasuk sunnah Nabi memelihara cambang hinggal lebat.”
“Oh, begitu ya,” pikirku waktu itu. Tapi ada yang belum dijelaskan oleh Pak Ustadz tentang kitab Al-Firqatun Najiyah. Juga tentang ucapan salam mereka yang saya rasa agak aneh. Tapi, saya sengaja tidak mempertanyakannya. Saya akan mencari tahu masalah ini lewat cara saya sendiri. Pada kesempatan tersebut saya justru mempertanyakan, “Mengapa baju gamis dianggap sebagai sunnah Nabi?”
Di Balik Simbol Baju Gamis
Pak Ustadz kembali menjelaskan. Memakai baju gamis adalah suatu bentuk “perlawanan.” Maksudnya adalah perlawanan atas budaya prestise dalam berpakaian. Tujuan memakai baju gamis untuk menghindari kesombongan. Dalam alam pikiran bangsa Arab, setiap orang yang memakai baju (jubah) besar sampai menutupi kedua mata kaki, apalagi sampai menyentuh tanah, adalah simbol kaum elite. Ditambah dengan kendaraan himar (onta merah), maka lengkaplah prestise seseorang.
Satu poin pelajarn penting yang saya dapatkan dari diskusi tersebut adalah bahwa jubah besar—bahkan sampai menyentuh tanah—adalah simbol kemewahan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyarankan agar memakai baju gamis dengan ukuran celana di atas dua mata kaki, tidak sampai menyentuh tanah—sebagai counter budaya tentunya. Juga tidak bermewah-mewahan dengan memakai kendaraan himar. Tampil bermewah-mewahan atau merasa diri paling hebat, berbeda dengan penampilan di antara yang lain adalah bentuk kesombongan. Nah, itulah konstruksi sosial budaya Arab pada waktu itu.
Nalar saya langsung banting stir. Konstruksi sosial budaya bangsa Arab kan berbeda dengan kita orang Indonesia, lebih spesifik lagi orang Jawa Tengah, lebih spesifik lagi orang Kebumen, lebih spesifik lagi orang Petanahan (pesisir) yang jarang atau malah tidak kenal sama sekali baju gamis.
“Apakah tidak sebaliknya, mereka justru yang sombong?” saya lantas balik bertanya.
Dengan agak belepotan saya berusaha menjelaskan. Mereka telah memperkenalkan suatu bentuk budaya dalam konteks budaya kita yang jelas berbeda. Konstruksi sosial kita juga berbeda dengan masyarakat Arab. Kita tidak mengenal motif baju gamis untuk melawan budaya kesombongan. Justru kita melihat baju gamis sebagai “budaya baru” yang lain dengan budaya kita. Sama artinya mereka “kelompok kittoh” telah tampil berbeda dan prestise dengan baju gamis itu. Dalam konstruksi sosial masyarakat kita, untuk melawan bentuk budaya kesombongan adalah dengan cara tampil sederhana. Tampil apa adanya sesuai dengan konteks budaya kita sendiri. Saya katakan pada Pak Ustadz, “Saya ragu, bisa jadi malah mereka yang sombong.”
Mendengar argumentasi saya yang terdengar belepotan, Pak Ustadz hanya senyum-senyum saja. Saya pun menangkap isyarat dari senyuman Pak Ustadz. Saya pun memilih diam, tidak melanjutkan diskusi agar tidak menjadi debat kusir.
Dalam hati saya, mereka “kelompok khittah” jelas latah mengadopsi suatu bentuk budaya lain ke dalam sebuah masyarakat yang memiliki konstruksi sosial dan budaya yang berbeda. Kelatahan tersebut kemudian malah menjadi bumerang. Sebab, pada mulanya motif baju gamis untuk melawan kesombongan, tetapi ketika diadopsi secara mentah-mentahan ke dalam sebuah masyarakat yang memiliki konstruksi sosial dan budaya yang berbeda justru menjadi suatu bentuk kesombongan baru. Wallahu A’lamu!
Editor: Azaki Khoirudin