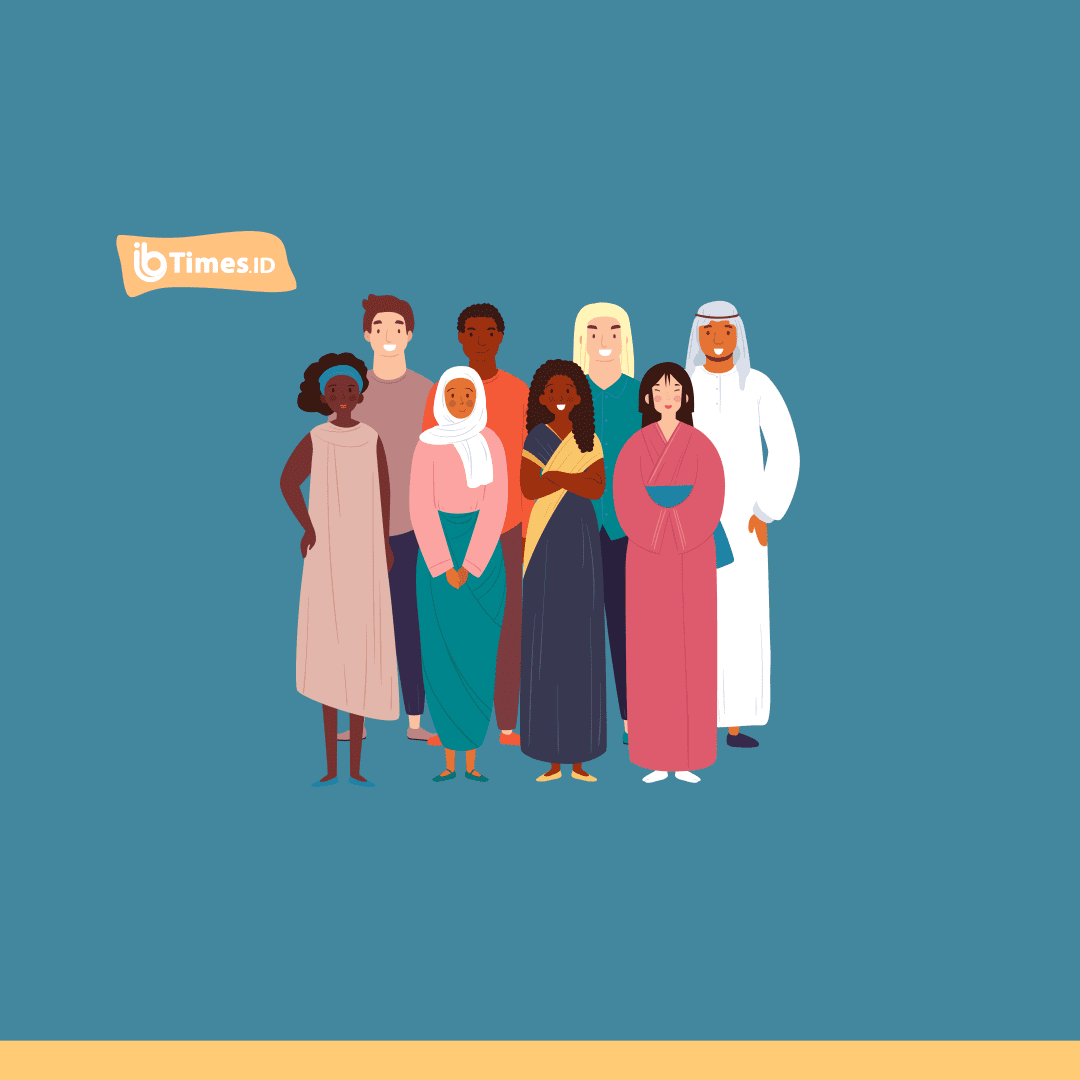Dalam buku Syamsul Ma’arif yang bertajuk Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia, tentang aliran kepercayaan/agama leluhur ketika kekuasaan Indonesia berada di tangan Suharto, mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan penganut agama pada umumnya.
Mereka dideskriminasi atas tuduhan termasuk gerakan komunis karena tidak menganut salah satu agama resmi Indonesia. Namun ketika memasuki era lengsernya Suharto pada tahun 1998, pada era reformasi ini juga berdampak pada “diskursus kepercayaan”.
TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 menetapkan pada bab terakhir tentang aliran kepercayaan, kata “kepercayaan” setelah kata “agama” telah disahkan pada era reformasi. Adanya hak-hak dan eksistensi penganut kepercayaan ini ditempatkan pada wacana HAM.
Sepanjang sejarah Indonesia, agama leluhur mengalami perlakuan yang tidak adil jika dibandingkan dengan agama resmi di Indonesia. Pada era reformasi, masyarakat adat mengkoordinir dan membentuk organisasi AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) melalui kongres perdana di Jakasrta pada 1999, lalu mendeklarasikan bahwa mereka enggan mengakui negara, jika negara sendiri enggan mengakui mereka.
Pembentukan AMAN menuntut negara untuk memenuhi hak-hak warga Indonesia serta mengakui masyarakat adat. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut negara untuk melindungi hak penganut kepercayaan sebagai warisan leluhur masyarakat adat. Dari upaya tersebut, akhirnya berhasil mempengaruhi beberapa kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat.
Bab tentang HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen dalam pasal 28E, mengkaji mengenai kepercayaan dan agama dalam ayat yang beda . Dalam ayat 1, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya…….berhak kembali”, sedangkan atar 2 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
Kedua ayat di atas menegaskan bahwa kepercayaan dan agama adalah hal yang tidak sama, namun keduanya berhak memiliki perlakuan, dan perlindungan yang setara dalam negara.
Awal Reformasi: Pelayanan Perkawinan yang Tidak Setara
Ketika awal reformasi banyak bermunculan organisasi keagamaan dengan agenda konservatisme, Martin van Bruinissen menyebutnya dengan conservative turn. Kelompok ini mempengaruhi wacana keislaman dan merabaknya kampanye anti sesat. Tahun 2005 MUI memberikan fatwa mengharamkan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme dikarenakan kampanye konservatisme tersebut melandaskan pada justifikasi legalnya UU PNPS 1/1965 yang berbenturan dengan HAM terkhusus pada penganut agama leluhur.
Nasib agama leluhur seakan kembali pada ujung tanduk akibat revitalisasi UU penodaan agama yang kembali dipertegas oleh negara melalui UU No. 16 tahun 2004 terkait kejaksaan. Isi Undang-Undang tersebut terutama pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa penganut kepercayan perlu diawasi karena berbahaya bagi negara dan agama.
Sikap tersebut terbangun ketika aliran kepercayaan dialihkan dari kementrian agama ke kejaksaan. Mendagri mengeluarkan surat no:447/707/MD yang ditujukan pada Gubernur Jawa Tengah (2006) yang intinya tentang perkawinan bagi masyarakat pemeluk kepercayaan jika tidak berafiliasi terhadap agama resmi Indonesia sementara waktu belum dapat dicatatkan. Adanya surat ini terkait dengan adanya 50 pasutri penganut kepercayaan yang ditolak oleh kantor catatan sipil di Kabupaten Cilacap karena mengguankan sistem kepercayaan.
Kembalinya Hak Perkawinan Penganut Kepercayaan
Dari kasus di atas, untuk memenuhi pelayanan terhadap penganut kepercayaan, UU Adminduk ditegaskan dalam pasal 105 yang sebelumnya penghayat kepercayaan harus memilih salah satu agama resmi Indonesia dinyatakan salah. Kini mendapat perlayanan yang lebih baik yaitu dalam aturan pemerintah no. 37, 2007, mengenai pelaksanaan UU no. 23, 2006.
Intinya, negara wajib memfasilitasi pencatatan perkawinan penghayat sesuai kepercayaannya, tidak lagi harus memilih salah satu agama resmi negara. Semisal pasal 81 ayat 1-3 yang menyatakan bahwa perkawinan penganut kepercayaan dilaksanakan di hadapan tokoh kepercayaan itu sendiri sesuai ajarannya.
Dalam peraturan presiden juga disebutkan dalam pencatatan sipil no. 25, 2008, tentang syarat, cara pendaftaran serta pencatatan sipil diterbitkan. Dalam perpres ini, posisi penghayat kepercayaan diperlakukan setara dengan penganut agama resmi.
Pengakuan terhadap agama leluhur dari negara juga tertera dalam peraturan Menteri dalam negeri no. 33 tahun 2012. Intinya, agama dan kepercayaan dibedakan, namun diperlakukan setara.
Organisasi yang dibentuk atas dasar agama dan kepercayaan dinyatakan sebagai organisasi kemasyarakatan (orkemas), dengan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu memenuhi dokumen, salah satunya surat rekomendasi. Orkesmas atas nama agama, harus memiliki surat rekomendasi dari kementrian agama (pasal 9 bagian “s”). Sedangkan orkemas atas nama kepercayaan harus memiliki surat rekom kementrian dan SKPD (membidangi perihal kebudayaan), (Pasal 9 bagian “t”).
Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pada 19 Juni 2013, no 22, 2013 menetapkan tentang pembinaan Lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Lembaga Adat. Lanjut dampaknya terhadap layanan pendidikan pendidikan agama lokal/kepercayaan yang tertera dalam Permendikbud no. 27, 2016.
Kebangkitan Agama Leluhur/Kepercayaan
Ketika masuk era kebangkitan agama leluhur/kepercayaan, diajukanlah surat peninjauan kembali UU No.1/PNPS/1965 ke Mahkamah Konstitusi RI pada 20 Oktober 2009. Dalam isi pemohon PK, isi UU No. 1/PNPS/1965 bertolakbelakang dengan HAM, prinsip negara hukum, dan UUD 1945.
Bagi pemohon PK, aliran kepercayaan, sebagaimana organisasi keagamaan lainnya, adalah bagian dari hak atas kebebasan berkeyakinan. Penghayat kepercayaan/agama leluhur bagi pemohon memiliki status dan hak setara dengan penganut 6 agama resmi Indonesia. Proses tersebut melibatkan pihak terkait yang juga diwakilkan oleh MUI.
Setelah menimbang dan mendengar semua pihak: pemohon, ahli pemohon, saksi, dan pihak terkait, seluruh permohonan pemohon ditolak oleh MK. Menurut MK, UU yang diajukan untuk menyetarakan aliran kepercayaan dan 6 agama resmi Indonesia hanya merupakan pengakuan faktual sosiologis waktu itu. Aliran kepercayaan akan tetap diakui dan dihormati. Mahkamah sendiri menilai bahwa negara seharusnya memenuhi hak-hak konstitusional penganut aliran kepercayaan tanpa adanya deskriminasi.
Dari ke-sembilan hakim konstitusi yang memutuskan terdapat satu hakim yang berbeda pendapat. M. F. Indrati mengemukakan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintah hanya enam agama resmi yang disebut UU tersebut yang dilindungi, dijamin dan dilayani. Fakta tersebut dapat di buktikan dalam urusan KTP, penerbit kartu kematian, dan dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan.
Lalu ia menyimpulkan bahwa pemohon para pemohon seharusnya dikabulkan. Perlu di ingat bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada 19 April 2010, bahwa penghayat kepercayaan dinyatakan memiliki hak berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi.
Editor: Dhima Wahyu Sejati