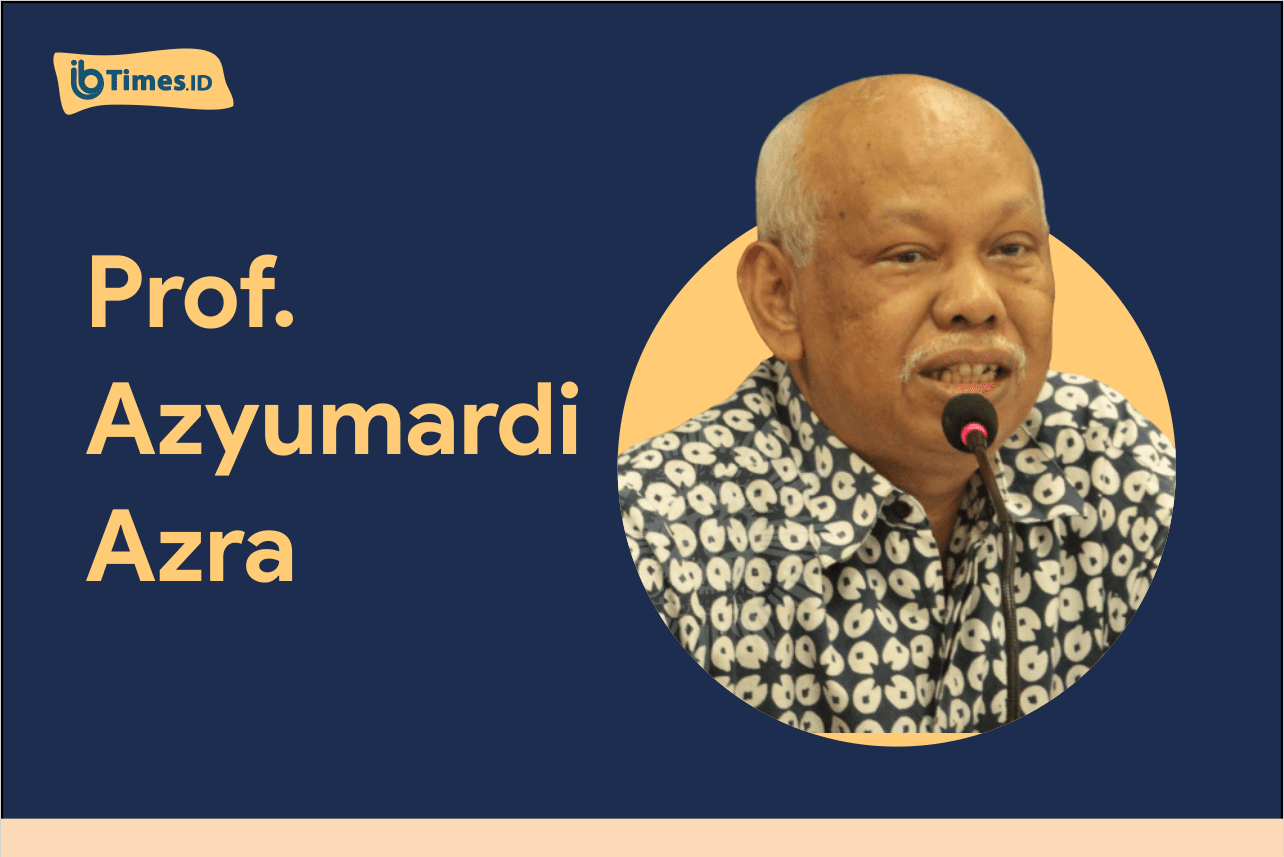Jika ada cendekiawan muslim dari Indonesia yang begitu produktif menulis, itulah Azyumardi Azra. Karya tulis guru besar UIN Syarif Hidayatullah kelahiran Lubuk Alung Sumatera Barat, 4 Maret 1955, tersebut sangat berlimpah, dalam bentuk buku maupun artikel/kolom di jurnal dan media massa. Yang paling mudah dijumpai hingga hari ini ialah di rubrik Resonansi Republika.
Saya belum pernah bersua dengan Prof. Azra—sapaan karibnya—dan juga belum pernah belajar di kelasnya. Pertama kali saya mengenal Prof. Azra dari buku yang berjudul “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia” yang berasal dari disertasinya di Universitas Colombia, New York, Amerika Serikat.
Setelah itu, saya lebih banyak menyimak Prof. Azra melalui buku-buku dan tulisannya yang rutin di Republika. Selepas membaca, saya terbiasa menyimpannya. Ada ribuan judul tulisan Prof. Azra yang saya simpan dalam bentuk file word di laptop.
Belakangan, Zoom menjadi wasilah utama untuk ngangsuh kaweruh ke Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 1998-2006 tersebut.
Intelektual Teladan
Prof. Azra, menurut saya, sosok intelektual teladan. Dia tidak hanya lihai bertutur secara lisan di kelas-kelas perkuliahan maupun bangku-bangku seminar, melainkan juga sangat terampil dan produktif berkarya tulis, sehingga kita dapat dengan mudah mengakses pemikiran-pemikirannya. Asal tahu, tidak semua tokoh mampu berbicara dengan baik sekaligus menulis secara menarik.
Gelar pendidikan tinggi, sekalipun bukan jaminan mampu berkarya tulis. Pembicara untuk acara-acara keagamaan maupun seminar/pelatihan pasti tersedia di seluruh kampus di Indonesia. Tetapi, menemukan intelektual yang mau dan mampu menguraikan pemikiran secara tertib dan menarik dalam karya tulis, benar-benar tidak mudah, sekalipun di kampus-kampus yang “punya nama”.
Prof. Azra memang istimewa, antara lain, karena memiliki tutur bahasa yang lincah secara lisan dan tulisan. Pengamat Senior LIPI, Fachry Ali, bercerita bahwa kala masih sekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA), setingkat SMA, di Pariaman, Prof. Azra berkirim puisi berbahasa Inggris dan dimuat di The Indonesian Observer. Judulnya: “Where My Heart Should be Anchored.”
Maknanya, hobi menulis itu telah tumbuh sejak lama. Tidak mustahil. Sebab, Prof. Azra sendiri mengaku bahwa buku adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya sejak dia mulai bisa membaca di tingkat SD.
Laksana teman setia, buku selalu ikut bersamanya di mana saja. Ketika perjalanan, di dalam maupun di luar negeri, mencari dan membeli buku adalah keharusan.
Ada hubungan erat antara membaca dan menulis. Menurut saya, untuk dapat menghasilkan karya tulis, seseorang tidak cukup hanya dengan membaca teori atau mengikuti seminar kepenulisan, melainkan harus mulai menulis.
Nah, untuk meningkatkan kualitas karya tulis, tidak ada cara lain kecuali dengan rutin menulis dan tekun membaca. Setiap penulis berbobot pasti pembaca serius.
Prof. Azra dan Personal Account-nya
Andina Dwifatma dalam buku “Cerita Azra, Biografi Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra”, berkisah bahwa Edy atau Mardi—panggilan Prof. Azra dalam keluarga—biasa meminjam buku-buku di perpustakaan sekolah ketika masih duduk di bangku SD Negeri 01 Lubuk Alung pada 1963. Bukan hanya buku-buku anak, namun kisah-kisah yang membangkitkan kesadaran sosial.
Di antara buku-buku kesukaan Prof. Azra ketika itu adalah “Salah Asuhan” karya Abdoel Moeis, “Tenggelamnya Kapal van der Wijck” karya Hamka, dan buku-buku cerita klasik, seperti “Sekali Tepuk Tujuh Nyawa” dan “Musang Berjanggut”. Buku-buku anggitan Utuy Tatang Sontani dan Taguan Hardjo juga kerap menjadi buruan Prof. Azra ketika masih berusia sangat belia tersebut.
Uniknya, Prof. Azra tidak lebay. Meskipun sangat mencintai buku, dirinya merasa enggan mengibaratkan, apalagi menyamakan, buku sebagai istri kedua.
Cinta istri berbeda dengan cinta buku. “Cinta ke istri tidak bisa diganti cinta ke buku, dan cinta ke buku juga tidak bisa diganti cinta ke istri. Namun, saya tidak mau kehilangan salah satunya, apalagi kedua-duanya,” tulisnya.
Prof. Azra melihat bahwa membaca dan menulis memerlukan etos, komitmen, dan konsistensi. Banyak orang rajin membaca, tetapi tidak punya cukup etos dan keterampilan menulis.
Ada pula yang mempunyai keterampilan menulis, tetapi tidak memiliki etos, komitmen, dan konsistensi dalam membaca maupun menulis. Bagi Prof. Azra, membaca dan menulis itu personal account.
Ya, kesadaran tentang pentingnya membaca dan menulis, menurut saya, perlu terus digelorakan. Dalam dunia kampus sekalipun, tidak ada jaminan dua aktivitas itu pasti menjadi tradisi.
Alibi ini dan itu kerap menyebabkan aktivitas membaca dan menulis tidak menjadi prioritas, termasuk oleh kebanyakan kalangan terdidik di Indonesia. Padahal, membaca dan menulis juga perintah Islam.
Menulis artikel di jurnal barangkali masih sering dilakukan, karena itu merupakan kewajiban dan tuntutan kepangkatan. Tetapi, tidak banyak intelektual kita yang mau dan mampu menulis buku atau artikel di media massa, yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat.
Tradisi Islam
Sebagai intelektual terkemuka dengan berjibun kesibukan, Prof. Azra masih sempat menulis buku dan artikel ringan.
Prof. Azra tentu paham bahwa membaca dan menulis itu tradisi mulia dan diperintahkan dalam Islam. Wahyu pertama adalah iqra’ yang berarti perintah membaca, sekaligus bermakna perintah menulis.
Misalnya, kita dilarang melukis fisik nabi dan rasul. Namun, menggambarkan secara detail dalam bait-bait kalimat hingga menjadi sebuah buku adalah upaya yang sangat diapresiasi.
Tradisi Islam adalah tradisi literasi, karena ditinjau dari sisi manfaat juga luar biasa. Bayangkan, kalau dulu Al-Qur’an dan kumpulan hadis Rasulullah tidak dituliskan. Kemungkinan besar tidak akan awet dan tidak pula sampai ke kita hari ini. Kita mengenal nama-nama tokoh dan ulama Islam juga dari karya tulis mereka. Kita dapat membaca karya tulis karena ada yang menuliskan.
Karena itu, saya setuju dengan pendapat bahwa membaca dan menulis adalah dua aktivitas yang sangat penting, dan sebaiknya ditekuni sepanjang hidup.
Membaca, berpikir, dan menulis harus menjadi tradisi, terutama di kalangan terdidik yang bergelar pendidikan tinggi. Selembar ijazah tidak akan berarti apa-apa ketika penyandangnya tidak terbiasa membaca, berpikir, dan menulis.
Prof. Imam Suprayogo pernah menyatakan bahwa ciri khas seorang doktor adalah selalu berpikir dan berkreasi tentang pembaruan. Seorang doktor tidak pernah berhenti berpikir. Tatkala dia berhenti berpikir, yang tersisa hanya gelarnya. Sedangkan substansinya sudah kembali menjadi manusia biasa atau sama dengan orang yang tidak bergelar doktor. Itulah doktor yang berselimut.
Doktor Tanpa Karya, Konstruksi Orientalisme
Dr. Airlangga Pribadi, dosen Universitas Airlangga, pernah menulis lebih tajam lagi. Baginya, tidak ada keutamaan seorang doktor dibandingkan yang lain tanpa teruji oleh karya.
Banyak yang tidak bergelar doktor tetapi punya karya lebih dahsyat dari 1000 doktor. Narasi keutamaan doktor dibandingkan yang lain tanpa dibuktikan oleh karya adalah konstruksi orientalisme.
Saya sendiri sering berpendapat, bedanya orang yang sekolah tinggi dengan yang bukan terletak pada kebiasaan membaca dan menulis. Biarpun gelar pendidikan berderet, tetapi kalau dia tidak gemar membaca dan tidak pula terampil menulis, ya tetap akan kalah dengan yang tidak sekolah tinggi-tinggi namun serius membaca dan rajin menulis. Fakta demikian sudah banyak terbukti.
Akhirnya, sebagaimana Prof. Azra, marilah menjadi intelektual muslim yang aktif membaca dan menulis sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam.
Sebagai sunah agama yang kerap dilupakan, setidaknya membaca dan menulis adalah dua cara ampuh untuk merawat pikiran kita agar tetap sehat. Kata sebuah judul buku karya Almarhum Hernowo, “Membacalah Agar Dirimu Mulia.”
Editor: Lely N