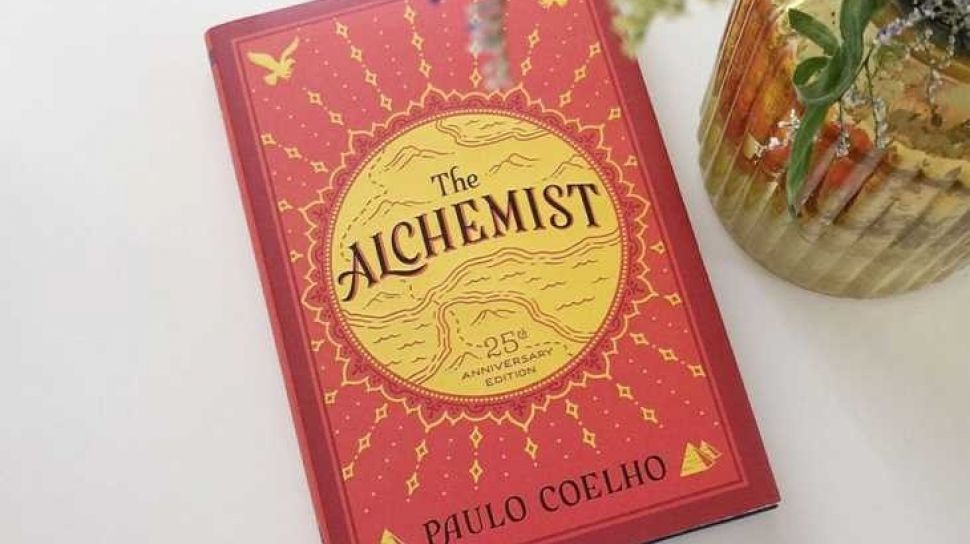Kalau kamu berencana melanjutkan studi ke Mesir, dan butuh asupan motivasi, ada baiknya kalau kamu memulainya dengan membaca The Alchemist (1988), alih- alih Ayat-Ayat Cinta (2008) atau Ketika Cinta Bertasbih (2009) yang terlalu kental nuansa ‘cinta-cintaannya’. The Alchemist berangkat dari hal yang berbeda. Mungkin masih tentang cinta, tapi bukan tentang cinta pada wanita, melainkan pada sesuatu yang tak kasat mata; impian, cita- cita, tekad, The Alchemist bakal menemanimu pergi ke Mesir dengan kecintaan itu.
Itulah yang saya rasakan saat membaca The Alchemist: kemujuran. Kemujuran pemula seorang yang baru pertama kali membaca karya Paulo Coelho, kemudian berpapasan dengan seorang kenalan. Santiago namanya, membaca kisahnya seperti bertemu teman seperjalanan secara kebetulan. Rasanya tidak ada kebetulan yang paling memuaskan selain pertemuan yang seperti itu; seakan segenap alam semesta bersatu membantu kita untuk saling bertemu.
Tepatnya di karavan, saat Santiago bilang: “aku mau ke Mesir,” saat itulah saya tahu, bahwa Paulo Coelho mempertemukan kami secara kebetulan di jalan. Setelah berjabat tangan, alangkah senangnya berbincang tentang mimpi yang sama- sama kami yakini: kemilau harta di (negeri) Piramida. Jauh memang, untungnya ada sang Alkemis yang menuntun kami ke sana, buntungnya kami juga jadi bertemu dengan pedagang kristal di pasar Tangier.
***
Ituloh pedagang yang bilang: “piramida-piramida itu hanyalah tumpukan batu. Kamu dapat membuatnya di halaman rumahmu.”Agaknya saat mendengar ungkapan itulah, saya, kamu, dan kita semua bertemu secara kebetulan dengan Santiago. Mungkin piramida, Mesir, tidaklah jadi mimpi kita bersama, namun kita sama karena sama-sama bermimpi, dan dalam meraih mimpi, pastilah kita akan berpapasan dengan pedagang kristal, yang meremehkan mimpi kita.
Sang pedagang tentu tidak melakukan itu semata-mata karena membenci kita. Ia hanya membenci dirinya sendiri yang punya mimpi berhaji ke Makkah, namun tak sanggup menutup toko kristalnya. “Dia harus memilih antara apa yang dia telah menjadi terbiasa dengannya dan apa yang ingin dimilikinya,” sebagai pemimpi, kita pasti pernah mengalami apa yang Santiago dan pedagang kristal itu lalui: tarik menarik antara zona nyaman dan hasrat untuk meraih impian.
Kenyamanan dan impian, di antara persimpangan itulah kadangkala sebagian kita berpisah dengan Santiago, lebih memilih jalan hidup si pedagang kristal: “Tak pernah pergi ke Mekkah, dan hanya menjalani hidupnya dengan menginginkan hal itu.” Itulah dusta terbesar yang dimaksud oleh pak tua Melchizedek sang raja Salem: ketika kita menyerah dengan mimpi, kehilangan kendali atas apa yang terjadi pada diri, dan hidup lalu dikendalikan oleh nasib.
***
Nasib, satu kata yang seringkali jadi alasan paling mutakhir untuk bertahan dalam kenyamanan, ialah yang kadangkala menggoda Santiago dan kita semua untuk bertahan dengan gembalaan, berakhir jadi saudagar kristal, menikah dengan Fatimah, hidup nyaman sebagai penasehat para tetua di gurun. Nasib kadangkala salah terjemah jadi pelarian, padahal nasib seharusnya senada dengan suara hati yang selalu menyeru kita untuk pergi meraih mimpi.
Sebab hati tidak pernah berkhianat, di tengah gurun keraguan kadang kala kita lupa kenyataan yang satu itu. Sang Alkemis padahal berkuda bersama dengan kita, begitu dekat, namun terkadang nasehatnya begitu jauh dari telinga kita: “Ingatlah bahwa di mana pun hatimu berada, di sanalah akan kau temukan hartamu.” Hati adalah kompas para pemimpi, ialah yang mengenalkan kita pada tanda- tanda sang pencipta yang menggiring kita pada piramida mimpi kita semua.
Hatilah yang membuat kita terus berjalan bersama kafilah sang pemimpi ke sana. Domba- domba, kristal yang berkilau, dan Fatimah yang jelita, itu semua juga harta, namun benar kata sang Alkemis: “Tapi tak satu pun dari itu semua yang berasal dari piramida.” Itu semua tak sebanding dengan mimpi yang kita terbangun karena memikirkannya, susah tidur karena belum juga mewujudkannya. Pemimpi sejati tidak akan pernah tawar- menawar untuk mewujudkan mimpinya.
Di tengah perjalanan, kita selalu bisa pulang ke Andalusia, Indonesia, kapan pun kita mau, namun begitu mimpi adalah nasib, nasib adalah mimpi, kalau cita- cita untuk tiba di (negeri) piramida belum terwujud, kita belum bisa menyebutnya nasib, pantang pulang sebelum datang; karena hati para pemimpi sejati selalu mendambakan langit, tidak pernah sedikit pun terbesit keinginan untuk jatuh di antara bintang-bintang, lalu dengan menyedihkan menyebutnya sebagai nasib.
Editor: Soleh