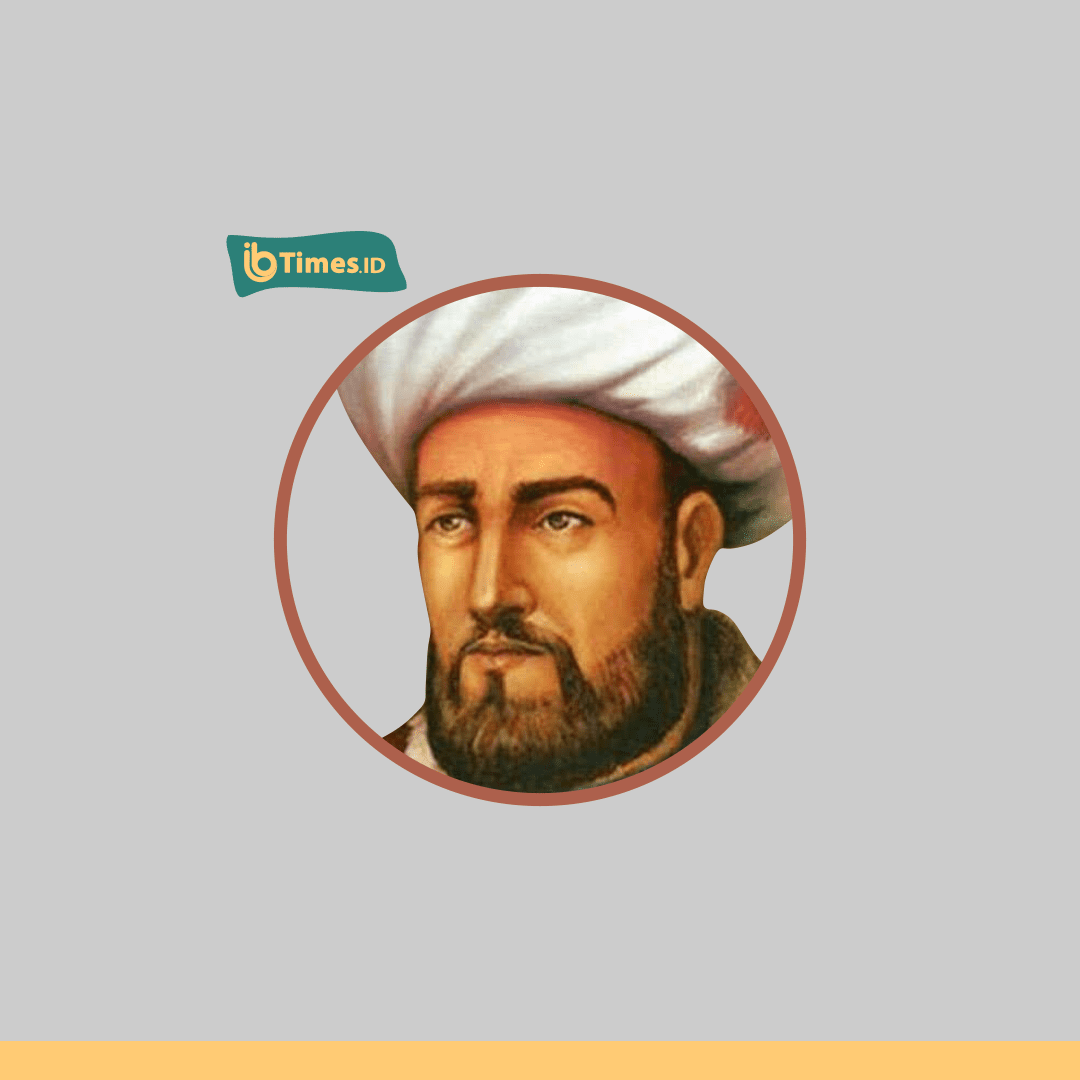Cahaya merupakan istilah dan realitas yang sangat dekat dengan para sufi. Salah satu sufi yang berbicara tentang cahaya secara intens adalah al-Ghazali. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Misykat al-Anwar, ia memaparkan persoalan cahaya secara mendalam.
Cahaya (nur) memiliki makna diya’ (sinar), dan antonimnya adalah kegelapan (zhulmah). Secara indrawi, cahaya menunjuk pada sesuatu yang terang dan berubah-ubah. Menurut al-Ghazali, makna cahaya tergantung pada siapa yang memersepsikannya. Jadi, pembagian maknanya dalam pandangan al-Ghazali sesuai dengan pembagian subjek (manusia) yang memersepsinya.
Al-Ghazali membagi manusia menjadi tiga kelompok: orang-orang awam (‘awwam), orang-orang khusus (khawash), dan orang-orang paling khusus (khawash al-khawash). Pembagian ini secara gamblang menunjukkan bahwa pada umumnya al-Ghazali juga membagi pandangannya kepada tiga kelompok tersebut.
Terkadang al-Ghazali menjelaskan sesuatu kepada orang-orang awam, terkadang kepada orang-orang khusus, dan kitab Misykat al-Anwar, di mana ia membabarkan realitas cahaya, tidak ditujukkan kepada orang-orang awam, melainkan—seperti yang ia teguhkan—kepada murid-murid terdekatnya (al-Ghazali, 1998).
Cahaya dalam Pandangan Orang Awam dan Khusus
Menurut al-Ghazali, cahaya dipahami oleh orang awam sebagai sesuatu yang terlihat oleh indra penglihatan dan sebagai sesuatu yang membuat sesuatu yang lain terlihat. Jadi, cahaya dalam pengertian ini seperti cahaya matahari, cahaya bulan, atau cahaya lampu, dan kesemuanya sepenuhnya bergantung pada persepsi indrawi, yang dalam tasawuf dianggap sebagai daya paling rendah dari semua realitas.
Jadi, dilihat dari hierarki ilmu dalam tasawuf, cahaya yang dipahami oleh orang awam menempati tingkatan yang paling rendah. Termasuk juga eksplorasi saintifik yang dengannya cahaya dipahami hanya dengan pengamatan empiris dan indrawi.
Tidak seperti orang awam, bagi orang-orang khusus, cahaya tidak mengacu pada sesuatu yang indrawi. Bagi mereka, cahaya bukanlah penampakan cahaya (sinar) itu sendiri, melainkan fakultas yang dapat menyerap cahaya. Jika cahaya sekadar mengacu pada sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang membuat sesuatu yang lain terlihat, ini tidak berlaku untuk orang buta.
Bagi orang-orang khusus, cahaya dikaitkan dengan “ruh melihat” (al-ruh al-bashirah): daya yang harus ada dalam persepsi. Jadi, dalam pandangan orang-orang khusus, cahaya adalah kemampuan yang dengannya sesuatu dapat tampak baik secara fisis maupun metafisis. Dengan kata lain, cahaya adalah “mata” yang umumnya disebut ‘aql (fakultas rasional), nafs (jiwa), atau ruh (al-Ghazali, 1998).
Orang-orang khusus lebih memahami cahaya sebagai fakultas rasional ketimbang penampakan cahaya lahiriah sebagaimana dipahami oleh orang awam. Dalam filsafat Islam, fakultas rasional (‘aql) dianggap sebagai medium yang dapat melihat yang tersembunyi dan dapat membaca yang tidak diketahui; sedangkan secara maknawi cahaya berarti sesuatu yang menghilangkan ketidakjelasan, keraguan, atau kegelapan.
***
Oleh karena itu, pada titik ini, kita menemukan bahwa cahaya dan fakultas rasional adalah dua sisi dari koin yang sama. Di sini tampak jelas bahwa proses berpikir, perenungan, atau tafakur—yang di dalamnya kita melibatkan fakultas rasional—disebut “cahaya” itu sendiri.
Hanya saja, al-Ghazali menegaskan bahwa meskipun fakultas rasional melampaui daya indrawi, itu tidak berarti bahwa fakultas rasional dapat mengetahui segala sesuatu yang ada. Memang, ada banyak hal yang dapat diketahui olehnya, tetapi ada banyak juga hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh fakultas rasional, atau tidak mungkin diketahui melaluinya.
Tak syak, fakultas rasional itu sendiri sering membuat simpulan yang salah karena pengaruh fantasi dan ilusi. Jadi, pada titik ini, fakultas rasional sebagai cahaya membutuhkan sesuatu yang lain, yaitu cahaya di luar fakultas rasional.
Cahaya yang dimaksud oleh al-Ghazali dalam hal ini adalah hikmah (kebijaksanaan). Kemudian, al-Ghazali (1998) menyatakan bahwa hikmah terbesar adalah firman Allah, yang secara khusus al-Ghazali menyebut Al-Qur’an.
Cahaya Bertingkat-tingkat
Tingkatan cahaya di dunia ini, di dunia kasatmata ini, dianalogikan oleh al-Ghazali secara sederhana: Cahaya bulan purnama bersinar melalui ventilasi sebuah rumah dan jatuh pada cermin di dinding yang kemudian membiaskan cahaya di dinding lain di depannya.
Kemudian membiaskan cahaya di lantai. Jadi, cahaya di lantai berasal dari dinding, cahaya di dinding berasal dari cermin, cahaya di cermin berasal dari bulan; dan cahaya bulan berasal dari matahari.
Setiap cahaya memiliki tingkatannya sendiri, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Dalam hal ini, menurut al-Ghazali, yang paling tepat disebut cahaya adalah sumber cahaya itu sendiri. Hierarki cahaya di dunia kasatmata juga berlaku untuk dunia metafisis (‘alam al-malakut).
Bahkan dia menyatakan bahwa ada begitu banyak tingkatan yang tidak terhitung di dunia metafisis, dan cahayanya bervariasi menurut tingkatannya.
Tingkatan-tingkatan itu berpuncak pada Sumber Cahaya, Hadirat Ilahi, yang merupakan sumber dari segala cahaya. Jadi, bisa dikatakan bahwa cahaya, baik di dunia kasatmata maupun di dunia metafisis, memiliki hierarki (al-Ghazali, 1998).
Tentu saja, semakin dekat dengan sumber cahaya, semakin besar intensitas cahayanya sekaligus semakin tinggi tingkatannya. Karena semakin dekat dengan Sumber Cahaya, semakin banyak cahaya yang diserap. Sebaliknya, semakin jauh dari Sumber Cahaya, semakin sedikit cahaya yang diserap.
Menurut al-Ghazali, hierarki cahaya tidak berlanjut hingga tak terhingga. Tetapi, berhenti pada Sumber Pertama, yaitu Cahaya itu sendiri, yang darinya semua cahaya dapat memancarkan diri mereka.
Di sini al-Ghazali seolah-olah memberikan jawaban dengan sebuah pertanyaan, “Apakah nama ‘cahaya’ masih pantas dinisbahkan kepada sesuatu yang diterangi oleh dan meminjam cahayanya dari cahaya lain?”
Cahaya dalam Pandangan Orang Paling Khusus
Dengan demikian, al-Ghazali (1998) mengukuhkan bahwa semua cahaya yang masih meminjam cahaya lain hanyalah realitas metaforis (majazi). Karena dilihat dari cahayanya, cahaya itu bukan miliknya. Hanya cahaya yang memancarkan semua cahaya dan di atasnya tidak ada lagi cahaya yang memancar itulah cahaya yang sesungguhnya.
Perlu dicatat bahwa cahaya dalam hal ini disamakan oleh al-Ghazali dengan keberadaan (wujud). Maka, keberadaan dari semua entitas, termasuk diri kita, bukanlah keberadaan kita. Tetapi disinari oleh keberadaan di atasnya. Artinya, cahaya-cahaya lain itu tidak benar-benar ada (gelap), melainkan keberadaan mereka hanya ada selama Sumber Cahaya memancarkan Cahaya-Nya kepada mereka.
Keberadaan segala sesuatu selain Sumber Cahaya sebenarnya hanyalah keberadaan kiasan atau metaforis. Yang pada dirinya sendirinya tidak benar-benar ada (‘adam) dan hanya Sumber Cahayalah yang ada (wujud). Karena hanya Dia yang memiliki cahaya dalam dan dengan dirinya sendiri.
Dengan demikian, di sini dapat kita dapat tekankan bahwa satu-satunya eksistensi sejati (wujud) adalah Sumber Cahaya, yaitu Allah. Sedangkan selain Allah, hanyalah wujud kiasan.
Inilah Cahaya yang dipahami oleh orang-orang paling khusus (khawash al-khawash). Hal ini ditegaskan secara eksplisit oleh Al-Qur’an dalam surah al-Nur ayat 35, “Allah adalah (pemberi) Cahaya (kepada) langit dan bumi.”
Editor: Yahya FR