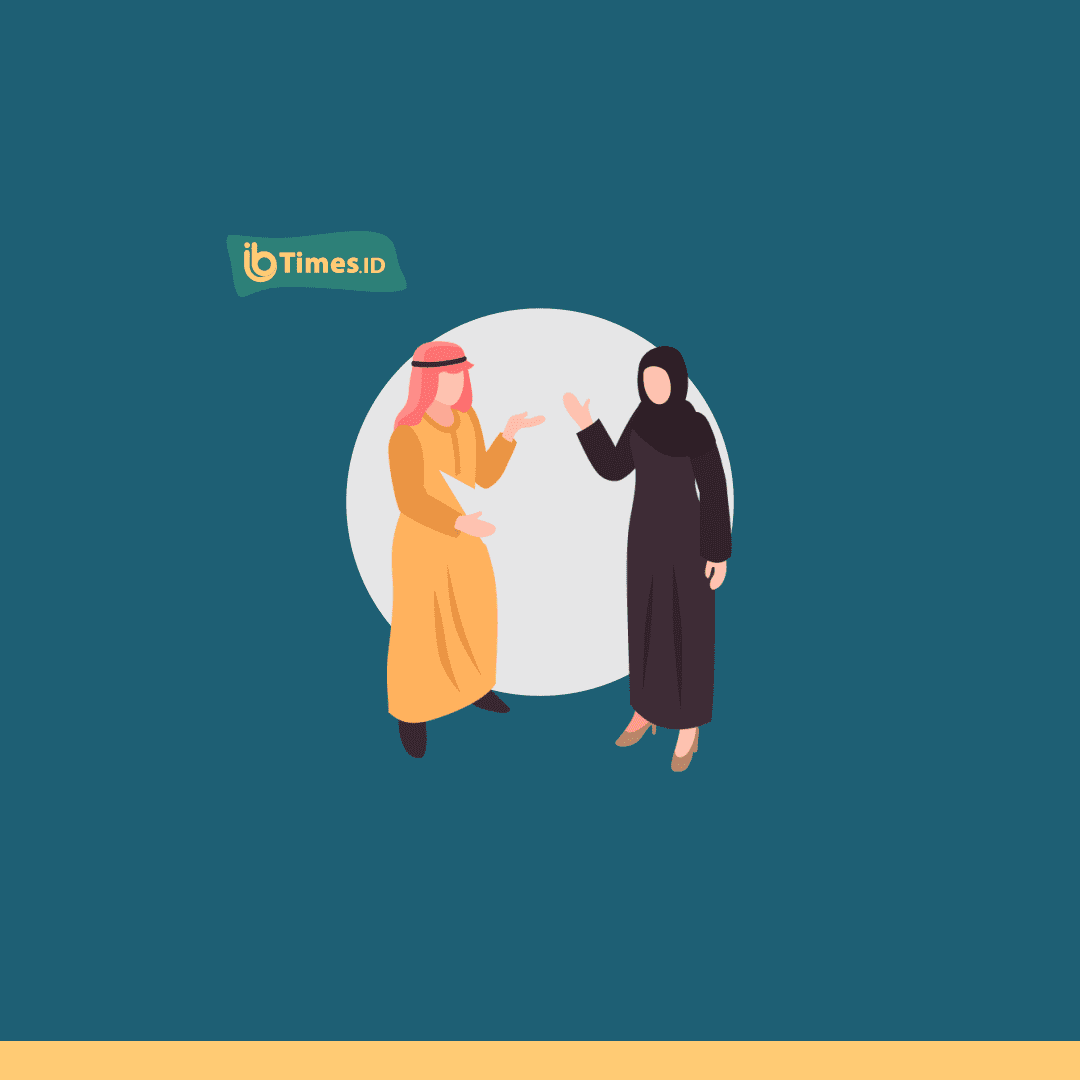Penulis AS Garrison Keillor pernah berseloroh seperti ini, “Jika orang yang duduk di gereja dapat membuat Anda menjadi seorang Kristen, maka tentunya orang yang duduk di garasi dapat membuat Anda menjadi mobil.” Maksud dari metafora ini adalah seorang ahli ibadah belum tentu dapat dijadikan sebagai representasi dari pemeluk sebuah agama sekaligus membuat dirinya dan orang lain menjadi saleh secara hakiki.
Pasalnya, cukup sering agama mengalami objektifikasi, yakni dijadikan piranti oleh pemeluknya untuk sekadar legitimasi atau untuk mendapatkan sesuatu yang sejatinya bertolak belakang dengan tujuan agama itu sendiri. Objektifikasi agama bukan monopoli politisi atau cendekiawan yang tamak kepada dunia, tapi siapa pun memiliki potensi untuk melakukannya tanpa terkecuali.
Ada kutipan yang sangat terkenal dari guru sufi Jalaluddin Rumi (1207-1273), “Agamaku adalah hidup dengan cinta.” Pada kesempatan lain, dia mengatakan, “Dalam setiap agama ada cinta, tetapi cinta tak mengenal agama.” Jadi, agama selaiknya menebar kasih dan membuat pemeluknya menjadi pengasih.
Agama di Tangan Orang yang Terluka
Seorang yang masih memenjara luka-luka perasaan, tidak menyelesaikannya tetapi justru lari ke agama atau mendadak religius sangat rawan melakukan objektifikasi terhadap agama. Alih-alih agama akan membuatnya terbebas dari luka, agama malah rawan dijadikan topeng, pelarian (sebagaimana candu), dan alat untuk memenuhi hasrat-hasrat yang dia sendiri tak sepenuhnya sadar.
Seorang yang dalam hatinya menyimpan amarah pada keadaan (keluarga, pasangan, sosial, ekonomi dll) kemudian mendadak dekat dengan agama, belum tentu kedekatannya pada agama akan melenyapkan luka perasaan yang ditanggungnya. Bisa jadi malah sebaliknya, dia menggunakan agama sebagai pembenaran atau alat untuk melampiaskan kemarahan yang sebelumnya tak tersalurkan dan membalas dendam.
Di tangan orang ini, agama akan tampak bengis, penuh penghakiman/vonis kepada orang lain, serta kering dari nalar (dalam keadaan marah, orang biasanya tak pakai akal waras). Orang yang memeluk agama dengan cara ini akan memilih fatwa-fatwa yang keras dan cenderung memicu konflik (sebagai kompensasi dirinya menjadi sasaran amarah tetapi tak pernah mempunyai kesempatan untuk meluapkannya).
Jika memiliki kesempatan, agama akan dikondisikan menjadi alat untuk menghancurkan apa saja yang menurutnya tak berkenan (aksi balas dendam dari kondisi dia sebelumnya). Orang ini tidak akan segan menggunakan agama sebagai bara teror.
Padahal, apa yang menurut jiwanya yang sakit itu benar, secara esensial belum tentu sebuah kebenaran dan dosis fatwa yang terlalu tinggi belum tentu pula hasil dari resep yang jitu dalam beragama, karena agama yang normal dan fungsional adalah yang pertengahan atau moderat, wasatiyah. Setakat ini, apa yang sebagian orang sebut sebagai “agama” lebih sering adalah produk hukum, penafsiran atau persepsi terhadap agama, yang tentu saja sulit untuk diabsolutkan kebenarannya, tetapi orang-orang tersebut malah mengabsolutkannya.
Agama di Tangan Orang yang Kotor
Contoh lain, di tangan orang yang memiliki aib (dosa yang membuatnya merasa kotor) dan kesedihan yang tak pernah terobati, agama hanya akan dijadikan topeng dan kamuflase. Aib yang disebut di sini berbeda dengan perasaan malu yang sehat, yakni kita merasa malu jika melanggar aturan, mengakuinya, lalu bertobat.
Orang yang dikuasai aibnya sendiri sampai merasa kotor akan memandang dirinya adalah kesalahan. Misalnya, seorang anak yang besar dengan cacian, seseorang yang di masa lalu hidup dalam gelimang dosa dan tak paham agama, atau seseorang yang hidupnya penuh dengan duka dan perundungan.
Orang-orang ini akan menganggap dirinya tidak berharga, kotor, dan bodoh. Begitu ingin lari ke agama, orang-orang seperti ini cenderung akan menjadi pengikut agama mode, yaitu beragama pakai logika mode—yang baru dan berbeda dari keumuman adalah yang menarik dan dianggap benar. Karena agama hendak dijadikan topeng dan kompensasi aibnya, mereka juga cenderung memilih fatwa/ajaran dengan dosis tinggi, dengan harapan hal tersebut akan lebih cepat dan efektif menutupi perasaan bersalahnya.
Tak berhenti di sini, mereka juga cenderung mencari-cari kesalahan kelompok lain sebagai kompensasi dari keadaan yang selama ini menyalahkan dirinya.
Agama tak Sepenuhnya Menjadi Petunjuk
Jadi, agama tak selamanya dapat menjadi petunjuk jalan menuju Tuhan atau kontrol terhadap nafsu karena pemeluknya tidak dalam keadaan pasrah dan mengosongkan hati ketika menerimanya. Mereka yang menutup hati dan nalar untuk menerima cinta sebagai hakikat dari agama hanya menjadikan agama sebagai alat dan legitimasi dari berbagai hasrat yang sudah ada di diri mereka.
Siapa pun, yang merasa mendadak beragama sebagai pelarian, belajar atau beragama karena terpaksa (misalnya karena ingin menyelamatkan muka keluarga), ikut pengajian karena tren, ikut kelompok agama karena kecewa dan ingin membalas dendam kepada kelompok sebelumnya, dekat dengan agama karena tahu di situ ada kapital serta kondisi tak normal lainnya, mari introspeksi: jangan-jangan sejatinya kita hanya melakukan objektifikasi agama, sebagai akibat dari jiwa yang selama ini dijadikan objek oleh subjek-subjek lain di luar diri.
Editor: Ahmad