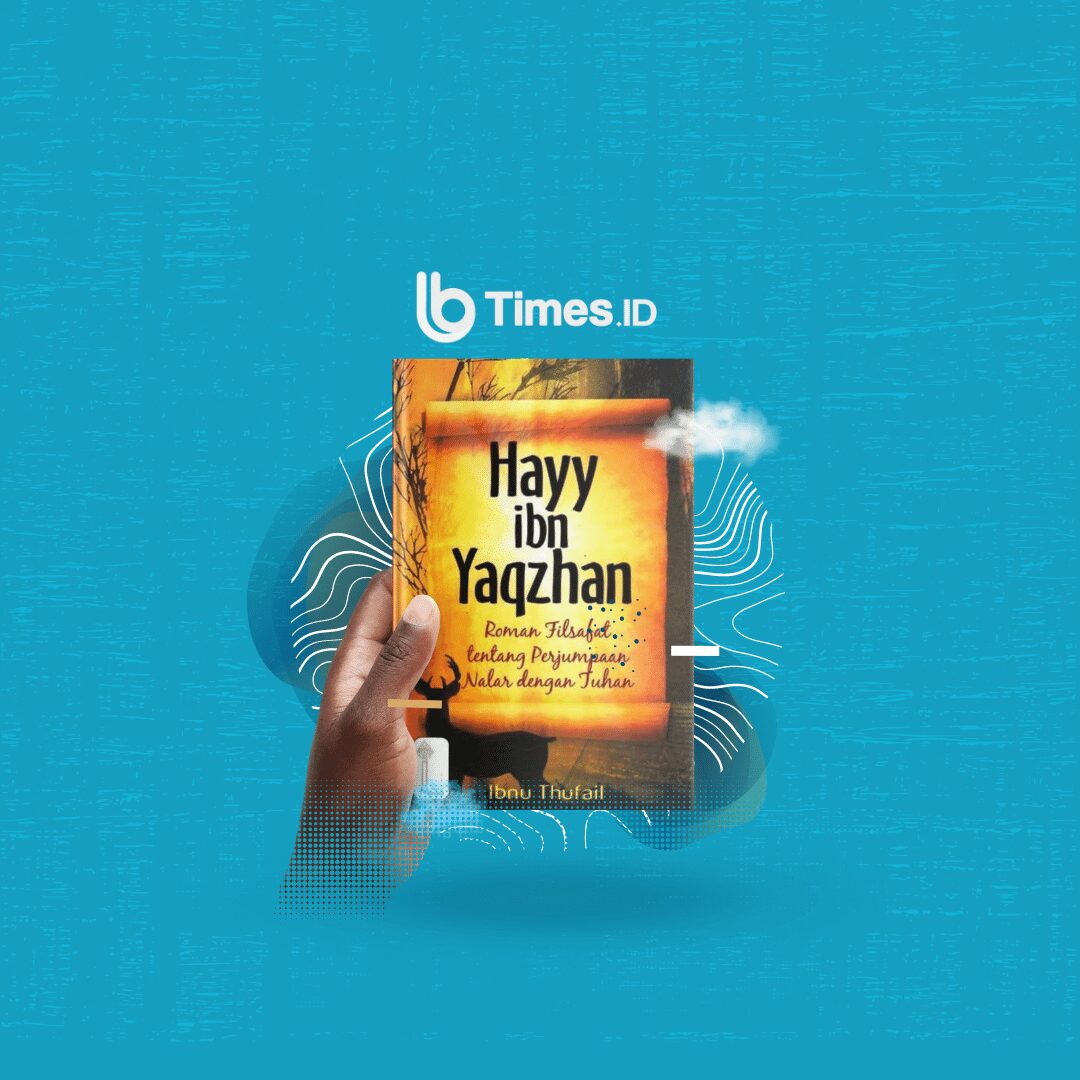Era modern ini, pembahasan mengenai akal dan wahyu kiranya terbilang cukup klasik untuk peradaban intelektual, terutama di bidang filsafat dan teologi. Namun, meski begitu, di area tertentu seperti pada kurikulum studi Islam, pembahasan akal dan wahyu yang bisa dibilang masuk dalam problem perenial selalu tidak lepas dari bagiannya. Maka, berangkat dari konteks sebagai pembelajar filsafat otodidak seperti saya, atau mungkin mahasiswa lain yang tidak kebagian tema perenial itu, ihwal akal dan wahyu merasa sangat perlu untuk dibahas lebih mendalam.
Dalam tradisi filsafat Islam, tentu tidak sedikit para filsuf yang membahas persoalan akal dan wahyu, seperti misalnya Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Secara garis besar, munculnya persoalan tersebut tidak lain adalah ketika masa para filsuf paripatetik mendapati stigma bahwa keberadaan filsafat menjadi ancaman bagi agama. Sebagaimana akal diketahui menjadi ciri khas filsafat, kala itu ditolak mentah-mentah karena dianggap membahayakan kebenaran murni (wahyu) yang disampaikan oleh Nabi dalam nash, baik Al-Qur’an maupun hadis. Namun pada akhirnya, para filsuf Islam mampu menyelesaikan masalah tersebut dan menyelaraskan antara akal dan wahyu sebagai dua alat untuk mencari kebijaksanaan.
Tulisan ini juga tidak jauh-jauh berangkat dari latar belakang itu. Salah satu di antara filsuf Islam yang tidak kalah menariknya dalam membahas persoalan akal dan wahyu adalah Abubacer, atau lebih akrabnya disebut Ibnu Thufail. Dikatakan menarik bukan karena idenya yang dibawa atau kedalaman Ibnu Thufail dalam menganalisisnya. Melainkan dari caranya menuangkan pembahasan akal dan wahyu lewat roman yang terkenal sebagai masterpiece-nya, yaitu berjudul “Hayy bin Yaqzan”.
Ibnu Thufail dalam karyanya tidak secara khusus membahas persoalan akal dan wahyu. Tema-tema besar kefilsafatan seperti teologi, epistemologi, etika, dan kosmologi pun turut dibahas dalam romannya. Namun, mengingat tema-tema besar tersebut sangatlah kompleks dan panjang jika dibahas satu per satu, maka keseluruhan isi dalam romannya akan saya batasi dengan mengerucut pada tema: Relasi antara akal dengan wahyu.
Hayy bin Yaqzan, Absal, dan Salman
Dalam romannya, Ibnu Thufail menuangkan pemikirannya lewat tiga tokoh. Hayy bin Yaqzan adalah tokoh utama yang dikisahkan sebagai manusia penyendiri yang mengamati segala hal yang ada dalam realitas, termasuk sang pencipta. Tokoh lainnya, dua orang bersaudara bernama Absal dan Salman dikisahkan sebagai pemeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Absal dikisahkan sebagai pemeluk agama yang berorientasi pada ta’wil. Sementara Salman menghindari ta’wil karena lebih berorientasi pada nash-nash lahir.
Hayy dan Absal adalah gambaran dari dua jenis pemikiran yang saling berkesinambungan. Meskipun Hayy (sebelum diajari Absal tentang kebahasaan) tidak bisa memahami kata-kata dari Absal, tapi Hayy sangat mengerti dengan segala aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh Absal. Hayy sempat berdiskusi dengan Salman. Tapi sayangnya, Salman tidak suka dengan penjelasan Hayy dan bahkan menghindarinya. Hayy lalu menyadari, betapapun mendalamnya sebuah kebijaksanaan, ia tidak akan bisa membuat orang paham tentang sebuah kebijaksanaan jika tanpa menggunakan kiasan-kiasan. Barangkali itulah mengapa Nabi menggunakan perumpamaan-perumpamaan dalam menyampaikan wahyu lewat nash.
Pergumulan dari tiga tokoh tersebut, mengingatkan saya pada sebuah epistemologi yang kerap diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Meskipun tidak begitu persis, tetapi bagi saya ketiganya cukup menggambarkan: Hayy sebagai seorang irfani dan burhani, Absal sebagai seorang burhani dan bayani, dan Salman hanya sebagai seorang bayani. Sekelumit inti pelajaran yang bisa diambil dari kisah ketiga tokoh itu adalah bahwa setiap orang mempunyai porsinya masing-masing, baik perihal pemahaman maupun permasalahan. Akan lebih mudah jika tiap-tiap porsinya diselesaikan dengan apa yang sudah menjadi kemampuannya.
Kesejajaran dan Fitrah Manusia dalam Novel Hayy bin Yaqzan
Dari kisah pertemuan antara Hayy dan Absal, Ibnu Thufail agaknya hendak mengatakan bahwa penggunaan akal secara serius bukanlah suatu penolakan atas wahyu. Di mana Hayy sebagai simbolisasi dari pengalaman batin dan penggunaan akal tanpa teks, itu merupakan sebuah gambaran dari penafsiran realitas yang dapat dikonfirmasi sebagai kebenaran yang ada dalam wahyu. Tepat di situlah antara akal dan wahyu mempunyai keterhubungan yang sejajar.
Hayy sebagai tokoh utama, secara tersirat juga menunjukkan bahwa setiap manusia yang berakal mempunyai fitrah untuk mencapai kebenaran filosofis. Apa yang disebut akhlak di dalam diri manusia merupakan unsur alamiah yang menjadi modal sekaligus pagar dari pendayagunaan akal. Sehingga tanpa adanya teks-teks, manusia sebenarnya mampu mencapai kebenaran filosofis lewat pengalaman spiritualitas dan intelektualitas-nya. Hanya saja, sebagaimana eksitensi manusia yang tidak lepas dari keterbatasan, demikian akal juga kadang kala mengalami kemacetan dan ketumpulan yang akhirnya mengharuskan wahyu membentengi situasi semacam itu.
Di samping fitrah keterbatasan, kemampuan mendayagunakan akal yang tidak semua manusia mampu mengaksesnya secara serius juga menjadi bagian dari fitrah. Hal itu dijelaskan Ibnu Thufail dengan adanya pembagian jenis pemahaman manusia. Pertama, orang-orang yang diposisikan sebagai manusia yang mampu menjangkau hakikat realitas tanpa teks. Kedua, orang-orang yang bersahabat dengan teks-teks dan mampu menafsirkan makna yang terselubung di dalamnya. Ketiga, orang-orang yang hanya mampu mendapat kebenaran dengan bergantung pada teks-teks.
Kontekstual dan Transformatif
Selain hubungan yang sejajar, akal dan wahyu dalam roman Hayy bin Yaqzan juga menjelaskan sebagai dua unsur yang dapat berhubungan secara kontekstual dan transformatif. Dengan kata lain, kesejajaran antara akal dan wahyu dapat dijadikan sebagai alternatif bagi manusia untuk menghadapi berkembangnya zaman. Sebagaimana wahyu adalah pedoman yang sudah final, tentu keberadaannya tidak lepas dari kondisi pada zamanya. Maka, pemaknaan suatu wahyu, juga berkorelasi dengan bagaimana akal mengkonstruksinya agar tetap relevan dengan kondisi realitas yang sedang berjalan.
Keterhubungan itu disampaikan Ibnu Thufail lewat tiga jenis pemahaman tokoh-tokoh tadi. Pertama, Hayy disimbolkan sebagai kemampuan yang dapat membaca realitas secara reflektif, Salman sebagai kemampuan yang dapat menafsirkan wahyu secara kritis, dan Absal sebagai kemampuan yang dapat mencari benang merah dari kondisi realitas dengan makna wahyu secara korelatif. Ketiga kemampuan itu yang menggambarkan bahwa akal dan wahyu mempunyai hubungan yang kontekstual dan transformatif.
Catatan
Dari penjelasan relasi antara akal dan wahyu di atas, menunjukkan adanya problem perenial baru di khazanah pemikiran Islam. Bukan lagi tentang apakah ada hubungannya atau tidak antara akal dan wahyu, tetapi bagaimana lanjutannya setelah tahu bahwa akal dan wahyu ini sebenarnya saling berhubungan. Ibnu Thufail sudah memberikan penjelasan terkait yang harus dilakukan. Tinggal bagaimana pemikir-pemikir Islam, atau mungkin kita semakin produktif dalam belajar dan mengembangkan pemikiran Islam agar bisa relevan dengan kondisi sekarang.
Editor: Yahya