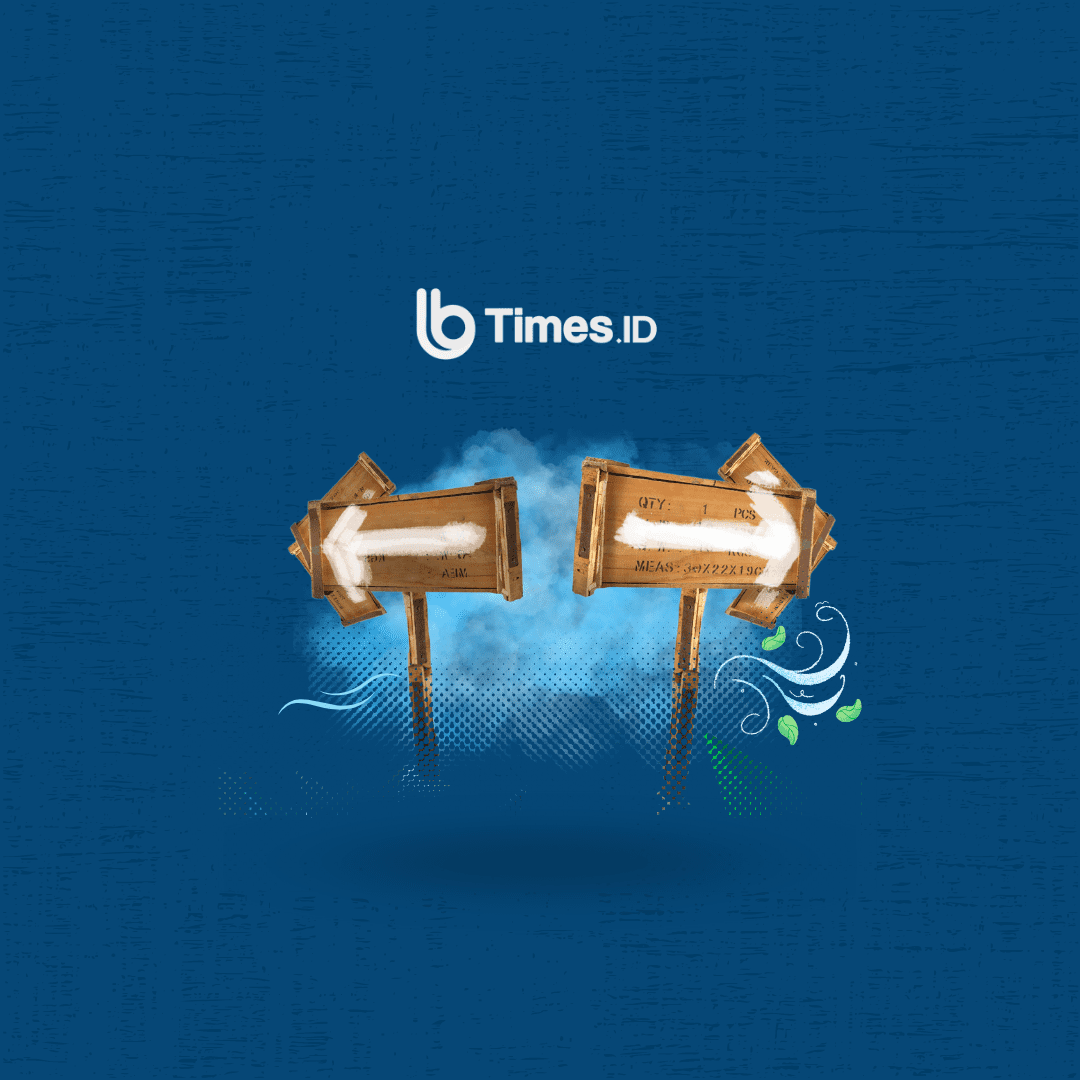Persoalan Islam garam dan Islam gincu telah bergulir sejak era awal kemerdekaan Indonesia. Perbincangan itu menandakan bahwa ada realitas di mana orang Islam saling berebut klaim terkait dengan tafsir-tafsir agama.
Sebagian menghendaki tafsir agama yang substansial. Sebagian lagi menghendaki tafsir yang simbolis. Rupanya, persoalan itu tak kunjung selesai hingga dewasa ini.
Jauh ke belakang, kita menyaksikan sebuah babak sejarah di mana Sahabat Umar berpolemik begitu hebat dengan sahabat-sahabat yang lain dalam persoalan yang kira-kira tidak terlalu jauh berbeda dengan saat ini.
Umar, sebagai seorang murid Nabi Muhammad yang sangat cerdas menghendaki tafsir agama yang subtantif. Ia berpikir begitu maju dan berani. Ia, dengan mempertimbangkan banyak hal, memutuskan untuk menyatukan suhuf-suhuf Alquran yang berserakan di tengah meninggalnya para sahabat penghafal Alquran. Umar khawatir, penghafal Alquran akan lenyap dan Alquran akan dilupakan.
Tindakan itu, bagi sebagian sahabat, merupakan sebuah bid’ah. Perbuatan dosa yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang sahabat besar yang kelak menjadi penerus estafet kepemimpinan umat Islam secara global.
Namun, Umar tetaplah Umar. Ia melihat agama dari substansi, dan salah satu substansi agama adalah maslahat. Maslahat supaya umat Islam di masa yang akan datang tetap dapat membaca dan mempelajari ayat-ayat suci Alquran tanpa harus menemui penghafal Alquran secara langsung. Kini, umat Islam di seluruh dunia menikmati apa yang dulu diperjuangkan oleh Umar.
Lebih jauh, Umar memberi kompensasi bagi pencuri. Bagi Umar, tidak semua pencuri harus dipotong tangan. Ia melihat ada persoalan yang lebih mendasar dibandingkan memotong tangan setiap pencuri. Persoalan itu adalah persoalan kemiskinan.
Bahwa jika terjadi ketidakmerataan distribusi kekayaan sehingga terjadi kemiskinan yang begitu parah, maka wajar ada satu dua kasus pencurian. Sehingga, pencurian yang dilakukan dengan sebab-sebab tertentu dan dalam batas-batas tertentu, tidak meniscayakan pelakunya dihukum dengan hukuman potong tangan.
Reformasi hukum itu tentu mengagetkan. Sebagian umat Islam saat itu begitu patuh pada titah Sang Nabi. Bahwa potong tangan berarti potong tangan. Tidak ada kompromi bagi kejahatan tersebut. Namun, sekali lagi, Umar berpikir lebih jauh dan lebih progresif, sekaligus lebih substansial.
Bahwa substansi dari ajaran Islam adalah distribusi kekayaan yang adil dan merata sehingga tercipta kesejahteraan. Dengan kesejahteraan, orang tidak perlu mencuri untuk sekedar menyambung hidup mengisi periuk nasi. Bahwa belakangan banyak pencuri dari kalangan politisi-politisi yang kaya, itu lain soal.
Rupanya, perdebatan soal substansi dan simbol itu telah terjadi sejak era sahabat. Dan, sekali lagi, ia belum selesai hingga dewasa ini. Pendulum keberagamaan umat Islam, terutama di Indonesia, masih terus berayun di antara dua kutub ini.
Kalau kita perhatikan secara jujur, sejatinya dampak negatif dari bergesernya pendulum keberagamaan ke arah simbolis ini memiliki banyak dampak negatif. Salah satu dampak yang paling serius adalah hilangnya relevansi dari agama itu sendiri.
Hilangnya relevansi agama adalah sudut pandang yang sangat Barat, tentu saja. Sebagian umat Islam yang masih percaya diri dengan budaya Islam dengan tegas menampik gagasan itu. Namun, bagi sebagian umat Islam yang realistis, perasaan was-was tentu hadir dan menghantui.
Dalam sebuah pertemuan dengan Forum Guru Besar Muhammadiyah tahun lalu, Haedar Nashir berpesan kepada forum tersebut untuk menjawab tantangan-tantangan yang digulirkan oleh berbagai pemikir Barat, terutama Yuval Noah Harari.
Harari, sebagaimana sama-sama kita tahu, dalam beberapa tulisannya menyinggung tentang agama yang semakin tidak relevan. Terutama ketika membincangkan prediksi-prediksi masa depan, seperti algoritma, kecerdasan buatan, kediktatoran digital, agama data, revolusi bioteknologi, dan seterusnya.
Dalam konteks itu, Haedar berpesan supaya guru besar Muhammadiyah mendiskusikan dimensi-dimensi spiritualitas manusia. Supaya manusia tidak termekanisasi dan menjadi sekular sepenuhnya di tengah gempuran kemajuan teknologi.
Bagaimanapun, kekhawatiran Haedar merepresentasikan kekhawatiran sebagian kelompok umat Islam terhadap hilangnya kedigdayaan agama di ruang publik, sebagaimana yang telah terjadi dalam sejarah peradaban Barat.
Namun, di sisi lain, sebenarnya ada hal yang lebih fundamental daripada menawarkan gagasan-gagasan spiritualitas kepada tantangan revolusi teknologi yang begitu gila di masa depan. Hal itu adalah upaya untuk membuat agama menjadi substansial. Menjadi garam. Bukan gincu.
Jika bicara masa depan dianggap terlalu jauh, maka kita bisa bicara masa sekarang untuk mengukur di mana bandul keberagamaan kita berada. Hari ini, semua agama memfatwakan bahwa korupsi adalah perbuatan haram.
Namun, Anda sudah tahu, korupsi seperti sudah mendarah daging dalam tubuh kita. Ia seperti denyut nadi perpolitikan kita. Tak hanya negara, virus ini juga memperkosa sebagian gerakan sipil.
Islam, secara substansi, mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia. Namun, rentetan pelanggaran HAM yang terus terjadi sama sekali tidak menarik mata penegak hukum. HAM adalah barang asing yang tidak masuk ke dalam kamus kehidupan para elit.
Islam, secara substansi, bersama-sama dengan agama lain, mengajarkan umatnya untuk mewujudkan kehidupan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Bahwa penghormatan terhadap kemanusiaan universal meniscayakan penghormatan kepada laki-laki maupun perempuan. Namun, setiap hari, benar-benar setiap hari, lini masa kita dipenuhi dengan berita pelecehan terhadap harkat martabat perempuan.
Kemiskinan, pendidikan yang rendah, intoleransi, permusuhan, eksploitasi sumber daya alam, pengrusakan lingkungan, dan ketidakadilan hukum dapat kita saksikan dengan mata telanjang. Padahal, Islam, sekali lagi, secara substansi, melarang itu semua. Hal-hal di atas menjadi sedikit contoh dari sekian banyak nilai-nilai ideal dari substansi agama Islam yang dalam realitas begitu kontradiktif. Seperti langit dan sumur. Hitam dan putih. Terbalik.
Sementara, pada saat yang sama, sebagian dari kita sibuk dengan simbol-simbol. Tentu tidak salah. Ia hanya salah ketika simbol membutakan kita terhadap fakta bahwa nilai-nilai etik Islam telah dikangkangi sedemikian rupa. Jadi, Anda ada di posisi yang mana?