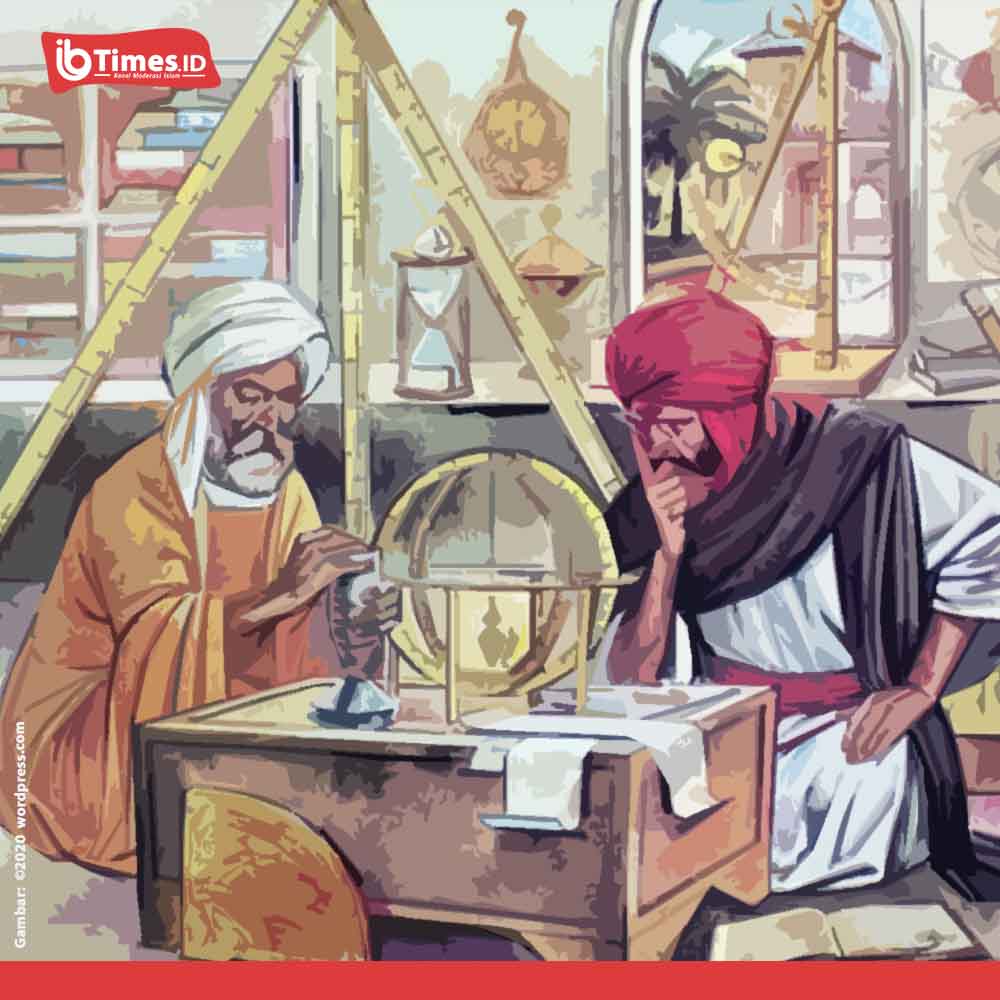Teori Civil Religion
Dalam kajian sosiologi agama, salah satu karakteristik agama yang paling ditekankan di dunia modern adalah agama sebagai pengikat peradaban. Agama seperti ini disebut dengan civil religion. Sebagai civil religion, agama memainkan peran sebagai ikatan komunal yang menjaga sebuah masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dapat berjalan harmonis.
Teori civil religion sebenarnya tidak asing dalam dunia kesarjanaan Islam. Kita ambil contoh Al-Farabi. Sekitar abad ke-10 masehi, dalam karyanya Tahshil al-Sa’adah, sarjana Muslim legendaris ini sudah menyinggung peran agama sebagai perekat ikatan sosial dalam sebuah masyarakat madani. Menurut Al-Farabi, agama bukan sekadar ajaran peribadatan. Lebih dari itu, agama mengandung memori kolektif suatu bangsa, dan memperjelas tujuan hidup bangsa tersebut.
Teori civil religion semakin menemukan relevansinya di dunia pasca-revolusi industri dan pasca-kolonialisme. Saat ketika dunia akhirnya membagi kavlingnya ke dalam bentuk-bentuk negara-bangsa (nation-state). Agama yang menjadi warisan sejak abad pertengahan, kini harus menemui tantangan baru.
Tantangan itu adalah menyesuaikan diri dalam bentuk kehidupan yang sama sekali baru. Jika dulu agama juga sekaligus penguasa negara (dalam sistem teokrasi dan aliansi negara-agama), maka kini agama hanya satu unsur saja dari identitas dan budaya suatu negara.
Islam di Indonesia
Hal yang sama tak elak terjadi juga di Indonesia. Kepulauan Nusantara pernah terbagi-bagi ke dalam kerajaan-kerajaan berbasis agama. Ada Sriwijaya dan Majapahit yang Hindu-Buddha, Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Riau, Banten, Demak, Banjar, Gowa, dan Ternate yang Islam.
Pada masa-masa tersebut, agama dan agamawan memainkan peran sangat penting bagi kelangsungan hidup kerajaan. Raja adalah titisan dewa yang disembah; Sultan adalah bayangan Allah di muka bumi.
Namun sejarah akan membawa semua kerajaan tersebut melebur dalam satu entitas bangsa yang baru. Meski waktu itu belum ada kedaulatan secara de facto, akan tetapi tak ada keraguan dalam diri pendiri bangsa kita untuk mendeklarasikan lahirnya sebuah bangsa baru; bangsa Indonesia.
Kekuasaan tidak lagi di tangan raja dan sultan. Agamawan harus menyadari statusnya yang bukan lagi tangan kanan penguasa. Tidak ada lagi hierarki dinastik dan feodalistik. Egalitarianisme ditegakkan, dan persatuan didasarkan atas kebangsaan, bukan etnis dan agama.
***
Tampak seolah-olah agama semakin terpinggirkan. Jika dulu ia adalah sentral alias pusat sebuah peradaban, maka kini tempatnya peripheral atau pinggiran saja. Mantan pejabat menteri Irak selama tiga tahun pasca kejatuhan Saddam Hussein, Ali Allawi, mengajukan pertanyaan retoris dalam karyanya The Crisis of Islamic Civilization (2009): Apakah hari ini masih mungkin bagi kita berbicara sebuah peradaban di mana agama sebagai pusatnya? Tentu jawabnya; sulit dan hampir mustahil.
Terpinggirnya agama dari kekuasaan, merosotnya peran yang bisa ia mainkan untuk membentuk kultur nasional, membuat banyak pemeluk agama, seperti Islam di Indonesia, mengalami tekanan kejiwaan, kebingungan, dan kepribadian yang terpecah (split of personality). Sulit rasanya menerima kenyataan bahwa agama yang dahulu sangat berkuasa dan berjaya, kini harus menyingkir ke sudut-sudut privat kehidupan.
Tak heran jika usaha mengembalikan lagi agama, secara formal, sebagai inti peradaban di Indonesia tak pernah berhenti. Sejak dari perdebatan tentang landasan negara, piagam Jakarta, bentuk negara Islam, hingga formalisasi syariat dan khilafah modern, selalu menjadi agenda penting untuk dibicarakan para wakil rakyat di parlemen, dan para pemangku jabatan eksekutif. Tampaknya, meski agama secara empiris harus menjadi peripheral, namun dalam benak para pemeluk setianya, agama tetaplah sentral kehidupan. Termasuk kehidupan bernegara.
Islam Peradaban
Dalam suasana agak panas inilah, wajar jika akhirnya muncul satu spesies baru dari pemahaman keislaman di Indonesia. Ahli ilmu politik dan hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menyebut varian ini sebagai Islam Peradaban, atau Civil Islam.
Dilihat dalam konteks dan suasana kehidupan di era negara-bangsa saat ini, Islam Peradaban adalah bentuk pemahaman Islam yang modern dan merekatkan antara Islam sebagai agama yang berusia ribuan tahun dengan peradaban modern yang terus bergerak dan berubah.
Artinya, Islam yang merupakan wahyu ilahi dan bersifat abadi, direkatkan dengan peradaban manusia dalam konteksnya yang sudah dan selalu berubah. Salah satu ahli sosiologi agama, Robert N. Bellah dalam karyanya Beyond Believe: Religion in a Post-traditional World (1970) menyebut bahwa Islam sebagai agama punya pengalaman penting menjadi perekat ikatan sosial dalam sebuah masyarakat majemuk.
Secara historis, Islam di masa Nabi adalah perekat utama sehingga suku-suku Arab, Yahudi, dan Nasrani di Yatsrib waktu itu akhirnya dapat bersatu dan hidup dalam keadaan damai. Piagam Madinah adalah ikatan bersama (common platform) yang hadir di tengah-tengah mereka.
Tentu saja waktu itu, Islam tidak berpretensi menjadi sebuah kerajaan. Nabi Muhammad bukanlah raja dan sultan atas penduduk Madinah. Nabi adalah pemimpin politik mereka, yang menjadi penengah (moderator) bagi semua pihak dalam berkonsultasi dan melakukan musyawarah.
Islam yang direpresentasikan oleh Nabi adalah penengah bagi setiap kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Islam bukan penguasa atas sumber daya alam dan manusia di Madinah. Manusia dan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan semua golongan.
***
Inilah contoh empiris bagaimana agama berperan sebagai sebuah civil religion. Civil religion terbentuk ketika agama menjadi basis nilai bagi persatuan dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Ia berbeda dengan agama yang sudah mengalami proses dogmatisasi, sehingga ia lebih menyerupai sebuah suku daripada agama itu sendiri. Mustafa Akyol, intelektual Muslim asal Turki, dalam karyanya Islam Without Extremes: A Muslim Case for Liberty (2011), menyebutnya agama dengan semangat kesukuan (tribalism).
Inilah yang ditengarai oleh Robert N. Bellah sebagai memudarnya spirit civil religion dalam Islam pasca wafatnya Nabi, dan menemui akhirnya pasca berakhirnya kekhilafahan empat sahabat Nabi. Sejak masa Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyyah, Safawi, dan Mughal, Islam telah beralih dari sebuah civil religion, menjadi sebuah tribalistic religion. Agama (Islam) menjadi sumber legitimasi penguasa, menjadi alat politik penguasa dan agamawan, dan akhirnya menjadi komoditi sosial, politik, dan ekonomi semata.
Hingga akhirnya pada periode modern ini, pemeluk-pemeluk Islam yang setia namun peduli pada kelangsungan peradaban bangsanya, mampu menggali kembali akar-akar civil religion tersebut. Di Indonesia, kesadaran itu muncul terutama dalam diri kaum intelektual dan ulama, yang melihat bahwa Islam adalah bagian penting bukan dalam arti politik, melainkan dalam arti perekat sosiologis. Soekarno, Hatta, Hamka, Hasyim Asyari, Wahid Hasyim, adalah beberapa nama di antara mereka yang berusaha menggali kembali akar civil religion dalam Islam.
Peran civil religion ini kemudian akhirnya melembaga dalam pemikiran yang lebih solid lagi dalam diri intelektual prolifik seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif. Tentu bukan mereka saja. Tapi setidaknya mereka adalah pendekar yang bertarung di baris terdepan dalam menghidupkan Islam Peradaban yang kita bahas ini.
Peran penting pemikiran Islam yang moderat dan berorientasi kebangsaan ini semakin kentara tatkala seluruh dunia Islam mengalami gelombang formalisasi Islam pasca Revolusi Islam di Iran dan Pakistan di era 1970-an. Berkat pemikiran Islam Peradaban yang lebih mengutamakan nilai daripada formalitas, gelombang tersebut bisa dibendung, dan pemikiran Islam yang moderat bisa tetap bertahan di Indonesia.
Civil Religion dan Masyarakat Majemuk
Dalam teori civil religion, sebenarnya ada konteks sosiologis yang menjadi latar lahirnya agama dengan corak kebangsaan dan peradaban. Konteks tersebut adalah masyarakat majemuk. Sebuah masyarakat yang terdiri bukan hanya dari golongan Islam saja, melainkan juga Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konfusianisme, dan bahkan kepercayaan-kepercayaan leluhur. Artinya, sebuah masyarakat yang plural dan multikultural.
Tentu saja Indonesia adalah contoh paling gamblang dari fenomena masyarakat majemuk ini. Dan, dalam sebuah peradaban dengan masyarakat majemuk di dalamnya, maka diperlukan sebuah perekat sosial sehingga semua elemen masyarakat yang ada merasa aman dan nyaman untuk bereksistensi dan berpartisipasi.
Dalam sebuah masyarakat majemuk ini, sangat mungkin timbul pergesekan dan konflik horizontal, bahkan vertikal; apabila unsur keadilan hilang dan dominasi serta hegemoni ditegakkan atas nama mayoritas. Nah, inilah di antara masalah sosiologis yang bisa berujung pada kehancuran, yang harus dicegah dan diantisipasi. Untuk itulah diperlukan sebuah ikatan sosial, kesepakatan bersama, yang menjadi landasan hidup bagi semua warga negara.
Itulah yang di Indonesia dikenal dengan nama Pancasila. Lima rukun dan syarat dalam tingkah laku setiap individu bangsa Indonesia. Baik itu tingkah laku para ibu dan bapak di sawah, ladang, dan pasar, hingga tingkah laku para pemimpin politik dan wakil rakyat. Lalu, di manakah letak agama? Apakah agama tetap relevan dalam kondisi serba majemuk ini?
Tentu saja, ya. Justru, agama sebagai landasan spiritual dan emosional seorang individu dan sekelompok masyarakat adalah faktor utama bagi setia atau tidaknya seorang anggota masyarakat terhadap kesepakatan bersama yang sudah tertulis.
Berbeda dengan ideologi bangsa seperti Pancasila, agama-agama adalah sistem kepercayaan holistik yang juga mengatur perilaku pemeluknya, dan mengganjar setiap perilaku itu dengan pujian atau celaan. Agama menjadi penentu apakah seorang Muslim, misalnya, rela untuk patuh terhadap ideologi Pancasila dan aturan dalam UUD 1945, atau justru berani mengkhianatinya.
Islam Peradaban Penting untuk Dibicarakan
Di sinilah akan kentara apakah agama itu telah berhasil menjadi pendukung bagi ikatan sosial dalam masyarakat majemuk, atau justru menjadi perobek tenun kebangsaan yang sudah dibuat. Dengan begitu, seperti juga ditengarai para ahli seperti Robert N. Bellah, John L. Esposito, dan Charles Kimball, bahwa agama dalam hal ini akhirnya bisa memiliki setidaknya dua wajah. Wajah yang ramah, moderat, dan bersahabat dengan konsensus kebangsaan. Atau wajah yang berusaha meruntuhkan semua konsensus tersebut, dan berusaha menciptakan tatanan dunianya sendiri.
Akhirulkalam, setiap elemen masyarakat di Indonesia perlu menginsafi bahwa agama harus diletakkan dalam fungsinya sebagai perekat kehidupan sosial. Tak melulu soal teologis, norma, dan ritual; yang kental dengan nuansa perbedaan dan pertikaian; sebenarnya agama juga punya dimensi sosiologis dan spiritual yang dapat membantu kita, pemeluknya, untuk lebih santun, sabar, dan mampu bekerjasama dengan orang lain.
Bahkan, jangan-jangan sebenarnya untuk itulah agama diturunkan oleh Tuhan? Alih-alih untuk membuat kita menghafal secara kering baris demi baris rumusan dogma dan akidah; justru sebenarnya agama adalah teguran bagi kita untuk menjaga persaudaraan sesama manusia.
Dalam konteks inilah Islam Peradaban menjadi penting dibicarakan. Islam yang bukan merupakan agama tertutup, dan lebih mendahulukan identitas dan perbedaannya dari agama lain; melainkan Islam yang terbuka, dan lebih mendahulukan kesamaannya dengan semua agama sebagai pesan persaudaraan.
Editor: Yahya FR