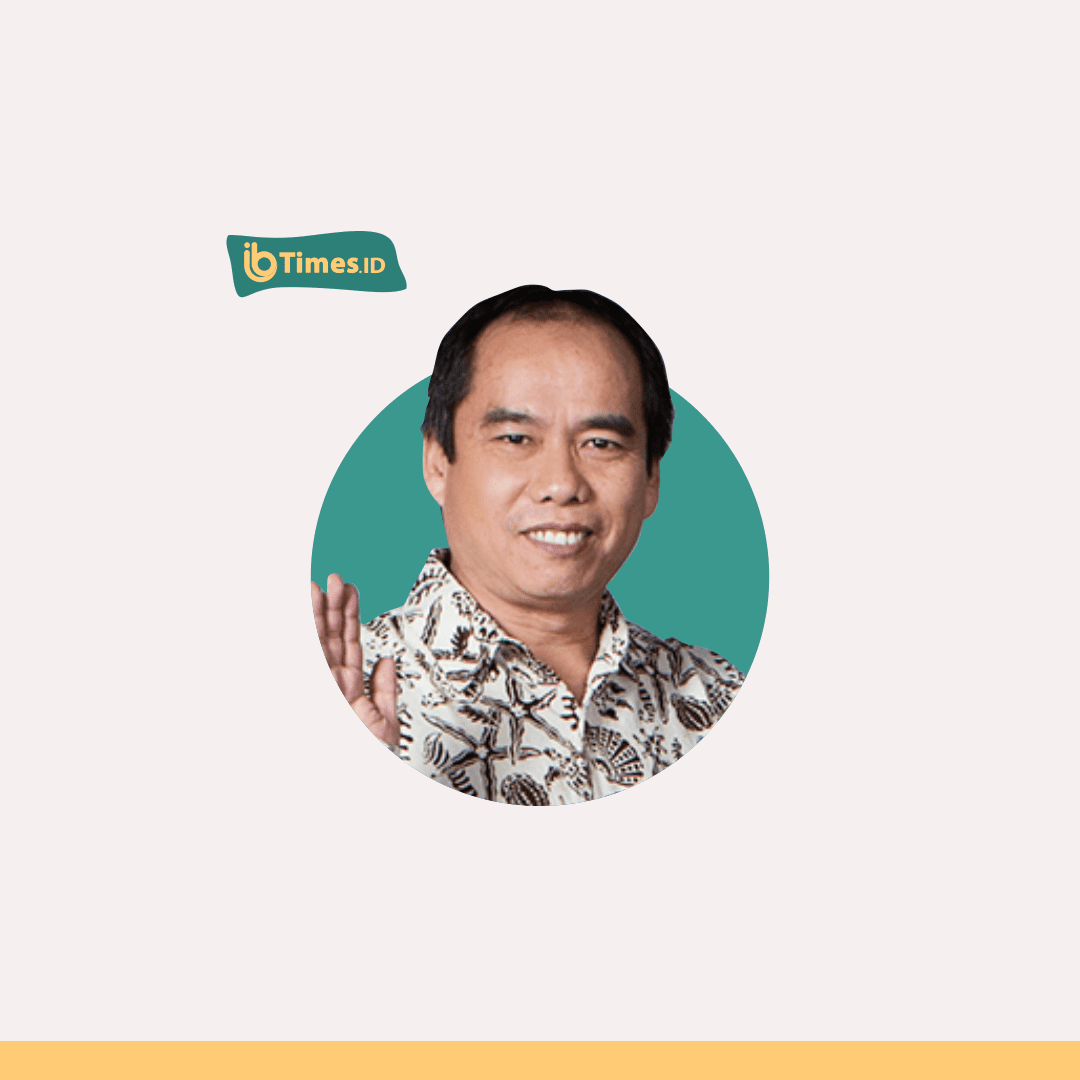Pasar Temon Kulonprogro, akhir 1980. Matahari sedang berada di puncak cakrawala ketika aku turun dari bis antar kota Jogja-Purworejo. Udara terasa panas menusuk. Perjalanan berlanjut dengan jarak tempuh lebih tiga kilometer. Jalan aspal yang aku lalui melewati perkampungan, dilanjutkan dengan melalui persawahan terbuka, untuk kemudian memasuki perkampungan terakhir di pantai selatan pulau Jawa.
Tidak ada angkutan umum. Tidak ada delman maupun ojek. Pilihan satu-satunya adalah jalan kaki. Setelah hampir satu jam berlalu aku memasuki sebuah rumah di tengah pedukuhan Sangkretan, desa Glagah. Seorang ibu setengah baya menyambutku dengan sumringah. Senyum tulus beliau membuat tiba-tiba udara panas siang itu terasa sejuk. Kebahagiaannya menjalar kepadaku dan membuat lelahku berjalan kaki di tengah terik hilang seketika. Aku bertemu lagi dengan beliau. Mamak.
Satu hal yang membuat aku betah bertahan meskipun dalam kondisi sulit secara finansial ketika merantau untuk sekolah di Jogja adalah dukungan psikologis dari beberapa ibu. Mereka memperlakukan aku, si perantau cilik seakan anak mereka sendiri. Semasa di kampung halaman, satu-satunya figur ibu yang aku kenal adalah Indok, ibu kandungku sendiri.
Di Jogja aku mengenal dekat beberapa ibu. Pertama, si Mbok ibu kos tempatku tinggal di Pengok Blok G. Kedua, Bu We, yang tinggal di Pengok juga. Tapi di Blok A, blok para petinggi PJKA. Tentang beliau sudah aku ceritakan dalam “Bu We ketangguhan Seorang Ibu.” Ketiga, Mami, ibunda dari teman akrabku semasa di SMA. Kebaikan beliau sekeluarga menghantarkan aku keliling Bali dengan sedan Premier selama seminggu lebih pada 1984. Keempat, ini pada masa yang jauh belakangan, Mak-e, seorang ibu di Jepara yang menganggap aku seperti anak sendiri yang juga adalah mertuaku. Kelima, Mamak, yang akan aku ceritakan dalam tulisan ini.
Aku mengenal Mamak seiring dengan dimulianya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa Indonesia. Pada 1980 KKN angkatan pertama diselenggarakan oleh IAIN Sunan Kalijaga (Suka) yang kini berganti nama menjadi UIN Suka Jogja. Salah satu peserta KKN IAIN Suka ini adalah kakakku Buw Mushlih. Buw ditempatkan di Glagah Kulonprogo, sebuah desa yang pada masa itu masih terpencil. KKN dilangsungkan selama dua bulan penuh.
Disana Buw tinggal di rumah Pak Prawotodiharjo, Pak Dukuh dusun Sangkretan. Pada suatu kesempatan Buw mengajakku ke lokasi KKN-nya ini. Inilah awal perkenalanku dengan Glagah. Kehadiranku saat itu mengejutkan Bu Prawoto yang belakangan aku panggil dengan Mamak. Beliau heran ada anak kecil yang sebaya dengan anak keempat dan kelimanya meninggalkan kampung halaman di pulau sebrang merantau begitu jauh ke Jogja. Mamak makin tertarik karena si perantau cilik ini mudah menyesuaikan diri dengan suasana pedesaan di Glagah. Mungkin juga ditambah dengan rasa kasihan, maka muncullah rasa kasih sayang Mamak pada si perantau cilik ini.
Sebagai orang yang berasal dari desa memang aku cepat beradaptasi dengan suasana pedesaan Glagah. Dua anak terakhir Mamak yaitu Aris dan Singgih masih sebaya denganku. Kami sama-sama masih sekolah SMP. Mereka segera menjadi teman akrabku. Aku menghormati Mas Bambang anak pertama Mamak seperti kakakku sendiri. Demikian juga aku menyikapi Mbak Tutut anak kedua dan mbak Abu anak ketiga Mamak. Selanjutnya teman bermain Aris dan Singgih juga menjadi teman-temanku juga.
Kunjungan-kunjunganku selama masa libur sekolah yang berlangsung seminggu sampai dua minggu membuat kebersamaan kami berjalan cukup lama. Aku terbiasa mengikuti Mamak ke sawah untuk menyiram tanaman semangka. Bagian yang paling menyenangkan dari kebersamaan ini adalah mecak, mencari ikan di pantai selatan. Alat penangkap ikan berbentuk jaring besar persegi empat yang empat sisinya dibingkai dengan bambu. Jala berbingkai ini diletakkan pada tempat yang tinggi di tepi laguna pantai Glagah. Jaring lalu ditenggelamkan dan di atasnya digantungkan sebuah lampu kecil. Lampu kecil itu menjadi daya tarik bagi penghuni laguna untuk mendekat.
Setelah beberapa waktu jaring lalu diangkat. Dengan cara ini banyak ikan, udang, dan kepiting terjebak sehingga bisa kami pungut. Maka di tengah malam, kami membakar mereka dengan arang di atas tungku yang sudah disiapkan. Kami menikmati hangatnya kebersamaan sambil makan ikan, kepiting, dan udang bakar di tengah gemuruh suara ombak pantai selatan di tengah malam yang menggetarkan.
Kunjungan ke rumah Mamak tetap aku lanjutkan meski pada 1984 Buw meninggalkan Jogja. Rata-rata setahun sekali aku hadir di Glagah. Biasanya pada musim libur sekolah. Kunjungan ke Glagah selalu diikuti dengan menginap disana. Setelah Buw tidak di Jogja maka Mamak dan beberapa orang tua lainnya menjadi figur orang tuaku di Rantau. Pada 1985, aku tamat dari SMA Muhi Jogja. Ini adalah periode tersulit dalam sejarah hidupku. Tentang ini telah aku ceritakan dalam tulisanku yang lain “BUW Berani Bermimpi.”
Keluargaku karena alasan-alasan objektif menyerah tidak bisa membiayai kelanjutan studiku. Maka aku hadir di depan mamak di Galagah. Setelah mendengar ceritaku mamak dengan penuh ketulusan berucap, “koe wis tak anggep anakku dewe, lee. Wis kowe manggong nang kene wae. Sok ne aku wis duwe rejeki, kowe tak kuliahke….” (Kamu sudah aku anggap seperti anakku sendiri, nak. Kamu tinggal disini saja. Nanti kalau aku punya biaya, aku akan kuliahkan kamu).
Kalimat ini persis sama dengan yang diucapkan Ibu We seorang ibu lainnya yang juga melihat aku seperti anaknya sendiri. Kalimat-kalimat itu menjadi peneguh semangat bagiku untuk terus bertahan dan tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Aku menjawab Mamak dengan, “maturnuwun Mak. Kulo tak usaha riyin. Kulo bade kuliah sinambi kerjo. Mangke nek mentok kulo sowan mriki malih…” (Terimakasih, mak. Saya mau berusaha dulu, mau kuliah sambil kerja. Nanti kalau tetap tidak ada jalan keluar, saya datang kesini lagi).
Cita-citaku untuk kuliah akhirnya bisa menjadi kenyataan. Alhamdulillah setelah bekerja sebagai karyawan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jogja selama setahun pada 1986 aku berangkat ke Solo untuk memulai kuliah di Pondok Shabran-FAI UMS. Kuliah ini beasiswa penuh selama lima tahun. Aku menjadi utusan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Sebelum ke Solo aku meluncur ke Glagah, menemui Mamak, menyampaikan kabar gembira sekaligus pamit karena akan hijrah ke Solo. Lima tahun kemudian, pada akhir 1991 setamat dari UMS aku kembali ke Jogja untuk melakukan tugas pengabdian pada persyarikatan Muhammadiyah. Pada suatu kesempatan aku kembali meluncur ke Glagah. Kali ini tidak lagi dengan jalan kaki dari Pasar Temon. Aku naik bis Menoreh dari Jogja yang melewati desa Glagah.
Mamak tidak berada di rumah saat aku sampai. Maka aku mencarinya ke sawah. Betul saja, aku bertemu dengan beliau yang sedang merawat tanaman semangkanya. Seperti biasa Mamak menyambut kedatanganku dengan wajah sangat bahagia. Sambil membantu Mamak menyiram tanaman aku menyampaikan progress report pada Mamak. Bahwa aku sekarang sudah menjadi orang Jogja lagi. Bahwa aku sekarang sudah bekerja di UMY. Nasib baik membawaku diterima menjadi dosen baru di UMY. Mendengar ini, di tengah sawah yang sejuk Mamak berteriak, “Mahli, kowe saiki wis dadi dosen… alkamdulillaah…..” (Mahli, kamu sekarang sudah menjadi dosen. Alhamdulillah).
Glagah berkembang pesat seiring perjalanan waktu. Pantai Glagah menjadi destinasi wisata andalan Kulonprogro. Maka isolasi menghilang dari Glagah. Masyarakat juga mengembangkan mata pencaharian di luar pertanian. Beberapa teman masa kecilku menjadi pemilik warung di Pantai Glagah. Lik Win, adik kandung Mamak memiliki sebuah rumah makan dengan halaman luas disana. Para petani pun mengembangkan diri. Beberapa dari mereka bukan lagi petani tradisional. Mereka sudah menjadi petani sekaligus pengusaha pertanian. Salah satu diantaranya adalah Mamak. Beliau menjadi pedagang semangka antar propinsi. Mamak menanam semangka di beberapa lahan yang beliau sewa sampai di luar desa Glagah dan menjual semangka dagangannya antara lain ke Pasar Induk Jakarta.
Pada suatu ketika, era 1990-an aku menjadi pejabat di kampus. Aku diberi amanat menjadi wakil dekan bidang-3 pada FAI UMY. Jabatan ini membuat aku sering mendampingi kegiatan mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Pada suatu waktu kegiatan kemahasiswaan berlangsung di Pantai Glagah. Kali ini untuk menuju ke Glagah aku tidak lagi naik angkutan umum, apalagi jalan kaki tiga kilometer. Sebuah mobil dinas setia menghantar perjalananku.
Di sela-sela tugas tentu aku gunakan kesempatan untuk mengunjungi Mamak. Mamak sedang menjadi pedagang semangka antar provinsi dan untuk itu beliau memiliki sebuah gudang besar. Mamak mengajak aku memasuki gudang semangkanya. Mamak lalu meminta sopirku membuka pintu bagasi mobil. Selanjutnya Mamak memerintahkan seseorang memasukkan puluhan semangka sampai memenuhi bagian belakang mobilku yang kosong. “Kanggo oleh-oleh…” (untuk oleh-oleh) kata Mamak singkat. Mamak tidak mempedulikan penolakanku. Ini tentu saja mengherankan sopirku. Kok bisa oleh-oleh sebanyak itu? Maka dalam perjalanan pulang ke Jogja aku bercerita panjang lebar tentang jalinan paseduluran (persaudaraan/kekeluargaan) antara aku dan Mamak sekeluarga. Jalinan kasih sayang seorang ibu dengan seorang perantau cilik yang melintasi batas suku dan waktu.
Kini Glagah bahkan sudah menjadi kota. Pantai Glagah Indah sebagai destinasi wisata selalu ramai dikunjungi wisatawan. Tegalan yang sebelumnya tempat orang Glagah menanam semangka dan sayuran lainnya telah berubah menjadi Yogyakarta International Airport. Sebuah lampu pengatur lalu lintas juga tepasang di simpang empat jalan bagian timur Glagah yang padat. Suasana perkampungan juga sudah telihat seperti kota. Rumah-rumah megah berdiri di kiri kanan jalan raya Deandels yang membelah desa Glagah.
Sejak bandara berdiri, beberapa orang Glagah mendapatkan rezeki besar karena ganti untung dari lahan rumah atau tegalan yang tergusur. Seorang sahabat masa kecilku kini mendirikan sebuah rumah gedung megah dan tiga mobil mewah bertengger di garasi rumahnya. Satu untuk dia, satu untuk suaminya, dan satu untuk anak semata wayangnya. Tetapi persaudaraanku dengan Mamak sekeluarga tidak pudar oleh gempuran modernisasi. Kata pepatah Melayu, tidak lapuk karena hujan tidak lekang karena panas. Kunjungan-kunjunganku masih disambut dengan kehangatan seperti era 1980-an.
Jogja, 20 November 2020. Hujan deras awal musim hujan mengguyur kampus UMY. Aku sedang duduk di ruang kerjaku di lantai-2 Gedung Pascasarjana. Aku menghadap ke timur, memandangi taman asri di tengah kampus yang berkali-kali meraih predikat Green Campus dari Kementerian Lingkungan Hidup ini. Tetapi pikiran dan perasaanku mengarah ke barat. Khayalanku berkelana menunggangi bis jurusan Jogja-Purworejo dan berhenti di Pasar Temon. Rinduku terhadap Mamak tiba-tiba datang menyergap.
Setahun lebih aku tidak berkunjung ke Glagah. Biasanya dalam kondisi seperti ini aku langsung meluncur dengan si Terios ditemani bait-bait Rideak Rile, lagu wajib orang Kerinci. Kali ini langkahku terhenti. Covid-19 menghadang dimana-mana. Maka aku hanya bisa duduk terpaku di sudut ruang kerja. Akhirnya aku membuka laptop dan menumpahkan perasaan. Butir-butir rindu yang aku patrikan dalam tulisan ini, entah bagaimana caranya, suatu saat semoga sampai dan dibaca Mamak. Ketika itu terjadi, Mamak tahu, bahwa si perantau cilik, anak yang beliau temui dan sayangi sejak kakaknya KKN di rumah Mamak empat puluh tahun yang lalu, masih selalu menyimpan hormat dan rindu pada Mamaknya.
Tamantirto, 20 November 2020,
Editor: Yusuf