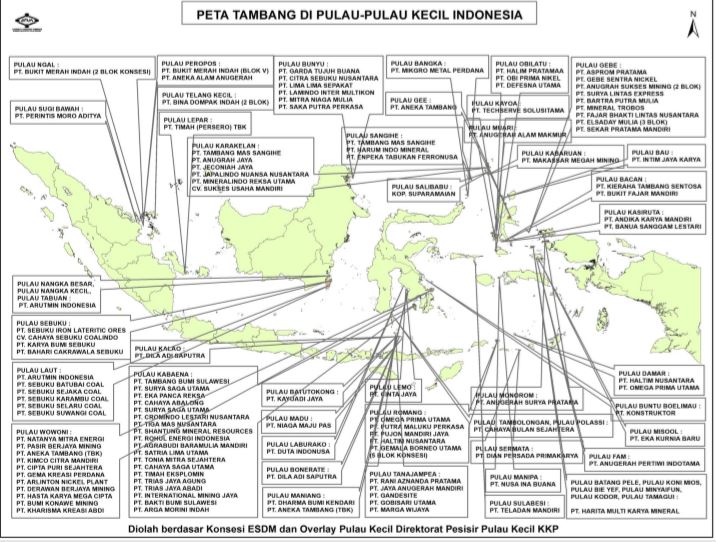Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Perekonomian secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyampaian Dokumen Elektronik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan Naskah Akademisnya, tertanggal 13 Februari 2020.
Secara eksplisit, RUU Cipta Kerja menyebutkan soal investasi asing di pulau-pulau kecil, khususnya di dalam Pasal 19 yang merevisi UU No. 1 Tahun 2014, dengan redaksi sebagai berikut: “Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”
Pasal yang akan direvisi oleh RUU Cipta Kerja ini terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 2014, khususnya pasal 26A ayat 1-3, sebagaimana tertulis: (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri; (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; b. menjamin akses publik; c. tidak berpenduduk; d. belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal; e. bekerja sama dengan peserta Indonesia; f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; g. melakukan alih teknologi; dan h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.
Jika kita bandingkan pasal yang membahas penanaman modal asing di pulau-pulau kecil di dalam RUU Cipta Kerja memiliki sejumlah perbedaan yang sangat mendasar bahkan diametral dengan UU No. 1 Tahun 2014, Pasal 26A Ayat 1-3, yaitu: pertama, RUU Cipta Kerja tidak memberikan batasan dan syarat kepada pelaku penamanan modal asing sebagaimana diatur dengan sangat rinci dalam UU No. 1 tahun 2014; kedua, menghilangkan pertimbangan sosial, khususnya kehidupan masyarakat pesisir, dan pertimbangan ekologis, khususnya ekosistem pulau-pulau kecil dan wilayah perairan di sekitarnya; ketiga, menghilangkan peran pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau walikota. RUU Cipta Kerja terlihat akan melakukan resentralisasi kekuasaan untuk mempermudah investasi di kawasan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.
Terkait dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang akan dijadikan dasar penanaman modal asing di pulau-pulau kecil oleh RUU Cipta Kerja, hal ini wajib disorot secara sangat kritis. Semangat UU tersebut jelas-jelas memperkecil peran dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir. Tak hanya itu, UU ini juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) yang mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Tak hanya itu, investasi asing di pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010, Majelis Hakim MK saat memutuskan untuk menghapuskan pasal-pasal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menafsirkan frasa ‘dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ dengan sejumlah poin berikut:
Pertama, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia berhak untuk mengakses dan melintas wilayah perairan; kedua, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berhak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat; ketiga, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi, ekologi, dan manfaat sosial dari sumber daya pesisir dan kelautan; dan keempat, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil berhak untuk mempraktikkan adat istiadat dalam mengelola sumber daya pesisir dan kelautan di wilayah Indonesia.
Belajar dari Pengalaman Pulau Romang
Pada tahun 2016, penulis yang mewakili lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama dengan KONTRAS, WALHI, dan JATAM, terlibat di dalam advokasi kasus pertambangan emas di Pulau Romang, sebuah pulau kecil yang secara geografis dekat dengan Timor Leste tetapi secara administrasi berada di Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Maluku Barat Daya. Pulau ini memiliki luas 175 km persegi yang terdiri dari tiga desa, yaitu: desa Jerusu, Desa Hila, dan Desa Solath.
Adalah PT Robust Recources. Ltd, sebuah perusahaan yang yang berasal dari Darwin Australia yang memiliki anak perusahaan bernama PT Gemala Borneo Utama. PT Robust Recources memiliki kantor cabang di Kota Kupang, NTT., dan telah beroperasi sejak tahun 2006.
Berdasarkan dokumen yang dipublikasikan oleh KONTRAS, Perusahaan tersebut mulai melakukan eksplorasi pasca Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi No 540/052.a/rek/2008 yang ditandatangani oleh Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitzael S. Temmar, tertanggal 10 Juli 2008.
Pada tahun 2009, perusahaan juga mendapat surat rekomendasi No 542/207/209 yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Maluku Barat Daya, Drs Jacob Patty, tanggal 20 Maret 2009 untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Romang. Namun, sejak perusahaan tersebut beroperasi, masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan komprehensif. Dampaknya adalah sebagai berikut:
Pertama, kehadiran Perusahaan di Pulau Romang memicu konflik internal antar warga yang pro dan kontra tambang. Ada serangkaian kejadian yang ditemukan di lapangan, seperti perbedaan pelayanan oleh kepala desa/camat terhadap warga penolak tambang dan sengketa tanah adat.
Kedua, hancurnya ekosistem di Pulau Romang, yang ditandai oleh hilangnya tanaman agar-agar di laut. Padahal sebelumnya, tanaman ini sangat melimpah dan mudah ditemukan. Tak hanya itu, tanaman cengkeh dan pala mengalami kerusakan parah akibat uap panas yang dihasilkan proses pertambangan. Begitu pula dengan semakin hilangnya madu hutan sejak adanya proyek pertambangan.
Keempat, hilangnya debit air. Walaupun tersedia stok air di pulau ini, tapi secara kualitas sangat buruk karena warnanya sangat keruh dan tidak layak untuk dikonsumsi.
Kelima, pihak keamanan perusahaan telah terbukti melakukan tindakan intimidatif, seperti pemukulan, bahkan dugaan pembunuhan, khususnya terhadap Goorge Pookey (warga penolak tambang) yang hilang selama beberapa hari dan tewas ditemukan di pinggir laut dengan keadaan kepala terputus.
Apa yang terjadi di Pulau Romang, menggambarkan bahwa investasi asing di pulau kecil tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup masyarakat setempat, khususnya dalam aspek sosial-ekonomi. Lebih jauh, investasi asing di pulau kecil terbukti menghancurkan keberlanjutan ekosistem pulau dan perairan sekitarnya yang sangat berharga bagi kehidupan masyarakat.
Hal itulah yang akan terjadi di banyak pulau kecil jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.
Editor: Arif