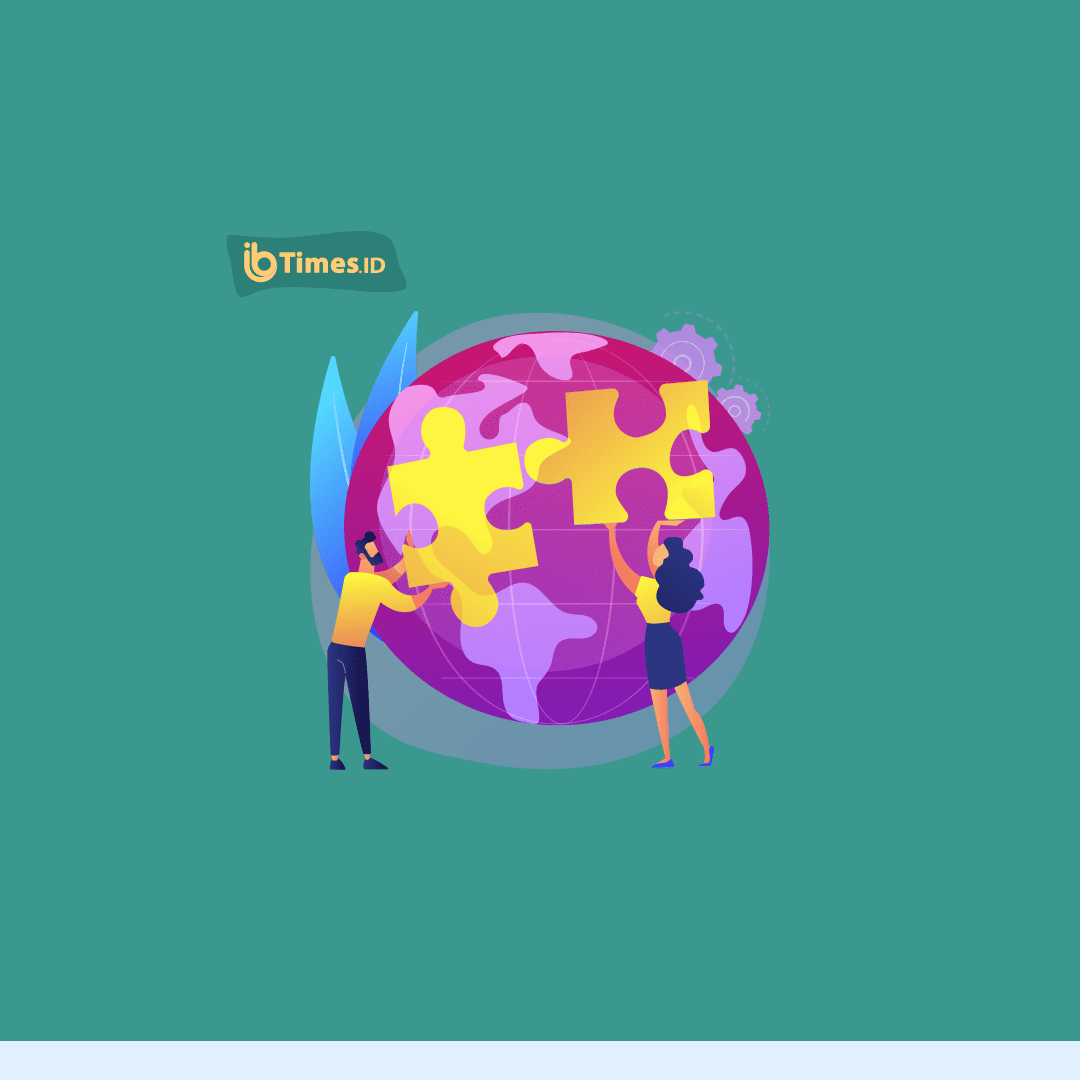Menjelang satu abad Nahdlatul Ulama, 7 Februari 2023, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menyelenggarakan gerakan halaqah kebangsaan dan halaqah fikih peradaban di 250 titik pesantren di seluruh tanah air. Pemilihan tema ini berorientasi pada redefinisi, reaktualisasi dan rekonteksualisasi fikih yang selama ini bergerak pada ranah hukum, untuk diperluas pada konteks kewarganegaraan demi peradaban yang memanusiakan manusia.
Islam – sebagai sebuah agama – meniscayakan pemeluknya untuk terus-menerus menumbuhkan kedamaian dan kesejukan dalam beragama. Visi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil ‘alamin) tidak sekadar jargon belaka, melainkan ruh agama itu sendiri. Untuk itu, tidak salah jika Islam berwatak toleran. Ia mendambakan keadilan dan kedamaian serta menjunjung tinggi kemuliaan dan kebebasan manusia untuk menentukan pilihannya sebagaimana tersebut dalam firman Tuhan, “Allah swt mengutus rasul-Nya, Muhammad saw, sebagai rahmat bagi semesta alam”. Rasulullah Muhammad saw sendiri mendeklarasikan tujuan risalah Islam yang diembannya tidak lebih hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Dalam konteks ini, pemahaman bahwa agama Islam mengabrogasi (me-naskh) eksistensi agama pendahulunya, ataupun agama terbaru – meminjam istilah Masdar Hilmy – merupakan heresy agama terdahulu, tidaklah bisa dibenarkan. Justru pemahaman seperti itu bisa dimaknai bahwa kehadiran agama terbaru akan menguatkan misi teologis – dalam gradasi tertentu berperan menyempurnakan – yang terkandung dalam agama terdahulu, karena setiap agama (Ibrahim) mengandung inti ajaran yang sama, yakni kredo monoteisme (tauhid).
Simplifikasi Beragama
Memang harus diakui bahwa di dalam Islam terdapat beberapa istilah yang berpotensi mengilhami kekerasan dalam beragama. Istilah ini kemudian yang acapkali digoreng oleh sejumlah oknum untuk kepentingan terselubung (hidden agenda), seperti jihad, al-wala’ wal barra, kafir, dan semacamnya yang secara sekilas cenderung menampilkan citra Islam yang kasar, garang, dan tidak dapat hidup berdampingan serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain. Kata sejumlah pengamat, perang saudara dan kekerasan kolektif menjadi lebih sulit dipadamkan kalau ada faktor Islamnya. Pendek kata, istilah tersebut kerapkali dipelintir sehingga fenomena politisasi agama yang marak terjadi di era sekarang menjadi sebuah realitas tak terbantahkan.
Namun, pandangan yang menyamakan Islam – dan agama pada umumnya – sebagai sumber kekerasan atau kejahatan, sudah barang tentu mensimplifikasi agama itu sendiri. Alasannya cukup sederhana bahwa faktanya banyak juga Muslim, yang juga mempercayai ajaran agama sebagaimana disebutkan tadi, tidak melakukan aksi-aksi kekerasan atau mencoreng agama, bahkan menentangnya dengan gigih. Dengan kata lain, ajaran yang sama bisa diinterpretasikan, objektivasi, diresepsi, dan dipraksiskan secara berbeda, bahkan pertentangan antar penganut agama tidak jarang terjadi.
Dalam Islam, misalnya, pengklarifikasian terhadap beberapa ayat Alquran yang selama ini diduga menjadi pemicu munculnya kebencian antaragama juga perlu dilakukan. Landasan berpikirnya sederhana, lanjut Masdar Hilmy, Allah tidak menghendaki pemusnahan agama tertentu melalui kehadiran Islam. Dengan demikian, pengertian ayat “bagimu agamamu, bagiku agamaku” harus dikonfirmasi dengan ayat di atas, selain “diluruskan” sesuai semangat konteks ruang dan waktu turunnya (asbabun nuzul). Dalam hal ini, kata “agamamu” (dinukum) ditujukan kepada agama kaum jahiliyah saat mereka berusaha menyumbat dakwah Nabi Muhammad saw.
Fikih Peradaban: Trajektori dan Signifikansi
Yahya C. Staquf, Ketua Terpilih Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam pidato perdananya ia menyinggung dua agenda besar PBNU, yaitu membangun kemandirian warga dan mewujudkan perdamaian dunia. Dua agenda besar itu sejatinya sudah di speak up oleh mendiang KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), namun karena beberapa alasan tertentu agenda tersebut kurang begitu masif sehingga Gus Yahya, sapaan akrab Yahya C. Staquf, memiliki tanggung jawab struktural dan moral untuk mengaktivasi kembali dua agenda tersebut.
Bagi Gus Yahya, yang diperlukan adalah bagaimana menjahit berbagai macam inisiatif yang sudah dilakukan dalam pengembangan ekonomi rakyat, pemajuan pendidikan, pengembangan layanan kesehatan, dan lainnya menjadi satu agenda nasional yang sustainable (berkelanjutan). Sementara, dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, Yahya C. Staquf menyebut, NU telah berhasil melakukan berbagai inisiatif yang diapresiasi oleh masyarakat internasional.
Pengarusutamaan Fikih Peradaban yang digencarkan NU menjelang satu abadnya setidaknya dilatari atas posisi agama yang sampai detik ini masih menjadi problem bagi kehidupan. Yahya C. Staquf menjelaskan, “sampai hari ini agama masih menempati posisi sebagai bagian dari masalah. Ini penting dicari solusinya untuk mengakhiri agama dari posisi sebagai ‘bagian dari masalah’ tapi bisa menjadi ‘solusi dari masalah’.” Mengikuti Masdar Hilmy, ketimbang menyebut non-Muslim sebagai ”kafir”, NU mengusulkan istilah Muwathinun, yaitu warga negara. Menurut NU, penggunaan istilah ”kafir” kepada sesama non-Muslim mengandung unsur kekerasan teologis.
Karena itu, tepat kiranya jika Yahya C. Staquf dalam Forum on Common Values Among Religious Followers (Forum Nilai-Nilai Bersama Umat Beragama) yang diprakarsai Rabithah ‘Alam Islami (Liga Muslim Dunia) mengeluarkan statement pamungkas, “Masih banyak kalangan umat beragama yang memandang hubungan antar agama sebagai kompetisi politik sehingga agama diperalat sebagai senjata politik untuk memperebutkan kekuasaan. Pola pikir ini harus diubah karena akan merusak harmoni sosial diantara kelompok agama yang berbeda-beda dan memustahilkan kelompok-kelompok yang berbeda itu hidup berdampingan damai”.
***
Pernyataan Yahya C. Staquf tersebut bukanlah tanpa alasan. Ia melihat problematika intoleransi di Indonesia dan global sedemikian akut dan masih kerap menghantui umat beragama. Pernyataan Yahya C. Staquf pula menandai kesadaran Muslim Indonesia, dalam hal ini, untuk mengajak masyarakat Muslim dunia untuk tidak menjadikan agama sebagai senjata politik sehingga agama kehilangan misi sucinya sebagai pembawa rahmat.
Dalam konteks Indonesia, beberapa konflik yang sekilas nampaknya konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia acapkali ternyata penyebab utamanya adalah faktor ekonomi, sosial dan politik. Mereka juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, bukan kekerasan. Bagi Yahya C. Staquf, di tengah konteks realitas yang kian dinamis, landasan-landasan nalar di atas mengerangkai sebuah persepsi tentang sebuah kepentingan. Kepentingan menuntut pemenuhan. Upaya memenuhi tuntutan kepentingan itulah agenda.
Karena manusia menjadi subjek dan objek dari perjuangan peradaban, maka keseluruhan prosesnya adalah pergulatan bersama manusia. Barang siapa tidak melakukan pergulatan bersama (engagement with) manusia, berarti tidak punya agenda. Tak punya agenda berarti tak punya eksistensi, tidak ada dan tidak relevan. Wujuduka ka’adamihi (wujudnya ada dan tiadanya sama saja), kata Yahya C. Staquf.
Dengan demikian, pengarusutamaan (mainstreaming) halaqah fikih peradaban dan gagasan fikih kewarganegaraan (muwathanah), dalam amatan Masdar Hilmy, memiliki relevansi dan signifikansi yang tinggi terhadap kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara di tengah membuncahnya politik transaksional dan friksi sosial kehidupan beragama di masyarakat. Untuk itu, apa yang dilakukan NU melalui gagasan fikih peradaban (atau fikih muwathanah) memastikan perlindungan maksimal bagi siapapun yang menjadi warga negara Indonesia untuk memenuhi hak-hak kemanusiaannya.
Sebagai penutup, pernyataan Yahya C. Staquf menarik untuk kita simak bersama, “harus dipahami bahwa baik mendirikan NU maupun NKRI bukanlah “proyek” langsung jadi bak mincuki mindhik. Semua itu adalah perjuangan merintis peradaban baru. Proyek raksasa yang harus digembalakan mengarungi sejarah, menembus bolak-baliknya zaman. Maka nilai yang paling transenden dalam hal ini adalah cita-cita peradaban itu sendiri. Membina dan membangun peradaban adalah membangun manusia, memperbaiki kualitas lahir-batinnya dan memuliakan akhlaknya”.
Editor: Yahya