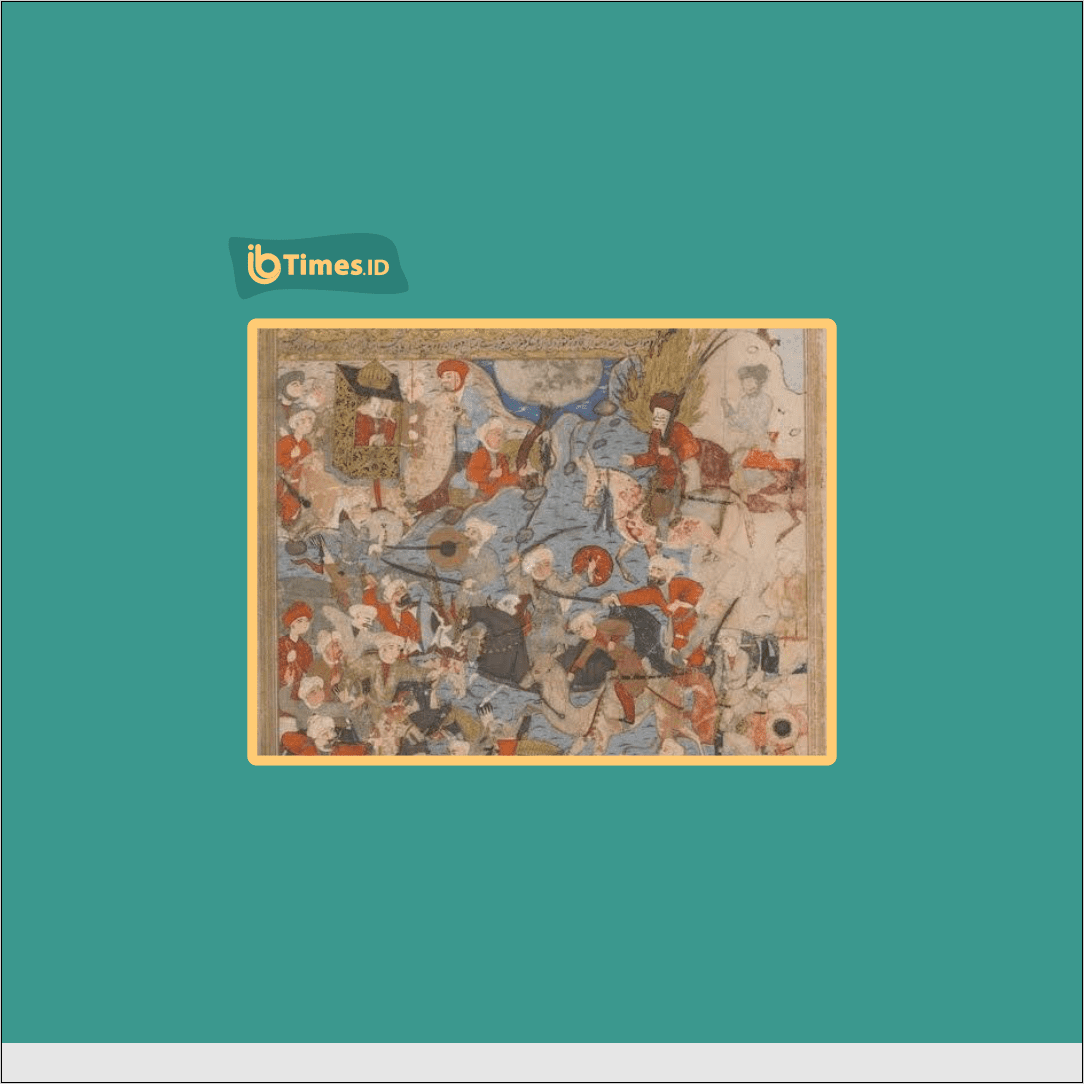Islam tidak cukup hanya dipahami pada pengertian yang sempit. Akan tetapi, harus dikembangkan restorasi makna keislaman pada pemahaman yang lebih subtansial dan esensial. Keislaman bukan hanya ranah dogma, doktrin dan ritual belaka. Islam sesungguhnya merupakan pemahaman yang autentik, natural, dan sublim dari spiritualitas dan transedentalitas sang hamba dalam “kekudusan” diri pada yang Maha Suci: autentik.
Memang agama-agama membutuhkan jawaban-jawaban terhadap realitas sosial dan kemanusiaan yang ditemui manusia dalam hidup. Peranan agama bisa dianggap tidak ada bagi pemuja materialisme, apabila problematika sosial dan kemanusiaan tidak mereka temukan dalam agama yang mereka anut.
Bila hal tersebut terjadi, tentu agama hanya sekedar dimanfaatkan apabila mendukung gensi, ambisi, kursi dan materi yang mereka harapkan. Dan, apabila tidak dapat memberi manfaat, tentu agama hanya tinggal pada ritual dan perayaan saja, seperti: menyambut kelahiran, khitanan, pernikahan dan upacara kematian. Sedangkan untuk problematikan sosial dan kemanusiaan, agama dianggap tidak memiliki obsi dan solusi. Sungguh sangat ironi di era kelimpahan yang sekuleristik.
Kontekstualisasi Makna Keislaman
Menurut Nurcholish Madjid, dalam buku Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, (Jakarta: Paramadina, 1992, h. Ixx), bahwa Islam selalu dilukiskan sebagai jalan, sebagaimana dapat dipahami dari istilah-istilah yang digunakan dalam Kitab Suci (shirath, sabil, syari’ah, thariqah, minhaj, mansak). Kesemua itu mengandung makna “jalan”, dan merupakan metafor-metafor yang menunjukkan bahwa Islam adalah jalan menuju kepada perkenan Allah dengan segala sifat-Nya.
Makna berislam harus dipahami lebih luas, yakni Islam sebagai “jalan” bagi hamba-Nya untuk meraih ridha-Nya. Untuk meraih ridha (perkenan) Allah, Tuhan Yang Maha Esa itulah manusia melakukan ritual-ibadah yang diikuti dengan amal saleh (ibadah sosial). Perpaduan ibadah ritual dan ibadah sosial merupakan “jalan” bagi hamba-Nya untuk sedekat-dekatnya kepada Allah (taqarrub ilallah).
Kitab Suci (Alquran) istilah-istilah yang digunakan adalah shirath, sabil, syari’ah, thariqah, minhaj, mansak. Istilah-istilah itu mengandung makna “jalan”, dan merupakan metafor-metafor yang menunjukkan bahwa Islam adalah jalan menuju kepada keridhaan Allah dengan segala sifat-Nya. Dan, sifat-sifat-Nya lah harus menjadi karakter hidup orang beriman. Sebab, sifat-sifat kemuliaan-Nya (asmaul-husna) merupakan “manifestasi” keagungan, maka sebagai insan yang bertakwa harus berakhlak seperti akhlak-Nya. Yakni tercermin dari pancaran sifat-sifat-Nya.
Berislam bukan hanya pada lisan belaka. Bagi manusia manusia beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, berislam adalah sama nilainya dengan berjalannya alam, yakni senantiasa mengikuti hukum-hukumnya sendiri yang ditetapkan oleh Allah, Maha Pencipta. Jadi, berislam adalah bersifat alami, wajar, fithri dan natural, serta autentik. Dan sikap sebaliknya, berarti mengingkari dan menantang Tuhan. Itulah yang terkandung dari pernyataan Nurcholish Madjid:
Menjalankan “Islam” bagi manusia adalah sama nilainya dengan berjalannya alam (secara tidak sadar) mengikuti hukum-hukumnya sendiri yang ditetapkan oleh Allah, Maha Pencipta. Karena itu “al-Islam” bersifat alami, wajar, fithri dan natural. Sedangkan sikap sebaliknya, yaitu sikap menentang Kehendak dan Rencana Tuhan adalah tidak alami dan tidak wajar, atau absurd. (Ibid, h.432)
Restorasi Makna Keislaman
Menurut M. Din Syamsuddin, dalam buku Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani, (Jakarta: Logos, 2002), h. 163-164), paling tidak ada dua faktor saling tarik-menarik yang menjadikan isu pembaharuan Islam—persisnya pemahaman pembaharuan tentang Islam—aktual sekaligus kontroversial sepanjang sejarah pemikiran Islam. Kedua faktor ini bersifat intrinsik, melekat pada Islam itu sendiri, karenanya dapat dipandang sebagai watak-watak Islam.
Pertama, watak keuniversalan Islam. Watak ini meniscayakan adanya pemahaman selalu baru untuk menyikapi perkembangan kehidupan manusia yang selalu berubah. Islam universal—dalam arti cocok untuk segala ruang dan waktu (salih li kulli zaman wa makan)—menurut aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks dinamika kebudayaan.
Hakikat Islam, kerahmatan dan kesemestaan (rahmatan lil’alamin), berhubungan secara simbolik dengan semangat zaman, yaitu kecondongan kepada kebaruan dan kemajuan. Pencapaian cita-cita kerahmatan dan kesemestaan (dalam ungkapan lain kemaslahatan untuk semua) sangat bergantung pada penemuan-penemuan baru akan metode dan teknik untuk mendorong kehidupan yang lebih baik, lebih maju. Dengan demikian, keuniversalan mengandung muatan kemodernan. Islam menjadi universal justru karena mampu menampilkan ide dan lembaga modern serta menawarkan etika modernisasi.
Kedua, watak kemutlakan Islam. Sebagai agama berdasarkan wahyu Ilahi, Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai kebenaran mutlak (al-haq). Keyakinan ini membawa implikasi bahwa Islam adalah sistem nilai yang mengatasi sistem-sistem nilai lain (ya’ lu wa la yu’la’alaih), dan, bahkan Islam merupakan satu-satunya sistem nilai yang absah, sedangkan yang lainnya adalah absurd.
Membangun Kultur Islam Wasathiyah
Pemutlakan semacam ini juga mendorong penafikan kebenaran dari ideologi-ideologi modern serta segala bentuk ide serta lembaga yang melahirkannya. Pada akhirnya, sikap keberagamaan demikian menantang kemodernan dan menantangnya dengan ideologi yang dianggap Islami, baik dengan kembali ke masa lalu mengangkat “Islam sejati” (pristine Islam) seperti yang ditunjukkan oleh puritanisme atau konservatisme Islam, maupun dengan menawarkan “prinsip-prinsip” Islam seperti ditampilkan oleh prinsipalisme atau fundamentalisme Islam.
Restorasi makna keislaman dalam konteks keindonesiaan adalah upaya untuk membangun kultur Islam Wasathiyah; yakni: Islam yang terbuka, moderat, tengahan, dan inklusif. Sikap tersebut bukanlah “melemahkan” apalagi “merendahkan” hakikat Islam. Karena watak keuniversalan Islam meniscayakan adanya pemahaman selalu baru dan berkembang untuk senantiasa mampu menyikapi perkembangan kehidupan manusia yang selalu berubah.
Maka, wujud Islam yang universal sesungguhnya adalah Islam yang dinamis, yang hadir untuk segala ruang dan waktu (salih li kulli zaman wa makan). Dalam konteks tersebutlah nilai-nilai subtantif Islam dapat diaktualisasikan dalam dinamika kebudayaan yang ada di masyarakat Indonesia.
(Bersambung)
Editor: Nabhan