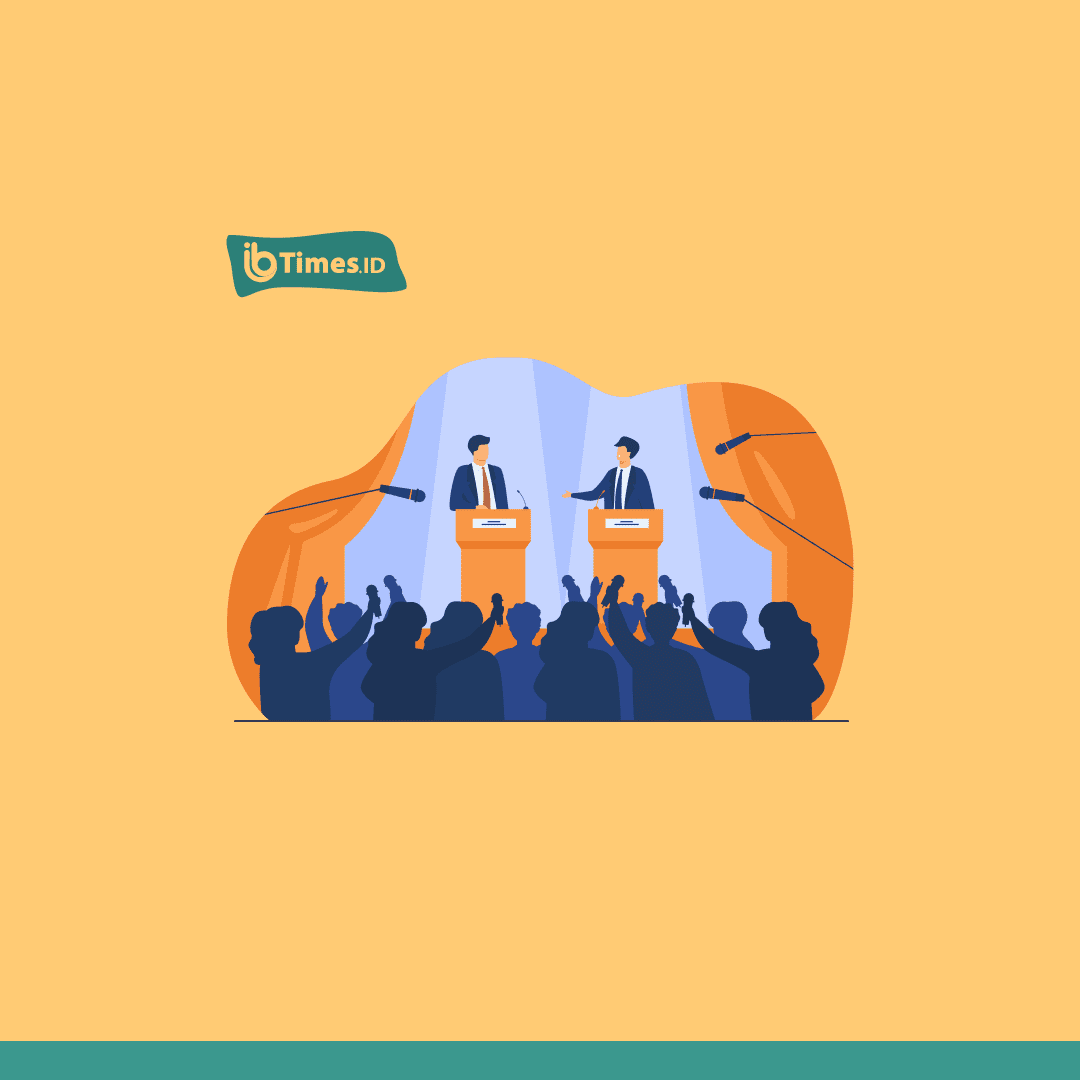Segregasi politik dalam bentuk kecurigaan masih memiliki tempat dalam publik Indonesia. Seregresi politik dan sosial terjadi melalui politik pelabelan. Polanya tetap sama, dengan membawa isu yang terus bermetamorfosis. Hampir di setiap era, politik pelabelan (politics of labelling) dapat ditemukan.
Di era Orde Lama misalnya ada pelabelan “kontra revolusi” dan “antek Moskow”, di era Orde Baru hingga awal Reformasi terdapat label “PKI/komunisme”, “anti-pembangunan”, di Pemilu 2014 dan 2019 label “cebong” dan “kampret”, dan sekarang yang menyeruak adalah label “fundamentalisme”, “radikalisme”, “Islam radikal”, “kadrun”, “pribumi” dan “non pribumi”.
Menarik untuk melihat pergeseran segregasi politik ini dalam dua era terakhir (Orde Baru dan Reformasi). Terjadi perpindahan politik pelabelan dari PKI-komunisme ke arah perang terhadap radikalisme, fundamentalisme, dan terorisme—kelompok Islam tertentu.
Perpindahan ini didahului oleh fase penghubung. Yaitu mengacu kepada kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Thahaja Purnama (Ahok) pada 2017. Di tahun yang sama juga turut dibubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap mengancam kestabilan nasional.
PKI/komunisme telah dijadikan oleh Soeharto sebagai landasan untuk menerapkan kebijakan diskriminatif sepanjang di sepanjang era Orde Baru. Pelabelan PKI/komunisme telah dimulai sejak tahun 65-66. Dan sampai Pemilu 2014 isu PKI/komunisme masih laku dalam kancah perpolitikan Indonesia.
Sedangkan isu radikalisme, fundamentalisme, dan Islam radikal baru muncul secara kentara dalam kurun tiga tahun terakhir dalam dinamika sosial-politik—kendati telah berakar sejak lama, bisa dilacak sampai Kartosoewiryo. Isu radikalisme telah dijadikan oleh pihak-pihak tertentu dalam kurun tiga tahun terakhir sebagai senjata. Label ini diberikan kepada pihak yang ber-oposisi kepada pemerintah. Semakin hari, semakin mendekatnya Pemilu, penyematan label ini semakin gencar.
Agenda di Balik Label
Label-label politik tidak pernah muncul dalam bentuk yang netral. Selalu terdapat apa yang tidak semestinya di dalam praktik. Peperangan dan perlawanan terhadap PKI/komunisme maupun radikalisme terkadang berubah makna. Bukan lagi secara konkret dalam arti perlawanan yang sebenarnya, tapi sebagai legitimasi untuk melekatkan stigma pada kelompok tertentu.
Kehadiran pelabelan tertentu sudah pasti dilandasi oleh suatu tujuan dan motivasi. Sulit untuk mengatakan bahwa pembentukan citra, membangun stigma, dan mengupayakan framing terlepas dari kepentingan. Label-label seperti yang disebutkan di atas tidak mungkin hadir sebagai sebuah kecelakaan. Tetapi ia dihadirkan untuk sebuah tujuan tertentu.
Sebagai strategi, label dibuat bukan secara asal-asalan. Tetapi ia dilahirkan dalam latar strukturalisasi yang terukur, memiliki motivasi dan tujuan. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai label harus bisa hadir secara rasional yang difasilitasi oleh argumen-argumen yang jelas. Tujuannya adalah untuk merendahkan lawan politik atau kelompok yang berbeda (out group ), memberi stigma dengan menggunakan pembingkaian (framing) tertentu. (Masykuri & Ramadlan, 2021: 73).
Terkait fundamentalisme, Rahmatul Izad, mahasiswa doktoral UIN Sunan Kalijaga dalam tulisannya yang berjudul Asal-Usul Diskursus dan Politik Moderasi Beragama dalam Konteks Global di Ibtimes.id menguraikan bagaimana pembentukan label fundamentalisme berawal.
***
Izad menjelaskan bahwa dikotomi “moderat” dan “fundamentalisme” diawali oleh kebijakan politik luar negeri George W. Bush pasca peristiwa 9/11. Pemerintahan Bush menggunakan slogan “perang melawan teror” yang sering kali diartikan perang terhadap Islam.
Pola ini dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Obama dengan membingkai dikotomi Islam “moderat” dan “fundamentalis”. Moderat mengacu kepada mereka yang menerima nilai-nilai Barat yang dianggap universal dan yang di luar mereka—tidak menerima nilai-nilai Barat—dicap fundamentalis.
Terdapat indikasi ala yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memainkan isu fundamentalisme dan sejenisnya juga tidak berbeda dengan agenda Bush seperti yang dikatakan oleh Rahmatul Izad. Juga, perlawanan yang dihadirkan juga tidak bersifat konkret, melainkan perlawanan terhadap ketakutan yang “diadakan” demi kepentingan politik—politik hantu.
Perlunya Jalannya Keluar dari Segregasi Politik
Politik pelabelan dan framing adalah sesuatu yang niscaya dalam demokrasi. Negara memberi ruang dan melegitimasi keadaan tersebut. Bahkan negara yang mempunyai porsi kekuasaan yang paling besar ikut memainkan politik yang serupa untuk mematikan oposisi dan lawan-lawan politiknya.
Namun, jika kondisi ini diterima begitu saja, sama saja dengan mengatakan demokrasi telah memfasilitasi perpecahan. Tentu ini bertentangan dengan teori demokrasi itu sendiri. Demokrasi menghendaki pertemuan ide dan gagasan. Dalam regresi politik, tujuan itu tidak terlihat.
Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mencarikan penyelesaian. Perlu adanya konsolidasi politik supaya dalam persaingan, publik tidak diombang-ambingkan dengan isu-isu. Perlu adanya narasi yang proporsional, melahirkan kritikan-kritikan yang substantif . Yang diharapkan dari demokrasi adalah adanya ruang terbuka lebar untuk beradu gagasan. Tidak mungkin untuk melembagakan kebodohan secara terus-menerus.
Apa yang akan dilahirkan oleh praktik yang seperti ini tak lain hanyalah perpecahan. Segregasi yang terus dipertahankan membuat praktik demokrasi tetap terjebak dalam situasi yang tidak ideal. Yang lahir adalah sentimen bukan ide seperti yang diharapkan.
Perlu sekitar 55 tahun untuk menghapuskan isu PKI/komunisme dalam permainan wacana sosial-politik. Sedangkan wacana ekstremisme dan pelemparan sentimen khilafah baru menghangat (kembali) sekitar tiga sampai lima tahun belakangan.
Apakah butuh 50 tahun lainnya untuk meruntuhkan sentimen radikalisme dari ruang wacana kita? Kalau memang benar, kita adalah bangsa yang tidak pernah belajar. Seharusnya sekarang adalah waktunya untuk belajar.
Editor: Yahya FR