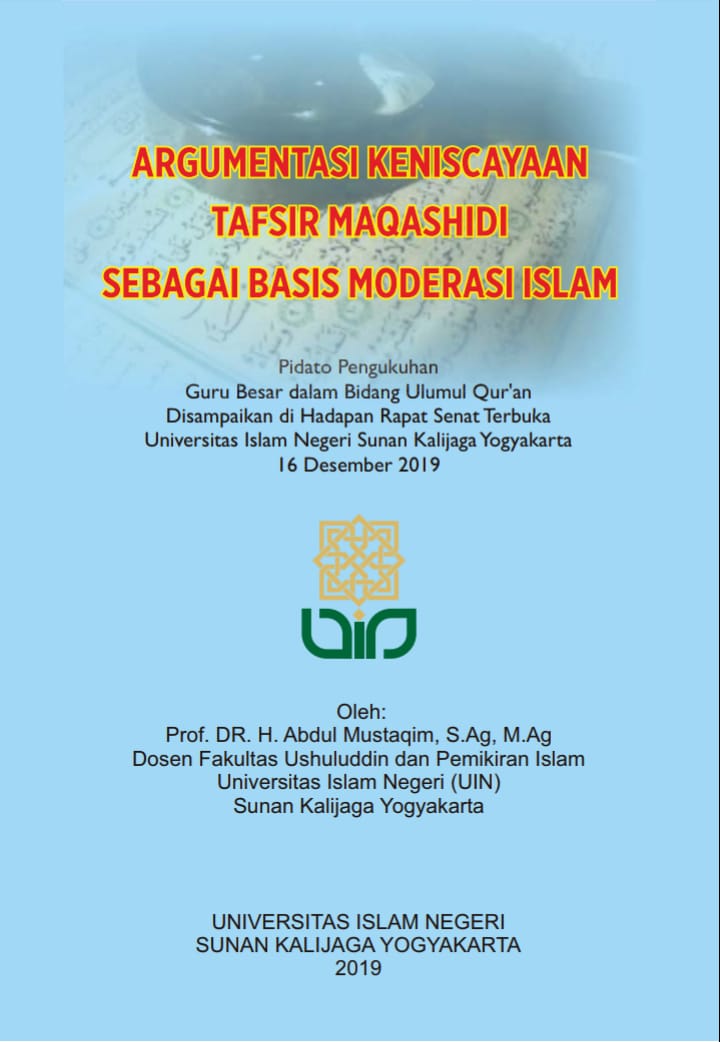Moderasi Islam (Islam Wasathiyah) dewasa ini menjadi isu yang selalu aktual. Terutama di tengah-tengah munculnya ekstremisme beragama yang seringkali disebabkan oleh pola pikir ekstrem (tatharruf) dalam memahami teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan Hadis) secara rigid, tidak mempertimbangkan dinamika konteks dan maqâshid.
Situasi ini disambut oleh Prof. DR. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ulumul Qur’an dengan Judul “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 16 Desember 2019.
Kebaruan Tafsir Maqashidi
Istilah Tafsir Maqashidi merupakan istilah yang relatif baru, —untuk tidak menyebut baru sama sekali—, mengingat sebelumnya sudah ada istilah maqâshid al-syari’ah (the aims of the Islamic law) yang merupakan salah satu tema dalam kajian Ushul Fiqh. Akan tetapi, kemudian dalam diskursus kajian Islam kontemporer dewasa ini, teori Maqashid al-Syariah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri (`ilm mustaqill) terpisah dari Ushul Fiqh, bahkan sering dijadikan pisau bedah dalam menganalisis isu-isu aktual-kontemporer.
Dalam hal ini, Mustaqim mencoba mengembangkan teori maqashid dalam diskursus kajian tafsir, sehingga ia menggunakan istilah Tafsir Maqashidi (h. 6-7). Dalam pidatonya, Mustaqim mencoba menelisik akar-akar pemikiran Tafsir Maqâshidi secara historis-kronologis sebagai argumentasi dan basis epistemik untuk meneguhkan dan mengembangkan moderasi Islam. Pertanyaannya, bagaimana akar-akar historis dan kontsruksi logis Tafsir Maqashidi, baik secara ontologis maupun epistemologis?
Dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis (historical-phisophical approach), Mustaqim beragumen bahwa Tafsir Maqashidi secara historis cukup memiliki cantholan epistemik yang kuat dalam tradisi Islam, sejak zaman Nabi Saw, sahabat dan para ulama. Dengan kata lain, Tafsir Maqashidi adalah ‘anak kandung’ yang lahir dari peradaban Islam sendiri.
Menurut Mustaqim, secara ontologis tafsir maqashidi dapat dipetakan menjadi tiga macam, yaitu Tafsir Maqashidi sebagai filsafat tafsir (as philosophy), Tafsir Maqashidi sebagai metodologi (as methodology) dan Tafsir Maqashidi sebagai produk tafsir (as product). Ketiga hirarkhi ontologis yang saling terkait terkelindan tersebut penting dikemukakan, sehingga body of knowledge dari Tafsir Maqashidi menjadi clear and distinct.
Mustaqim beragumen bahwa secara epistemologis, Tafsir Maqashidi dapat menjadi salah satu alternasi dalam meneguhkan kembali moderasi Islam, ketika kita harus berdialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis. Tafsir Maqâshidi adalah bentuk wasathiyah (moderasi) antara kelompok tekstualis-skriptualis, hingga seolah ‘menyembah teks’ (ya’budûn al-nushûsh) dan kelompok liberalis-substansialis, hingga mendesakralisasi teks (yua`th-thlûn al-nushûsh).
Tafsir Maqashidi ingin menggali maqashid (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) yang ada di balik teks, dengan tetap menghargai teks (yahtarim al-nushûsh), sehingga tidak terjebak pada sikap de-sakralisasi teks (ta’thîl al-nushûsh) di satu sisi dan ‘penyembahan teks (`ibadat al-nushûsh) di sisi lain. Pertimbangan terhadap dinamika konteks dan maqashid secara cermat-kritisdalamrangkamerealisasikankemaslahatan dan menolak kemudlaratan (tahqîq al-mashlahah wa dar’ al- mafsadah) itulah fundamental structure dari Tafsir Maqashidi.
Hakikat Tafsir Maqashidi
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, mendefisisikan Tafsir Maqashidi secara sederhana sebagai model pendekatan penafsiran al-Qur’an yang memberikan penekanan (aksentuasi) terhadap dimensi maqashid al-Qur’an dan maqashid al-Syariah. Tafsir maqashidi, tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit (al- manthûq bih), melainkan mencoba menelisik maksud dibalik teks yang implisit, yang tak terucapkan (al-maskût `anh), apa sebenarnya maqashid (tujuan, signifikansi, ideal moral) dalam setiap perintah atau larangan Allah dalam al-Qur’an. Menurutnya Tafsir maqahisidi juga akan mempertimbangkan bagaimana gerak teks (harakiyyah al-nash). Jika objek penafsirannya ayat-ayat kisah, maka tafsir maqashidi akan menelisik lebih dalam apa sebenarnya maqâshid terdalam dari narasi kisah al- Qur’an tersebut (h. 12-13).
Eksistensi Tafsîr Maqâshidi ini cukup urgen (penting) sebagai basis moderasi Islam, di tengah-tengah kontestasi epistemologis –untuk tidak menyebut ‘konflik’– antara pendekatan tafsir tekstualis-skriptualis-literalis (al-ittijâh al-zhâhiri-al-harfi-al-nashshi) dan pendekatan de-tekstualis- liberalis (al-ittijâh -al-ta’thîli-al-liberâli).
Menurut Mustaqim, dua paradigma tersebut, tampak sama-sama ekstrem dan saling berseberangan secara diametral. Jika kelompok pertama cenderung memandang teks sebagai pokok (ashl) dan konteks sebagai cabang (far’), sehingga terkesan mengabaikan konteks dan maqashid, maka kelompok kedua cenderung lebih mengutamakan tuntutan konteks, sehingga dapat mengarah kepada ta’thîl al-nushûsh (mengabaikan teks sama sekali, yang penting ‘kemaslahatan’).
Dengan kata lain, kelompok pertama cenderung ya’budûn al- nushûsh (‘menyembah teks’), dan menutup diri dari model pendekatan hermeneutis, sedangkan kelompok kedua cenderung yu`ath-thilûn al-nushûsh (de-sakralisasi teks) dan sangat longgar dengan pendekatan hermeneutik yang oleh sebagian ulama masih dianggap problematis, atau setidaknya masih diperdebatkan (h. 14-15).
Bagi Mustaqim, ada beberapa alas an mengapa hermeneutik masih dipersoalkan? Pertama, karena hermeneutik dianggap bukan berasal dari anak kandung tradisi Islam, melainkan tradisi Barat (baca; Bible) yang muncul dalam konteks textual criticisme untuk mempersoalkan otentisitas Bible. Ini tentu berbeda dengan teori Tafsir Maqashidi yang lahir dari anak kandung tradisi Islam sendiri dan tidak lagi mempersoalkan otentisitas al-Qur’an dan lebih memiliki cantholan epistemik yang cukup kuat dalam sejarah dan Turats para ulama dan masih terus bisa dikembangkan dalam rangka merespon tantangan zaman.
Kedua, hermeneutik cenderung untuk memposisikan teks al-Qur’an secara ontologis sama dengan teks-teks yang lain. Ini yabagi para penolak hermeneutik. Sebab bagaimanapun teks al-Qur’an adalah kalamullâh (wahyu) yang mengandung dimensi ilahiyah dan sakral. Menyamakan begitu saja antara teks al-Qur’an dengan teks-teks lain tentu dinilai problematis secara teologis bagi para penolak hermeneutik. Mustaqim dalam hal ini tidak anti sama sekali terhadap hermeneutik, melainkan bersikap moderat. Teori-teori hermemeutik yang paralel dengan teori maqashid dan dapat digunakan untuk pengembangan tafsir dan mengasah nalar kritis bisa dipertimbangkan. Namun, hermeneutik yang mempersoalkan otenstisitas al-Qur’an, tidak ikuti oleh Mustaqim.
Pendek kata, teori hermeneutik yang dapat membantu mengembangkan makna dan penafsiran al-Qur’an seperti model Jorge J.E. Gracia tentang teori fungsi interpretasi dan pentingnya konteks dan masih sejalan dengan maqashid al- Qur’an, bisa diakomodasi. Itulah sikap moderasi (wasathiyah) yang menjadi keberatan Mustaqim. Lagi pula, secara teoritis, hermeneutik juga bermacam- macam, ada practical hermeneutic, theoritical hermeneutic, philosophical hermeneutic dan critical heremeneutic? Sehingga seseorang mestinya jelas di level mana, ia memilih hermeneutik dalam mengkaji al-Qur’an dan di level yang mana ia menolak hermeneutik?
Keniscayaan Tafsir Maqashidi
Terlepas dari perdebatan tersebut, setidaknya ada beberapa argumentasi yang Mustaim kemukakan tentang pentingnya tafsir maqashidi sebagai alternasi pengembangan tafsir dan basis moderasi Islam. Pertama, tafsir maqashidi adalah anak kandung peradaban Islam dan dapat dinilai lebih memiliki basis epistemologi dalam tradisi pemikiran para ulama, dalam kajian Islam secara umum dan kajian penafsiran al-Qur’an secara khusus (h.18).
Kedua, tafsir maqashidi memiliki perangkat metodologi yang lebih ‘canggih’, ketimbang hermeneutika Barat dalam konteks penafsiran teks al-Qur’an. Ada term-term khusus dan teori-teori khas dalam maqashid, yang tidak dimiliki dalam teori hermeneutika Barat. Misalnya, konsep al-tsâbit wal mutaghayyir, ma’qûliyyat al-ma’na wa ghair ma’qûliyyat, ushûl-furuû’, kulli-juz’i, wasîlah-ghâyah dan sebagainya. Sebab dalam tafsir maqashidi, bukan hanya persoalan bagaimana memahami teks al-Qur’an dan bagaimana menghubungkan teks dengan konteks masa lalu dan sekarang, melainkan juga perlu menghubungkan teori-teori maqashid secara intergratif- interkonektif, baik maqashidi al-Qur’an-maqashdi al-Syari’ah maupun teori-teori sains dan sosial-humaniora.
Ketiga, tafsir maqashidi sesungguhnya bisa dipandang sebagai falsafah al-tafsîr yang memiliki dua fungsi, yaitu: 1) sebagai spirit untuk menjadikan penafsiran al-Qur’an lebih dinamis dan moderat, 2) sebagai kritik terhadap produk- produk tafsir yang mengabaikan dimensi maqashidi.
Keempat, tafsir maqashidi dapat menjadi sintesa kreatif untuk meretas kebuntuan epistemik dari dua model epistem (al-ittijâh al- zhahiriy-al-harfiy-al-nashshiy dengan al-ittijâh -al-ta’thîly-al- liberaly) yang keduanya saling ‘berkonflik’ (baca: kontestasi) dalam menafsirkan al-Qur’an.
Oleh sebab itu, kehadiran tafsir maqashidi relatif lebih bisa diterima umat Islam ketimbang hermeneutik.Tafsir maqashidi lebih memiliki cantholan yang sangat erat dengan teori maqashid syari’ah dan lebih familiar di kalangan para ulama. Tafsir maqashidi ingin menegaskan bahwa suatu ayat harus digali maksud dan tujuan yang ada di balik ayat.
Jargon al-Qur’an sebagai kitab yang shalih likulli zamân wa makân (relevan untuk setiap waktu dan tempat), menuntut kreativitas penafsir untuk melakukan pembaharuan pemahaman agama dalam menghadapi tantangan perubahan, melalui proses ijtihad kreatif. Masalahnya adalah bagaimana seorang mufassir dapat menjaga sikap moderasi dalam menafsirkan teks? antara yang terlalu kaku dalam memahami bingkai teks, hingga nyaris menjadi ‘penyembah teks’ (ya’bud al-nash), dan yang liberal hingga keluar dari bingkai teks (yu`ath-thil al-nash (men- desakralisasi) (h. 9). Di sinilah eksistensi Tafsir Maqashidi yang ditawarkan Mustaqim akan menemukan relevansinya sebagai basis moderasi Islam.