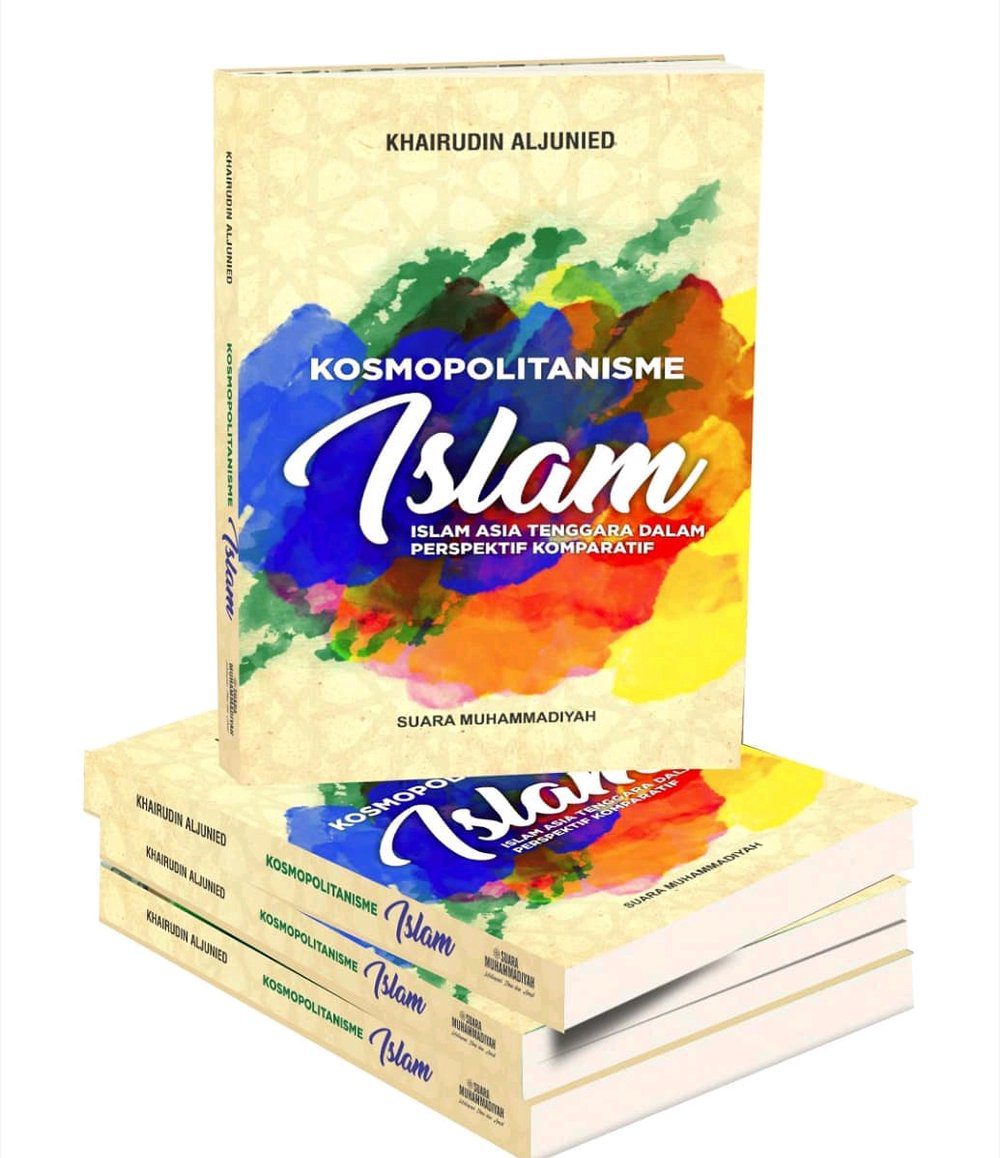Oleh: Fauzan Anwar Sandiah
Islam di Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, dan Singapura jarang diperhatikan sebagai pusat kehidupan kosmopolitan. Alih-alih, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, digambarkan tengah berada dalam kepungan konservatisme keagamaan (Bruinessen, 2013). Berbagai kajian mengenai kehidupan kaum muslim di Asia Tenggara cenderung menyatakan adanya gerakan balik ekstrimisme keagamaan, dan bahwa ancaman ini demikian nyata sehingga kelompok sipil moderat Islam harus mengambil sikap melawannya.
Tentu saja, Islam di Asia Tenggara bukan tanpa harapan sama sekali. Khairudin Aljunied dalam Kosmopolitanisme Islam: Islam Asia Tenggara dalam Perspektif Komparatif(2018) mempertanyakan kembali potret kehidupan komunitas muslim yang ditampilkan gagal mengadaptasi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan multikulturalisme. Apakah masyarakat muslim di Asia Tenggara ditakdirkan menemukan jalan buntu menegosiasikan keimanan sebagai identitas, dan kebutuhan menciptakan kehidupan harmonis dan toleran? Aljunied menganggap kita membutuhkan cara yang berbeda dalam memahami apa yang menjadi watak mendasar masyarakat muslim, tidak hanya di Asia Tenggara tapi juga dunia.
Pengalaman Indonesia
Bagian paling menarik dalam kosmopolitanisme Islam di Asia Tenggara adalah nuansa relasional antara model sekularisme negara pascakolonial (baik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dan muslim kosmopolitan yang terus menerus terjadi. Dalam kasus Indonesia sebagai negara Sekuler-Pragmatis, mengalami masa panjang di bawah kekuasaan sentralistis Soeharto (1966-1998) dan perubahan nuansa hubungan antara umat muslim dan negara. Salah satu tesis penting Aljunied adalah posisi keagenan negara berhadapan dengan tuntutan politik muslim kosmopolitan.
Menjelang berakhirnya gaya restriktif Orde Baru terhadap Islam antara tahun 1966 hingga 1989an, Soeharto berupaya merangkul ulama, cendekia dan aktivis Islam ke dalam lingkaran kekuasaannya. Dimulai dengan dibentuknya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975 dan kemudian mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990. Masa panjang transisi gaya restriktif menuju gaya liberalisasi terbatas pada tahun 1989 hingga 1998, didahului oleh upaya Orde Baru menjinakkan umat Islam melalui pembentukan MUI.
Lembaga ini diharapkan berperan sebagai juru bicara Islam yang otoritatif sehingga mampu menciptakan situasi kondusif, menghindari serangkaian kerusuhan yang pernah terjadi pada awal 1970an. Kendati demikian, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka yang ditunjuk memimpin MUI mengundurkan diri pada tahun 1981 setelah fatwanya tentang larangan merayakan Natal bagi umat muslim memicu perdebatan panjang antara dirinya dengan Alamsjah Ratoe Perwiranegara yang menjabat sebagai Menteri Agama.
Aljunied mencatat bahwa masa transisi gaya restriktif menuju liberalisasi terbatas ini menstimulasi hadirnya ruang non-politis yang sangat penting bagi kehidupan muslim kosmopolitan dan bahkan gaya politik negara. Pusat-pusat perdagangan dan Masjid merupakan kawasan kosmopolit yang menopang dan mendukung interaksi lintas agama dan bangsa. Rezim Orde Baru sangat fokus mempertahankan kekuasaan sentralistisnya dalam parlemen, birokrasi, dan Lembaga negara, memberi peluang bagi leluasanya perkembangan politik keseharian di ruang publik seperti pasar.
Muslim kosmopolitan memperoleh ruang alternatif dalam mengembangkan hubungan yang harmonis dan toleran di antara sesama warga bangsa. Artinya agenda persatuan yang bersifat politis ala Orde Baru melalaikan peran penting semangat muslim kosmopolitan dalam merawat kohesi sosial. Mungkin inilah alasan penting mengapa secara mendadak Soeharto pada akhirnya mengubah haluan kebijakan politiknya dengan umat Islam.
Dengan mendirikan ICMI, Soeharto berharap kegelisahan kelas menengah muslim dapat diserap secara cermat dan membantunya mengatasi potensi polemik menjelang masa-masa krisis ekonomi Asia. Apalagi krisis ekonomi yang disertai dengan buruknya kinerja pemerintah Soeharto menangani korupsi dapat menghempaskan kekuasaan Orde Baru lebih cepat. Para kelompok muslim kosmopolitan yang beredar sebagai ulama, cendekia, dan aktivis akan berpengaruh sangat besar pada masa depan Orde Baru. Dan terbukti, kejatuhan Orde Baru adalah akumulasi dari krisis ekonomi, praktik korupsi, dan kekecewaan bertahun-tahun kelompok Islam yang menganggap Orde Baru gagal membuktikan diri sebagai negara sejahtera.
Berakhirnya Orde Baru
Berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998 adalah momen penting bagi intelektual muslim kosmopolitan seperti Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk memastikan bahwa Indonesia melalui transisi ini secara efektif. Tentu saja ada peran besar Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menjaga integrasi kebangsaan, dua organisasi yang mampu bertahan sejak masa kolonial Belanda dan masa-masa berat di bawah pemerintahan Soeharto. Intelektual dan akademikus muslim kosmpolitan menjadi lebih leluasa merekonstruksi wacana Islam dalam kaitannya dengan politik, sosial, dan budaya. Pers-pers Islam pada akhirnya terlibat aktif dalam wacana kebijakan politik negara.
Makna penting berkaitan dengan kondisi ini adalah watak Islam kosmopolitanisme tidak dapat diredam oleh kekuasaan otoriter. Makna intinya adalah bahwa pengaruh gelombang demokrasi global bukan satu-satunya yang menjelaskan latar terwujudnya wacana kehidupan interaktif dan kolektif lintas agama dan bangsa dalam kasus Indonesia. Watak Islam sebagai agama kosmopolitan berperan secara lebih meyakinkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Aljunied, sejak masa perdagangan global pada dekade niaga di Asia Tenggara pada abad pertengahan, kosmopolitanisme adalah watak yang mendasari aktivisme umat Islam. Watak kosmopolitan tersebut terus menerus dinegosiasikan di bawah berbagai bentuk kepengaturan politik dan sosial.
Tampaknya tidak adil secara historis dan sosiologis membicarakan gaya dan ekspresi politik umat Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia tanpa menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang menjadi watak fundamental mereka dari waktu ke waktu. Ekstrimisme keagamaan merupakan kuasa wacana demokrasi global yang terhubung dengan kebutuhan orientasi politik Barat mengatur kebijakan pertahanan (Lih, Mueller, 2006). Peran-peran muslim kosmopolitan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura lebih mudah diabaikan karena mereka tampak sebagai agen demokrasi daripada subjek Islam kosmopolitanisme.
Reformasi kehidupan sosial di Asia Tenggara sangat bergantung pada peran yang mereka mainkan karena dasar keistimewaan kelompok Melayu-Islam yang turut dibesarkan oleh imperium Inggris dan Belanda. Kendati demikian, pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru, narasi penggulingan rezim negara sekuler di Timur Tengah telah menganggu banyak pengamat tentang masa depan Islam di Asia Tenggara. Beberapa orang mengkhawatirkan Indonesia akan jatuh ke dalam pusaran kekerasan politik dan agama sebagaimana yang terjadi di Pakistan dan Irak (Hasan, 2016).
Ketakutan tersebut harus diimbangi dengan pembacaan yang lebih teliti berkaitan dengan perkembangan Islam pasca-Soeharto. Setidaknya sejumlah pengamat politik Islam di Indonesia telah mengetengahkan pentingnya peran muslim kosmopolitan. Mereka terdiri dari individu, masyarakat, institusi, dan organisasi Islam dalam menyuarakan visi Islam kosmopolitanisme. Mereka merupakan aktor kunci dalam membentuk kesadaran toleran, harmonis, dan berorientasi pada perbaikan persoalan ekonomi. Mereka tidak saja beredar di lingkungan universitas tapi juga di pasar, masjid, dan internet.
Masa Depan Muslim Kosmopolitan
Konsep kosmopolitanisme Islam sebetulnya memberi ruang alternatif di antara dua tesis besar mengenai prospek kehidupan demokrasi di Indonesia. Pertama,tesis “Islam Sipil” yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat muslim punya kemampuan menyerap nilai dan cita-cita demokrasi liberal (Lih, Hefner, 2001). Kedua,tesis “Islam konservatif” yang menampilkan kegagalan masyarakat muslim mengadaptasi diri terhadap cara kerja demokrasi (Lih, Bruinessen, 2013). Tesis mengenai kosmopolitanisme Islam merupakan cara lain memahami ruang di antara dua tegangan antara Islam sipil dan Islam konservatif.
Menurut Aljunied, muslim kosmopolitan memiliki kemampuan kreatif mempertemukan kelompok konservatif dan progresif dalam tubuh politik umat Islam. Mereka juga menjembatani pertemuan kekuatan tradisionalis dan modernis Islam di Indonesia. Mereka merupakan agen partisipatif yang terus menerus memperantarai antara nilai-nilai Islam dan tata kehidupan modern.
Beberapa pengamat meletakkan mereka sebagai agen ekonomi dan kultural. Noorhaidi Hasan (2012) dan Farish Noor (2015) melihat bahwa Islam Indonesia tidak akan jatuh ke dalam radikalisme agama karena kebanyakan muslim terlibat dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Muslim kosmopolitan sebagaimana dijelaskan Aljunied beredar di ruang publik. Mereka merupakan warga dalam ruang publik ekonomi sekaligus keagamaan bersama-sama dengan warga beragama lainnya.
Eksistensi kekuatan Islam radikal seperti FPI (Fron Pembela Islam) masih merupakan ganjalan besar bagi tesis “Islam Sipil” dan Islam Kosmopolitanisme. FPI merupakan organisasi masyarakat muslim yang berdiri pada tahun 1998 dan berpusat di Jakarta di bawah kepemimpinan kharismatik Muhammad Rizieq Shihab. FPI sebetulnya tidak cukup relevan dipotret sebagai fenomena keagamaan secara keseluruhan. Mereka adalah bagian dari vigilantisme politik yang muncul akibat tindakan minimal negara dalam menyediakan layanan-layanan dasar bagi masyarakat (Wilson, 2018).
Keberhasilan FPI dalam mengonsolidasi Aksi Bela Islam pada tahun 2016 merupakan episode baru kebangkitan populisme Islam di Indonesia. Apakah ini bermakna sesuatu dalam konteks Kosmopolitanisme Islam? Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana ruang publik kosmopolitan keagamaan dapat dipertahankan.
*Penulis adalah Kurator Rumah Baca Komunitas, Yogyakarta.