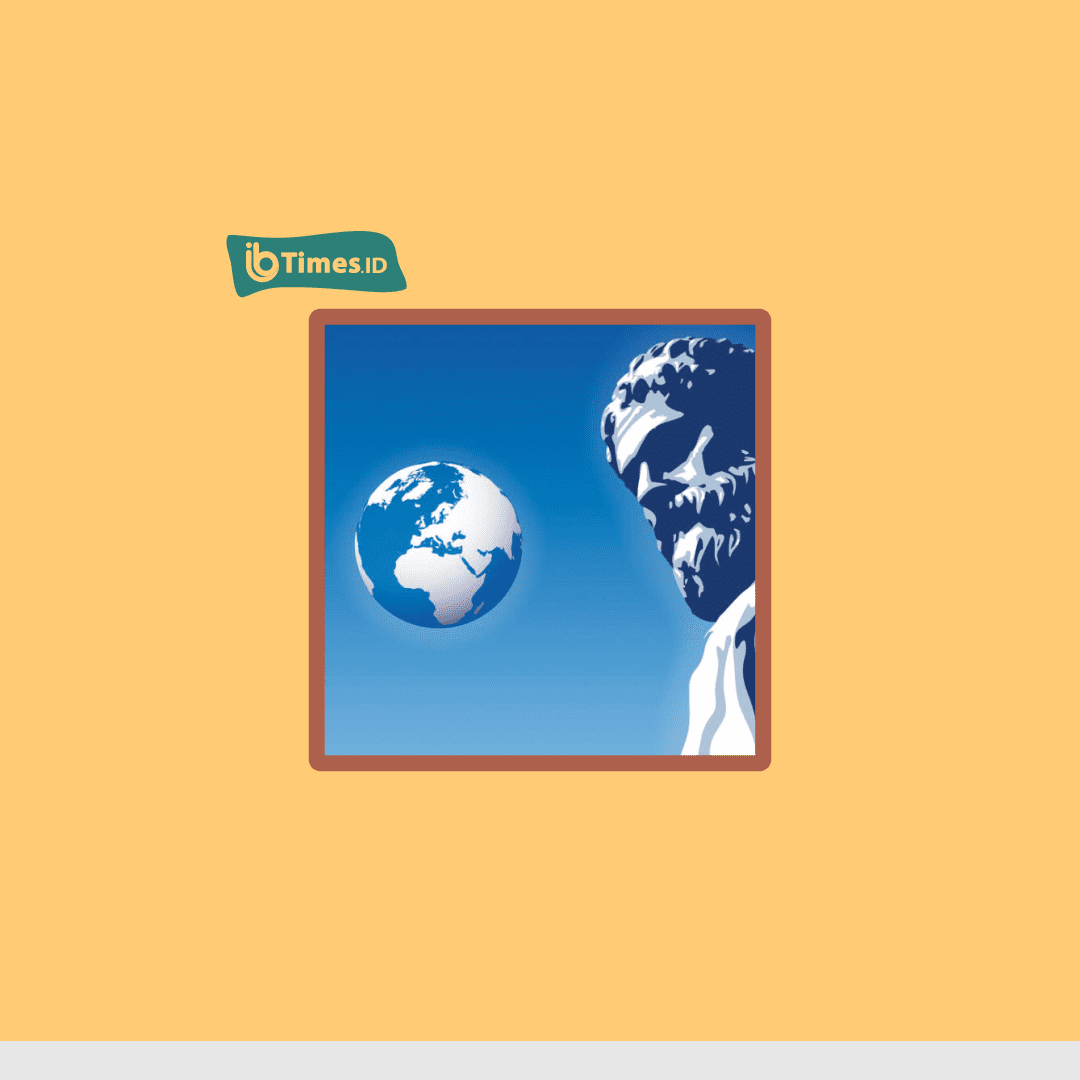Tuntutan untuk mengikuti suatu jalan yang pasti semakin menjadi-jadi di zaman industrial–teknologi ini, melimpahkan ekspektasi-ekspektasi yang secara tidak langsung memberatkan batin dan jiwa kita, diikuti oleh fisik kita. Kita akan merasa kewalahan oleh keinginan-keinginan yang dilontarkan oleh keluarga, kerabat, dan bahkan kawan-kawan sendiri kepada diri kita.
Sampailah ke suatu titik yang mana kita bertanya kepada diri kita. “Untuk apa aku sebenarnya hidup di dunia ini?”. Perdalam lagi pertanyaan tersebut, dan pertanyaan itu akan berubah bentuk menjadi, “Untuk apa aku hidup?”. Pertanyaan ini telah lama muncul di benak para manusia, terlebih lagi para cendikiawan dari masa ke masa. Filsuf Yunani Kuno, Sokrates, berargumen bahwa dalam diri setiap manusia ada esensi yang harus diikuti, “esensi sebelum keberadaan (eksistensi)”. Argumen ini dikenal sebagai aliran esensialisme.
Dalam esensialisme, manusia bergantung secara penuh kepada esensi yang telah ada pada dirinya sejak lahir sebagai tujuan hidupnya. Argumen ini kemudian dielak oleh Jean Paul-Sartre, Filsuf Prancis, yang menyatakan bahwa “keberadaan (eksistensi) sebelum esensi”.
Argumentasi Eksistensialisme
Argumen ini dikenal sebagai aliran eksistensialisme. Sartre menjelaskan bahwa manusia lahir tanpa adanya “esensi”. Esensi manusia, yaitu tujuan hidupnya, hendak dicari oleh manusia tersebut. Hal ini menyebabkan kebebasan, dikarenakan manusia lahir tanpa mempunyai makna dan tujuan sama sekali.
Sartre menganggap kebebasan dari makna sama sekali ini sebagai kutukan karena tanggung jawab yang harus diemban dari segala keputusan yang manusia ambil selagi dalam kebebasan. Hal ini menyebabkan depresi dan “keyakinan buruk”, yaitu tidak mengikuti hati nurani sendiri dan justru melawannya. Lalu, apa hubungannya keberadaan eksistensialisme dengan pertanyaan pada paragraf sebelumnya?
Manusia pasti akan kebingungan dengan tujuan hidupnya, dan di sepanjang jalan kehidupannya, terus mencari sesuatu “obat penenang” agar tidak memberatkan otaknya. Kierkegaard, yang mencetuskan aliran eksistensialisme, berargumen bahwa agama dapat menjadi “obat penenang” tersebut.
Masalahnya, keberadaan agama telah menyebabkan mentalitas kolektif yang radikal di antara masyarakat, menyebabkan munculnya peraturan-peraturan yang tidak menenangkan tetapi membingungkan. Sebagai alternatif, Kierkegaard, Filsuf Denmark, menekankan hubungan yang pribadi antara Tuhan dan manusia, sebagai keputusan yang irasional yang paling rasional.
Bunuh Diri Filosofis
Albert Camus, Filsuf Prancis juga, secara tidak langsung menentang preposisi ini. Ia menggagaskan “bunuh diri secara filosofis” untuk menjelaskan keadaan yang mana seseorang menggantikan ketidaktahuan dari keberadaan di dunia dengan keyakinan-keyakinan buatan manusia, yang secara intinya berarti “membunuh” kapabilitas diri kita untuk menghadapi anehnya dunia yang dialami.
Alih-alih menyerahkan diri kepada keyakinan buatan, Albert Camus menyarankan untuk menyerah kepada alam semesta yang serba kacau, aneh, dan tanpa makna. Dengan begitu, kita akan bebas menentukan makna yang ingin kita perbuat di dunia dan mencegah kewalahan dengan kekacauan alam semesta yang bisa berujung kepada bunuh diri secara fisik.
Lalu, dengan segala tuntutan dan ekspektasi yang diberikan kepada kita sebagai manusia dalam suatu kolektif, apa sesungguhnya keputusan paling terbaik untuk kita, sesuai dengan keinginan pada diri kita ini? Jika alam semesta tidak ada makna inheren sama sekali, bukankah berarti kita lebih baik menyerah saja?
Justru tidak begitu. Makna dan tujuan hidup kita, kita sendiri yang membuat dan tanpa campur tangan yang tidak baik dari orang lain. Memang, tampak sulit untuk menentukan hal-hal tersebut, terlebih lagi merealisasikannya. Namun, ketahuilah bahwa dari kehampaan bisa muncul keberadaan, dan keberadaan tidak akan muncul jika tidak bergerak sama sekali.
Dalam kehidupan modern ini, walau dibombardir dengan informasi yang berlimpah yang belum tentu baik bagi kita, tuntutan-tuntutan dari sekeliling mengenai masa depan, dan ekspektasi diri terhadap yang harus kita lakukan selagi hidup, sembari menyadari bahwa apapun yang terjadi, keputusan dalam hidup kita tidak akan berarti karena kita akan mati juga, cobalah duduk sejenak dan renungkan pertanyaan ini, “Apa makna yang harus aku hasilkan di alam semesta tak bermakna ini?”
Editor: dky.bgss