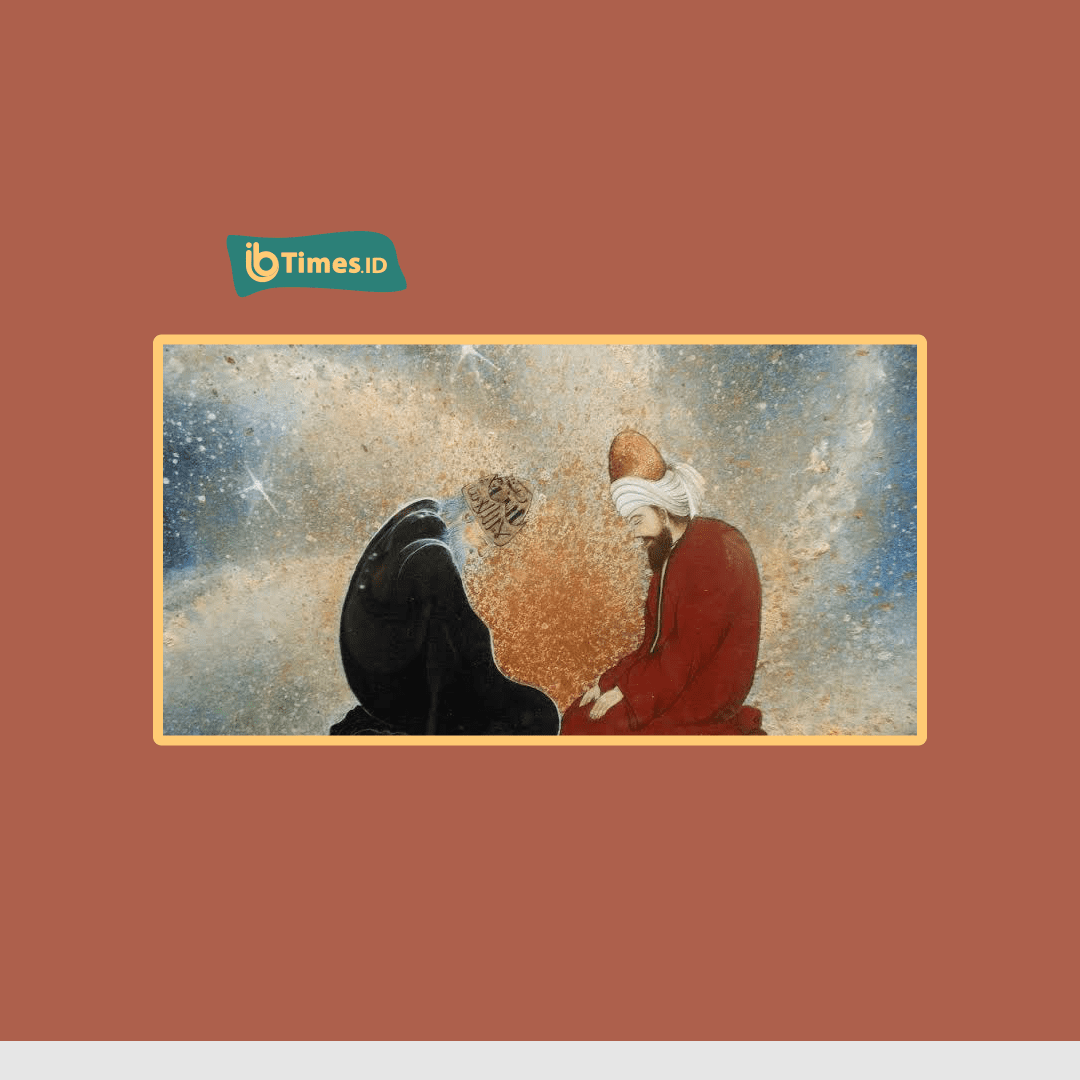Pada era modern ini, banyak sekali permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia selain kemudahan-kemudahan yang ia tawarkan bagi manusia. Namun di samping itu, modernitas juga menimbulkan krisis multidimensi yang tak berkesudahan yang dialami oleh manusia modern di era dewasa ini.
Di antara krisis yang sedang dialami oleh manusia modern tersebut adalah krisis spiritual yang begitu parah, yang tidak pernah terjadi sepanjang perjalanan sejarah peradaban manusia hidup di bumi ini. Saat ini, manusia tengah terjebak dalam dunia paradoks yang menggiring mereka ke dalam keagamaan yang absurd dan profan. Manusia modern menemui jalan yang terputus dengan jalan zaman sejarah agama-agama mulai terbentuk, di antaranya agama Islam.
Seorang pembaharu muslim dari Pakistan yang terinspirasi dari pendahulunya Ibnu Taimiyah, mencoba menjawab permasalahan yang tengah dialami oleh manusia modern saat ini. Dengan memunculkan konsep kesufian yang baru yang ia sebut dengan neo-sufisme, pembaharu itu adalah Fazlur Rahman. Sebenarnya selain, Rahman masih banyak sekali para tokoh muslim yang mengggagas neo-sufisme dengan bahasa yang lain, namun dengan konteks yang sama.
Latar Belakang Munculnya Neo Sufisme
Neo sufisme pertama kali dimunculkan oleh pemikir muslim kontemporer, yakni Fazlur Rahman (1919-1988) dalam bukunya Islam (1979). Kemunculan istilah itu tidak begitu saja diterima oleh para pemikir muslim, tetapi justru memancing polemik dan diskusi yang luas.
Sebelum Fazlur Rahman, sebetulnya di Indonesia Hamka telah menampilkan istilah tasawuf modern dalam bukunya Tasawuf Modern. Tetapi dalam buku ini, tidak ditemui kata neo-sufisme. Keseluruhan isi buku ini, terlihat adanya kesejajaran prinsip-prinsipnya dengan tasawuf Al-Ghazali kecuali dalam masalah uzlah. Jika Al-Ghazali mensyaratkan uzlah dalam penjelajahan menuju kualitas hakikat, maka Hamka justru menghendaki agar seseorang pencari kebenaran hakiki tetap aktif dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.
Menurut Fazlur Rahman, perintis apa yang ia sebut neo-sufisme, adalah Ibnu Taimiyah (w. 728H) yang kemudian diteruskan oleh muridnya Ibnu Qayyim, yaitu tipe tasawuf yang terintregasi dengan syariah.
Kebangkitan sufisme di dunia Islam dengan sebutan neo-sufisme, nampaknya tidak bisa dipisahkan dari apa yang disebut sebagai kebangkitan agama seperti penolakan terhadap kepercayaan yang berlebihan kepada sains dan teknologi, selaku produk modernisme. Modernisme dinilai telah gagal memberikan kehidupan yang bermakna bagi manusia, karenanya orang kembali ke agama. Karena, salah satu fungsi agama adalah memberikan makna bagi kehidupan (Rivey Siregar).
Di samping itu menurut Rahman neo-sufisme, ini muncul karena penolakan terhadap konsep zuhud pada kaum sufi terdahulu yang cenderung melakukan isolasi diri. Yang menimbulkan keganjilan dalam beragama Islam. Hal ini menurut rahman tidaklah sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan hadis. Karena hal itu tidaklah membuat seseorang beragama Islam secara kaffah.
Konsep Neo-Sufisme
Menurut Fazlur Rahman selaku penggagas istilah ini, neo-sufisme adalah “reformed sufism”, sufisme yang telah diperbaharui. Jika pada era kecemerlangan sufisme terdahulu, aspek yang paling dominan adalah sifat estatik-metafisis atau mistis filosofis. Maka dalam sufisme baru ini, digantikan dengan prinsip-prinsip Islam ortodoks.
Fenomena neo-sufisme yang Fazlur Rahman munculkan hampir sama dengan yang dilakukan Tariqah Sanusiyah yang ada di Afrika Utara, yang didirikan oleh Muhammad bin Ali al-Sanusi (w. 1275 H) di Mekah. Tariqah Sanusiyah adalah sebuah Tariqah yang menerapkan kesufian yang ketat namun mereka aktif dalam praksis kemasyarakatan.
Tujuan dari neo-sufisme sendiri sebenarnya adalah penekanan yang lebih intens pada penguatan iman sesuai dengan prinsip-prinsip akidah Islam dan penilaian terhadap kehidupan duniawi sama pentingnya dengan kehidupan ukhrawi. Atau lebih dikenal dengan penyeimbangan (tawazun) antara yang bersifat duniawi dengan yang bersifat ukhrawi agar tercapainya pemahaman Islam secara kaffah tidak secara parsial saja.
Sikap puritanis pendukung neo-sufisme menyebabkan perseberangan dengan paradigma sufisme terdahulu yang mengarahkan para pengikutnya untuk membenci duniawi sehingga mereka pasif. Berlainan dengan neo-sufisme, yang malah mendorong dan memotivasi para pengikutnya agar aktif dan kreatif dalam kehidupan ini, yang bersifat karya-karya praktis maupun dalam kreatifitas intelektual.
Sufisme terdahulu kelihatannya cenderung tertutup terhadap perkembangan pemikiran di luaran. Sehingga, pengertian uzlah itu bukan saja dalam arti lahiriyah, tetapi juga dalam pengertian uzlah dari pendapat yang beragam. Lain halnya dengan neo-sufisme, kelihatannya justru sangat mendukung keanekaragaman pemahaman keagamaan dan hidup dalam pluaritas masyarakat manusia.
Artinya, bahwa neo-sufime berupaya untuk menampung berbagai paham yang berkembang baik yang bersifat hukum atau fikih, aspek teologis maupun aspek sufisme untuk kemudian dikristalisasikan. Mereka tidak menutup diri dari perkembangan dunia dan peradaban manusia, tetapi justru sangat menekankan pentingnya perlibatan diri dalam masyarakat secara intensif.
Cara pandang dan gaya hidup yang demikian di tuangkan dalam semacam dotrin yang disebut “Ruhaniyah Al-Ijtima’iyah” atau spiritualisme sosial, istilah ini berasal dari judul buku karangan Said Ramadlan, yaitu seorang penggerak neo-sufisme di Jeneva.
Tujuan utama dari neo-sufisme bukanlah ittihad, fana’ baqa’, hullul, atau wahdatul wujud. Namun yang menjadi tujuan neosufisme adalah kesalehan sosial yang imbang antara esoteris dan eksoteris (Nurcholis Majid).
Perbedaan dan Persamaan Neo Sufisme Dengan Tasawuf Terdahulu
Dari keseluruhan pemaparan terdahulu telah kelihatan adanya persamaan dan perbedaan antara sufisme terdahulu dengan neo-fisme. Yang penting dicatat adalah sebagai berikut:
Pertama, kelahiran sufisme klasik dan kebangkitan neo-sufisme nampaknya dimotivasikan oleh faktor-faktor yang sama, yakni gaya kehidupan yang glamour dan materistik-konsumeristik, formalisme pemahaman, dan pengalaman keagamaan sebagai imbas dari rasionalisme, dan faktor kekerasan perebutan hegemoni kekuasaan yang merasuki seluruh aspek kehidupan manusia.
Kedua, kesucian jiwa rohaninya, bahwa keduanya sama mendambakan dan menekankan betapa urgennya kebeningan dan kesucian hati nurani dalam segala aspek kehidupan umat manusia-aspek tazkiyah an-nafs.
Ketiga, pendekatan esoteris; keduanya sama berkeyakinan, bahwa untuk memahami dan menghayati mana keagamaan harus melalui pendekatan pengalaman metafisis atau al-kasyf. Namun dalam dalam hal kemutlakan nilai kebenarannya, terlihat antara keduanya ada perbedaan yang tajam.
Kalau sufisme terdahulu meyakini secara mutlak kebenaran yang diperoleh melalui esoteris al-kasyf, tetapi neo-sufisme akan menyakini kebenaran itu apabila sejajar dengan syariat. Di samping itu, sufisme terdahulu hanya mengakui pendekatan esoteris satu-satunya yang dapat digunakan dalam rangka penghaatan keagamaan, tetapi neo-sufisme tetap mengakui terhadap pluralitas pendapat.
Keempat, dzikru’llah dan muraqobah, keduanya sama-sama meyakini betapa pentingnya masalah ini dalam segala situasi demi tercapainya rida Allah.
Kelima, sikap ‘uzlah, jika sufisme terdahulu menempuh cara hidup ‘uzlah total, maka neo-sufisme menempuh cara itu hanya sewaktu diperlukan saja sekedar untuk menyegarkan wawasan melalui musahabah-introspeksi.
Keenam, zuhud, askestisme, apabila sufisme terdahulu “membenci” kehidupan duniawi karena dianggap menghalangi pencapaian tujuan, tetapi sufisme baru menyakini kehidupan duniawi ini sangat bermakna dan sangat penting.
Oleh karena itu, kehidupan duniawi harus diperjuangkan dan harus disesuaikan dengan kepentingan ukhrawi. Menurut pandangan ini, makna kehidupan duniawi tergantung pada keterkaitannya dengan nilai ukhrawi yang dihasilkan aktivitas duniawi itu. Karena mereka berkeyakinan, bahwa neo-sufisme menjadi satu-satunya alternatif kultur yang dapat meng-counter kultur materialisme-konsumeris dan hedonis.
Editor: Yahya FR